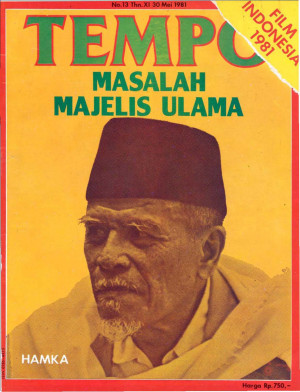FATWA bukan semacam ensiklik. Surat keputusan kepausan itu,
lazim juga memuat ajaran atau pandangan dasar, bersifat
mengikat. Kata itu sendiri semula berarti 'surat yang
dimeteraikan'.
Fatwa sebaliknya, lebih dekat pengertiannya dengan 'petuah'.
Hanya saja lebih khusus: mengenai hukum agama, yang biasanya
jarang diketahui orang atau memang belum ada -- dan karena itu
diputuskan dalam satu kesepakatan para ahli. Ia lazimnya memang
diikuti, tapi ia toh hanya bisa mengikat bila diundangkan.
Karena itu biasanya kedudukan mufti (pemberi fatwa, bila ia
hanya seorang) sebagai semacam "bapak" bagi pemerintah maupun
badan legislatif yang kebetulan sedang shopping pendapat. Di
Timur Tengah lazim dikenal para mufti ini. Ada misalnya Mufti
Besar Palestina. Juga Mufti Mesir Syekh Mahmud Syaltut almarhum,
sesepuh Al Azhar Kairo. Di beberapa negara Islam dibentuk pula
majlis fatwa (majlis ul iftaa' atau daarul iftaa'). Mereka
semacam penasihat.
KH Syukri Ghazali, Ketua Komisi Fatwa MUI yang tempo hari
memimpin sidang fatwa perkara Natal bersama itu, membedakan dua
macam fatwa dari segi daya ikat. Pertama, fatwa yang boleh
diikuti dan boleh tidak -- bila ia merupakan semata-mata usaha
perumusan hukum (baru) bersandar pada sumber. Sebab, meski
misalnya ia diputuskan beramai-ramai, tetap saja ia bisa dikenai
kategori 'kontroversial'.
Kedua, fatwa yang mesti diikuti yang hanya "mengukuhkan saja
hukum yang sudah ada dalam Quran dan Hadis." Di sini fungsi
fatwa tersebut sebenarnya hanya mengingatkan -- karena itu
biasanya diambil tanpa banyak kerepotan.
Di sini pula, memang, Kiai Syukri meletakkan fatwa Natal itu. Ia
mengikat -- meski tentunya bila kalimat 'mengikuti upacara
Natal' itu diartikan sebagai ikut beribadah. Sebab 'mengikuti'
itu sendiri masih umum (mujmal), dan perlu diberi afsil alias
perincian -- seperti ada diterangkan KH Hasan Basri, juga Ketua
MUI (TEMPO 16 Mei 1981). Sedang bila 'mengerti' itu hanya
sekedar hadir, sudah tentu tergantung niat masing-masing. Semua
itu adalah 'boleh' dan 'tidak boleh' menurut agama -- alias
sanksi dari Tuhan, bukan sanksi duniawi. Dan memang di situlah
kompetensi sebuah dewan fatwa.
Bicara soal sanksi dari Tuhan, secara umum diyakini bahwa
hukuman tidak akan jatuh bila seseorang -- berdasar keyakinannya
yang jujur -- tidak menyetujui keputusan sebuah fatwa. Sedang ia
punya argumen kuat, setidaknya untuk dirinya -- meski andai pun
fatwa itu kemudian diundangkan, dan ia harus mengikutinya dalam
hubungan sosial.
Itulah sebabnya mengapa, seperti dituturkan Kiai Syukri kembali,
walaupun sudah ada fatwa dari Syuriah NU atau Tarjih
Muhammadiyah misalnya, orang masih juga menanyakan htwa MUI.
Kebetulan, yang sudah terjadi, hasilnya meman sama -- seperti
dalam soal vasektomi dan tubektomi dalam ikhtiar KB, yang
dinyatakan haram. Tapi kemungkinan perbedaan antar fatwa bukan
tak ada -- seperti antara Tarjih Muhammadiyah dan Majlis Hukum
dan Syara' Departemen Kesehatan, dalam soal cangkok jantung.
Yang pertama cenderung melarang, yang kedua membebaskan.
Contoh lain dari tubuh MUI sendiri. Sebagian dari permintaan
fatwa kepada MUI, dikirim kembali ke MU daerah -- "karena tenaga
ahli kami tidak terlalu banyak, dan juga memang untuk
memfungsikan MU daerah," kata Kiai Syukri. Tapi sering orang
daerah tak puas -- maklum. Menanyakannya lagi ke "pusat". Keluar
kemudian fatwa MUI -- yang mengukuhkan kembali fatwa daerah...
Itu berarti, pada akhirnya: dunia fatwa adalah dunia pasaran
bebas. Lebih banyak pemberi fatwa tampaknya menjadi lebih bagus,
baik hasilnya sama maupun bertentangan, asal semua dinilai
kompeten. Menjadi lebih longgar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini