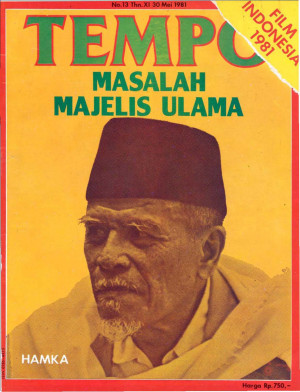SURAT itu pendek. Ditulis oleh Hamka dan ditujukan pada Menteri
Agama RI Letjen. H. Alamsyah Ratuperwiranegara. Tertanggal 21
Mei 1981, isinya pemberitahuan bahwa sesuai dengan ucapan ang
disampaikannya pada pertemuan Menteri Agama dengan pimpinan MUI
pada 2 3 April, Hamka telah meletakkan jabatan sebagai Ketua
Umum Majeiis Ulama Indonesia (MUI).
Menteri Agama membacakan isi surat itu Sabtu lalu di Bina Graha
seusai menemui Presiden. Sebelumnya, yang pagi itu tidak
mengenakan kopiah, membacakan naskah dua lembar tulisan
tangannya pada para wartawan. Isinya tanggapan Pemerintah
mengenai persyaratan mundur Hamka tersebut.
Pemerintah berpendapat pengunduran diri Buya Hamka adalah hak
seorang dalam negara demokrasi yang memang diakui dan dihargai.
"Maksud Buya mundur dari jabatan Ketua Umum MUI bukan untuk
merusak MUI, apalagi merusak kesatuan dan persatuan. Sebab dalam
pernyataan beliau, masih tetap bersedia membantu pemerintah,"
kata Alamsyah. Presiden percaya, lanjut Alamsyah, sebagai ulama
besar Hamka akan tetap menyampaikan saran atau pertimbangan
apabila perlu pada Presiden atau pemerintah.
Buat banyak orang pengunduran diri Hamka sebagai Ketua Umum MUI
mengagetkan. Timbul bermacam dugaan tentang alasan dan latar
belakangnya. Agaknya sadar akan kemungkinan percik gelombang
yang ditimbulkannya, pemerintah dalam pernyataannya mengharapkan
agar mundurnya Hamka "jangan sampai dipergunakan golongan
tertentu untuk merusak kesatuan dan persatuan bangsa, apalagi
merusak umat lslam sendiri."
Menapa Hamka mengundurkan diri? Hamka sendiri pekan lalu
mengungkapkan pada pers, pengunduran dirinya disebabkan oleh
fatwa MUI 7 Maret 1981. Fatwa yang dibuat Komisi Fatwa MUI
tersebut pokok isinya mengharapkan umat Islam mengikuti upacara
Natal, meskipun tujuannya merayakan dan menghormati Nabi Isa.
Menurut K.H.M. Syukri Ghozali, Ketua Komisi Fatwa MUI, fatwa
tersebut sebetulnya dibuat untuk menentukan langkah bagi
Departemen Agama dalam hal umat Islam. "Jadi seharusnya memang
tidak perlu bocor keluar," katanya. Fatwa ini kemudian dikirim
pada27 Maret pada pengurus MU di daerah-daerah. (TEMPO, 16 Mei
1981).
Bagaimanapun, harian Pelita 5 Mei lalu memuat fatwa tersebut,
yang mengutipnya dari Buletin Majelis Ulama no. 3/April 1981.
Buletin yang dicetak 300 eksemplar ternyata juga beredar pada
mereka yang bukan pengurus MU.
Yang menarik, sehari setelah tersiarnya fatwa itu, dimuat pula
surat pencabutan kembali beredarnya fatwa tersebut. Surat
keputusan bertanggal 30 April 1981 itu ditandatangani oleh Prof.
Dr. Hamka dan H. Burhani Tjokrohandoko selaku Ketua Umum dan
Sekretaris Umum MUI.
Menurut SK yang sama, pada dasarnya menghadiri perayaan antar
agama adalah wajar, terkecuali yang bersifat peribadatan, antara
lain Misa, Kebaktian dan sejenisnya. Bagi seorang Islam tidak
ada halangan untuk semata-mata hadir dalam rangka menghormati
undangan pemeluk agama lain dalam upacara yang bersifat
seremonial, bukan ritual.
Tapi bila itu soalnya, kenapa heboh? Rupanya "bocor"nya Fatwa
MUI 7 Maret itu konon sempat menyudutkan Menteri Agama Alamsyah.
Hingga, menurut sebuah sumber, dalam pertemuannya dengan
pimpinan MUI di Departemen Agama 23 April, Alamsyah sempat
menyatakan bersedia berhenti sebagai Menteri. Kejengkelan
Menteri Agama agaknya beralasan juga. Sebab rupanya di samping
atas desakan masyarakat, fatwa itu juga dibuat atas permintaan
Departemen Agama. "Menteri Agama secara resmi memang meminta
fatwa itu yang selanjutnya akan dibicarakan dulu dengan pihak
agama lain. Kemudian sebelum disebarluaskan Menteri akan membuat
dulu petunjuk pelaksanaannya," kata E.Z. Muttaqien, salah satu
Ketua MUI. Ternyata fatwa itu keburu bocor dan heboh pun mulai.
Melihat keadaan Menteri itu, Hamka kemudian minta iin berbicara
dan berkata, menurut seorang yang hadir, "Tidak tepat kalau
saudara Menteri yang harus berhenti. Itu berarti gunung yang
harus runtuh."
Kemudian inilah yang terjadi: Hamka yang mengundurkan diri.
"Tidak logis apabila Menteri Agama yang berhenti. Sayalah yang
bertanggungjawab atas beredarnya fatwa tersebut .... Jadi
sayalah yang mesti berhenti," kata Hamka pada Pelita pekan lalu.
Tapi dalam penjelasannya yang dimuat majalah Panji Masyarakat
20 Mei 1981, Hamka juga mengakui adanya "kesalahpahaman" antara
pimpinan MUI dan Menteri Agama karena tersiarnya fatwa itu.
Kepada TEMPO Hamka mengaku sangat gundah sejak peredaran fatwa
itu dicabut. "Gemetar tangan saya waktu harus mencabutnya.
Orang-orang tentu akan memandang saya ini syaithan. Para ulama
di luar negeri tentu semua heran. Alangkah bobroknya saya ini,
bukan?" kata Hamka.
Alasan itu agaknya yang mendorong lmam Masjid Al Azhar ini
menulis penjelasan, secara pribadi, awal Mei lalu. Di situ Buya
menerangkan: surat pencabutan MUI 30 April itu "tidaklah
mempengaruhi sedikit juga tentang kesahan (nilai/kekuatan hukum)
isi fatwa tersebut, secara utuh dan menyeluruh."
HAMKA juga menjelaskan, fatwa itu diolah dan ditetapkan oleh
Komisi Fatwa MUI bersama ahli-ahli agama dari ormas-ormas Islam
dan lembaga-lembaga Islam tingkat nasional -- termasuk
Muhammadiyah, NU, SI, Majelis Dakwah Islam Golkar. Fatwa
dikeluarkan sebagai tanggungjawab para ulama untuk memberikan
pegangan kepada umat Islam dalam kewajiban mereka memelihara
kemurnian Aqidah Islamiyah, tanpa mengabaikan kerukunan hidup
beragama.
Di sinilah tampaknya letak perbedaan pandangan mulai muncul.
Menteri Alamsyah pada pertemuannya dengan Komisi IX DPR 20 Mei
lalu tentang fatwa MUI ini menegaskan, "Fatwa tersebut berisikan
beberapa ayat Al Quran dan Hadis yang hanya dilihat dari segi
aqidah saja, tidak melihat soal-soal lainnya. "
Alamsyah mengingatkan, bahwa bangsa Indonesia terdiri dari
pemeluk banyak agama. "Karenanya menghadiri perayaan agama lain
dalam rangka menghormati undangan pemeluk agama lain adalah
layak, dan wajar, dan akan meningkatkan rasa persatuan dan
kesatuan bangsa serta kerukunan hidup antar umat beragama," ujar
Menteri di DPR pekan lalu itu. Namun, ditambahkannya, dalam
perayaan yang bersifat ibadat, tidak perlu pemeluk agama lain
hadir.
Tapi Alamsyah mengakui, "Batasan mana yang ibadat dan mana yang
cuma perayaan hingga bisa dihadiri umat agama lain memang belum
ada," katanya pada TEMPO pekan lalu. Departemen Agama, menurut
dia, kini sedang mengumpulkan bahan dari ahli masing-masing
agama tentang pembatasan tersebut. Setelah bahan itu terkumpul,
barulah Departemen Agama akan mengeluarkan semacam pedoman.
"Sasarannya toh tidak banyak, cuma pegawai negeri, karyawan dan
anak sekolah," lanjutnya.
Batasan ini memang penting, sebab yang diatur sebenarya adalah
toleransi dan kerukunan hidup umat beragama di Indonesia. Dalam
situasi di mana masalah agama bisa menjadi sangat peka, dan bisa
eksplosif, bisa dimengerti bila semua pihak -- termasuk
pemerintah -- sangat berhati-hati menanganinya.
PERSOALANNYA rupanya bermula dari perayaan Natal bersama di
beberapa daerah. Yang menjadi sumber keresahan kabarnya perayaan
Natal di beberapa sekolah, yang mengharuskan siswa yang beragama
Islam hadir, bahkan juga dipungut iuran.
"Inilah yang sekarang sedang diurus. Artinya supaya cara-cara
seperti itu tidak terulang kembali," kata Alamsyah. Sebab,
menurut dia, yang dimaksud kerukunan bukanlah campur aduk yang
serupa itu.
Pedoman semacam itu sebetulnya sudah lama ada. Misalnya "fatwa"
Direktorat Pembinaan Pendidikan Agama Islam pada sekolah umum
negeri, Departemen Agama tanggal 11 Februari 1981 yang
menegaskan siswa yang beragama Islam wajib menghadiri perayaan
hari besar Islam atau upacara keagamaan. Siswa yang beragama
Islam juga tidak diperkenankan ikut serta melakukan upacara
keagamaan lain.
TNI-AD rupanya juga sudah mendahului. November 1980, Kepala
Dinas Pembinaan Mental TNI-AD telah mengeluarkan instruksi
tentang Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Keagamaan.
Pertimbangan dikeluarkannya instruksi tersebut antara lain guna
menghilangkan hambatan "masalah yang kelihatannya kecil tetapi
mendasar dari segi keimanan masingmasing penganut agama."
Menurut instruksi itu, penyelenggara an peringatan hari besar
keagamaan suatu agama yang dihadiri juga oleh penganut agama
lain, hendaknya diusahakan sedemikian rupa, hingga tidak
menimbulkan masalah yang merepotkan kerukunan hidup antar umat
beragama.
Caranya menurut instruksi di kalangan Angkatan Darat itu pihak
penyelenggara tidak mempersilakan penganut agama lain, meskipun
sebagai kehormatan, melaksanakan kegiatan yang termasuk ibadat.
Pihak penyelenggara juga diwajibkan memberitahu saat akan
diselenggarakan kegiatan ibadat tersebut, agar yang penganut
agama lain diundang mengetahuinya.
Instruksi ersebut dilampiri daftar kegiatan yang termasuk dan
tidak termasuk ibadat Pada peringatan hari besar keagamaan Islam
seperti Maulid Nabi atau Isra Mi'raj, yang dianggap termasuk
ibadat adalah salam, pembacaan kitab suci Al Quran, salawat nabi
dan doa. Sedang yang tidak termasuk ibadat antara lain
pembukaan, ceramah, sambutan hiburan, penutup, serta "sikap
berdiri pasif": tidak mengikuti acara ibadat .
Buat agama Kristen Protestan, yang termasuk ibadat adalah:
tahbisan dan salam, penyalaan lilin, pujian atau nyanyian dan
paduan suara, doa, pembacaan Al Kitab, khotbah dan renungan
serta berkat. Sedang yang tidak termasuk ibadat, antara lain
sambutan, hiburan, ramah tamah dan juga, "sikap berdiri pasif".
Buat agama Katolik instruksi tersebut menjelaskan, semua acara
yang bersifat ibadat dilaksanakan dalam acara khusus.
Pegangan di kalangan Angkatan Darat itu agaknya cukup praktis,
jelas -- dan tak akan menimbulkan kerepotan. Tapi toh tampaknya
belum ada pemahaman yang cukup tentang pembedaan ini. Di samping
itu, rupanya masih adanya perbedaan pendapat.
Misalnya yang tercermin dalam pendapat KH Misbach, Ketua MUI
Jawa Timur tentang perayaan Natal. "Biarpun di situ kita tidak
ikut bernyanyi dan berdoa, tapi kehadiran kita itu berarti kita
sudah ikut bernatal," katanya. M nurut pendapatnya, "Seluruh
acara dalam perayaan Natal merupakan upacara ritual. Di sini
hadis, "Innamal a'malu binniat (Segala perbuatan itu dinilai
dari motifnya) tampaknya tidak bisa diterapkan," ujarnya.
Kalangan Kristen sendiri mengakui, "Bagi golongan Protestan,
antara ritual dengan yang seremonial tak bisa dipisahkan:
keduanya merupakan satu keutuhan," ujar Dr. SAE Nababan, Sekjen
Dewan Gereja Indonesia (DGI). Menurut dia, Natal merupakan
perayaan yang mempunyai makna yang sesuai dengan apa yang
dipercayai. "Tak ada pembedaan antara ritus dengan seremoni.
Bahkan istilah itu tak dipakai. Yang dipakai adalah perayaan dan
ibadat. Dalam perayaan ada ibadat ," kata Nababan.
Tapi dari kalangan Katolik nampaknya ada perbedaan. Dr. J.
Riberu, Kepala Bagian Dokumentasi dan Penerangan Majelis Agung
Waligereja Indonesia (MAWI), misalnya mengatakan: "Bagi kami
orang Katolik, baru disebut ibadat atau kultus, jika diadakan
dalam rangka ekaristi suci, jika ada Imam yang mempersembahkan
kurban misa. Dan ini diwujudkan dengan seremoni tertentu," kata
Riberu. Di luar itu, biarpun pakai lilin - yang hanya untuk
menyemarakkan saja -- adalah "nonkultus". Ini biasanya diadakan
sesudah yang benar-benar ibadat dijalankan dan sekedar merupakan
perayaan keluarga atau kewargaan.
Melihat berbagai pandangan tadi, yang cukup berbeda, pedoman
tentang mana yang batasan ibadat dan yang tidak memang tampaknya
perlu. Tak ada yang ingin melihat retaknya kerukunan antar umat
beragama hanya karena persoalan ini. Dan untuk kerukunan itu,
betapa pun terbatasnya peran MUI, ia tetap diperlukan sebagai
jembatan (lihat: MUI, Kisah Sebuah Jembatan).
Lalu, apa yang terjadi setelah pengunduran diri Hamka "MUI akan
jalan terus," tegas EZ Muttaqien. Sampai terpilihnya ketua umum
baru, pimpinan MUI akan dipegang secara bergiliran antara ke
enam ketua MUI. Giliran pertama dipegang oleh KH Hasan Basri.
Rapal pengurus paripurna untuk memilih ketua umum itu diharapkan
berlangsung sebelum bulan Ramadhan.
Ketua MUI yang lain, H. Soedirman, mengharapkan agar dengan
berhentinya Buya Hamka, MUI bisa mawas diri dan melahirkan
semangat baru. "Sebab selama ini MUI hanya lebih dikenal Buya
Hamkanya," katanya. "Saya pribadi menghendaki agar MUI bisa
berbuat lebih banyak."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini