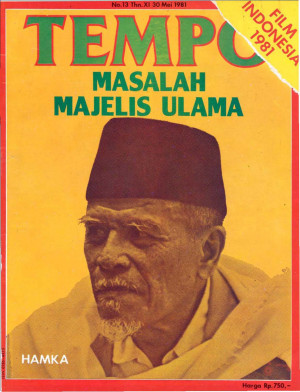ANGGOTA Majelis Ulama tidak digaji. Ini memang salah satu
"syarat" yang dulu diminta Prof. Hamka, waktu ia diminta jadi
ketua MUI, 1975. Permintaan yang lain: ia akan dibolehkan
mundur, bila nanti ternyata sudah tidak ada kesesuaian dengan
dirinya dalam hal kerjasama antara pemerintah dan ulama.
Mohammad Roem, dalam buku Kenang-kenangan 70 ahun Buya Hamka,
menyebut masalah gaji itu sebagai bagian dari "politik Hamka
menghadapi pembentukan Majelis Ulama". Ulama mubaligh ini,
menurut Roem, kuat sekali menyimpan gambaran "ulama yang tidak
bisa dibeli". Walaupun gaji sebenarnya tidak usah selalu
menunjuk pada pembelian, kepercayaan diri ulama sendiri agaknya
memang diperlukan. Sebab, tak lain, pemerintahlah yang membentuk
Majelis Ulama.
Dan itulah beda MUI, misalnya, dengan Dewan Gereja-gereja di
Indonesia (DGI) dan Majelis Agung Waligereja Indonesia (MAWI),
dari Protestan dan Katolik. Kedua lembaga ini tumbuh berdasar
kebutuhan dari bawah, atau dari dalam Hamka, di rumahnya di
samping Masjid Al Azhar Kebayoran Baru, menyebut satu-satunya
majelis ulama yang tumbuh dengan cara seperti itu adalah yang di
Sumatera Barat, di bawah Datuk Palimo Kayo. Itu sebelum ada MUI
(pusat). MU Sum-Bar tersebut, bersama Majelis Ulama DI Aceh yang
dibentuk oleh Pemda Provinsi, praktis memang merupakan "pemberi
ilham" pembentukan MUI.
Pembentukan majelis ulama di Jakarta kemudian (yang diberi
tambahan untuk Indonesia, sebagai pembedaan dari MU daerah,
termasuk daerah DKI) seakan tinggal merapikan saja. Terpenting,
betapa pun, adalah fungsi MUI (dan kemudian MU semua daerah)
sebagai "penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) serta
penerjemah timbal-balik antara pemerintah dan umat. . . "
Fungsi itu memang hanya dicantumkan dalam Pedoman Dasar sebagai
nomor empat alias terakhir. Tapi tak urung, niat baik pemerintah
itu memerlukan beberapa waktu untuk penerimaan di kalangan umat.
H.A. Hamid Wijaya, misalnya, Sekjen (Katib Aam) Syuriah NU, bisa
menghargai MUI. Toh ia menganggap lebih baik kalau badan seperti
itu dibentuk "melalui potensi umat yang ada -- bukan ditentukan
dari atas. "
Padahal kalau ia semata tumbuh dari bawah, belum tentu ia akan
jadi jembatan itu. Lagi pula sebagian orang melihat kepada
hasil. Dan dilihat dari pihak pemerintah, menurut K.H. Hasan
Basri, yang sekarang ini Ketua Periodik MUI, biasanya "pendapat
MUI diterima dengan baik karena murni sifatnya". Yakni bukan
merupakan suara golongan atau partai.
Memang, dalam kasus fatwa Natal ini terlihat seolah majelis ini
hanya menyuarakan "kepentingan umat Islam" semata -- tanpa
mempertimbangkan pihak lain. Juga dalam fatwa tentang aliran
kepercayaan dahulu. Toh, sementara masalah fatwa Natal memang
kompleks, dalam masalah kepercayaan akhirnya apa yang dimaksud
MUI sejalan belaka dengan pandangan pemerintah -- seperti
dikatakan Hasan Basri. MUI tak setuju aliran kepercayaan
dianggap sebagai agama atau disamakan dengan agama. Dan
penetapan terakhir ternyata begitu pula.
Lebih dari itu, seperti disebut dalam rekomendasi Munas II
Majelis Ulama se-Indonesia, Mei tahun kemarin, para ulama itu
merekomendasikan pula penyebarluasan P4 -- meski dalam
'pembudayaan dan penghayatan Pancasila' diminta agar usaha tidak
terutama dititikberatkan pada penataran. Melainkan pengamalan
dan partisipasi yang nyata. Manfaat MUI yang lain: seorang
menteri bisa saja mengundang para anggotanya dan meminta pikiran
-- misalnya dalam soal lingkungan, oleh Emil Salim, yang
kemudian disambung pula dengan beberapa pertemuan.
Toh tidak benar bila dianggap MUI hanya memikirkan hal-hal yang
tidak mendasar. Hasil Munas 11 yang telah disebut, selain
mempercayai Mandataris MPR untuk melanjutkan kepresidenannya,
juga meminta perhatian pada berbagai akibat sampingan
pembangunan. Seperti meluasnya kesenjangan antara kaya dan
miskin, korupsi, dekadensi moral, ekses teknologi, permintaan
pengutamaan masyarakat desa, permintaan perhatian kepada
pengusaha pribumi dan ekonomi lemah, ajakan pemupukan semangat
cinta tanah air dan idealisme, pikiran untuk pembaruan sistem
pendidikan nasional, bahkan saran koordinasi lebih intensif
zakat dan sumber dana muslimin oleh pemerintah.
Manfaat lain: MUI berhasil menjadi tempat berkumpul berbagai
golongan. Inilah yang pertama kalinya, sebenarnya, umat Islam
punya wadah kumpul-kumpul itu -- ukhuwah Islamiyah, istilahnya,
yang memang digariskan sejak pembentukannya sebagai fungsi MUI
yang kedua.
Hamid Wijaya, Sekjen Syuriah NU itu, di titik ini memuji
kelebihan organisasi ulama ini, -- yang menyebabkan "langsung
atau tidak langsung tindakan MUI akan dirasakan oleh masyrakat,"
dan "jika benar, umat Islam akan mendukungnya." Apalagi dengan
kepemimpinan model Hamka. Buya yang dulu pengarang novel ini
"bisa diterima di pemerintah, bisa pula di kalangan ulama." Ia
juga ulama Muhammadiyah " yang tidak pernah menyakiti hati NU,"
kata Hamid Wijaya pula.
Hanya kerukunan dengan umat agama lain memang seolah terganggu,
akibat kasus fatwa itu. Meskipun bagi para ulama itu sendiri,
fatwa itu justru merupakan bekal menghadapi kesimpang-siuran .
Orang mungkin membayangkan bahwa MUI akan agak mundur -- meski
Letjen (Purn.) H. Sudirman, salah seorang ketuanya, menyatakan
justru peristiwa ini memaksa MUI mawas diri. H. Burhani
Tjokrohandoko, Sekjen majelis tersebut, yang juga Dirjen Bimas
Islam dan Urusan Haji di samping pimpinan GUPPl Pusat dan
Majelis Dakwah Islamiyah (MDI)-Golkar Pusat, menyatakan bahwa
pemerintah masih tetap menghendaki MUI berfungsi seperti biasa.
Juga Menteri Agama.
Namun Hamka juga menuturkan, di rumahnya, bahwa kehadiran ulama
secara informal -- sendiri-sendiri -- belum tentu kuran efektif
dibanding keberadaannya dalam majelis resmi. Ia sendiri
misalnya, yang menyatakan akan tetap membantu pemerintah dan
Presiden, sejak dulu tak habis-habisnya dimintai fatwa -- juga
oleh kalangan pemerintah.
Hamka tentu tak ingin MUI bubar, ataupun mundur -- dan
pernyataan itu pernah disiarkan pers. Hanya, seperti dikatakan
seorang anggota biasa Majelis yang tak mau disebut namanya,
persoalannya akan sama saja baik ada atau tak ada Hamka --
tergantung pada seberapa jauh pemerintah masih akan memberi "hak
otonomi" kepada lembaga itu.
Obsesi bahwa para ulama itu dulu diangkat pemerintah, meski
tidak digaji, di saat-saat tertentu ternyata memang justru bisa
menimbulkan was-was. Misalnya terhadap kemungkinan majelis para
pengayom umat itu hanya dijadikan "dapur" atau bagian dari
departemen mana pun, atau jadi bagian dari kekuatan politik atau
partai.
Padahal, sebagaimana dimaksud sejak mula, ia memang jembatan
--yang seharusnya bisa menghubungkan dua pinggir, dan tidak
goyang. Untuk itu tak mungkin hanya dengan mengumpulkan sejumlah
tokoh di MUI -- yang tak berwibawa, yang tak bisa mengantarkan
ke seberang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini