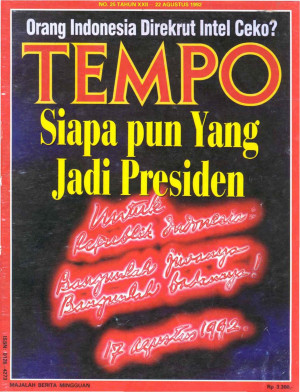Ada yang tak enak bagi kaum penganggur. Pekan lalu dikabarkan PT Indah Kiat akan memasukkan 5.000 pekerja asal RRC. Mereka bakal dipekerjakan di pabrik PULP (bubur Kertas) milik konglomerat Eka Tjipta Widjaya di Pekanbaru. Berita itu mengejutkan, mengingat dalam pelita VI nanti tenaga kerja Indonesia akan meledak jadi 12 juta. Apalagi kalau tenaga kerja impor itu tidak semua terampil, seperti untuk menjaga gudang, yang sebenarnya busa dilakukan tenaga kerja Indonesia. Sebab, angkatan kerja Indonesia dari pelita lalu yang menganggur benar-benar sekitar tiga juta (3% dari seluruh angkatan kerja). "Dari yang tercatat bekerja pun, sebenarnya ada 44% yang setengah menganggur," kata Menteri tenaga kerja Cosmas Batubara. Yang dimaksud setengah menganggur (Underemployment) adalah mereka yang bekerja kurang dari 35 jam per minggu. Sebab, standar yang dipakai agar tak disebut penganggur adalah bekerja 40 jam per minggu. Bagaimana mengatasinya? Cosmas lantas memperkirakan lapangan kerja yang bakal tersedia bila pertumbuhan ekonomi mencapai 5% per tahun. Lapangan kerja yang tersedia diperkirakan menampung 11,5 juta orang. Itu pun belum berarti bisa mengikis tumpukan penganggur, karena tiap pertumbuhan ekonomi 1% diperhitungkan cuma mampu menyedot 0,6% tenaga kerja di pasaran. Bila angkatan kerja, menjadi 12 juta, maka masih ada sekitar setengah juta penganggur pada akhir pelita VI nanti. Tenaga penganggur ini jelas berbeda dengan penganggur di periode sebelumnya. Adanya wajib belajar dan pesatnya pendidikan membuat mereka lebih terpelajar. Ini rupanya menjadi problem baru. "Karena mereka jadi pilih-pilih pekerjaan yang tinggi," ujar Cosmos. Pendidikan ini juga mengubah perilaku tenaga kerja. Seperti anak petani yang sudah terdidik, ia cenderung enggan bergumul kembali dengan tanah, tapi terpikat bekerja di sektor industri atau jasa yang mencuat lebih bersih. Ini tampak dari turunnya prosentase angkatan kerja di sektor pertanian (56,3% pada tahun 1980 menjadi 54,7% pada tahun 1985), dan meningkat di bidang manufaktur (9,1% menjadi 9,3%) atau perdagangan (13,7% menjadi 15,8%). Penurunan di sektor pertanian ini tak menjadi masalah, karena pemerintah malah mendorong agar tenaga kerja juga bergeser ke industri. "Sayangnya, ada structural gap, ketidaksamaan lapangan kerja yang ditawarkan dengan kualifikasi pendidikan pencari kerja," kata Cosmas lagi. Karena, tiap sepuluh penganggur sebenarnya tersedia tiga lowongan kerja, namun yang bisa diisi hanya dua. Yang tidak terampil bukan cuma untuk tenaga tingkat ahli. tenaga kerja terampil kelas menengah, seperti tukang las bawah air dan pengebor minyak bawah air, juga langka. Hingga seorang pemuda lulusan STM asal Kisaran, Sumatera Utara, yang piawai mengelas di bawah air sering diundang ke mana-mana untuk menyelesaikan pekerjaan itu. Sementara itu, sebagian tenaga yang tersedia adalah mereka yang terpelajar tetapi tak punya ketrampilan. Umumnya, tenaga semacam ini getol di kota dan cuma beberapa yang dapat bekerja. Sisanya, mereka memilih luntang- lantung. Dalam pada itu, pemerintah tak berdiam diri untuk menjembatani pendidikan dengan pekerjaan. Jembatan itu adalah latihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK). Tapi sedikit lulusan yang bisa diserap. Sebanyak 153 BLK yang ada hanya punya kapasitas 120 ribu orang tiap tahunnya. Di sini peran swasta diharapkan. Itu tadi adalah masalah yang akan dihadapi calon pekerja. Tapi tenaga kerja yang sudah dapat gawe pun tak luput dari masalah, yang sebagian besar dibuat pemerintah. Mereka hampir tak berdaya menghadapi masalah itu karena banyaknya pencari kerja, ditambah kondisi tenaga kerja Indonesia yang sebagian besar (77,9%) berpendidikan SD, sehingga membuat mereka dalam posisi yang tidak punya kekuatan tawar menawar. Sedangkan bagi yang sudah bekerja ternyata tidak pula semua busa menikmati hasil keringatnya. Hak-hak buruh, seperti upah dan jaminan kesejahteraan diabaikan majikan. Sementara itu, hak untuk membentuk serikat pekerja tanpa campur tangan pengusaha sudah tercantum dalam undang-undang nomor 18 tahun 1956 dan undang-undang nomor 4 tahun 1969. Namun dengan dikeluarkannya peraturan Menteri nomor 4 tahun 1986, ketentuan tersebut malah dihapuskan, sehingga mereka loyo menghadapi majikan. Misalnya, asalkan sudah membayar paling kurang 50% dari upahnya enam bulan kepada karyawan bersangkutan, maka si majikan boleh melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) tanpa menunggu keputusan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Daerah, atau Pusat (P4D atau P4P). selama menunggu penyelesaian dari P4D itu, si karyawan merasa sudah di-PHK-kan. Dan peran P4D atau P4P biasanya berpihak kepada majikan (Tempo, 8 Juni 1991). Pemerintah juga mengatur kegiatan buruh dalam wadah tunggal Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI). Hasilnya, tujuan SPSI untuk menyalurkan aspirasi pekerja dan memperjuangkan kesejahteraan anggota tak terwujud hingga kini. Posisi SPSI dalam Tripartit pemerintah-pengusaha-SPSI ternyata lemah. Ini dibenarkan oleh Imam Soedarwo, ketua umum SPSI. "Kami dikritik sebagai banci dan impoten," katanya. Diakuinya, keterbatasan seperti disebut tadi membuat buruh lumpuh. Beberapa hak buruh kemudian diperlonggar. Mereka boleh mogok, dan ada ketentuan upah minimum. Perubahan ini dilakukan tahun lalu. Di DKI Jaya, misalnya, upah minimum dinaikkan dari Rp 2.100 menjadi Rp 2.600 tiap hari dengan jumlah jam kerja yang ditetapkan 40-53 jam per minggu. Langkah lain untuk menipiskan tumpukan pengangguran adalah dengan mengirimnya ke luar negeri. Dalam pelita V ini akan dikirim 500 ribu tenaga, terutama Arab Saudi. Dan yang terealisasi hingga kini baru 390 ribu orang. Sebetulnya ada lagi cara yang efektif untuk menampung ledakan tenaga kerja. Sektor yang tidak terlalu membutuhkan fasilitas dari pemerintah, itu adalah sektor informal. Tenaga yang terserap sekitar 70% lebih tinggi ketimbang sektor lain. Namun sektor ini sering bertubrukan dengan ketentuan formal, seperti soal ketertiban, keindahan, dan tatanan yang dibuat pemerintah. Sektor ini, menurut Cosmas, harus diperhatikan karena merekalah penyisih pengangguran. Tapi, katanya, belum semua pemerintah daerah memikirkan hal ini. Masalah-masalah yang berkaitan dengan pengangguran ini mungkin akan menjadi pekerjaan rumah yang merepotkan di masa datang. Bukan saja soal mencari pekerjaan, tapi terutama soal perut dan status sosial di masyarakat. Mereka sebagian besar terpelajar dan memiliki daya kritis yang tajam. Inilah yang mungkin akan mengganggu masalah sosial: kriminalitas atau gangguan Stabilitas lainnya. Diah Purnomowati Dan Indrawan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini