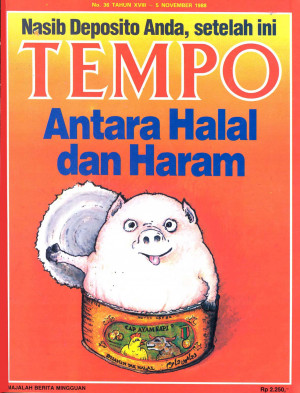SEBAGAI bahasa pemersatu, sebagaimana diikrarkan lewat Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia sudah berumur 60 tahun. Dan hingga pekan lalu, tatkala dimulainya Kongres Bahasa Indonesia V di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, bahasa nasional ini masih belum merata dipakai di seluruh provinsi. Ada penelitian yang menyebutkan, sekitar 30% penduduk Indonesia "buta bahasa Indonesia". Yang lebih menyedihkan adalah apa yang dikatakan Dr. Muljanto Sumardi, bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang tidak disenangi, membosankan, dan malah ditakuti di sekolah-sekolah. "Padahal, mata pelajaran ini merupakan salah satu mata pelajaran yang menentukan seorang siswa naik kelas atau tidak," tulis Muljanto dalam makalahnya berjudul Pengajaran Bahasa Indonesia di Sekolah: Gramatika atau Komunikasi? Apa yang dikatakan pakar bahasa dari Himpunan Pembina Bahasa Indonesia itu di dalam kongres memang kenyataan di banyak sekolah. Ignas Widhiharsanto, siswa kelas I SMP Kanisius di Jakarta, misalnya, setuju bahwa bahasa Indonesia sebagai pelajaran yang paling membosankan. "Semua teman saya di kelas juga nggak suka," katanya. Tiga kali ulangan bahasa Indonesia, Ignas memperoleh nilai 6, 2, dan 1. "Eh, di rapor saya dapat angka 5. Apa Bu Guru itu nggak berani kasih angka 3, ya?" tanyanya melecehkan. Untunglah, ini baru rapor bayangan, belum semesteran. Begitu pula Indrajayanto, siswa kelas III SMAN I Semarang. Ia merasa tak perlu lagi belajar bahasa Indonesia, karena sudah bisa berbicara dengan bahasa itu. "Daripada belajar bahasa Indonesia sampai pusing, lebih baik belajar kimia atau fisika, yang banyak gunanya," katanya. Kedua murid ini, sekadar contoh, mungkin tidak salah. Pelajaran bahasa Indonesia di SD sampai SMA diberikan dengan cara tidak menarik dan banyak sekali hafalannya. Dalam pelajaran kesusastraan, misalnya, Ignas mengaku bosan ditanya yang itu-itu juga sejak SD. "Siapa pengarang Siti Nurbaya, roman apa yang dikarang Sutan Takdir Alisjahbana. Apa nggak ada buku sastra yang baru?" tanya Ignas. Sedihnya, Pak dan Bu Guru hanya menanyakan saja, tanpa menganjurkan murid agar membaca buku sastra itu, apalagi membahas di mana kelebihannya. Pelajaran tata bahasa pun membosankan, sementara, "kalau Bu Guru ngobrol dengan kita-kita, eh, dia juga pakai lu, gue," kata Ignas. Keadaan itu semakin parah karena faktor lingkungan. Pengaruh bahasa daerah masih dominan. Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup Prof. Dr. Emil Salim dalam kongres ini menyebutkan hasil penelitian yang diramu dari sensus 1980. Terungkap di situ pemakai bahasa Indonesia terbanyak adalah DKI Jakarta, dan menyusul Maluku. Paling menyedihkan Provinsi Jawa Tengah, DIY, dan Sumatera Barat. Karena itu, dengarlah keluhan F.R. Titik Palupi, guru bahasa Indonesia di SMP Maria Mediatrik, Semarang. "Bahasa Indonesia di lingkungan keluarga belum membudaya. Akibatnya, begitu susahnya jika murid-murid disuruh mengarang," kata Palupi. Tapi ia juga menyalahkan banyak guru. "Mereka berbahasa Indonesia kurang benar jika mengajar." Rekan Palupi, Sumardiono, menyebut kelemahan lain, yakni ketidakstabilan kurikulum. Kurikulum 1975 belum sepenuhnya dipraktekkan, sudah muncul Kurikulum 1984. "Itu pun buku paket pedoman pelajaran bahasa Indonesia belum ada sampai sekarang," kata Sumardiono. Pedoman yang dipakai sekarang adalah Ejaan yang Disempurnakan (EYD). Susahnya, EYD sendiri tidak konsisten. Sumardiono menyebut contoh: sesuai dengan EYD, pemisahan suku kata berdasarkan kata asal. "Tapi kata April dipisahkan Ap-ril, padahal jika mengikuti kata asal mestinya A-pril. Ini 'kan membingungkan," katanya. Kalau guru bingung, apalagi muridnya. Bagaimana memperbaiki semua ini? Dr. Bistok A. Siahaan, guru besar IKIP Jakarta, menyebutnya sebagai benang kusut, "Kita tidak dapat memulai dari mana memperbaikinya." Orang mengeluhkan kurikulum, bahan pelajaran, pendekatan, proses belajar-mengajar, dan cara penilaian. Meluaskan wawasan guru, kata Bistok, belum banyak diharapkan. Ada satu juta lebih guru SD yang sekaligus menjadi guru bahasa. Mereka belum memiliki persyaratan khusus sebagai guru bahasa. Mereka memerlukan buku yang amat lengkap sehingga bisa mengajar dengan baik, selain kurikulum yang jelas. "Namun, buku pelajaran selalu ketinggalan bukan saja dari kurikulum, tetapi dari perkembangan masyarakat dan perkembangan ilmu pengajaran bahasa. Guru memang kebingungan dan itu yang kita catat di lapangan," kata Bistok. Dalam situasi begini, dibutuhkan guru yang kreatif dan mengikuti perkembangan. Mungkin yang dilakukan Sri Lestari, guru bahasa di SMA Theresia, Jakarta, bisa dicontoh. Dalam pelajaran sastra, umpamanya, Tari menyuruh muridnya membaca novel Jalan Tak Ada Ujung-nya Mochtar Lubis. Lalu didiskusikan temanya, alur dan latarnya. Tari mengarahkan diskusi model CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif). "Bu Tari memaksa murid untuk berpikir dan membaca. Kita jadi semangat," kata Yani, salah seorang murid. Bacaan pun tak hanya novel-novel lama, juga yang baru. Guru yang hanya berkiblat pada kurikulum dan hanya menyiapkan murid untuk menghadapi ujian bukan masanya lagi. Perkembangan bahasa jauh melampaui daftar isian kurikulum. Tapi, "Guru juga sulit disalahkan, karena mereka terikat memenuhi data yang sesuai dengan kurikulum itu," kata Sapardi Djoko Damono, sastrawan dan staf pengajar UI. Sejak Kongres Bahasa I di Solo (1938) sampai Kongres Bahasa IV di Jakarta (1983) masalah ini mendapat perhatian khusus. Dalam Kongres Bahasa V yang berakhir Rabu pekan ini, tampak ada kemajuan dalam mengurai benang kusut itu. Kritik pun lebih terbuka. Yus Badudu, misalnya, melihat sistem penilaian dan materi ujian lebih banyak teori dan hafalan, sehingga guru pun mengajar dengan target seperti itu. Pemahaman jadi kurang. Lalu? Kita tunggu hasil kongres. Agus Basri, Linda Djalil, Indrayati (Jakarta), dan Heddy Lugito (Yogya)
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini