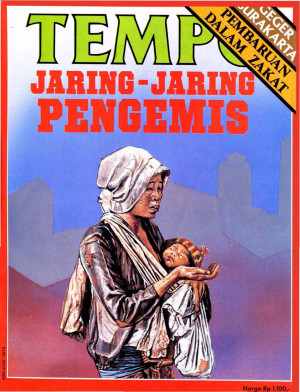EMPAT buah bis malam dari Jakarta beriringan memasuki Kota
Pemalang, Jawa Tengah. Membelok ke selatan, bis-bis itu menuju
arah Kecamatan Randu Dongkal. Setelah melewati Kelurahan Warung
Pring, kendaraan-kendaraan tadi berhenti. Para penumpang pun
turun.
Rombongan yang sarat dengan barang itu berjalan beriringan,
menempuh jalan desa berdebu dan berbatu. Sepanjang hampir 7 km.
Sampailah mereka di desa, disambut dengan girang oleh sanak
saudaranya yang menunggu. Desa itu adalah Desa Kreyo yang
sebagian besar penduduknya "bekerja" sebagai pengemis di
Jakarta. Desa itu pun mendadak cerah dan ramai tiga hari
menjelang Lebaran -- jauh beda dengan hari-hari biasa yang sepi.
"Jika baru datang dari Jakarta, mereka kelihatan mewah. Siapa
yang tidak bangga," kata Sugimo, 43 tahun, lurah Desa Kreyo.
Yang agak disayangkan sang lurah, tingkah mereka yang agak aneh.
"Pakaian mereka juga agak aneh dan percakapan mereka menggunakan
bahasa Indonesia logat Jakarta yang sukar dipahami," katanya.
Sugimo yang memimpin Desa Kreyo sejak 1975, tak tahu persis
berapa jumlah penduduk desanya yang merantau ke Jakarta. Yang
lebih aneh lagi, semua pamong Desa Kreyo tak tahu pasti, kerja
warga mereka di Ibukota. "Mereka pergi tanpa surat jalan," ujar
lurah. "Saya sendiri heran, berangkat ke Jakarta tak pernah
sama-sama, pulangnya serentak. Apa di sana mereka kumpul?"
Lurah yang juga jadi guru SD Karang Kreyo II ini pernah
mengusut, apa yang mereka kerjakan di Jakarta. "Kebanyakan
menjawab, jadi karyawan pabrik," tutur Sugimo. Tapi tak pernah
jelas, pabrik di mana dan sebagai apa. Ia tak mau mengusut lebih
lanjut.
Desa Kreyo terletak 39 km di barat daya Pemalang, berpenduduk
5.000 jiwa lebih atau 1.110 kk. Di sini ada 223 ha sawah yang
subur. Hampir semua penduduk desa itu memiliki sawah minimum 2
petak. "Termasuk mereka yang hijrah ke Jakarta itu," kau Sugimo.
"Andai kata mereka mengolah sawahnya di desa, hasilnya akan
mencukupi seluruh keluarganya."
Yang tak terbayangkan oleh Sugimo adalah, bagaimana mungkin
warganya di Jakarta mendapat pekerjaan dengan penghasilan begitu
besar. Pendidikan mereka paling tinggi SD. "Banyak yang tak
tamat SD, bahkan buta huruf. Di desa pun mereka tergolong malas
bekerja. Bagaimana mungkin bisa mendapat pekerjaan di Jakarta
dengan mudik ke kampung penuh bawaan?"
Lurah ini bukannya tak pernah mendengar, bahwa warga desanya di
Jakarta hidup sebagai pengemis. "Boleh jadi berita itu benar,
warga desa saya mengemis di Jakarta," katanya. "Namun saya tak
berani memastikan, karena belum ada bukti atau laporan resmi."
Bekas lurah Kreyo, Sumarta, 67 tahun, lebih tegas mengakui,
penduduk desa yang pergi ke Jakarta itu memang hidup sebagai
pengemis. "Sudah sejak dulu saya tahu. Tetapi mereka tak
sebanyak sekarang, sampai desa ini sepi," kata Sumarta terus
terang. Bahkan bekas lurah ini tahu persis "sejarah kepengemisan
itu". Ketika itu, sekitar tahun 1970-an, katanya, ada lima warga
desa yang pergi ke Jakarta berjualan petai. Di kota metropolitan
itu, mereka kehabisan bekal, sementara dagangan tak laku.
Akhirnya mereka meminta belas kasihan orang. Ternyata dengan
mudah uang diperoleh dan kelima orang itu pulang dengan bekal
yang jauh lebih cukup dibandingkan nilai dagangannya. Ketika
diceritakan di desa, kemudahan mendapat uang di Jakarta itu
menjadi daya tarik. Sampai sekarang.
Kini di Desa Kreyo ada semboyan: "Nek maring Jakarta, rekasa
ngemis, namung maring desa ketingal mulya". Artinya, biarlah di
Jakarta jadi pengemis, asalkan di desa tampak sejahtera.
Falsafah hidup seperti ini, menurut lurah Kreyo, dijadikan
kebanggaan. Keluarga yang ditinggal di desa juga dengan mudah
mencari utang, dengan jaminan dibayar menunggu kiriman dari
Jakarta.
Bambang Nurcahyo, agen bis malam jurusan Pemalang-Jakarta bisa
memastikan penduduk yang mencarter bisnya itu adalah para
pengemis di Jakarta. Bahkan ia menyebutkan tak cuma Desa Kreyo,
juga penduduk Desa Warung Pring, Rembul, Gombong Kembaran dan
Sedayur (semuanya di wilayah Kecamatan Randu Dongkal) menjadi
pengemis di Jakarta. "Yang terbanyak memang penduduk Kreyo,"
kata Bambang. Lebaran tahun lalu, empat bis yang dicarter
semuanya pakai AC, yang saat itu lagi model. Sekarang selain
empat bis biasa, ada pula yang mencarter colt.
Penduduk yang pulang kampung dan tengah asyik menikmati Hari
Raya itu tak suka diwawancarai. Mereka selalu menghindar.
Khudori, 29 tahun, salah seorang dari mereka yang pulang,
membantah hidup sebagai pengemis di Jakarta. Ia bersama 20 "anak
buahnya" mengaku bekerja sebagai pengrajin tas sejak 1977. Tapi
ia tak menyebutkan di daerah mana dan berapa besar usaha itu.
Ditanya berapa penduduk Kreyo yang pulang Lebaran dari Jakarta,
ia menyebut, "sekitar 500 orang". Menurut Khudori, mereka
kembali ke Jakarta, "segera setelah Hari Raya."
Untuk mengusut benar tidaknya penduduk Kecamatan Randu Dongkal
menjadi pengemis di Jakarta, tidaklah mudah. Perkampungan
pengemis di Jakarta yang diduga menjadi pangkalan orang Pemalang
ini terletak di Simprug, Kelurahan Grogol Selatan. Selain itu
juga di rumah-rumah bedeng Pasar Prumpung, Cipinang Besar.
"Perkampungan" itu sendiri begitu tertutup, bahkan terkesan
angker.
Asrama pengemis di Simprug termasuk wilayah RW 04 Kelurahan
Grogol Selatan. Ketua RW, M. Rosyid Hadiyanto dengan nada tinggi
berkata, "siapa bilang di daerah kami ada pengemis?" Yang benar
menurut Rosyid, ada sekelompok penduduk yang tinggal di daerah
pinggiran RW 04 yang tidak jelas pekerjaannya. "Di hadapan
pengurus RW dan RT mereka tak mau dikatakan pengemis -- siapa
sih yang mau dikatakan pengemis?" ujar Rosyid.
Rosyid yang bekerja di Departemen PU menyebutkan, kelompok
masyarakat itu hidup tertutup, tidak mau berkumpul dan ngobrol
dengan warga lain. Karena pendidikan mereka rendah, pengurus RW
sulit memberikan penerangan tentang prosedur tinggal di Jakarta.
Menjelang Lebaran baru lalu, berbarengan dengan operasi pengemis
di Jakarta, pengurus RW 04 mulai mendata mereka. Ternyata memang
hampir semuanya tak memiliki surat jalan, apalagi surat pindah.
Mereka mengaku dari Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Tetapi ketika
rombongan DPRD DKI meninjau perkampungan yang padat itu April
lalu, mereka mengaku dari Pemalang. Rumah dinding gedek dan
papan yang mereka huni disewa cukup mahal, Rp 500 sehari. Namun
Tinah, ibu 2 anak balita yang ditemui TEMPO sebelum Lebaran,
menyebutkan rata-rata penghasilannya sekitar Rp 4.000 sehari.
Kerja di mana? "Ya minta-minta," katanya. Penghuni di sana
rata-rata memiliki radio kaset yang cukup baik.
Di Pasar Prumpung, Cipinang Besar, para pengemis ini membayar
sewa bedeng berukuran 3 x 3 meter Rp 400 per hari. Kehidupan
mereka pun lumayan, ada perabotan rumah tangga yang dicicil.
Bahkan ada yang punya tv. Ny. Ratmi, ibu enam anak yang semuanya
mengemis, termasuk suammya, setiap hari membayar cicilan Rp
1.400 untuk seperangkat alat-alat dapur. Keluarga ini menyewa
dua kamar.
Galib, kakek berumur 76 tahun, juga sedang mencicil radio dan
tempat tidur. Setiap hari ia menyisihkan Rp 1.100 untuk
disetorkan ke pemilik rumah, Haji Ibrahim Zahri, yang sekaligus
mencicilkan barang. Para pengemis ini rata-rata berpenghasilan
Rp 2.000. Ditemui TEMPO sebelum Lebaran Galib dan teman-temannya
mengaku akan mudik dengan mencarter truk. Kemana? "Ke Brebes,"
jawabnya.
Pengemis asal Brebes juga terkenal di Bandung. Mereka menghuni
perkampungan di Kelurahan Cipedes, Bandung. Persisnya di Kampung
Cibarengkok. Ketua RT 09 yang mewilayahi asrama pengemis ini,
tak tahu persis berapa jumlah mereka. "Selain tidak lapor,
mereka terus bertambah dan sering berganti-ganti," kata Maman,
ketua RT 09.
Luas perkampungan pengemis itu tak lebih dari 4.000 m2. Rumah
petak dibangun sendiri oleh keluarga pengemis, sementara
tanahnya disewa dari penduduk setempat. "Mereka mengemis, dari
anak-anak sampai kakek-kakek," ujar Ny. Maman, istri ketua RT
yang kebetulan rumahnya dekat kompleks itu. "Tetapi mereka tak
mengaku sebagai pengemis."
Mereka berangkat dari rumah berpakaian yang baik, di jalan baru
diganti pakaian "dinas" yang compang-camping. Penghasilannya,
menurut Ny. Maman, tak kurang dari Rp 6.000 sehari. "Saya sering
dengar mereka ngobrol, kalau dapat Rp 1.500 mereka bilang bukan
duit. Di rumah mereka rata-rata ada tv, radio kaset, jam
dinding. Mereka lebih kaya dari kita," kata Ny. Maman pula.
"Setiap mereka pulang kampung menjelang Lebaran, bawa uang lebih
dari Rp 300.000."
Seperti halnya di Simprug dan Prumpung, Jakarta, penghuni
kampung pengemis Cibarengkok ini juga sangat tertutup. Banyak
yang meragukan mereka berasal dari Brebes, karena tak pernah
bisa menunjukkan desa asalnya yang persis. "Mereka menyebutkan
Brebes karena Kabupaten Brebes lebih tandus, sementara logat
Tegal tak bisa dihindari," kata seorang pengurus RW 11 Kelurahan
Cipedes yang mewilayahi kampung ini. Pengurus RW ini menduga,
"pengemis itu dari Pemalang, entah kecamatan mana".
Adakah mereka juga dari Kecamatan Randu Dongkal, Pemalang?
Entahlah. Tapi yang pasti, mereka bangga setiap pulang ke
kampung! meski tak pernah menyebutkan nama desa itu dengan
tepat.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini