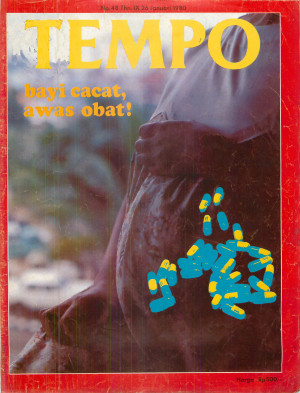PARA petani Kongsi Lima, sudah sejak 1953 lalu, menggarap areal
yang menjadi sengketa itu. Luasnya 162 Ha. Semula berupa hutan.
Pada 1943 balatentara Jepang merambahnya -- dan menanaminya
padi, kacang, guna keperluan tentaranya. Setelah Jepang angkat
kaki, rakyat memanfaatkannya. Areal itu memang rawan karena
berbatasan langsung dengan perkebunan karet milik asing,
Sandilands Buttery & Co. Di zaman Soekarno mengganyang nekolim,
1962, perkebunan asing itu mengubah namanya menjadi PT Mara
Djaja (kini Mara Jaya).
PT itu kemudian mendapat hak guna usaha (HGU) dari Menteri
Pertanian dan Agraria Agustus 1962 lalu seluas 1.030 ha di areal
eks Jepang tadi. Padahal areal yang tersedia, serti yang
disetujui Kepala Inspeksi Agraria Sumatera Utara, hanya 802
saja. Maka pihak perkebunan pun lantas menoleh areal 162 ha yang
sudah didiami 90 KK penduduk. Penduduk bertahan.
Enam tahun kemudian, Oktober 1968, Agraria Sumatera Utara
menetapkan areal perkebunan Mara Jaya seluas 1030 ha. Dengan
begitu areal 162 ha milik penduduk pun dengan sah dikuasai pihak
perkebunan. Desember 1969, Bupati Deli Serdang dan Panitia
landreform Deli Serdang menyetujui pembayaran ganti rugi
tanaman penduduk.
Pengadilan
"Kami sudah bayar ganti rugi tahun 1969 itu," ujar Teuku Syamsul
Bahri, Direksi PT Mara Jaya pekan lalu di rumahnya, Jalan
Diponegoro, Medan, "tapi belakangan tanah itu mereka garap
lagi." Ganti rugi itu memang dibenarkan Paeran, salah seorang
pemuka Kongsi Lima. "Tapi caranya dengan kekerasan. Kami
ditangkapi dulu, lalu dibawa ke kantor polisi Bangun Purba,"
ungkap Paeran.
Cerita Paeran: waktu itu, sementara para lelaki ditahan polisi,
petugas perkebunan membongkar rumah dan tanaman penduduk sampai
3 hari. Setelah selesai, penduduk yang ditahan dilepas. Mereka
disuruh menuju kantor perkebunan, katanya untuk mendapat ganti
rugi rumah dan tanaman. Di antara mereka, hanya Paimun, kepala
lorong, yang mendapat ganti rugi paling besar yaitu Rp 30.000.
Yang lain rata-rata cuma Rp 3.000 saja.
Pihak perkebunan kemudian menyatakan akan menampung penduduk
yang tergusur, tapi ternyata tidak dipenuhi. Karena ternyata PT
Mara Jaya menunjuk areal yang sudah berpenghuni. "Akibatnya kami
berpencar di beberapa desa, menumpang di rumah famili," tutur
Paeran lagi. Tapi memang ada beberapa orang yang kebagian di
areal penampungan yang 50 ha itu.
Tapi pada 1977, PT Mara Jaya menggugat penduduk lewat
pengadilan. Tuduhannya: areal penampungan yang 50 ha itu sudah
berkembang menjadi 63 ha karena penduduk menggarap tanah-tanah
sekitarnya. Dan pengadilan memenangkan gugatan itu. "Herannya
pengadilan memutus vonis tapi areal yang dimaksud tidak jelas,"
kata Paeran lagi dengan lancar.
Pada tahun yang sama penduduk balik menggugat Mara Jaya lewat
pengadilan mengenai areal 162 ha yang dicaplok perkebunan itu.
Gugatan sudah masuk tapi penduduk yang menggugat tak pernah
dipanggil pengadilan. Usaha lain ditempuh mengadu kepada
bupati, Muspida, dinas agraria, DPRD. Hasilnya: berkali-kali
mereka dipanggil ke kantor polisi, Kodim, Korem. Dan soal tanah
itu tak kunjung beres-beres juga.
Padahal areal 162 ha itu jelas berada di luar areal perkebunan.
Peta konsesi perkebunan yang dikeluarkan Direktorat Agraria
Sum-Ut mencantumkan areal tersebut berada di luar konsesi.
Begitu pula bunyi surat Kepala Desa, Camat dan laporan tim
agraria yang pernah meninjau ke sana.
Juga ada surat dari PT Mara Jaya yang menyatakan bahwa areal 162
ha itu memang benar di luar konsesi perkebunan mereka sesuai
dengan HGU. Surat itu bernomor BR/X/39/64, 12 September 1964.
Ditujukan kepada Camat Bangun Purba, surat itu ditandatangani
oleh salah seorang pimpinan Mara Jaya, Choo Kim Huat, lengkap
dengan stempel perusahaan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini