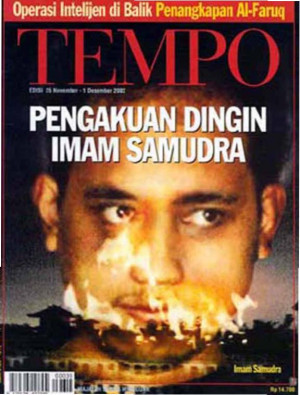Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Eh ujan gerimis aje
Ikan bawal diasinin
Si Romlah menangis aje
Bulan Syawal dikawinin…(Pantun Betawi)
Krisis moneter seolah cuma numpang lewat. Janur kuning melengkung pertanda pesta muncul di mana-mana, di mulut-mulut gang sempit Jakarta, di perempatan jalan yang disesaki motor para pengojek, sebelah-menyebelah dengan spanduk ajakan salat Ied yang mulai lusuh berdebu. Itulah suasana khas pada bulan Syawal, saat orang Betawi umumnya hanyut dalam ritual dua pesta sekaligus: Lebaran dan perkawinan. Syawal adalah musim kawin.
"Dunie ude penyok begini, tapi orang tetep aje pesta kawinan," kata Ahmad dalam logat Betawi tengah yang medok.
Ahmad, 68 tahun, tidak sedang meratapi ironi. Pesta perkawinan justru berkah bagi dia dan grup marawisnya—kelompok musik tradisional Arab yang sudah dibetawikan. Bagi Ahmad, Syawal kali ini mungkin akan menjadi musim panen seperti bulan Ruwah lalu, sebelum Ramadan. Ketika itu Ahmad dan kelompoknya yang bermarkas di bilangan Kalibata, Jakarta Selatan, harus dibuat sibuk dengan jadwal manggung yang ketat.
Menjelang Ramadan lalu, beberapa hari berturut-turut kelompok itu tampil dalam tiga pesta perkawinan sekaligus. Setelah mengeluarkan empat lagu ketika mengarak pasangan pengantin di Condet, Jakarta Timur, mereka harus cepat-cepat angkat kaki buat meramaikan upacara lain di Kali Malang. Lantas, selang beberapa jam istirahat, keesokan harinya mereka harus siap meladeni pengantin lain lagi di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta Pusat.
Pesta perkawinan setelah Lebaran memang tak sebanyak saat sebelum Ramadan, tapi cukup membuat dapur para pengarak kembali ngebul. Tidak jadi masalah jika selama Ramadan mereka terpaksa menggantung alat musiknya, lantaran aneh orang kawin pada bulan Puasa. Yang penting, permintaan ngarak pengantin mulai berdatangan lagi. Dalam satu pekan selama Syawal, setidaknya tiga kali mereka bisa beraksi.
Ahmad, yang pernah bekerja sebagai sopir di perusahaan penerbangan PT Garuda Indonesia, mengaku bisa menghidupi keluarga hingga anak-cucu dengan mengandalkan the art of marawis itu. Ahmad tidak sendirian. Bersama antara lain empat bersaudara—Taha, Ama, Ucen, dan Kamal yang sejak masih ingusan telah akrab dengan marwas, dia membentuk kelompok musik dua belas orang yang praktis menggantungkan hidup pada perkusi yang khas itu.
Marwas adalah gendang berkerangka kayu, berdiameter 15 sentimeter dan setebal 10 sentimeter, yang kedua permukaannya diselimuti kulit kerbau, sapi, atau kambing. Ciri khas marawis terletak pada bagaimana marwas ditabuh dengan tangan kosong. Nada ritmis yang energetik muncul karena para pemain menggunakan Arabian scale, satu oktaf terdiri dari 24 nada sehingga jarak antara satu nada dan lainnya hanya seperempat_-bandingkan dengan musik Barat yang berjarak setengah nada dan punya 12 nada dalam satu oktaf.
Dalam marawis, gendang itu menjadi satu-satunya jenis alat musik. Tapi marwas sebenarnya juga kerap dikerahkan dalam sebuah pertunjukan orkes tradisional Betawi yang disebut zafin. Menyajikan napas irama dinamis, zafin memadukan permainan biola, suling, marwas, dan gambus. Yang terakhir ini sering disebut 'ud dalam perbendaharaan musik Arab.
Sebagian besar pemain marawis umumnya lihai pula memainkan zafin, sehingga mereka bisa memiliki pendapatan tambahan. Penabuh marwas seperti Ucen, yang sehari-hari berprofesi sebagai makelar mobil, mengaku lebih tenteram karena bisa mendapatkan sumber nafkah lain dari bermain marawis dan zafin. Demikian pula dengan Fauzi, yang sehari-hari bekerja sebagai karyawan sebuah yayasan pendidikan sosial; atau Hasyim, seorang sopir pribadi.
Setiap kali ngarak, kelompok ini memperoleh imbalan Rp 400-500 ribu, yang akan mereka bagi rata tanpa membeda-bedakan pemimpin atau anak buah, senior atau junior. Maka, seperti perilaku mereka dalam kelompoknya yang demokratis-egaliter itu, kepada para pelanggan pun mereka fleksibel. Honor yang mereka pasang biasanya bukan harga mati. Untuk kerabat dekat yang membutuhkan, mereka siap potong harga. Kalau perlu gratis.
Dunia terus berputar. Toh, walaupun warna Kali Ciliwung tak lagi jernih seperti Betawi tempo doeloe, dan kesenian tradisional macam gambang kromong kalah bersaing dari dangdut yang menjadi primadona dunia rekaman, marawis tetap bertahan dengan segala keterbatasannya. Marawis lestari turun-temurun.
Ahmad dan kawan-kawan tak mengenal sekolah marawis, tak mengerti partitur, apalagi menguasai teori musik yang njlimet. Mereka menyaksikan, dan kemudian mempraktekkan, cara-cara paman, ayah, atau sepupu yang usianya lebih tua menepuk marwas.
Seumur-umur Ahmad tak pernah menyesal bersentuhan dengan marawis di bawah bimbingan seorang guru istimewa: Alwi, ayahnya sendiri. Berkat sang ayah, dia kini dipercaya kelompoknya memegang hajir, gendang lebih besar yang punya peran sentral dalam mengatur irama pemain marwas lain. Ada nada kagum, bangga, dan nostalgis setiap kali Ahmad bercerita bagaimana grup-grup zafin ternama pada 1950-an bersaing mendapatkan ayahnya, seorang penepuk marwas yang tersohor kala itu. Memang, dalam jenis musik apa pun, perkusionis hebat sering dilirik orang.
Sementara itu, Hasyim masih duduk di bangku sekolah dasar, berambut keriting-berperawakan kecil, ketika pertama kali tampil menepuk marwas di antara kerumunan orang dewasa dalam pesta-pesta kawin di bilangan Pasar Minggu, awal 1970-an. Hasyim, Ucen, dan Taha tidak mempunyai ayah yang menularkan kepiawaian menepuk marwas kepada anak-anaknya. Mereka belajar dari seorang paman.
Dari proses yang mengalir seperti air ini mulailah mereka memahami tradisi marawis, lengkap dengan kelihaian menyanyikan lagu wajib seperti Syarrul-leil. Masuk dalam golongan syarah—nada gembira yang bergerak dengan birama 6/8—lagu itu biasa dipakai untuk mengiringi pengantin.
Selain itu, mereka juga menghafal luar kepala syair-syair zhohifeh yang berisi pujian kepada Rasulullah, seperti dalam lagu Ya Salam. Lagu ini, dengan birama 4/4, umumnya disajikan dalam acara Mauludan untuk memperingati Nabi Muhammad. Bernyanyi diselingi teriakan pemanas suasana yang dilepas pada saat yang tepat—malah sewaktu-waktu bersahut-sahutan—mereka kerap menggunakannya sebagai senjata untuk menutupi kesalahan kawan main. Di samping zhohifeh dan syarah yang riang, masih ada zafin yang biasa dipakai untuk mengiringi tarian pergaulan yang mengutamakan derap kaki.
Apa sih yang sebenarnya bisa disumbangkan marawis dalam upacara-upacara perkawinan? Lagu seperti Syarrul-leil atau Pantun Pengantin jelas bukan komposisi anggun seperti The Wedding March karya komponis Felix Mendelssohn Bartholdi, yang biasa dipakai mengiringi langkah pengantin mendekati altar gereja. Sebaliknya, dengan bermodalkan sebaris melodi sederhana, paling-paling cuma beranggotakan empat hingga lima nada yang dimainkan naik-turun, lagu itu lebih menyajikan suasana riang ketimbang syahdu. Suasana tegang justru menjadi cair. Apalagi bila permainan sinkopasi—tepukan jatuh di antara dua ketukan yang rumit dan gampang bikin orang terpeleset itu—ikut dimunculkan.
Salah satu kemampuan marawis memang justru menimbulkan suasana yang tidak formal, mengendurkan tensi, menghalalkan pretensi untuk sedikit main-main, dan tidak membuat dirinya eksklusif di antara para tamu. Tanpa memperhitungkan kualitas suara, dan tanpa pembagian suara secara sistematis, semua pemain dipersilakan bernyanyi mengikuti melodi dasar dalam satu suara. Dan mereka dianjurkan memekik pada timing yang pas sekadar untuk menularkan kemeriahan.
Bagaimanapun, marawis adalah bagian dari sebuah tradisi yang turun-temurun di dunia maskulin. Sedari kecil, anak lelaki dikasih dorongan, dibukakan kesempatan lebar-lebar untuk menabuh marwas. Sedangkan kalangan perempuan hanya menyaksikan dari jauh sebagai penonton. Sesekali kaum perempuan memang berjoget mengikuti irama syarah dan zhohifeh_-dan respons seperti ini merupakan sesuatu yang menimbulkan satu kebanggaan tersendiri bagi para pemain marwas seperti Ahmad. Namun, sejauh ini belum pernah tercatat dalam sejarah seorang wanita memainkan marwasnya di muka umum dan untuk konsumsi umum.
Tapi inilah dunia yang berubah cepat. Di sebuah pengajian di bilangan Kalibata, tanpa banyak gembar-gembor, Ucen melangsungkan sebuah perubahan besar dalam belajar-mengajar marawis. Ilmu menepuk marawis tak lagi diajarkan melalui jalan tradisional: diwariskan turun-temurun melalui tradisi keluarga. Ucen mengajar kelas marawis, kegiatan "ekstrakurikuler" di pengajian itu. Namun, yang mengejutkan bukanlah masalah kelas itu. Murid-murid Ucen perempuan. Seperti murid lelaki, mereka juga mulai dapat menangkap irama yang memukau itu setelah berlatih selama sekitar tiga bulan. Namun tidak sama seperti rekan-rekan lelakinya, mereka tidak pernah bermimpi akan memainkan marawis di muka umum. Mereka sudah dijanjikan untuk bermain di lingkungan terbatas, sangat terbatas.
November kemarin, di kawasan Condet yang masih diselang-selingi deretan pohon pisang, pohon sawo, dan duku, Ahmad dan kawan-kawan berjalan sepanjang 30 meter sambil menari, menepuk marwas, mengantar mempelai pria muda ke rumah keluarga calon istrinya. Saat itu, Ahmad beserta delapan rekannya yang mengenakan seragam sarung langsung terjun ke lokasi ngarak.
Hari masih pagi, namun matahari musim kemarau sudah membuat tubuh berkeringat dan kening berkerut tegang. Tapi, begitu Syarrul-leil dinyanyikan bareng-bareng, marawis ditepuk bergantian, suasana seketika menjadi riuh-rendah.
Apalagi setelah Ahmad yang memegang hajir itu kelihatan bermain dengan semangat empat lima. Ahmad yang memasuki usia uzur, dengan rambutnya yang memutih perak itu, tersenyum lebar, seolah-olah ingin memperlihatkan gigi di gusi kiri dan kanannya yang mulai tanggal itu, bergoyang dan berputar-putar. Seraya menggendong dan memukul gendang besarnya di tengah rekan-rekan juniornya, Ahmad tak ubahnya seperti matahari dikelilingi planet-planet yang bergerak mengikuti garis orbitnya.
Para instrumentalis perkusi tradisional ini bukanlah sejenis artis terasing yang memelihara rambut sampai sepinggang untuk menunjukkan eksentrisitas individual yang tanpa kompromi. Profesi yang mereka geluti hampir serupa dengan profesi insinyur dan kontraktor dalam kehidupan modern, atau tukang cerita dan dukun beranak dalam kehidupan semitradisional.
Dalam diri Ahmad dan kawan-kawan sama sekali tak terdapat kesan bahwa para seniman diberi perlakuan istimewa untuk tidak dinilai dengan ukuran orang biasa. Sebab, marawis pada akhirnya hanya bagian dari rangkaian upacara perkawinan, seremoni yang sedang populer-populernya pada bulan Syawal ini.
Eh ujan gerimis aje…
Ikan bawal diasinin
Si Romlah menangis aje
Bulan Syawal dikawinin….
Idrus F. Shahab
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo