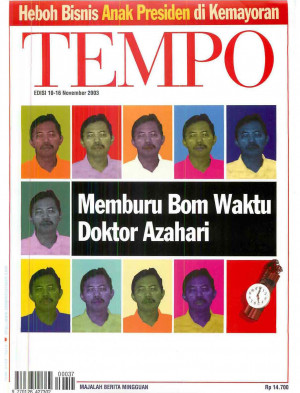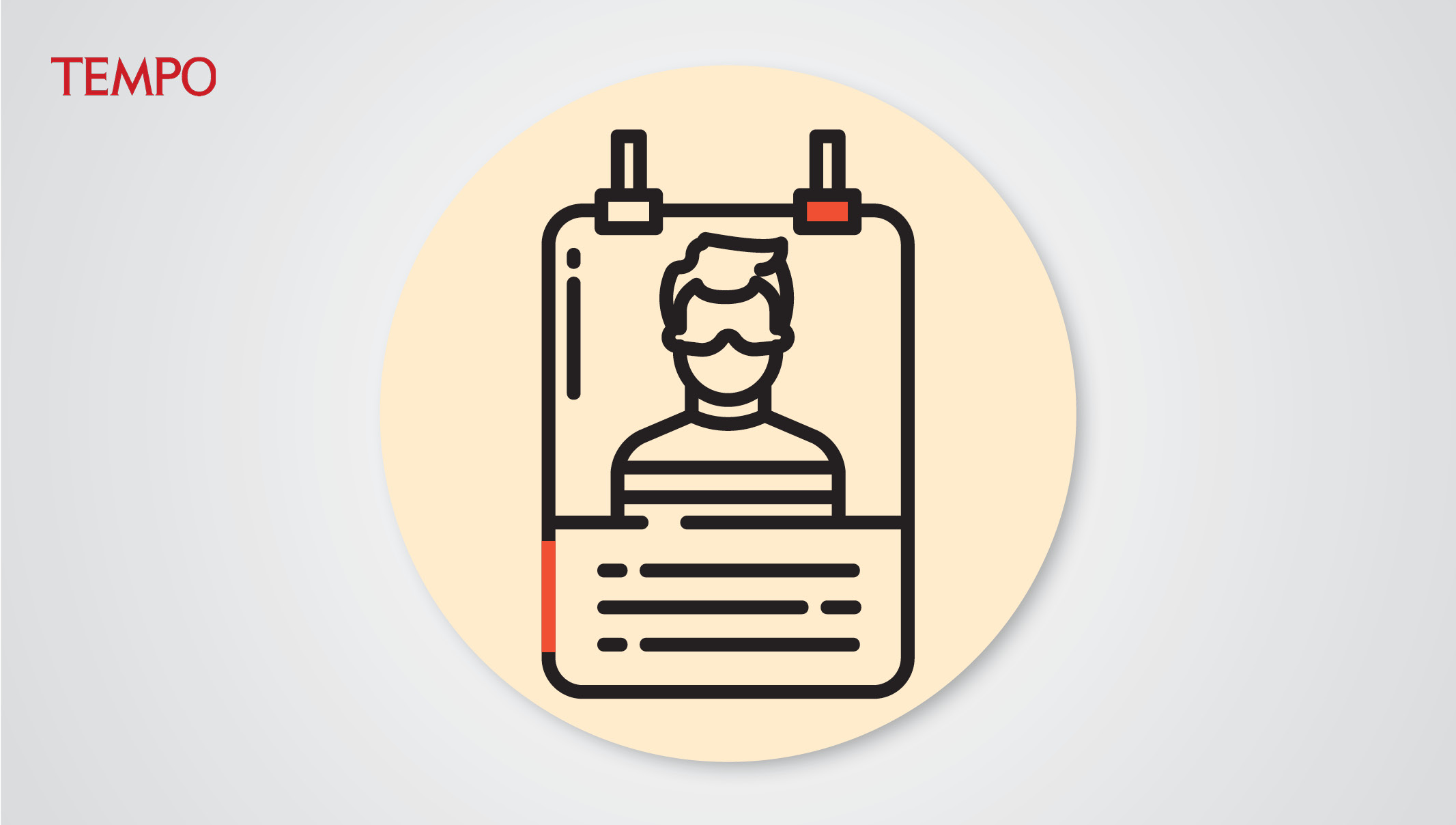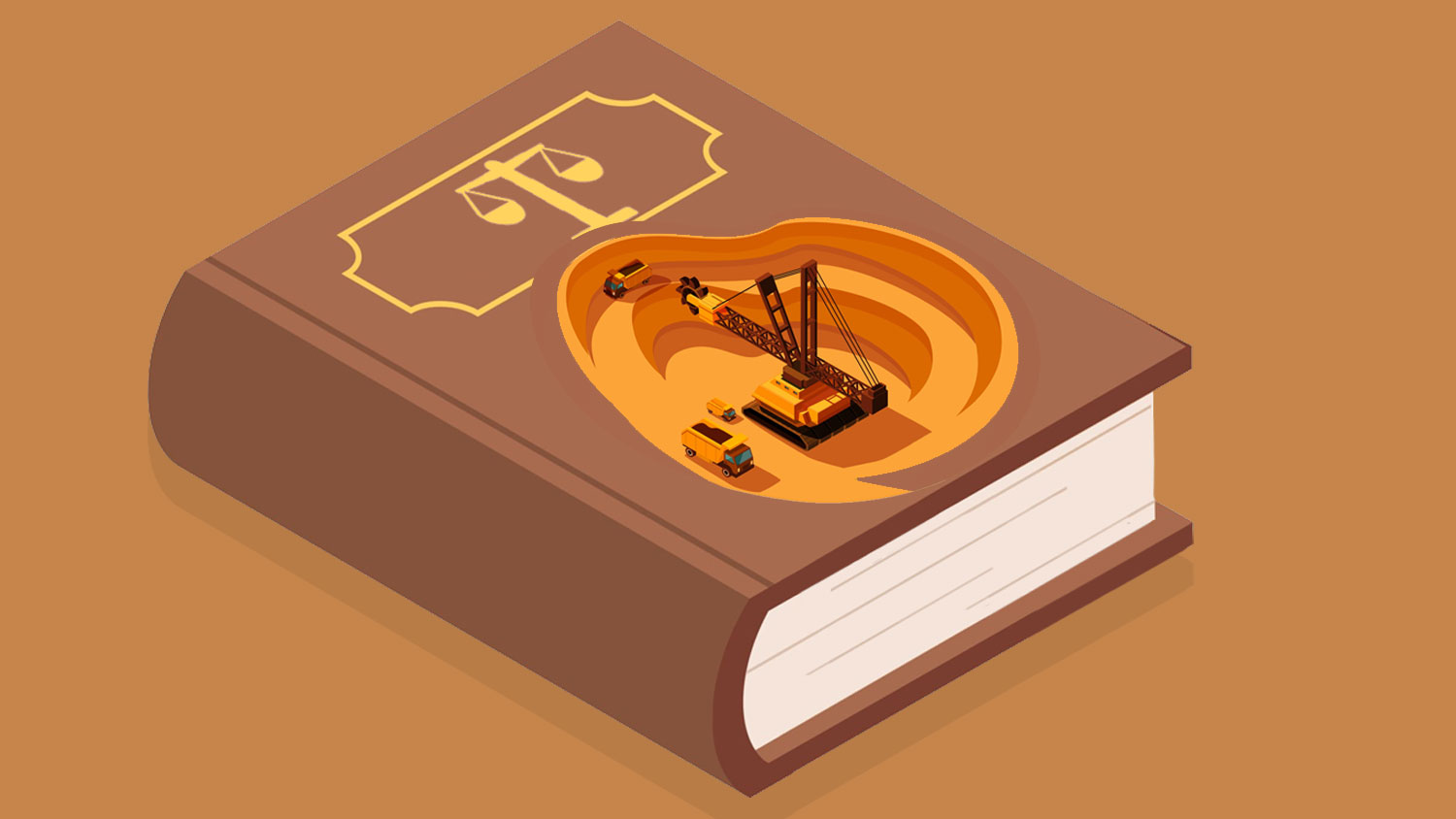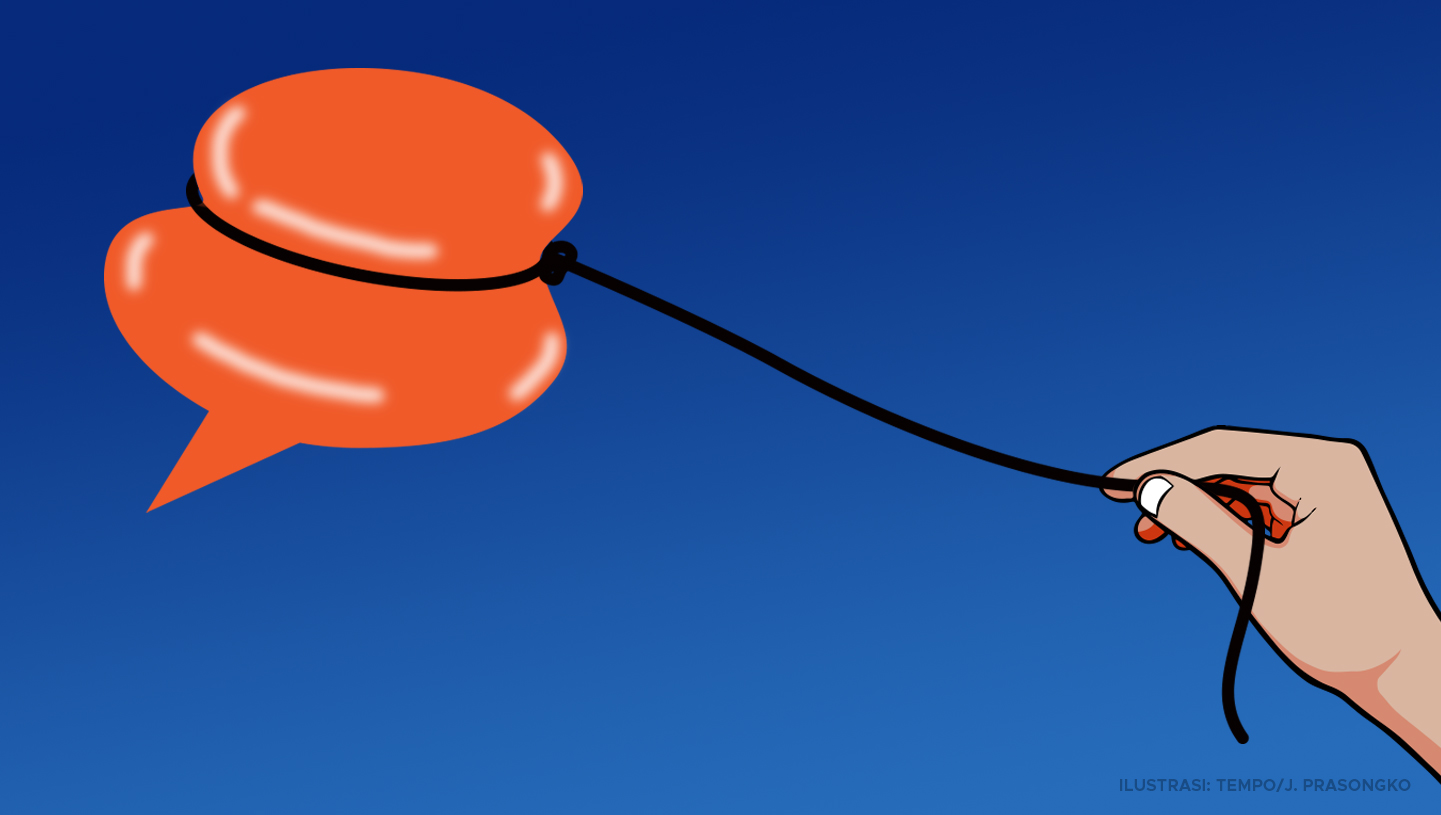Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
DUNIA Islam dan dunia Barat perlu memperbaiki kekurangan masing-masing untuk menghindari salah pengertian di antara keduanya. Kamp konsentrasi dan eksterminasi Auschwitz barangkali bisa menjadi salah satu tempat untuk memulai: cermin bagi dunia Barat dan pelajaran bagi dunia Islam dalam memahami sikap Barat terhadap Islam.
Kamp Auschwitz I dan II, yang berturut-turut terletak di Desa Auschwitz dan Birkenau, Polandia, tak pelak lagi merupakan manifestasi paling ekstrem dari wajah paling gelap kemanusiaan. Di sana, menurut catatan Museum Negara Auschwitz, 1,1 juta sampai 1,5 juta manusia, sebagian terbesar bangsa Yahudi, mengalami dehumanisasi yang paling radikal sebelum akhirnya tewas karena penyakit, kelaparan, kelelahan, dieksekusi, atau secara massal digiring ke kamar gas untuk menghirup gas beracun Cyclone B (hydrocyanic acid).
Auschwitz I, yang di pintu gerbangnya secara diabolik terpampang tulisan "arbeit macht frei" (kurang-lebih berarti "kerja akan membebaskanmu"), merupakan titik akhir dari rencana final solution-nya Hitler bagi "masalah" Yahudi. Ia dirancang dengan teliti. Efisiensi pun dipikirkan masak-masak sebagaimana layaknya sebuah pabrik berteknologi tinggi. Misalnya saja, kamar gas digunakan sebagai sarana pembunuhan yang murah, bersih, dan massal, lalu ruang kremasi dirancang bersebelahan dan memiliki pintu yang langsung berhubungan dengan kamar gas untuk memudahkan pemusnahan mayat seusai pembunuhan dengan gas.
Namun, dengan efisiensi yang sedemikian tinggi pun, kamp ini segera menjadi terlalu kecil dengan datangnya kargo manusia secara nonstop dari semua penjuru Eropa. Tungku kremasi yang ada tak mampu berpacu dengan jumlah mayat yang harus dimusnahkan. Karena itu, Auschwitz II, yang lebih besar, lebih canggih, dan lebih efisien, dibangun kurang dari dua tahun kemudian di Birkenau, hanya tiga kilometer dari Auschwitz I.
Tahun lalu, saya berkunjung ke sana bersama beberapa teman dari berbagai bangsa, negara, dan agama. Dalam perjalanan keluar-masuk gedung-gedung, lorong-lorong, dan ruang-ruang di dalam kamp yang kini menjadi museum negara tersebut, kami bungkam seribu basa. Tak ada yang berkomentar. Sebab, setiap komentar rasanya begitu tidak relevan di hadapan bayang-bayang penderitaan penghuni kamp. Yang ada hanya beban berat menggelayut dalam benak.
Beban yang datang tidak hanya dari empati yang dalam terhadap korban, tapi juga dari kengerian bahwa spesies manusia—kita termasuk di dalamnya—mampu melakukan kekejian ini. Juga dari kemusykilan atau absurditas paradoks modernitas yang ada di hadapan kita: sains dan teknologi yang merupakan puncak prestasi rasionalitas manusia digunakan untuk melampiaskan impuls-impuls dan prasangka yang paling keji; mesin dan birokrasi paling canggih pada zamannya sebagai buah-buah aufklärung/enlighment atau masa pencerahan menjadi alat pemusnah manusia.
Barangkali memang sulit memberikan reaksi yang manusiawi untuk Auschwitz. Sebab, apa yang berlangsung di sana lebih dari setengah abad yang lalu memang memporakporandakan segala ukuran mengenai yang manusiawi dan yang tidak manusiawi. Apa yang berlangsung di sana bukan manifestasi dari kejahatan biasa, melainkan ekspresi dari—meminjam istilah Hannah Arendt—the radical evil.
Auschwitz memang sangat radikal. Di sana hal-hal yang biasanya hanya dialami manusia dalam situasi ekstrem—seperti kelaparan, kekejaman, dan kematian—menjadi pengalaman sehari-hari dan biasa. Yang ekstrem menjadi normal. Auschwitz telah menjadi keekstreman itu sendiri. Dikirim ke Auschwitz sama dengan dijebloskan ke lorong yang merosot pasti menuju kemusnahan. Dalam lorong ini, manusia, sebelum secara fisik dimusnahkan, mengalami suatu proses degradasi fisik, psikologis, dan moral yang, setelah satu situasi batas tertentu terlampaui, berujung pada hilangnya kemanusiaan itu sendiri.
Tawanan yang tak cukup cepat menyesuaikan diri dengan kondisi dan kehidupan kamp akan segera melampaui situasi batas ini. Hidup mereka dalam kamp pendek, tapi mereka terus mengalir dalam jumlah yang banyak. Merekalah yang secara konstan berakhir di dalam kamar gas. Mereka ini menghuni titik paling ekstrem dari keekstreman Auschwitz. Secara fisik mereka tinggal sebagai seonggok fungsi-fungsi fisik dalam denyut-denyut terakhirnya. Secara psikologis mereka tak mampu lagi bereaksi secara emosional. Secara moral mereka tak dapat membedakan baik-buruk, benar-salah.
Mereka adalah mayat hidup yang sudah kehilangan cahaya ilahiah. Tak punya lagi semangat untuk survive, mereka tampil fatalistik. Mayat-mayat hidup yang ditakuti sekaligus dibenci oleh setiap penghuni dan petugas kamp ini punya nama. Mereka dijuluki der muselmann atau muslim. Julukan ini cukup menyebar walau ada pula kata lain yang dipakai di kamp lain, misalnya keledai (di Majdanek), kretin (di Dachau), unta (di Neungamme), dan sheikh yang lelah (di Buchenwald).
Barangkali karena atmosfer "politically correct" hari ini, kata der muselmann tidak kita temukan di dalam museum. Namun ada sejumlah literatur serius yang membahasnya (Amery, 1980; Levi, 1986; Sofsky, 1997; Kogon, 1979). Ini karena gambaran manusia dalam situasi batas antara hidup dan mati serta antara manusiawi dan tidak manusiawi ini memang telah banyak mengundang telaah medis, psikologis, antropologis, politik, hukum, etika, dan filsafat. Yang kurang mendapat perhatian adalah mengapa Islam/muslim diasosiasikan dengan kondisi ini. Apa latar belakangnya?
Ada beberapa penjelasan menurut Agamben (1999). Dalam Encyclopedia Judaica, di bawah istilah muselmann, kita temukan penjelasan sebagai berikut: "dipakai terutama di Auschwitz, istilah ini tampaknya berasal dari sikap para tawanan tertentu, yaitu membungkuk di lantai, kaki ditekuk gaya Oriental, wajah kaku bagai topeng." Penjelasan lainnya mengasosiasikan "gerakan-gerakan yang khas... gerakan bergoyang-goyang dari tubuh bagian atas" dengan ritual salat orang Islam. Namun penjelasan yang paling mungkin berkaitan dengan arti harfiah kata "muslim" itu sendiri, yaitu mereka yang pasrah tanpa syarat terhadap kehendak Tuhan. Arti inilah rupanya yang menjadi dasar mitos mengenai fatalisme Islam, suatu mitos yang dalam menghunjam di kebudayaan Eropa sejak Abad Pertengahan. Karena itulah kita temukan penjelasan Kogon (1979) berikut ini: (di dalam kamp) "the relatively large group of men who had long since lost any real will to survive... were called 'Moslems'—men of unconditional fatalism" ("kumpulan manusia yang cukup banyak yang telah lama sekali kehilangan kehendak untuk hidup... diberi nama 'muslim'—mereka yang mengidap fatalisme total").
Latar belakang penggunaan kata "muslim" di kamp konsentrasi ini tak pelak lagi merupakan proyeksi dari imaji yang sangat negatif dunia Barat terhadap Islam yang sama sekali tak ada hubungannya dengan realitas. Yang pasti, pada tahun-tahun itu tak ada suicide bombers yang menjadi prototipe dari citra mengenai fatalisme Islam hari ini.
Lalu apakah latar belakang semacam ini masih mendikte pandangan dunia Barat mengenai Islam hari ini? Menarik hubungan langsung begitu saja di antara keduanya tentunya merupakan kesembronoan. Barangkali mahasiswa muslim yang banyak belajar Islam di universitas-universitas Barat perlu pula merunut pandangan Barat terhadap Islam secara serius dan historikal. Dunia Islam perlu tahu dan mempelajari hal ini agar tak selalu terkejut dan menjadi reaktif dalam menghadapi citra negatif Islam yang datang dari dunia Barat.
Selain itu, kajian yang mendalam mengenai hal ini diperlukan, agar tak selalu terjebak dalam teori konspirasi dalam menjelaskan benturan antara dunia Islam dan dunia Barat. Sebab, dengan mitos yang begitu negatif, tidak perlu ada konspirasi untuk melahirkan segala macam bias negatif mengenai Islam dan muslim. Memahami hal ini membuat dunia Islam lebih produktif dalam memerangi citra negatif Islam atau muslim serta dalam berdialog dengan dunia Barat.
Sebaliknya, dunia Barat dapat menggunakan "muslim di Auschwitz" sebagai cermin untuk menimbang seberapa besar pandangan mereka terhadap Islam dan muslim berpijak pada realitas dan seberapa besar berpijak pada mitos. Diperlukan kejujuran dan kerendahan hati dalam hal ini yang kadang-kadang sulit terlahirkan. Perlu diketahui, hanya 45 menit dengan mobil dari Auschwitz, di Kota Krakow, kita dapati contoh warisan kebudayaan Islam yang jelas-jelas bertentangan dengan mitos fatalisme. Di kota ini berdiri Universitas Jagiellonian, salah satu universitas tertua di Eropa (berdiri pada 1364). Di tempat Copernicus belajar ini kita dapat melihat sejumlah astrolab dan peralatan astronomi Abad Pertengahan lainnya bertuliskan huruf dan angka Arab. Tak pelak lagi ini merupakan warisan peradaban Islam yang tidak saja bertentangan dengan citra yang fatalistik, tapi juga penuh optimisme dalam mengeksplorasi alam semesta.
Toh, jarak yang dekat ini tak mampu mengoreksi mitos tadi. Barangkali semangat memerangi terorisme global kali ini juga perlu disertai ketulusan hati untuk mengikis mitos itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo