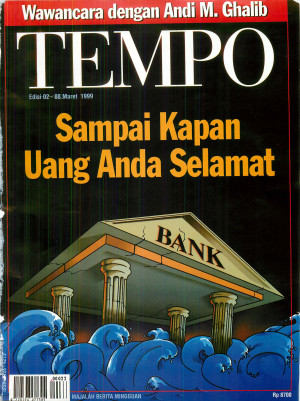TIDAK mudah memilih, memang. Untuk mengatasi krisis perbankan, pemerintah harus melikuidasi sejumlah bank yang buruk dan memperbaiki permodalan bank yang lolos ujian. Dalam rekapitalisasi ini dana publik akan dimasukkan. Apa boleh buat, dalam krisis ekonomi ini dana swasta sedang seperti sumur yang kering. Walhasil, nanti praktis pemerintahlah—sebagai wakil publik—yang akan berperan sebagai pemilik utama bank-bank di Indonesia.
Dalam arti tertentu, ini adalah "pe-negara-an" satu sektor perekonomian yang penting. Indonesia sudah mengalami buruknya kehadiran para birokrat dalam pengambilan keputusan bisnis. Maka persoalan yang akan terjadi nanti ialah bagaimana melepaskan kendali pemerintah di dunia perbankan, sementara posisinya demikian sentral.
Membuka pintu bagi swasta untuk menjadi pemilik merupakan pilihan yang bagus. Tetapi, soalnya, swasta yang mana. Dalam pemerintahan Habibie cukup kuat kecenderungan bahwa kalangan swasta "pribumi"-lah yang harus dapat prioritas. Orang seperti Menteri Adi Sasono punya argumen, bahwa justru hubungan antara yang "pribumi" dan keturunan Tionghoa bisa tetap rawan bila Indonesa tak menerapkan kebijakan affirmative action mirip Malaysia.
Argumen ini layak didengar. Sejak kebijakan perekonomian yang mengutamakan "bumiputra" di Malaysia diterapkan, memang bisa dibuktikan bahwa tidak ada lagi kerusuhan rasial di Malaysia seperti tahun 1968. Tapi bukan hanya karena itu kerusuhan rasial tak terjadi lagi di sana. Di Malaysia, partai politik, yang memberi kesempatan kepada semua kelompok ras, lebih hidup. Lembaga peradilan masih berwibawa. Tak adanya proses politik yang hidup dari bawah, dan tidak adanya lembaga peradilan yang berwibawa—yang tidak mudah disogok dan digertak—itulah yang menyebabkan persengketaan di Indonesia tidak dikelola dengan cepat dan melalui jalan hukum.
Meniru cara Malaysia juga punya risiko yang lebih besar di Indonesia. Orang pemerintah yang harus mengelola kebijakan perbankan kelak—siapa pun mereka—telanjur tak meyakinkan. Mereka mungkin jujur, tetapi kata "KKN" belum habis beredar dalam percakapan di Indonesia. Kini, misalnya, banyak yang curiga besarnya pengaruh koneksi pengusaha Aburizal Bakrie dan pemerintah (atas nama "pribumi") dalam pengambilan keputusan dalam masalah perbankan. Ini menunjukkan tipisnya kepercayaan masyarakat kepada bersihnya proses pengambilan keputusan itu. Tipis pula keyakinan bahwa pemberian keistimewaan kepada swasta (baik "nonpri" maupun "pri") tidak akan melahirkan ekonomi yang tak efisien dan mahal di ongkos. Krisis ekonomi kini membuktikan bencana yang bisa terjadi karena moral hazard itu: sikap manja dalam berbisnis.
Tentu, tujuan untuk memperbaiki pengusaha menengah dan lemah ("pribumi") itu baik. Tapi "tujuan menghalalkan cara" bukan saja buruk secara moral, juga bisa merusak hasil yang dituju itu sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini