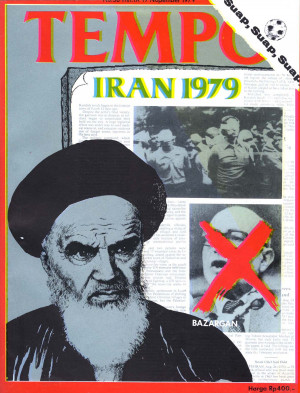MAKASAR, abad ke-17. Seorang Eropa, disebut Bapa Alexander de
Rhodes, berkunjung ke kerajaan di Timur itu.
Di sana bertahta raja Karaeng Pattengaloan. Bapak Rhodes
terkesan nampaknya. Dalam catatan perjalanannya yang kini dapat
dibaca para ahli sejarah, ia menulis bagaimana Karaeng
Pattengaloan bukan saja "teramat sangat bijak" serta "jujur
sekali", tapi juga seorang menggemari ilmu. Raja Makasar itu
fasih berbahasa Portugis, punya koleksi besar buku Spanyol,
pandai matematika dan punya catatan yang cermat tentang kejadian
dari ke hari di kerajaannya.
Banyak orang Indonesia sendiri kini yang tak kenal nama penguasa
yang mentakjubkan tersebut. Padahal Pattengaloan adalah contoh
zaman itu, tatkala kerajaan di Indonesia tumbuh di
pantai-pantai, makmur, maju, dan terbuka ke segala arah.
Di tahun 1654 misalnya, di Makasar sudah tiba sebuah teleskop
Galileo yang sangat mahal dan jarang terdapat -- hanya 45 tahun
setelah Galileo sendiri mengembangkan teknik teropong astronomi
itu. Hubungan Aceh dan Turki sudah ada di tahun 1560-an, dan
karenanya di Aceh berkembang teknologi senjata yang hebat:
meriam-meriam raksasa.
Kota-kota Indonesia, diisi oleh pribumi yang sama jangkungnya
dengan orang Eropa, juga tak kalah besar dan sibuk ketimbang
kota di Eropa. Kekayaan para saudagar dan raja-rajanya juga
mencengangkan. "Dalam hal ini, paling tidak, negara-kota di Asia
Tenggara dalam abad ke-16 dan awal 17 menyerupai Venisia, Genoa,
Antwerp dan pusatpusat lain kapitalisme Barat di masa awalnya,"
demikian tulis seorang sejarawan Australia, Anthony Reid.
Tapi, apa gerangan yang terjadi, hingga kita kini termasuk
negeri "miskin" sementara Venisia dan lain-lain itu termasuk
negeri kaya"? Anthony Reid mungkin sedikit dari sejarawan yang
mencoba mencari jawab bagi pertanyaan besar itu. Tulisannya, The
Origins of Poverty in Indoesia, yang dibacakannya dalam sebuah
seminar di Canberra bulan ini, merupakan khasanah yang memikat
di balik bahasanya yang sederhana dan tebalnya yang cuma 26
halaman.
Agak sukar memang mengikhtisarkan sejarah sekian abad. Namun
dapatlah disebut bahwa para penyerbu dari Barat, terutama dengan
cara ganas orang Belanda, berhasil memukul kota kerajaan di
pantai-pantai itu. Rupanya dengan teknologi yang cukup
sekalipun, mereka tak siap buat berperang. Cara perang kerajaan
Asia Tenggara adalah cara perang yang menghemat jiwa manusia,
karena penduduk masih jarang dan tenaga sangat berharga.
Sementara itu serbuan bangsa Belanda belum pernah ada duanya,
bukan cuma di Asia Tenggara, tapi juga di seluruh dunia . . .
Sejarah pun serasa mempercepat langkah. Keharusan berperang yang
makin mahal itu, menyebabkan hanya penguasa kuat saja yang bisa
bertahan. Dan pada gilirannya, hadirnya persenjataan dan
prajurit sewaan asing tambah mengukuhkan para penguasa di
hadapan rakyat mereka. Dan karena para penguasa itu sendiri
berdagang dengan dunia luar, bahkan memaksakan monopoli,
akibatnya mudah ditebak akumulasi modal swasta, yang bebas dari
gebrakan raja, bertambah-tambah mustahil.
Akibat lain dari serbuan bangsa Belanda dan terpukulnya kerajaan
di pantai ialah bergesernya pusat kegiatan dari pesisir ke
pedalaman.
Abad ke-17 adalah abad Asia Tenggara yang tergusur dan tersisih.
Mereka bukan lagi bandar dagang internasional. "Hanya sedikit
orang Asia Tenggara yang kaya di luar istana yang berkuasa,"
tulis Reid, "dan istana-istana ini pun telah mengundurkan diri
dari perdagangan sama sekali (Jawa misalnya) atau telah jadi
terlampau lemah untuk memperlakukan para pedagang Eropa atas
dasar persamaan ekonomi dan kebudayaan. "
Dan ketika kota besar di pelabuhan jadi koloni asing, serta
pribumi seakan sembunyi di pedalaman, kontak dengan perkembangan
dunia luar pun macet. Karaeng Pattengaloan tak ada lagi.
Teknologi tak kunjung berkembang. Dan kita pun bertanya apakah
semua itu memang kelemahan suatu bangsa, ataukah kebetulan
sejarah yang kemudian berlarut-larut.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini