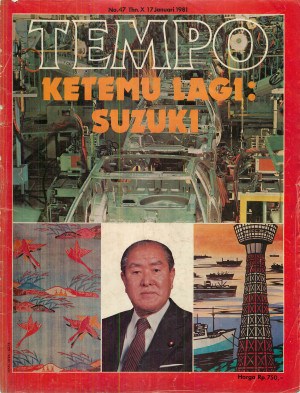KELIRU besar menduga sebutan "Ayatullah" itu hanya ada di negeri
Persi. Padahal, dia ada di mana-mana seperti kereta api,
transistor, atau jarum pentul. Yang beda cuma penampilannya.
Jika Ayatullah di sana berjenggot sarat, sorban besar dan jubah
gombrong, tidak demikian halnya Ayatullah asal Pulogadung.
Biasa-biasa saja, tidak menggemparkan. Busana normal, seperti
umumnya anggota Korpri. Air muka tidak seram, tapi lugu
bagaiikan petani bawang.
Dari sudut keturunan, katakanlah 100 lapis ke atas, tak ada yang
istimewa, met of zonder Hukum Mendell. Pokoknya, berasal dari
manusia-manusia kebanyakan sekitar-sekitar situ, paling jauh
Cikampek. Berbeda misalnya dengan Ayatullah asal Qum yang
kakeknya sebetulnya orang kelahiran Kashmir, tanah di mana
kebun-kebun bunga berciuman dengan salju.
Ayatullah dari Pulogadung ini tidak beri petuah baik sambil
berdiri, bersila, maupun berlari. Bahkan, dia tidak merasa perlu
bikin petuah seumur hidupnya. Dia menjauhi mikropon seperti
orang menjauhi cacing tambang. Ini bukan berarti dia anti
"revolusi elektronik" melainkan sekedar tidak suka hiruk-pikuk
dan hingar-bingar. Contohnya, dia mengangguk-angguk sambil
senyum saja ketika dengar rencana Telkom "Tilpun masuk desa
liwat satelit." Dia cuma suka tenang seperti akuarium yang
gelembungnya berkejaran dan pecah di permukaan. Dia pemuja
SARA-nya Kopkamtib dan proyek Atlas-nya Kotamadya Bandung: Aman,
tertib, lancar, sehat.
Pokoknya tenang, sekali lagi tenang. Orang mau ganti enerji asal
minyak dengan "oil shales" atau pasir tar atau karang minyak,
kek. Orang mau kembangkan sel-sel "photovoltaic" penyimpan
listrik, kek. Masa bodoh. Pokoknya tenang. Bahkan dia melirik
dengan sebelah mata orang-orang gila nuklir yang bermimpi bikin
substitusi enerji kendati takutnya setengah mati kena radiasi,
peras otak hingga ngos-ngosan bikin "reaktor breeder" sambil
hitung-hitung pengawasan siklusnya. Masa bodo teuing, terserah
di situlah.
Berhubung Ayatullah penduduk asli Pulogadung, dia lebih suka
naik bis daripada digotong-gotong orang, karena menurut hematnya
sebagai awam hanya penderita polio dan yang tergencet pintu yang
dibegitukan orang. Dia pilih salaman daripada diciumi tangannya
seperti ulah lelaki Prancis yang gatal. Lebih suka bikin dan
jual mebel daripada tunggu bagian setoran "khoms" dari penduduk.
Tidak paham maksud "sandera" sama sekali, dikiranya sandera itu
sama saja dengan Titik Sandora.
Akibat kangen yang tak tertanggungkan, suatu hari saya mampir di
rumahnya, orang yang memang betul-betul bernama Ayatullah dari
Pulogadung, bekas pimpinan lembaga legislatif ibukota, pistonnya
demokrasi. Dia bukan lagi mendiktekan "Valayat-Faghih" atau
"Kashfal-Asrar" atau "Tawzihal-Masail" seperti orang yang punya
panggilan serupa yang pernah tinggal di kota An Najaf di Irak --
dan dilindungi baik-baik -- selama 14 tahun, lantas dengan
kemauannya sendiri pergi ke Kuwait tapi karena negeri ini
menolak, kembali lagi ia ke Baghdad lantas langsung berangkat ke
kota kecil Neauphle le Chateau tanpa maksud yang jelas. Dan
kembali ke Teheran tanggal 31 Januari 1979 naik pesawat istimewa
"Air France" dengan kawalan ketat pasukan keamanan Prancis.
Ayatullah dari Pulogadung lagi menggodok sampah jadi bubur,
diolah jadi kertas, memenuhi anjuran Gubernur Tjokropranolo.
Ampasnya digoreng jadi krupuk, dilego ke pasar induk.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini