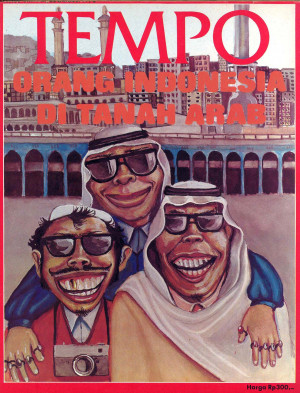BAHASA, kata orang tua kita, menunjukkan bangsa. Itu tak
berarti bahwa orang tua kita sudah memikirkan suatu konsep
"nasionalisme", tentang keutuhan bangsa (nation) dengan bahasa.
Sebab bila kita terjemahkan dan renungkan kembali, kalimat di
atas sebenarnya hanya menunjukkan kecenderungan suatu struktur
masyarakat tertentu keinginan untuk menilai klas sosial
seseorang dari cara bertutur orang itu. Dengan kata lain,
seseorang ditimbang martabat dan latar belakangnya adakah ia
bangsawan atau bukan -- dari cara ia menempatkan kata, dari lagu
ia mengucapkan kalimat.
Hal ini bisa terlihat dengan jelas dalam bahasa Jawa misalnya.
Seorang Jawa yang berlagak priyayi, tapi tak tahu di mana ia
harus memakai kata sare dan di mana ia harus menggunakan kata
tilem (kedua-duanya berarti "tidur"), akan tak diakui sebagai
anggota lapisan yang luhur. Setidaknya ia akan dianggap kurang
tahu adat.
Maka bahasa pun ikut berfungsi sebagai pengontrol tingkah-laku
individu. Pak Tani tak bisa akan seenaknya bersikap kepada Pak
Bupati, karena sejak awal proses yang berlangsung di kepalanya
untuk menyatakan diri, ia sudah harus menempuh jalur yang
ditentukan.
Memang mentakjubkan bagaimana bahasa itu bisa menjadi semacam
alat penggerak dari jauh, dalam suatu mekanisme remote control,
bagi individu yang ratusan ribu jumlahnya. Jelas suatu evolusi
yang panjang dalam sejarah sosial-politik telah membentuk
jaringan semacam itu. Dan sejarah sosial-politik itu pula,
dengan segala korban dan pemenangnya, yang telah menciptakan
pusat-pusat tertentu -- tempat orang mengukur diri dalam
berbahasa dan beradat istiadat. Bahasa Jawa punya bahasa
Jawa-Surakarta, bahasa Bugis punya bahasa Bugis-Bone.
Bahasa Indonesia, sebaliknya, belum mempunyai suatu centre of
excellence yang sedemikian. Begitu ia berkembang dari bahasa
Melayu-Riau menjadi bahasa pengantar untuk seluruh Nusantara,
dan apalagi setelah ia memencar di zaman Indonesia merdeka, ia
"kehilangan" suatu pusat. Mungkin tak ada jeleknya. Bahasa ini
dengan demikian menjadi bahasa yang mudah diikuti, memiliki
basis pendukung yang semakin luas, dan dengan demikian mempunyai
kemungkinan yang semakin kaya. Tak ada ukuran yang jelas mana
yang "baik dan sopan" dan mana yang tidak. Ia tak perlu menjadi
mahal untuk dipelajari.
Namun barangkali, seperti kata ahli bahasa, kita membutuhkan
kesamaan dalam lambang-lambang. Kalau tidak bahasa Indonesia
bukanlah bahasa persatuan. Kita membutuhkan "pembakuan". Dan
dari semangat ini lahirlah ejaan baru, misalnya.
Ketika para ahli bahasa berhasil memperkenalkan dan mengharuskan
kita memakai ejaan yang diperbaharui, enam tahun yang lalu suatu
momentum sebenarnya terbangun. Tak kurang dari Kepala Negara
sendiri yang menganjurkan agar kita "berbahasa Indonesia yang
baik dan benar" -- apa pun artinya "baik dan benar" itu. Di TVRI
muncul pelajaran bahasa Indonesia. Di koran-koran
diskusi-diskusi terjadi. Di Jakarta nama-nama toko dan gedung
tak boleh menunaikan bahasa asing.
Tapi ahli bahasa, dengan segala kecenderungan teknokratisnya,
rupanya memang tak. bisa diharapkan menjadi para penggerak
masyarakat. Momentum yang terjadi telah terlepas. Kita tak
segera memanfaatkannya. Seminar demi seminar selesai, belum juga
terdengar jawab ke masyarakat setelah ejaan, apa? Kita bahkan
tambah kacau sampai 6 tahun ini: apakah "Sujono" berarti
"Suyono" ataukah "Sudjono"?
Sementara itu, ketika para ahli bahasa kita sibuk memikirkan
bahasa tulisan (ejaan adalah sendi pertamanya), kita pun seperti
lupa bahwa sekitar 30% bangsa kita tak mengenal bahasa yang
disusun dalam huruf Latin itu. Kita lupa pentingnya bahasa
lisan, yang mungkin merupakan bahasa komunikasi 75% atau lebih
dalam hidup kita radio, TV, khotbah, pidato di balai desa. Kita
lalai barangkali bahwa dengan memprioritaskan bahasa tulisan,
kita memprioritaskan satu segi dari bahasa kita yang terbatas.
Tapi barangkali bahasa memang menunjukkan bangsa. Dalam arti
lain: bahwa apa yang baik dan apa yang terlantar di sana
mencerminkan apa yang baik dan apa yang terlantar di antara
kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini