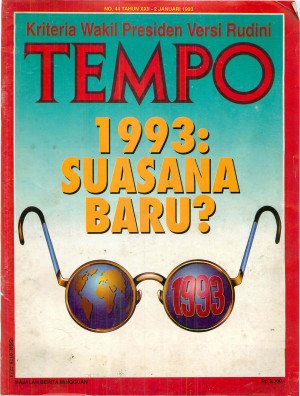ADALAH John Lennon yang menyenandungkan bait yang mengiris itu, ''Imagine then ... no country. And no religion too.'' Memang banyak darah yang telah ditumpahkan atas nama bangsa atau agama. Bagaimana keadaan kita di Indonesia, sebagai umat beragama dan sebagai bangsa? Adakah patokan agar bangsa kita ikhlas menerima dan hidup bersama dalam perbedaan? Wilfred Cantwell Smith pernah menyatakan bahwa, ''Di semua negeri Islam (kecuali mungkin di Indonesia?) kaum muslimin tak pernah memandang sebangsa yang bukan muslim sebagai ''bagian dari kita''. Minoritas bukan muslim tak pernah merasa diterima''. Tapi pernyataan Smith ini kurang pas dengan sejarah interaksi antaragama di dunia muslim, terutama dalam abad-abad kegemilangan Islam. Dalam karya monumentalnya, The Venture of Islam, Marshall Hodgson antara lain mengimbau perlunya kita mengakui bahwa banyak kalangan bukan muslim -- Kristen, Yahudi, Hindu, dan lain-lain -- tidaklah semata-mata hidup dalam lingkup kebudayaan muslim. Mereka bahkan menjadi ''partisipan integral dan punya andil'' serta ''terlibat aktif dalam banyak dialog kulturalnya''. Memang pada tiap kelompok agama dan bangsa selalu ada bigot yang terus saja bermimpi memonopoli kebenaran. Mereka lupa bahwa kebenaran final tak bisa diapropriasi dan bahwa memimpikan lingkungan yang tanpa perbedaan adalah memimpikan kemustahilan. Selain itu, homogenitas agama dalam sejarah sama sekali bukan jaminan bagi tiadanya pembantaian sesama. Ciri utama para bigot ialah gampangnya mereka menghalalkan darah pihak yang mereka ''sesat''-kan. Tak mereka sadari bahwa, dengan kesempitan cakrawala, mereka pun penyembah berhala. Bukankah berhala tak lain dari simplifikasi Kebenaran? Merasa paling benar berarti mengklaim ''menangkap'' Tuhan, padahal entitas manusia sama sekali tak terbandingkan dengan entitas Tuhan. Bacalah Surah al-Ikhlas dan simaklah tulisan Reinhold Niebuhr dalam Christ vs. Socrates. Dialah the perfect Other, yang tak mungkin diukur, apalagi diapropriasi, oleh ciptaan-Nya. Tapi seberapa signifikankah para bigot ini berhadapan dengan mayoritas umat beragama kita yang sudah berabad-abad belajar dan hidup damai dalam perbedaan? Tak perlukah apresiasi pada kenyataan bahwa di Indonesia kedua aliran Islam terbesar -- Muhammadiyah dan NU -- umumnya mengamalkan moderasi serta kelapangan iman? Dan sehubungan dengan masalah melemahnya toleransi agama di beberapa tempat di Tanah Air, tidakkah kita keliru terpancing mencocor soal iman, sementara masalahnya mungkin tidak di situ? Khusus di kalangan muslim kita, rasanya cukup tertanam pemahaman bahwa Tuhan tak memerintahkan mereka menjadi hakim atas agama lain. Tuhanlah satu-satunya hakim Kebenaran. Mereka menyadari bahwa tugas muslim hanyalah mengingatkan dan mengamalkan. Adapun iman sendiri adalah kandil yang penyalaannya dalam sanubari seseorang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Justru yang selalu diingatkan Quran ialah universalitas Islam serta universalitas jalan kepada-Nya: regular prayer and regular charity. Jika Islam Indonesia selapang itu, bagaimana dengan konsep kita tentang ''bangsa''? Mari menoleh kepada kedua pendiri republik ini. Sejak tahun 1925, Bung Hatta sudah menekankan bahwa paham kebangsaan kita bertolak dari penerimaan setulus-tulusnya atas pluralitas kita. Itulah dasar nasionalisme Indonesia. Setahun sesudahnya, Bung Karno menegaskan bahwa nasionalisme kita ''terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan''. Dengan bersendikan ''pengetahuan atas susunan ekonomi-dunia dan riwayat'', nasionalisme kita ''lebar dan luas, sebagai lebar dan luasnya udara yang memberi tempat pada segenap sesuatu yang perlu untuk hidupnya segala hal yang hidup''. Sesungguhnyalah pada kita telah berpadu paham kebangsaan serta sikap keimanan yang sama lapangnya. Maka bertentangan dengan bait Lennon, bangsa dan agama di sini adalah sumber rahmat yang tak ternilai. Tanpa agama dengan sikap iman seperti yang umumnya dimiliki masyarakat kita dan tanpa bangsa dengan nasionalisme seperti yang kita punyai, amat mungkin tanah ini sudah tercabik-cabik dalam perang saudara yang tiada habisnya. Dengan demikian, gangguan atas kerukunan agama kita mungkin sebaiknya dilacak tidak pada paham kebangsaan atau sikap iman. Mungkin cocoran pada keduanya hanyalah mistifikasi dari dinamik yang sebenarnya sangat materiil sifatnya. Maka, perlu diajukan dua alternatif penempatan masalah. Pertama, sejauh mana apa yang disebut ''keretakan kerukunan'' di negeri kita bukannya merupakan ''hasil kerja'' kekuatan-kekuatan luar yang senantiasa getol me- ngemas umat beragama kita sebagai ''fundamentalis'' dan bangsa kita sebagai ''chauvinis pelanggar hak asasi'' demi kepentingan-kepentingan ekonomi-politik global. Kedua, sejauh mana meningkatnya kesenjangan ekonomi dalam lima belas tahun terakhir menindih akal sehat sehingga sebagian masyarakat kita mudah terpancing untuk memanfaatkan peluang atau picuan apa saja guna membalikkan kesenjangan tadi. Dalam situasi demikian, orang tak lagi peduli pada asal-usul kerusuhan. Orang hanya melihat pada apa yang bisa dibuat dengan kerusuhan itu. Kita berkepentingan menjaga negeri ini agar tak menjadi bulan-bulanan ''politik kemasan'' orang dan kemata-gelapan saudara-saudara kita yang tersisih selama ini. Tentu tanpa lalai memelihara kemurnian iman dan paham kebangsaan kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini