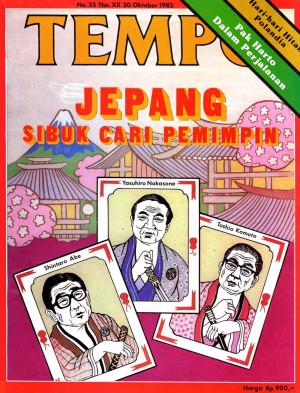SALAHKAH ketidakkompakan? Di Jepang orang pun berbicara tentang
harmoni dalam sebuah ide, atau "rumah" kita. Tapi partai-partai
politik seringkali terdengar sebagai sebuah rumah gila.
Masing-masing gaduh oleh pertikaian antara habatsu.
Habatsu, tentu saja, adalah kelompok-kelompok dalam partai.
Lihatlah Partai Liberal-Demokrat yang berkuasa, misalnya. Ia
bukan saja terbentuk oleh dua partai. Masing-masing partai yang
tergabung juga membawa kelompok yang bertentangan dalam dirinya.
Ada persaingan sengit antara orang-orang yang memasuki kehidupan
politik dengan latarbelakang sebagai birokrat. Mereka menghadapi
tojin, yang karir politiknya berasal dari lembaga perwakilan
tingkat bawah sampai atas.
Ada pula orang-orang yang berkelompok di bawah satu boss, karena
sang oyabun mampu mengumpulkan dana politik. Uang ini penting,
tentu saja: diperkirakan 100 juta yen diperlukan untuk kampanye
agar seorang calon anggota partai menang. Seorang calon yang
menerima bantuan dari seorang oyabun dengan demikian masuk, dan
setia, kepada sang boss sebagai pemimpin kelompok.
Jika demikian halnya, apakah sebenarnya yang menyebabkan
sejumlah habatsu timbul? Perbedaan ideologis? Agaknya bukan.
Prinsip? Juga hampir tak pernah. Partai Liberal-Demokrat
menamakan diri "pragmatis". Dan itu artinya ia tak terlalu repot
dengan ideologi ataupun prinsip.
Barangkali kata yang paling dekat untuk menjelaskan fenomena
khas Jepang ini ialah "kesetiaan". Kesetiaan itu terjalin dalam
hubungan antara pemimpin dan pengikutnya. Dengan kata lain,
ikatan pribadi begitu penting. Barangkali itulah sebabnya, bagi
orang luar, kegaduhan dalam Partai Liberal-Demokrat sekarang
membingungkan bagaikan teka-teki Cina: unsur-unsur berbentuk
sendiri dan nyaris tak membentuk satu pola.
Ada yang mengecam kehidupan politik macam itu sebagai satu
penerusan dari mas feodal lampau. Di masa yang telah lewat itu,
para hamba sahaya bergabung di bawah seorang tuan: para samurai
mengabdi kepada seorang shogun, pribadi. Ada pula yang
menganggapnya sebagai semacam kemacetan sistem demokrasi yang
sebenarnya: partai pada akhirnya selalu dikuasai orang
konservatif, dan kehidupan politik pada akhirnya berkisar pada
kehidupan tokoh-tokoh.
Lagipula, bukankah ketidakkompakan yang terjadi karena itu bisa
merusak? Tidakkah patai lebih sering digiring oleh oportunisme,
dan tak ada perekat ideologis yang mempertautkan faksi yang
berpecah-pecah?
Barangkali memang demikian. Tapi menarik juga untuk mendengar
pendapat yang lain. Misalnya pendapat Hans H. Baerwald, guru
besar ilmu politik dari Universitas California, seorang penelaah
politik Jepang. Dalam salah satu esei yang dimuat dalam Politics
and Economics in Conternpoay Japan (1979), Baerwald justru
melihat hal yang berguna dalam ketidakkompakan Partai
Liberal-Demokrat.
Yang pertama ialah guna kehidupan demokrasi itu sendiri. Partai
itu untuk masa yang akan datang nampaknya tetap akan jadi partai
yang memerintah. Seandainya ia utuh bersatu, ia mungkin sekali
jadi otoriter. Pemimpinnya, sebagai Perdana Menteri Jepang, bisa
bersifat diktatorial. Ketidakkompakan atau fasionalisme dengan
demikian jadi semacam penangkal sikap otoriter oligarkis yang
bisa terjadi.
YANG kedua, betapapun juga habatsu itu merupakan peluang untuk
khalayak ramai yang ingin mengemukakan ide mereka, usul mereka
dan rencana mereka. Dengan demikian cukup tersedia alternatif
lain dalam tubuh partai yang memerintah. Sebab ketika
partai-partai oposisi begitu lemah, saluran yang paling efektif
hanya lewat unsur-unsur dalam partai yang berkuasa yang tidak
satu warna.
Memang, dapat dibayangkan bahwa ide atau usul dari pelbagai
suara di bawah itu pada akhirnya akan disaring, dan mungkin
ketajamannya hilang. Tapi demokrasi agaknya harus menghargai
keniscayaan kompromi. Demokrasi juga -- dengan demikian--harus
menerima perbedaan.
Maka salahkah ketidakkompakan? Di Partai Liberal-Demokrat di
Jepang jawabnya ialah tidak selalu. Kita ingin tahu bagaimana
jawabnya di kelompok besar di tempat lain--misalnya Golkar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini