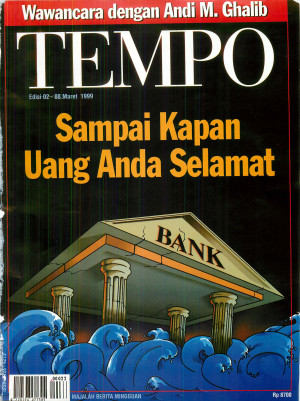Horor di Ambon menunjukkan betapa jauhnya Jakarta dari kota yang sedang hancur di Maluku itu.
Kota itu bertahun-tahun punya citra sebagai tempat yang asyik. Lagu-lagu Maluku yang gembira bernyanyi tentang "Sinyo Ambon" yang riang, pantai yang dihiasi "ombak putih-putih", dan tentang "suara tifa ramai-ramai". Tapi kini apa yang terjadi? Ribuan orang saling membinasakan, dan tak banyak yang tahu apa yang menyebabkannya.
Jauh benar jarak informasi itu. Jauh pula jarak antara suara besar para pemimpin di Pusat dan kemampuan mereka untuk mengatasi keadaan. Suara besar ini—bukan berasal dari pemerintahan Habibie, tapi jauh sebelumnya—telah menyebabkan bertahun-tahun lamanya orang Indonesia mengira bahwa pemerintah, khususnya birokrasi sipil dan militernya, bisa membereskan apa saja. Tapi sampai hari ini tak banyak yang bisa diperbuat oleh birokrasi itu, setelah hampir 200 orang tewas dengan kekerasan yang mengerikan.
Suara besar itu juga yang menyebabkan orang di Jakarta mengidap sejenis narsisme politik: apa yang terjadi di Ambon (atau di mana saja) adalah perpanjangan dari politik di tingkat atas di Jakarta. Itu sebabnya ada bisik-bisik yang sampai sekarang belum terbukti bahwa di kancah pertikaian yang berdarah itu ada sejumlah "provokator" dari Jakarta—dan "provokator" itu dibisikkan pula sebagai diatur oleh "Cendana". Itulah sebabnya ada yang percaya bahwa Megawati bisa menyelesaikan konflik berat nun di tempat yang mungkin belum pernah dikunjunginya itu. Itulah sebabnya Gus Dur percaya bahwa ada tangan jahat yang membuat kerusuhan di Maluku—entah itu seorang tetangganya di Ciganjur ataupun Mayjen "K" di Jakarta.
Narsisme politik di Jakarta itulah juga yang menyebabkan orang menutup mata, bahwa di Ambon, persoalan lokal yang serius sudah lama berlangsung, dengan dasar dan arahnya sendiri. Hasil pengumpulan informasi oleh majalah ini (halaman XXXX) menunjukkan itu. Bila ada dampak dari politik di Jakarta, itu bermula dari apa yang jadi pola umum "Orde Baru": yakni hilangnya kemampuan masyarakat untuk menyelesaikan konfliknya sendiri, di tingkat yang paling bawah dan paling dini.
Sudah Lama Terjadi
Konflik itu bukan baru. Ambon, seperti di mana pun di Indonesia, selama 20 tahun terakhir berubah secara demografis. Memang, dalam sejarahnya, Ambon bukanlah tempat yang sepenuhnya homogen. Para pendatang, dengan agama dan adat dan kapasitas yang berbeda, sudah lama bermukim. Tapi tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi punya dampak juga pada wajah demografis itu. Pendatang dari Sulawesi (orang Makassar, terutama) masuk ke wilayah itu dan lambat atau cepat berada di dalam kancah konkurensi atas sumber-sumber ekonomi. Mereka pun menjadi "nonpri", sebagaimana orang Tionghoa di Jawa dan Sumatra, betapapun sudah lama mereka beranak-pinak di sana. Ketegangan tak bisa dielakkan. Di beberapa tempat bentrokan antarkaum terjadi, jauh sebelum horor yang berlangsung sekarang, meskipun perkelahian itu sporadis sifatnya.
Bahwa ketegangan semakin meningkat, itu erat hubungannya dengan ketidakpedulian pemerintah daerah kepada apa yang sudah terjadi di bawah. Pers di daerah itu sangat lemah, juga radio. Tak ada informasi yang bisa memberikan peringatan dini. Arus informasi lebih banyak berlangsung dari atas ke bawah, dan para pejabat setempat mulai terbiasa hanya mendengarkan suara mereka sendiri. DPRD? Hanya sebuah komedi kuda. Politik dimatikan, dan di birokrasi keangkuhan tumbuh.
Maka seorang wali kota, tanpa negosiasi lebih dulu, bisa saja memutuskan untuk mendirikan gereja besar di dekat masjid. Seorang gubernur bisa mengangkat sejumlah besar pejabat daerah yang muslim, tanpa mempertimbangkan bahwa ini akan merisaukan elite setempat yang lama, yang beragama Kristen. Para pejabat itu tak takut akan jatuh karena keputusan yang setengah sewenang-wenang itu. Mereka cukup mendapat dukungan dari Jakarta, dan itu sudah cukup jadi perisai yang dahsyat.
Karena proses politik yang terbuka sudah mati, para pejabat itu menambah kekuatan dengan menarik dukungan dari kelompok yang paling mereka percaya—dan itu adalah orang satu asal-usul. Agar tak mencolok, Pak Wali, sebagaimana Pak Gubernur, bisa menggunakan dalih yang lebih terhormat, yakni dalih agama.
Lagipula, apa yang diketahui oleh Jakarta? Jakarta tak merasa perlu tahu, asal tak ada kerusuhan besar, asal Golkar menang, dan asal upeti—berupa uang sogok—masuk ke sejumlah pejabat di Departemen Dalam Negeri, atau kalau perlu ke Cendana. Indonesia adalah sebuah Negara di mana yang disebut "Pusat" sebenarnya bukan merupakan sebuah lembaga yang impersonal. Semuanya bisa diatur.
Tampak, pemerintah daerah angkuh dan mesin pemerintahan republik Pusat tak efektif. Korupsi bukan sekadar pelanggaran moral, tapi rayap. Korupsi menggerogoti seluruh saluran manajemen pemerintahan dan mengacaukannya. Bahkan ini juga mengenai aparat keamanan, termasuk militer. Kenyataan bahwa ketegangan sosial yang punya benih yang lama ini tak dapat diatasi sejak dini menunjukkan bahwa ahli ilmu politik dari Cornell, Ben Anderson, benar. Ia menyebut Orde Baru sebagai "Orde Keropos".
Kini tak banyak yang bisa dilakukan—bukan karena tak perlu dilakukan. Perlu ikhtiar yang lebih serius—dan itu tak cuma dari pemerintah—untuk memobilisasi dukungan masyarakat untuk perdamaian di Ambon. Membawa konfik ini lebih meluas—menjadi konflik antarkelompok beragama, yang pasti melintasi wilayah Ambon sendiri—sungguh berbahaya. Juga salah asumsi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini