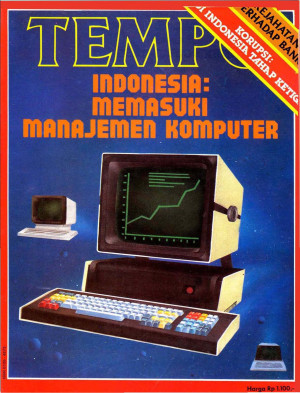"KAU belum membeli buku sejarah itu, kan?" tegur Mini di halaman
sekolah. Aku mengangguk.
"Pinjam saja bukuku," katanya.
"Tidak usah. Aku akan ke toko buku nanti sore."
"Pinjam dulu punyaku."
Buku sejarah itu berpindah ke tanganku. Entah kenapa ia begitu
ingin bukunya kupinjam.
Aha! Buku sejarah itu ternyata mengandung sejarah yang lain.
Terselip sepucuk surat di dalamnya. Mini menyatakan cintanya
dalam surat itu. Malam itu aku membuat pekerjaan rumah yang
paling sulit: mengungkapkan perasaanku terhadap Mini dalam
sepucuk surat. Bukan cinta pertamaku, tetapi itulah pertama
kalinya aku mengetahui kegunaan buku yang lain.
Sejak itu kami rajin pinjam-meminjam buku. Lalu Mini pindah ke
kota lain. Dan aku pun menemukan teman lain yang suka
meminjamkan bukunya. Dengan sepucuk surat terselip. Atau, kalau
buku itu buku cerita, ada beberapa ungkapan cinta dari karangan
itu yang digarisbawahi dengan pensil, lalu di margin halaman ada
tambahan ungkapan atau pernyataan khusus dari si empunya buku.
Sudah semestinya pula aku merasa perlu membubuhkan garis-garis
bawah yang lain, dan catatan-catatan margin yang lain.
Ya, kalau kau tanya padaku sejak kapan aku akrab dengan buku,
itulah jawabnya. Waktu itu SIM (Surat Izin Mencium) belum jadi
isu. Dan Eko Sulistyo belum lahir dan belum lagi diramal bakal
membuat kejutan dengan angket seksnya. Apakah aku harus malu,
bahwa aku perlu buku terutama bukan karena isinya, tapi karena
fungsi mediasinya? Tidak. Buku memang langka di zamanku.
Dan mahal. Di zaman itu aku harus antre di kelurahan dengan
kupon untuk mendapat jatah beras campur jagung. Tekstil pun
harus ditebus dalam antrean yang panjang dan kacau. Juga minyak
tanah. Juga minyak jelantah (begitu kotornya minyak goreng itu
sehingga Ibu selalu menyebutnya minyak jelantah -- minyak bekas
menggoreng). Toko buku memang tidak diantre. Karena orang tidak
mempunyai uang untuk buku. Aku ingat, aku harus menunggu ulang
tahunku yang masih tiga bulan untuk mendapat buku fabel Jean de
la Fontaine. Dan heran, buku yang hanya satu kopi itu belum laku
juga di toko buku Van Dorp ketika akhirnya dibeli Ayah untukku.
Untung ada Perpustakaan Negara di halaman sekolah. Dan hierarchy
of needs untuk buku mulai meningkat menjadi kebutuhan yang cukup
penting, tidak sekadar untuk menukar surat cinta.
Zaman memang sudah berubah. Aku tidak perlu lagi menunggu tiga
bulan untuk mendapat buku yang kuinginkan. Anakku tak kenal Jean
de la Fontaine. Yang dikenalnya Herge dengan Tin Tin-nya, atau
Gosciny dengan Asterix-nya. Anakku tidak membaca Karl May.
Pengetahuan lingkungan hidup dan kemasyarakatan kini diajarkan
oleh Barbara Ward (almarhmah) atau seri Time-Life. Masih untung
mereka membaca, karena di rumah memang tidak ada video.
Toko buku bermunculan di mana-mana. Penuh pengunjung, sekalipun
banyak yang masuk hanya untuk numpang baca komik. Tetapi pada
saat yang sama depot penyewaan kaset video pun "masuk desa",
menyusup di mana-mana. Jumlah toko buku pasti sudah kalah
sekarang. Di sebuah kantor penerbitan, dengan sedih kulihat para
karyawannya pulang menenteng kaset video, bukan buku. Di sebuah
kampus Rosihan Anwar menyebut ia mempunyai jatah membaca dua
buku dalam seminggu. Dan, ketika ditanya, tidak seorang pun
mahasiswa yang mempunyai disiplin membaca seperti Rosihan.
Padahal merekalah yang paling rajin mengeluh tentang kurangnya
fasilitas perpustakaan. Debu-debu di rak buku perpustakaan
menjadi saksi kecilnya minat terhadap perpustakaam Seorang dosen
UI menyuruh mahasiswa baru mencatat buku-buku di perpustakaan
yang sesuai dengan bidang minatnya. Seminggu kemudian para
mahasiswa menyerahkan daftar itu. Tetapi tidak seorang pun yang
meminjam buku. "Lho, katanya hanya disuruh mencatat," jawab
mereka.
Tanyai keponakan Anda yang mahasiswa: berapa anggarannya untuk
rokok. Ehm, sepak sehari. Tanyai lagi: berapa kaset video
dilihatnya dalam seminggu. Ya, nggak mesti. Tadi malam sih tiga.
Habis, Brooke Shield. Tapi biasanya cukup satu kaset sehari,
kecuali silat. Pertanyaan ketiga: berapa anggarannya untuk buku.
Dan jawabannya hampir pasti hanya tatapan mata yang kosong. Ini
tentu bukan generalisasi. Belum ada riset yang otoritatif
tentang hal ini. Jadi jangan anggap ini pars pro toto: sebagian
untuk seluruhnya. Tetapi gejala ini tampak jelas. Mahasiswa yang
banyak membaca buku dan tidak pernah kelihatan menggandeng cewek
malah disangka homo, impoten atau kuper, kurang pergaulan.
Pernah menanti di ruang tunggu praktek dokter? Orang-orang
menunggu tanpa sabar. Sebentar mendesah, sebentar mendecak, lalu
berdiri merentakkan kaki dan berjalan ke suster penjaga: "Masih
lama, ya?"
Menanti memang menjengkelkan. Anda sendiri mungkin lantas iseng
membeli majalah dan membacanya untuk membunuh waktu. Tetapi,
berapa orang yang telah mempersiapkan diri menghadapi situasi
itu, dan membawa buku atau bacaan dari rumah?
Buku adalah guru yang tidak pernah marah. Buku adalah teman yang
setia bersama Anda: di mana saja, kapan saja -- kecuali ketika
meyelam di laut atau bersembunyi di kolong selama gerhana. Dalam
Injil, amsal Sulaiman menyebut banyak hal tentang kegiatan
membaca sebagai sumber ilmu. Quran pun mencatat ayat penting
yang menyuruh orang membaca. Iqra! Iqra!
Buku memang tidak perlu menjadi komoditi yang sakral dan
intelektual, karena buku adalah produk yang horisontal dengan
kehidupan. Perpustakaan pun tidak boleh menjadi sanctum
sanctorum yang steril dan sunyi bagai ruang rekaman. Buku dan
perpustakaan harus ditank segaris dengan dimensi manusia.
Prancis telah memasyarakatkan komik dan sekaligus meningkatkan
derajatnya Komik bukan lagi bacaan murahan yang bersifat
hiburan, tetapi juga punya komitmen. Jepang menerjemahkan begitu
banyak buku asing dan menerbitkan dengan kertas koran yang
murah. Orang membeli buku di sebuah stasiun, membacanya habis
dalam perjalanan, dan membuangnya ke tempat sampah di stasiun
tujuan. Bagi mereka buku bukan diperlukan untuk pajangan, tetapi
ditelan isinya.
Maindert de Jong, orang Amerika pertama -- kelahiran Belanda
yang memenangkan Andersen Award di tahun 1962 menyerukan agar
anak-anak sedunia mencari teman melalui buku. Itu dialaminya
sendiri semasa kecil, ketika ia baru tiba di New York. Ia mulai
belajar berbicara bahasa Inggris, tetapi ia hanya bisa membaca
buku dalam bahasa Belanda.
Alhasil, karena langkanya buku berbahasa Belanda, buku-buku
untuk orang dewasa pun dilahapnya. Sampai ia menemukan teman
yang berkata: "Kalau kau bisa berbicara dalam bahasa Inggris,
kau pun tentu bisa membacanya. Kalau perlu mulallah dengan
membaca buku cerita anak-anak." Teman itu lalu mengajaknya ke
perpustakaan, dan di sanalah ia menemukan dunianya -- cerita
anak-anak.
Imbauan membaca buku memang tidak perlu disampaikan secara
serius. Kalau targetnya adalah remaja yang masih suka bermain CB
dan bergabung dalam Corolla Club, kenapa tidak dicoba: "Carilah
Pacar lewat Buku"? Atau, lebih ekstrem: "Berpacaranlah di
perpustakaan. Sepi dan sejuk". Dan para pustakawan boleh bersiap
menghadapi jenis pengunjung yang baru. Tidak lagi remaja serius
dengan kaca mata setebal pantat botol, tetapi remaja santai
berkaca mata Porsche dan rambut digunting model punk. Meminjam
istilah orang teman, perpustakaan pun harus di-sersan-kan.
Sersan ? Ya, serius tapi santal.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini