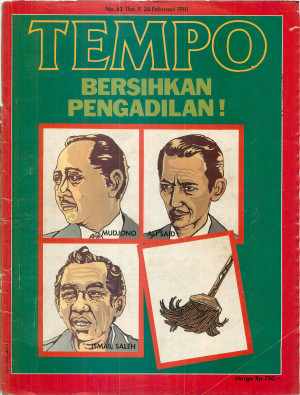DI akhir Mei 1979 selesailah saya membaca buku John Ingleson
yang berjudul Road to xile. Saya tidak berla gak. Tetapi
tanggal ini saya ingat benar saya tuliskan di sampul dalam buku
tersebut.
Kesan saya? Biasa saja. Buku ini hasil penelitian yang cukup
teliti dan ditulis dengan baik, tanpa berteori yang aneh-aneh.
Dan lebih penting lagi ialah bahwa Ingleson tidaklah berbeda
dari sebagian terbesar para penulis asing tentang sejarah dan
politik di Indonesia dalam berhadapan dengan Sukarno (atau gaya
politik pemikiran ke-Sukarno-an) dan Hatta (atau gaya politik
dan pemikiran ke-Hatta-an). Mereka terpukau pada Sukarno dengan
gayanya dan loncatan pemikirannya, seakan-akan ia adalah sesuatu
yang "eksotis dari Timur", tetapi mereka merasa lebih mengerti
Hatta.
Maka dengan begini sikap terhadap Sukarno sering tidak
se-nuchter sikap terhadap Hatta. Senang dan jengkel lebih bisa
ditimbulkan oleh sesuatu yang "eksotis".
Tetapi biar sajalah. Namun heboh tentang "surat-surat" Bung
Karno dari penjara Sukamiskin yang diungkapkan buku tersebut dan
dikutip antara lain oleh Rosihan Anwar menyebabkan saya ingat
peristiwa lain, yang terjadi kira-kira empat setengah tahun yang
lalu di suatu konperensi ilmiah di negeri Belanda.
Begini. Setelah menguraikan dengan sangat menarik beberapa liku
dari kehidupan Eduard Douwes Dekker, yang pernah menjadi asisten
residen di Lebak itu, si penceramah, seorang sastrawan dan ahli
sastra Belanda, bertanya, "Nah, bagaimana bisa seseorang yang
gaya hidup dan tujuan hidupnya begitu bisa jadi mithos sebagai
pembela rakyat kecil di "Hindia Belanda" dulu?"
Memang pertanyaan yang cukup menantang. Dalam uraiannya si
penceramah memperlihatkan bahwa tokohnya adalah seseorang yang
kecewa dalam jabatan -- gagal naik pangkat dan mendapatkan
kesempatan hidup sebagai "tuan besar", dan sebagainya. Dalam
kekecewaan ini, ia mulai menulis. Maka ia dikenal sebagai
Multatuli dengan karyanya yang terkenal Max Havelaar.
Mungkin ada keinginannya yang tak disadari oleh si penceramah,
untuk menumbangkan mithos itu -- jika hal itu memang mithos --
sebagaimana dituduhkan oleh sebagian ahli sejarah sastra
Belanda. Mungkin juga ia seorang ikonoklast.
Namun masalahnya tidaklah di sana. Bisa saja Douwes Dekker itu
hanyalah manusia lata biasa, yang ingin segala yang hebat yang
berada di luar jangkauannya. Peduli amat. Bukan ia-lah yang
diingat atau dikenang. Yang tercatat dalam sejarah ialah
Multatuli, sedangkan Douwes Dekker hanyalah catatan kaki
tambahan saja.
Secara faktuil kedua nama ini dimiliki oleh orang yang sama,
tetapi dalam kenyataan historis keduanya berbeda. Maksud saya
ialah segala sesuatu tentang Douwes Dekker itu adalah masalah
biografis tentang seorang manusia yang harus bergumul dengan
nasibnya, keinginannya dan sebagainya. Tetapi Multatuli adalah
suatu "peranan", ketika manusia itu telah terkait dan dikaitkan
dengan masyarakat atau, katakanlah, dengan sejarah.
Adalah Multatuli, bukan Douwes Dekker, yang dianggap dalam
kesadaran sejarah dan tercatat sebagai salah seorang yang paling
penting menyentuh masalah kemanusiaan dalam hubungan kolonial.
Mungkin, sebagai Multatuli, ia merasa benar sendiri. Bukankah ia
demikian memaksakan penilaian moralnya terhadap lingkungan
sosial-kultural dari dunia lain? Betapa pun, tulisannya
merupakan salah satu faktor dari mulai ditinjaunya kembali corak
hubungan kolonial. Dan, tentu seorang ahli sejarash sastra
Belanda akan mengingatkan pula peranannya dalam membentuk suatu
corak suasana kepengarangan.
Jadi terlepas dari soal tepat atau tak tepatnya fakta dan
interpretasi yang diajukan si penceramah yang saya sebut tadi
tentang perjasanan hidup seseorang yang bernama Douwes Dekker,
ia tidaklah menyentuh "Multatuli" sebagai aktor sejarah.
Pengungkapan hal-hal yang selama ini tak diketahui dalam
kehidupan pribadi seseorang tidak harus serta merta menggugah
tempat dari "peranan"-nya dalam sejarah. Apalah artinya, jika
pun benar pengungkapan bahwa Syekh Jalaluddin Al Alghani,
sebenarnya bukanlah seorang yang berasal dari Afghanistan,
tetapi seorang Persia, yang waktu mudanya mungkin seorang Syiah,
seandainya ia secara faktuil telah memperlihatkan dirinya
sebagai mujtahid utama dari kebangkitan Islam modern?
Ada beda antara biografi dengan sejarah. Dalam biografi kita
ingin mengetahui seutuh mungkin perjalanan hidup seseorang,
sebagai manusia biasa, tidak sebagaimana citra-citra kita telah
membentuknya (sebutlah pahlawan, pendekar. atau apa saja yang
serba baik). Dalam sejarah, kita ingin mengerti pengalaman dan
dinamik manusia, sebagai suatu kelompok, di hari lalu. Ada beda
antara manusia dalam kediriannya, di saat ia adalah ia
sebagaimana adanya, yang bisa mencintai, membenci atau takut,
nekat, dan apa saja, dengan manusia sebagai pemeran, aktor,
ketika ia terluluh dalam kaitannya dengan masyarakat dan dinamik
sejarah.
Tokoh sejarah, jadinya tidaklah begitu saja diukur dari
perbuatannya ketika ia hanyalah dirinya.
Jika patokan ini diambil, maka legalah perasaan untuk melihat
permasalahan kehidupan pribadi seorang tokoh, baik yang dipuja
ataupun yang dibenci. Maka terlepaslah segala hambatan untuk
berhipothesa -- bahwa konsistensi dalam hidup manusia tak lebih
daripada hasrat yang ideal belaka. Jika saja manusia ini
konsisten dalam tindak-tanduk dan sikapnya, maka baiklah kita
persetankan saja kehadiran Freud, dan tak ada salahnya kita
hanya tersenyum mendengar para ulama sibuk berkhotbah.
Pernahkah anda mendengar dongeng si Pandir yang dalan
kepengecutannya malah bisa memberantas komplotan penyamun?
Maksud saya sederhana saja, bahwa penyimpangan -- artinya,
keluar dari apa yang biasa diperkirakan -- bisa terjadi.
Saat-saat tertekan, ketika seseorang hanya dapat berkomunikasi
dengan dirinya atau, mungkin dengan Tuhannya, ia dapat melakukan
hal-hal yang tak diduga sebelumnya. Katakanlah ini suatu
misteri, tetapi memang begitulah kebiasaan manusiawi.
Apalagi jika diingat pula bahwa orang berbuat berdasarkan
interpretasinya terhadap situasi yang mengitarinya. Sialnya
ialah apa yang dilihat dan dirasakan orang itu, si aktor,
tidaklah tentu sama dengan yang kita lihat sebagai peninjau.
Kembali kepada "surat-surat Sukamiskin". Saya tak bisa
mengatakan apakah surat-surat itu otentik alias sahih atau
tidak. Saya tidak menelitinya dan tak berselera untuk
menelitinya. Jika akan meneliti, saya lebih ingin mempelajari
Bung Karno sebagai "aktor sejarah", sedangkan "surat-surat" itu
jika pun benar, menurut perkiraan saya berada di luar lingkaran
"signifcance" (penting atau tidak) dari masalah pokok.
Biarlah mereka yang tertarik pada pendekatan psikologis terhadap
sejarah mempersoalkannya. Biarlah mereka, jika mau, mencari
kaitan antara manusia, dalam kesendiriannya dengan ia, sebagai
aktor sejarah.
Namun seandainya kita sekali-sekali menyadari perlunya suatu
kerangka konseptual dalam mengerti berbagai kenyataan, baik yang
hanya riil dalam kesadaran ataupun yang bisa diamati, masalah
"surat-surat" Sukamiskin itu tak perlu harus keluar dari
proporsinya yang wajar.
Dalam keadaan seperti sekarang ini, terkaburlah rasa keinginan
tahu terhadap hidup seseorang dengan hasrat-hasrat lain, yang
tak ada kaitannya yang jelas dengan keinginan tahu itu.
Perdebatan yang terjadi kini kurang menyumbang pada pengetahuan
kita tentang pribadi Bung Karno, tetapi lebih memperlihatkan
berbagai kecenderungan sosial-politik yang ada.
Karena itu, memang sebaiknyalah diadakan moratorium, istirahat.
Bukan demi keluarga Bung Karno dan para pencintanya (sebab jika
hal-hal ini harus selalu diperhatikan, tak ada biografi yang
"murni" yang bisa ditulis), tetapi masalahnya memang telah
berpindah padahal yang lain. Dan lagi, apa perlunya, melanjutkan
sesuatu yang tak produktif ini?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini