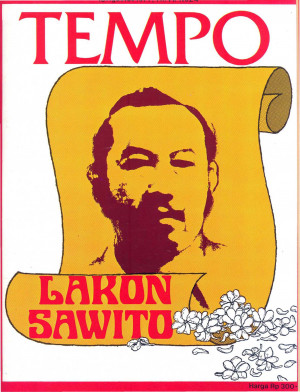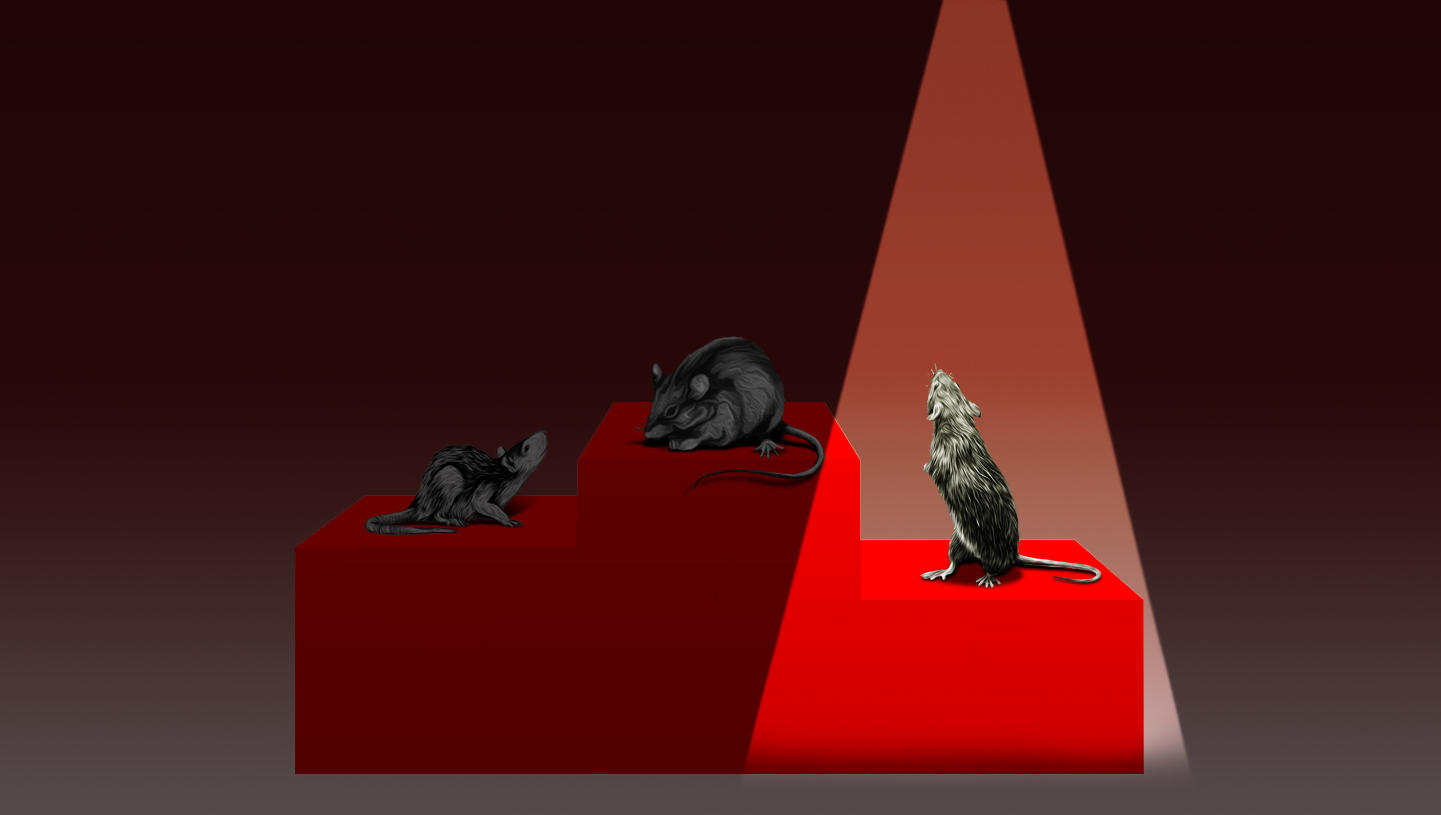RAUL Manglapus kini hidup dalam pengasingan. Bekas senator dan
intelektuil tenar dari Pilipina itu menghindari ancaman Marcos
kepada dirinya. Sebab ia meletakkan diri berhadapan dengan
Presiden yang di tahun 1972 mengumumkan "keadaan perang" itu.
Bagi Manglapus, ia tegak buat demokrasi. Bagi Manglapus, Marcos
mewakili kekuasaan kasar anti-demokrasi.
Tidak mengherankan bila ia begitu gundah ketika 11 Juli 1977
yang lalu seorang cendekiawan terkemuka Amerika Serikat, George
F. Kennan, berbicara bahwa demokrasi bukanlah "keadaan kodrati
dari sebagian besar umat manusia". Kennan agaknya tengah
meragukan niat Presiden Carter untuk mengisi diplomasinya ke
seantero dunia dengan cita-cita -- atau "khotbah moral"? --
tentang hak-hak azasi manusia. Kennan menentang demokrasi
dijadikan tujuan diplomasi itu. Ia memperingatkan agar orang
Amerika tidak "memaksakan nilai-nilai, tradisi dan kebiasaan
berfikir mereka kepada orang-orang yang tak merasa hal-hal itu
absah dan berfaedah."
Ini nasihat yang berniat baik, kata Manglapus. Tapi bagi
Manglapus kata-kata Kennan toh memperlihatkan "the color of
condescension" -- sikap meletakkan diri lebih tinggi dalam
memandang orang lain. Maka intelektuil Pilipina ini pun mengutip
seorang petani India dalam pemilu yang baru lalu di bulan Maret:
"Hanya karena saya miskin dan tak bisa membaca, tidak berarti
saya tak peduli akan hak hak azasi manusia." Dalam studi yang
dilakukan belakangan ini, kata Manglapus pula sambil menunjuk
kepada hasil penelitian Lloyd dan Susan Randolph di India,
musyawarah tingkat desa dan hukum adat cukup penting dalam
membangun demokrasi di negeri itu. Manglapus menunjukkan pula
latar belakang budaya wilayah dari mana ia berasal -- yakni Asia
Tenggara. Ia berbicara tentang adat yang memungkinkan
musyawarah, yang baginya berarti "diskusi bebas". Dan tak lupa
dalam tulisan untuk Washington Post itu Manglapus menyebut
istilah gotong royong.
Satu ironi terasa di sini - atau Manglapus mungkin tak jujur
berargumentasi. Sebab istilah musyawarah dan gotong royong lebih
sering dipakai di negeri tempat asalnya justru untuk menunjukkan
kelirunya "demokrasi" dalam tipe yang kurang lebih diyakini
Manglapus. Seandainya George F. Kennan seorang pejabat Indonesia
dari zaman Bung Karno hingga kini .... ia akan menjawab
Manglapus dengan tepat!
Apalagi nampaknya benar bahwa demokrasi bukanlah "keadaan
kodrati" -- sesuatu yang terbawa secara alamiah -- bagi banyak
rakyat di dunia kini. Apalagi cukup bisa meyakinkan bahwa
kesadaran akan hak-hak azasi manusia pertamatama bukanlah
kesadaran jutaan massa, melainkan kesadaran dari, untuk memakai
kata-kata Kennan, "kaum intelektuil yang resah."
Maka secara moral memang meragukan, jika suatu negeri datang
kepada negeri lain dengan sikap lebih tahu tentang kebenaran
--sementara orang masih bisa menunjukkan bukti tentang nisbinya
nilai-nilai. Satu kritik utama yang bisa diajukan ke depan
"diplomasi hak-hak azasi" Carter ialah bahwa langkah itu telah
menjadikan hak-hak azasi manusia satu bagian dari kekuatan yang
besar. Sekiranya pun ia benar dan adil. Sebab bila yang benar
dan yang adil kebetulan berada di pihak yang kuat, yang punya
senjata nuklir dan hegemoni ekonomi, -- tidakkah kita cenderung
cemas lagi tentang "polisi dunia" dan imperialisme nilai-nilai?
Dalam satu hal tentu Kennan benar. Tapi dalam hal lain agaknya
ia pun, seperti Manglapus, bisa silap. Sebab nilai-nilai bisa
berubah. Inggeris dan Amerika Serikat tak hanya melahirkan
demokrasinya dari nilai-nilai yang ada, tapi juga (dan mungkin
terutama) dari pengingkaran terhadap nilai-nilai itu. Orang
Inggeris memancung rajanya terlebih dulu dan kemudian Thomas
Jefferson menulis Deklarasi Kemerdekaan. Perancis yang
demokratis dan Rusia yang sosialistis lahir dari yang dulu
mungkin dianggap kekal.
Mustahilkah? Sejarah tak terdiri dari kurun demi kurun, angkatan
demi angkatan yang terpisah-pisah. Sejarah adalah persambungan,
yang juga berarti perubahan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini