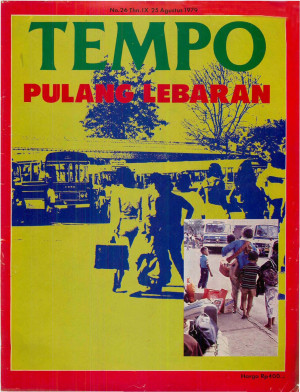DALAM sejarah Indonesia sebelum Perang Dunia ke-II, mungkin tak
ada suatu masa yang demikian penting seperti berdirinya PNI dan
perkembangannya antara 1927 sampai 1934.
Bukan saja karena itulah cetusan suatu gerakan nasional yang
sejati, tetapi juga karena para pemimpinnya adalah orang-orang
yang kemudian membawa Indonesia ke kemerdekaan di tahun 1945.
Sikap dan pertentangan antar mereka sangat mempengaruhi sejarah
Indonesia kontemporer.
Masa yang penting ini ditinjau oleh seorang sejarawan muda dari
Australia, Dr. John Ingleson, dalam bukunya yang baru terbit,
Road To Exile (Heinemans Educational Books, Kuala
Lumpur/Hongkong, 1979).
Tulisan ini bukan resensi atas buku yang sangat berharga itu.
Kita hanya akan memakainya untuk meninjau satu segi sejarah
pergerakan nasional kita -- yaitu mengenai sifat ideologinya.
Tokoh yang secara istimewa muncul dalam buku Ingleson adalah
Bung Hatta dan para mahasiswa Indonesia di Nederland di masa
itu. Di kalangan mereka inilah ide satu partai nasionalis
dilahirkan. Mereka adalah anggota Perhimpunan Indonesia (PI),
dengan penerbitannya Indonesia Merdeka, dan dengan tokoh-tokoh
seperti Hatta, Ali Sastroamidjojo Sartono, Sudjadi dan
lain-lainnya. Lewat Sudjadi, PI kemudian berhubungan dengan
klub-klub studi yang ada di tanahair, di mana ide nasionalisme
juga tumbuh.
Nasionalisme yang pada waktu itu dilahirkan punya beberapa pokok
fikiran. Pertama, kesatuan nasional, yakni mengesampingkan
perbedaan daerah dan suku utuk melahirkan suatu negara-nasion.
Kedua, solidaritas, yakni untuk menciptakan front yang dijajah
terhadap penjajah. Ketiga, nonkooperasi (tak hendak bekerja
sama) dengan penjajah dan berdiri atas kaki sendiri.
Sebenarnya dalam program ini tak ada yang baru. Sebelumnya ide
kesatuan nasional sudah dilancarkan oleh Indische Partij,
berdikari oleh Sarekat Islam dan kemerdekaan serta non-kooperasi
dikemukakan oleh Partai Komunis Ind-onesia. Tetapi dalam progra
PI semuanya disatukan.
Kalau pokok-pokok fikiran PI ditinjau, maka sebenarnya hampir
tidak ada sesuatu yang bersifat "isme" -- kecuali prinsip
"kesatuan nasional". Tak ada pemikiran mengenai perubahan
struktur masyarakat Indonesia. Yang menonjol adalah mengenai
cara untuk mencapai Indonesia merdeka, bukan pemikiran mengenai
masyarakat yang akan datang.
HATTA DAN MARXISME
PI sangat dipengaruhi oleh gerakan Sinn Fein yang di tahun
1920-an membebaskan Irlandia dari penjajahan Inggeris. Juga
gerakan nasional India jadi contoh. Tapi revolusi Rusia di tahun
1917, yang melahirkan tatanan masyarakat baru sama sekali tak
mengilhami PI. Mungkin karena revolusi Rusia tersisih dari dunia
intelektuil Belanda waktu itu.
Hatta dan banyak mahasiswa Indonesia waktu itu memang terpengaruh
oleh Marxisme, tanpa mempunyai tali dengan komunisme. Yang
menarik dari Marxisme bagi mereka adalah teorinya tentang
imperialisme, dan juga faham determinisme sejarahnya, yang
memberi mereka keyakinan bahwa Ihdonesia atau jajahan manapun
akan merdeka suatu hari nanti.ÿ20
Waktu itu Hatta juga tak menolak kerja-sama dengan kaum
komunis. Bahkan ada hubungan erat dengan Semaun, tokoh komunis
dan agen Komintern (Komunisme Interna~sional) waktu itu. Dalam
suratnya kepada Sudjadi ia menulis, bahwa " . . . kaum komunis
juga punya cita-cita sama seperti kita, yakni kemerdekaan."
Kalau mereka menekankan perjuangan klas, kata Hatta, itu sama
dengan "perjuangan rasial kita" (terhadap penjajah Belanda).
Pun Hatta tak percaya bahwa Semaun atau komunis Indonesia lain
adalah komunis sejati. Sebab, "Struktur sosial ekonomis
masyarakat Indonesia tak merupakan tempat yang subur bagi
komunisme dalam arti Barat . . . " Pendapat Hatta pada tahun
1920-an dan 1930-an ini kedengaran mirip dengan pemikiran Bung
Karno tentang kaum komunis.
Pembentukan suatu partai nasional sendiri sangat erat
hubungannya dengan kegagalan pemberontakan komunis di tahun
1927. Juga setelah terjadinya perpecahan Sarekat Islam (SI)
antara sayap kanan dan sayap kiri. Moh. Hatta dari Negeri
Belanda pun merencanakan suatu Indonesische Nationalistische
Volkspartij, yang kemudian di Indonesia dinamakan Sarekat Ra'jat
National Indonesia (SRNI).
Tapi program SRNI agak konservatif bila dibandingkan dengan
tulisan-tulisan PI awal tahun 20-an. Mungkin ini reaksi terhadap
rencana kaum komunis yang bertujuan menggulingkan kekuasaan
kolonial secara revolusioner.
KEKERASAN
Hatta agak segan memakai kekerasan untuk mencapai kemerdekaan
Indonesia, biarpun dia cukup realistis untuk melihat bahwa
kekerasan pada akhirnya harus dipakai. Kekerasan ini pun
diharapkannya hanya sekali saja perlu dalam sejarah Indonesia --
suatu ide yang sama dengan PNI Sukarno, yang di tahun 1927 juga
enggan untuk memakai kekerasan.
Meskipun begitu kalangan Sukarno (dan Sartono) tidak menyetujui
program SRNI yang meminta "hak suara umum" dari pemerintah
kolonial Belanda. Bagi Sukarno cs., ini bertentangan dengan asas
non-kooperasi. Bagaimana seandainya pemerintah kolonial memberi
hak itu, dan Volksraad (Dewan Rakyat) kolonial pun dipilih
secara demikian? Apakah itu menjadikan Volksraad legal di mata
kaum non-kooperator dan nasionalis?
Tapi juga program PNI yang dipimpin Sukarno pada dasarnya tak
lebih radikal dari program SRNI Hatta. Bagi kedua pemimpin
pergerakan nasional yang kemudian jadi proklamator itu,
masyarakat Indonesia kelak masih dilihat secara samar-samar.
Baik SRNI maupun PNI waktu itu tak memuat dalam programnya
hal-hal yang dapat menyinggung kalangan elite Indonesia sendiri.
Tak ada soal landreform, pembagian kekayaan dan lain-lain yang
biasanya dikaitkan dengan program sosialistis.
Juga tak ada analisa mengenai masyarakat Indonesia waktu itu,
kecuali mungkin mengenai golongan kooperator dan kapitalisme
asing. Seperti yang disebut oleh Ingleson, dan juga terlihat
dari tulisan-tulisan para pemimpin itu, tak ada suatu perbedaan
ideologis yang besar antara mereka. Khususnya antara Bung Karno
dan Bung Hatta. Keduanya samar-samar punya komitmen terhadap
sosialisme, tetapi tidak menjelaskannya lebih lanjut bagi
Indonesia.
Perpecahan yang timbul kemudian juga pada dasarnya merupakan
faksionalisme di kalangan yang berideologi sama. Ketika Sukarno
ditahan di tahun 1929, Hatta sangat kecewa bahwa tak ada aksi
apapun dari gerakan nasionalis. Bahkan PNI dibubarkan sendiri
oleh Sartono -- satu tindakan yang menurut Ingleson akibat
tekanan Jaksa Agung Hindia Belanda.
Periode bubarnya PNI itu kemudian jadi sumber perpecahan antara
PNI-Baru yang didirikan Hatta dan Sjahrir dengan Partindo, yang
dipimpin kembali oleh Sukarno. Disebutkan bahwa Partindo
menekankan aksi massa, sedang PNI-Baru menekankan kaderisasi.
Namun prakteknya kedua partai itu tak berbeda banyak.
PARTAI ORANG KOTA
Kaderisasi dilakukan juga oleh Partindo. Dari jumlah anggotanya
sebelum perang Dunia II, dapat ditarik kesimpulan Partindo tetap
merupakan suatu partai orang kota. Ia berbeda dari Sarekat Islam
(SI) atau Sarekat Rakjat (SR) dahulu, yang dapat berakar ke
desa-desa, karena SI dapat dukungan kaum ulama dan karena aksi
radikal SR menyalurkan keresahan sosial-ekonomis di pedesaan.
Sebaliknya PNI-Baru Hatta & Sjahrir juga dihadapkan pada
keperluan aksi massa, di desa-desa. Di Indramayu, misalnya,
pengaruh PNI-Baru sampai ke pedesaan -- karena kebetulan ada
seorang bupati yang sangat menekan rakyat dan dibenci penduduk.
Di situ penduduk desa pun berduyunduyun mencari keanggotaan pada
PNI-Baru untuk menghadapi tekanan bupati itu. Mereka butuh
perlindungan.
Keadaan seperti di Indramayu ditemui juga di desa-desa lain --
terutama berupa konilik klasik antara petani di dekat hutan
dalam menghadapi peraturan hutan negara. Meskipun begitu, kaum
elite nasionalis di kota-kota rupanya segan melihat aksi massa
seperti yang mulai nampak di Indraunayu itu. Sebab bukan maksud
mereka untuk memberikan kekebalan kepada rakyat, hanya
keyakinan. PNI-Baru pun mulai menegur para aktivis mereka yang
bergerak di kalangan rakyat.
Tapi tak urung, pemerintah Belanda sudah cemas sekali melihat
bergeraknya rakyat yang secara sporadis itu. Mereka tambah cemas
melihat bahwa rakyat desa kehilangan kepercayaan kepada lurah
dan bupati -- dan berpaling kepada para pemimpin cendekiawan
kota. Kecemasan yang terlalu berlebihan ini berakibat
ditindaknya semua pemimpin pergerakan nasional. Bung Karno, Bung
Hatta, Bung Sjahrir, ditahan dan dibuang.
Pergerakan nasional pun seakan-akan dihentikan, sebelum para
pemimpin itu secara dalam masuk ke dalam masalah sosial-ekonomis
masyarakatnya, dan sebelum mereka merumuskan suatu ideologi yang
akan menjawab masalah-masalah itu.
Maka kita dapat bertanya, sampai sejauh mana sebenarnya buah
pemikiran para pemimpin Indonesia di zaman pergerakan itu
merupakan metode untuk mencapai tujuan? Sampai di mana pula ia
memang merupakan suatu cita-cita yang dapat mendasari suatu
negara yang merdeka?
Pertanyaan itu mungkin tidak sekedar kita perlu tujukan ke masa
lalu, tapi juga ke masa kini.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini