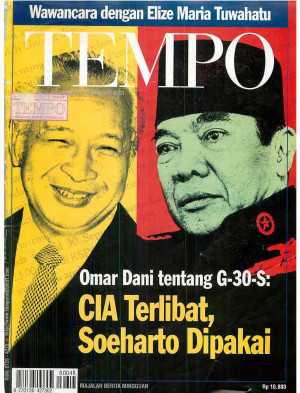Hadi Soesastro *)
*) Pengamat ekonomi dari CSIS
BELAKANGAN ini tersiar berita tentang akan hengkangnya sejumlah kegiatan manufaktur padat karya ke negara lain karena masalah perburuhan. Bagi para investor asing, masalah tenaga kerja ini memang semakin menghantui kegiatan usahanya di Indonesia. Hal ini mulai dirasakan sejak meningkatnya demonstrasi dan pemogokan serta tuntutan buruh yang dianggap berlebihan. Pihak investor, terutama dalam jenis kegiatan yang biasa disebut sebagai footloose, mudah mengancam untuk mengalihkan investasinya ke tempat lain.
Apakah ancaman tersebut masuk akal? Ada beberapa catatan dan pertanyaan yang perlu diajukan sebelum kita dapat membuat penilaian tentang persoalan ini. Investasi yang footloose, yaitu yang tidak mengakar di negara tuan rumah karena ongkos bermigrasi yang rendah, biasanya merupakan investasi yang padat karya. Itulah sebabnya investasi ini peka terhadap ongkos buruh dan ongkos menangani buruh. Investasi ini umumnya ditujukan untuk pasar ekspor. Dari sifatnya, bila jenis investasi ini merasa tidak betah, dan terutama bila kehilangan daya saingnya, investasi ini akan hengkang. Sebab, investor harus berupaya mempertahankan pasar globalnya. Bila investor tidak terancam kedudukannya di pasar global, ia tentu tidak akan mengangkat kaki dan bersusah payah untuk memulai usaha baru di tempat lain.
Globalisasi memang merupakan ancaman terus-menerus bagi investor dan buruh. Tetapi, investor mempunyai peluang lebih besar dari buruh untuk mengatasinya karena modal lebih mudah berpindah dibandingkan dengan tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlatih mempunyai mobilitas yang lebih tinggi daripada tenaga kerja yang tidak terlatih. Kalaupun mobilitasnya tidak bersifat internasional seperti halnya modal, tenaga kerja terdidik lebih mudah berpindah dari satu usaha ke usaha lain di dalam suatu ekonomi.
Khusus mengenai industri sepatu dan garmen, mungkin yang terjadi bukanlah hengkangnya investasi, melainkan beralihnya pemesanan. Banyak pabrik milik investor dalam negeri menerima pesanan dari produsen sepatu seperti Nike, Reebok, atau Adidas. Pesanan ini sangat mengandalkan diri pada ketepatan waktu karena produknya bersifat musiman dan cepat berubah. Bila tidak ada jaminan dan kepastian mengenai soal ini, dengan sendirinya pesanan akan dialihkan. Masalah ini begitu gamblang. Karena itu, aneh kalau kemudian diributkan.
Persoalan apakah baik bagi Indonesia untuk menarik masuk investasi yang bersifat footloose, itu tak perlu lagi diperdebatkan. Investasi ini bisa menyerap banyak tenaga kerja. Karena itu, investasi ini harus dibuat betah dan bila mungkin dibikin mengakar. Dengan investasi ini, selain terjadi penciptaan lapangan kerja, keuntungan yang dapat dipetik oleh Indonesia adalah terlatihnya tenaga kerja. Maka, dalam kegiatan usaha ini, dan sebenarnya juga kegiatan usaha lainnya, buruh dan serikat buruh harus belajar untuk bersikap "ilmiah" ketimbang politis.
Tentu saja buruh tidak boleh menjadi tawanan dari kenyataan ini. Hak-hak buruh harus terjamin dan perlindungan bagi mereka harus terpenuhi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tuntutan buruh tidak selalu berhubungan dengan kenaikan upah. Perbaikan perlakuan dan lingkungan kerja merupakan tuntutan utama. Tuntutan ini harus bisa diartikulasikan dengan jelas dan mekanisme untuk itu harus berkembang dalam setiap kegiatan usaha, sehingga bisa terjadi negosiasi yang beradab antara buruh dan manajemen.
Dalam hal tuntutan buruh ini, LSM yang memperjuangkan hak-hak buruh kini juga sering dituding sebagai sumber persoalan. Tudingan ini salah arah. Bila negosiasi yang beradab itu tidak terjadi, itu bukanlah disebabkan oleh adanya "hasutan". Upaya LSM adalah memberdayakan buruh dengan memberikan amunisi kepada mereka untuk bisa bernegosiasi secara efektif. Tentu saja, agar bisa membantu proses negosiasi yang beradab, LSM di bidang perburuhan juga harus bersikap "ilmiah" ketimbang emosional.
Tetapi, yang paling perlu bersikap "ilmiah" adalah pemerintah. Pemerintah adalah fasilitator akhir?facilitator of the last resort. Fasilitator harus memastikan bahwa ada aturan yang jelas bagi negosiasi antara buruh dan manajemen. Fasilitator harus bisa bersikap profesional dan netral. Fungsi ini tidak, bahkan belum pernah, terselenggara dengan baik. Di waktu lalu, tentara dan aparat keamanan dilibatkan untuk "mengatasi" masalah perburuhan. Kini birokrasi tidak lagi bisa bersembunyi di balik tentara. Celakanya, fasilitator bagi terselenggaranya iklim bernegosiasi yang beradab justru menciptakan aturan yang tidak masuk akal, seperti tecermin dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. 150/2000 itu. Belum lagi aturan bahwa 10 orang saja sudah bisa membentuk serikat buruh. Kesemua ini bukanlah aturan yang masuk akal, juga bukan aturan yang mendidik. Aturan pertama menciptakan suatu "moral hazard", sedangkan aturan kedua memperlemah serikat buruh. Kesemua itu jelas anti-ilmiah.
Selain itu, iklim investasi yang sudah buruk semakin rusak dengan adanya beberapa persoalan. Ada masalah perpajakan bagi ekspatriat, juga diskriminasi harga bahan bakar minyak bagi PMA. Ada kasus Sony, kasus Manulife, dan kasus Ajinomoto. Belum lagi masalah keselamatan dan keamanan yang banyak dihadapi perusahaan pertambangan. Ketidakpastian usaha sehubungan dengan desentralisasi juga dirisaukan. Bagi investasi yang bersifat footloose, masalah perburuhan merupakan faktor penting. Tetapi buruh per se bukanlah persoalannya. Tuntutan buruh juga bukan persoalan bagi investor. Bahwa buruh menuntut, itu adalah masalah lumrah dan terjadi di mana-mana. Yang dipersoalkan adalah bahwa di Indonesia proses negosiasi yang beradab hampir tidak bisa terjadi. Dan fasilitator, yaitu pemerintah, dianggap tidak punya kredibilitas untuk bisa menjalankan fungsinya secara efektif, edukatif, dan adil.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini