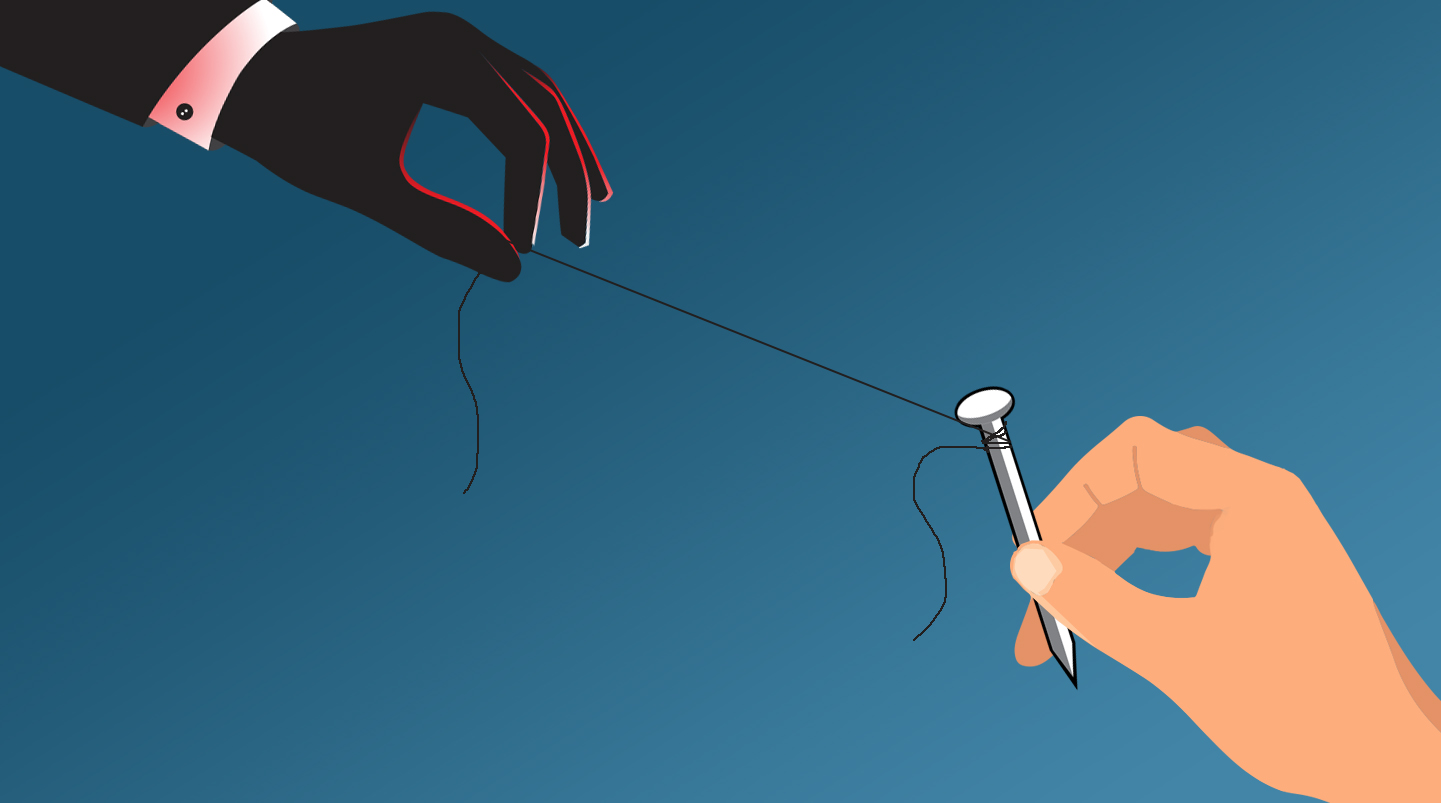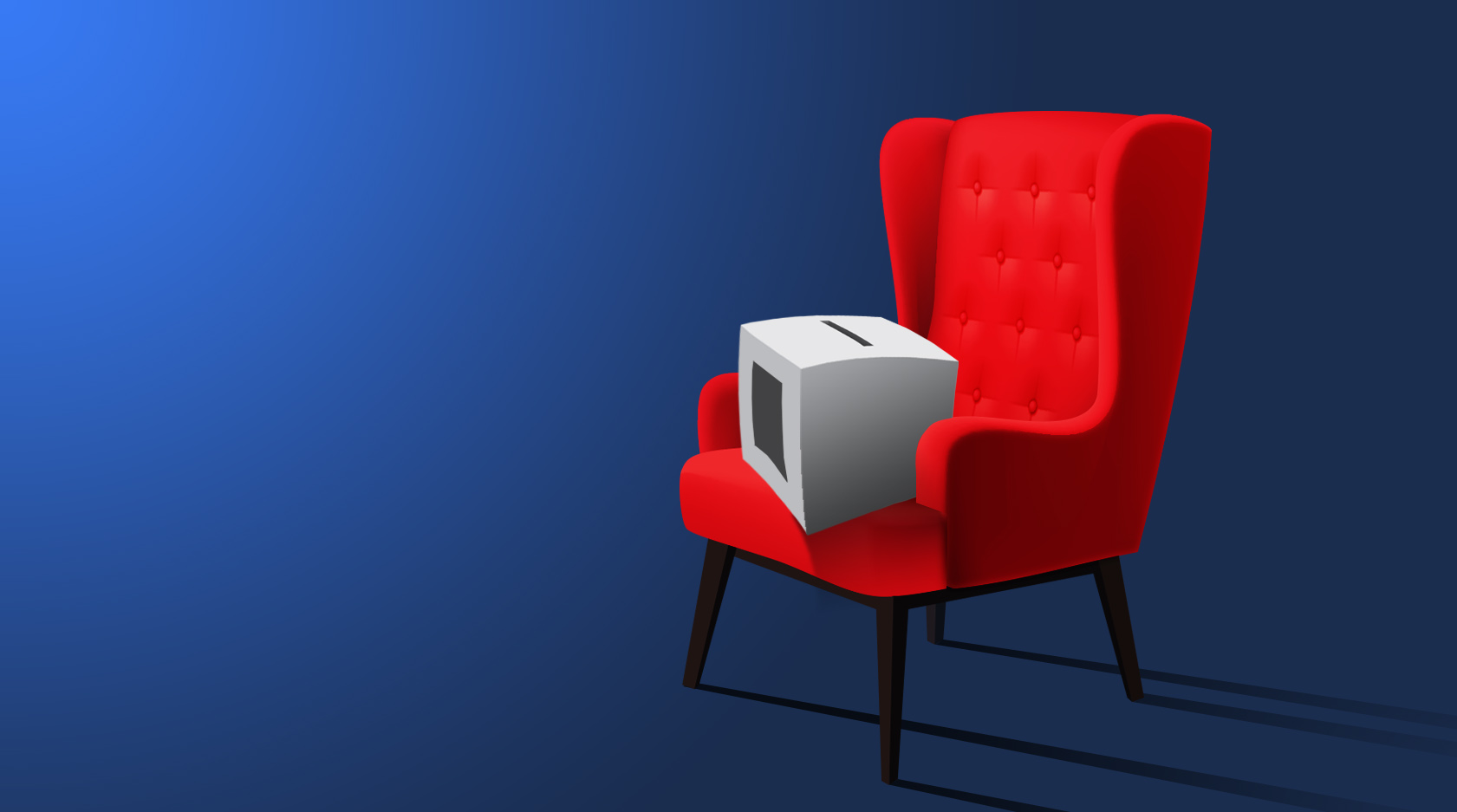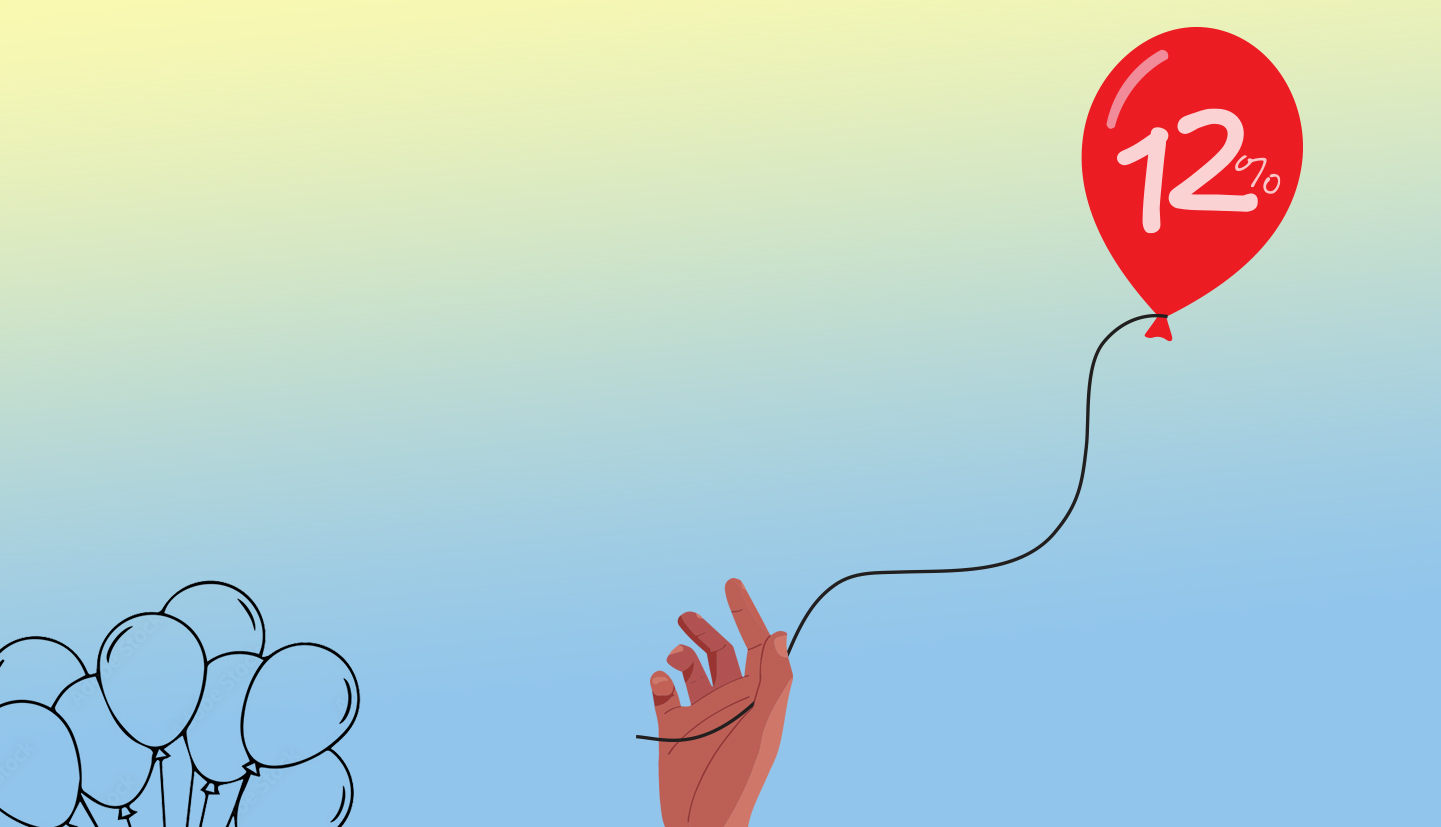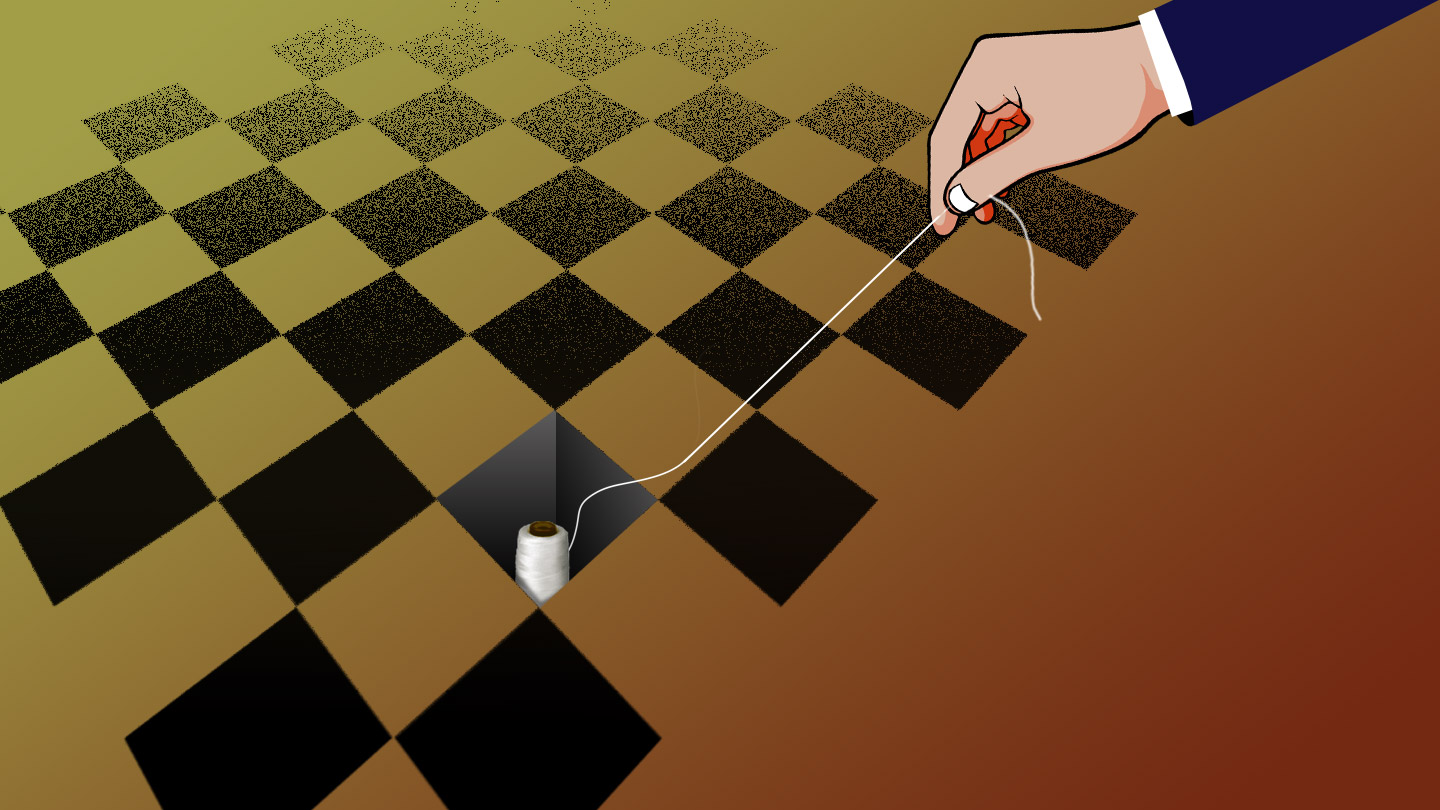Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
PENERBITAN Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Cipta Kerja menunjukkan bahwa pemerintahan Joko Widodo semakin lihai dalam mengakali prosedur hukum. Pemerintah pun kian berani mengabaikan suara rakyat dalam pembuatan undang-undang.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sewaktu masyarakat menolak keras pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Jokowi mempersilakan mereka yang tak puas menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Setelah MK menyatakan UU Cipta Kerja cacat formil dan inkonstitusional bersyarat, Jokowi menerbitkan perpu agar omnibus law itu tetap berlaku. Bagi Jokowi, tampaknya selalu ada kesempatan dalam kesempitan apapun.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pemerintah memang bisa menerbitkan perpu dalam situasi darurat atau ada kegentingan yang memaksa, seperti dijamin Pasal 22 Undang-Undang Dasar 1945. Namun, ukuran darurat atau kegentingan itu tidak bisa dibuat serampangan. Putusan MK Nomor 139 tahun 2009 telah membatasi dengan ketat “kegentingan” untuk menerbitkan perpu.
Menurut MK, ada tiga kondisi yang bisa disebut kegentingan memaksa. Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum, atau ada undang-undang tapi tak memadai. Ketiga, kekosongan hukum tersebut tak bisa diatasi dengan membuat undang-undang melalui prosedur normal karena memerlukan waktu lama.
Bila merujuk pada putusan MK itu, sungguh tak ada kegentingan yang memaksa ketika Jokowi menerbitkan Perpu Cipta Kerja. Mahkamah Konstitusi memberi waktu kepada pembuat undang-undang (pemerintah dan DPR) untuk memperbaiki UU Cipta Kerja sampai November 2023. Sementara UU Cipta Kerja dinyatakan inkonstitusional bersyarat, undang-undang lain yang mengatur urusan yang diubah lewat omnibus law itu masih berlaku. Walhasil, tak ada kekosongan hukum sama sekali.
Yang terjadi, demi memberlakukan aturan sapu jagat yang sarat kepentingan para oligark, pemerintah memaksakan alasan “kegentingan yang memaksa”. Jokowi meneken Perpu Cipta Kerja di masa libur akhir tahun, ketika DPR sedang masa reses. Seolah-olah, Indonesia akan runtuh jika perpu tersebut tak segera terbit. Pemerintah pun membuat dalih yang mengada-ada: Perpu Cipta Kerja diperlukan untuk mengantisipasi inflasi, stagflasi, dan resesi ekonomi serta dampak perang Rusia-Ukraina.
Jurus culas seperti itu sebetulnya sudah lama terbaca. Ingat apa yang terjadi setelah MK menyatakan metode omnibus tidak dikenal dalam peraturan perundangan kita. Pemerintah dan DPR sigap merevisi Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan memasukkan metode omnibus. Alih-alih mengoreksi kesalahan, DPR dan pemerintah malah bersepakat melegalkan apa yang sebelumnya ilegal.
Berdasarkan perintah MK, kewajiban pemerintah dan DPR adalah membahas ulang seluruh isi UU Cipta Kerja dengan melibatkan dan menampung aspirasi publik. Apalagi, banyak catatan atas konten UU Cipta Kerja. Antara lain berkaitan dengan urusan ketenagakerjaan, tanah, dan lingkungan, yang dinilai lebih memihak kepentingan pengusaha. Namun, dengan menerbitkan Perpu Cipta Kerja, pemerintah terang-terangan menabrak prinsip “partisipasi publik yang bermakna” dalam pembuatan undang-undang di negara demokrasi itu. Buktinya, Perpu dirumuskan diam-diam, dengan memuat ulang semua isi Undang-Undang Cipta Kerja yang kontroversial.
Bila masih ingin dianggap sebagai pilar demokrasi, DPR seharusnya mempermasalahkan dan menolak Perpu Cipta Kerja selepas reses nanti. Sebab, perpu itu tak hanya menegaskan pembangkangan pemerintah atas putusan Mahkamah Konstitusi. Dengan menerbitkan perpu tersebut, Presiden juga menunjukkan bahwa kekuasaan membuat aturan ada di tangannya sendiri, tanpa perlu melibatkan DPR sebagai lembaga yang mewakili publik. Sayangnya, karena DPR lebih sering bersekongkol dengan pemerintah, harapan dan kepercayaan kita atas peran kritis badan legislatif itu kian menipis.