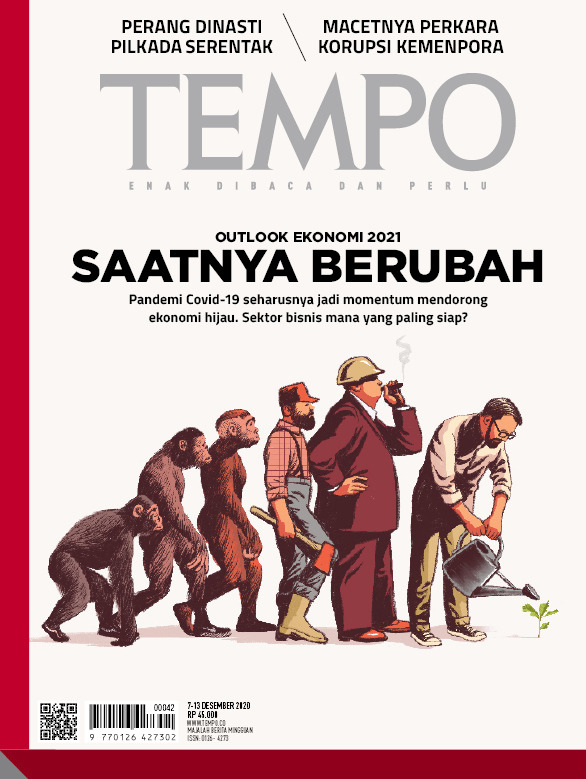Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SETENGAH abad yang lalu, dengan sebilah pedang pendek Yukio Mishima menusuk perutnya sendiri dan merobek ususnya. Ritual bunuh diri ini dirampungkan Morita Masakatsu: anak buahnya yang setia itu mengayunkan pedang samurai panjang ke leher Mishima—agar kematian datang cepat dan rasa sakit tak berkepanjangan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Tapi gagal. Pedang itu beberapa kali hanya menghantam bahu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Melihat ini, temannya yang berdiri di sampingnya bertindak. Ia pemain kendo yang mahir. Ia berhasil: pedangnya menebas keras dan tepat. Kepala Mishima lepas.
Masakatsu menyusul bunuh diri dan seperti Mishima, panutannya, ia siap lehernya dipenggal.
Dua butir kepala yang menggelinding. Lantai yang bergelimang darah. Adegan yang ganjil dan mengerikan, seperti mimpi buruk.... Semua itu terjadi pada 25 November 1970 yang sejuk, di ruang komandan pasukan tentara di markas Ichigaya, bagian timur Tokyo. Dan sang komandan, Jenderal Kanetoshi Mashita, tak bisa berbuat apa-apa.
Beberapa puluh menit sebelumnya, ia tak menduga Mishima—sastrawan termasyhur, dengan prosa yang mengagumkan dalam 24 novel, salah satu calon pemenang Nobel dari Jepang—akan bunuh diri secara dramatis ketika masuk ke kamarnya. Ia disertai empat pemuda berseragam; mereka taruna Tatenokai, milisia “Perhimpunan Perisai” yang didirikan Mishima. Tak disangka-sangka, mereka ringkus tuan rumah, mereka ikat Jenderal Mashita di kursi dan mereka sumbat mulutnya. Lalu mereka paksa ia mengumpulkan seluruh pasukan untuk mendengarkan Mishima berpidato....
Berdiri di tepi tembok tinggi yang mengelilingi lapangan barak, dengan kepala diikat bandana yang dihiasi kata-kata dari sejarah samurai, Mishima menyerukan kudeta. Ia ingin mengubah Jepang. Pengarang besar ini mengulang kecamannya yang terkenal terhadap Jepang modern: negeri lembek, komersial, mengingkari tradisi gagah yang dikukuhkan kasta samurai dan pemujaan kepada Kaisar.
Sejarah, bagi Mishima, harus dibalikkan arahnya.
Pidato itu tak selesai. Di antara para prajurit ada yang berteriak, “Orang gila!”
Mishima berhenti bicara dan kembali ke ruang Jenderal Mashita—dan bunuh diri. Jepang dan dunia terkejut. Mishima melakukan seppuku, ritual para samurai berabad-abad yang lalu, untuk sesuatu yang nonsens. Kenapa?
Ia tak gila. Bunuh dirinya yang mengerikan itu sudah ia rancang sejak setahun sebelumnya—dan ia sadar akan sia-sia. Jepang yang sudah jadi bagian dunia modern, dan menikmatinya, mustahil akan kembali ke kehidupan lama yang diidamkan Mishima. Pekik peperangan itu tak efektif, dan ia tahu itu. Tapi “efektivitas bukanlah minat kita”, ia pernah menyatakan itu dalam sebuah manifesto empat tahun sebelumnya.
Mishima menyamakan milisinya dengan pilot kamikaze Jepang dalam Perang Dunia II: patriot yang bersedia tewas menabrakkan pesawatnya ke kapal-kapal Amerika. Tapi ia lupa, pasukan bunuh diri itu mati dengan harapan akan jadi alat yang efektif buat melumpuhkan armada Amerika di Pasifik. Sedangkan sebenarnya bagi Mishima harapan dan perhitungan untuk mencapai satu hasil bukan tanda tindakan heroik. Tindakan heroik: kehancuran tanpa pengharapan.
Itu juga yang membedakannya dari para pembajak yang menabrakkan dua pesawat ke Twin Tower Kota New York pada 2001. Al Qaedah memuliakan aksi “Sebelas September” itu sebagai laku gagah berani melawan kezaliman Amerika. Tapi, dalam asas heroisme Mishima, bunuh diri mereka tak semurni seppuku. Para pembajak itu membunuh ratusan orang yang sedang dalam keadaan tak berperang—berharap masuk surga.
Mishima tak hendak membunuh orang lain. Ketika seorang prajurit mencoba mencegahnya meringkus Jenderal Mashita, ia hanya melukainya di punggung. Prajurit itu kemudian bercerita, andai Mishima mau, saat itu ia dengan mudah akan bisa menghabisi nyawanya.
Tapi tak ada kegairahan membunuh, tak ada juga janji keindahan di akhirat. Mishima hanya mempercayai momen indah kematian—saat yang murni, yang cuma sekali, yang membuat ajal memukau dengan rasa menjulang. Seperti orgasme, seperti puisi. “Kemurnian yang sempurna bukan mustahil, jika hidupmu kau ubah jadi puisi yang ditulis dengan percikan darah”, tulisnya dalam novel Honba (“Kuda-kuda Lepas”).
Darah—elemen jasmani yang tampaknya tak bisa dilepaskan Mishima dari imaji kematian sebagai keindahan. Jika ada yang menakjubkan saat nyawa terlepas, itu bukanlah karena roh membebaskan diri dari sisi fisik manusia, tempat darah mengalir. Mishima, yang membentuk badannya jadi otot-otot yang rapi diraut, tak melihat manusia sebagai “otak” yang dijunjung tubuh.
Ia mengecam desakan kehidupan modern yang—dengan rasionalitas sebagai andalan—kian asing dari peran jasmani, bagian non-rasional manusia. Dalam kehidupan modern, tulis Mishima, otot dianggap sama dengan bahasa Yunani kuno: tak banyak gunanya lagi. Ia memang belum mengalami zaman digital, ketika peran fisik tak diperlukan dalam kerja dan percakapan. Meski demikian, Mishima, seperti banyak pemikir dan seniman lain, risau atas berkuasanya rasionalisme tatkala “akal” meremehkan “okol” dan manusia entah di mana.
Hari ini ia mungkin akan bunuh diri berkali-kali. Ia berhadapan dengan sesuatu yang begitu menjanjikan, tapi begitu jauh dari yang jasmani: kecerdasan yang dahsyat, kehidupan dan kematian yang tanpa darah, artificial intelligence. Saya tak mau mengikuti Mishima, tapi saya tetap mendengar detak jantungnya yang cemas.
GOENAWAN MOHAMAD
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo