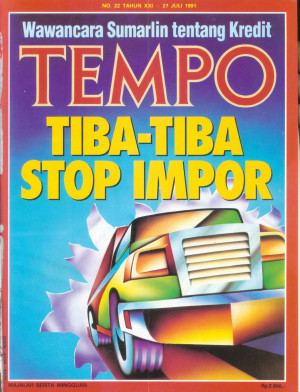SEORANG yang jadi termasyhur selama 330 tahun karena pandai mencemooh adalah Moliere. Pada tahun 1660, di Paris, ketika ia belum begitu tersohor, Moliere mencemooh gadis-gadis pedalaman yang berlagak omong elegan seperti orang terhormat di kota besar. Tahun 1673, sebelum ia roboh di atas pentas dan meninggal, Moliere men- cemooh mereka yang belajar banyak tapi tak punya akal: calon dokter. Tak mengherankan bila penulis komedi terbesar dari zaman Raja Louis XIV ini dapat sambutan yang riuh tapi pada saat yang sama juga menghadapi konflik dan kemarahan. Soalnya, tak semua orang mau berkonfrontasi dengan kemunafikan dan kekonyolan sendiri -- hal-hal yang bisa ditertawakan seorang penulis bersama para penonton. Awal Agustus 1665, Moliere mementaskan Tartuffe di Palays- Royal, tiga tahun setelah lakon itu ditonton secara terbatas di Istana. Gereja Katolik marah. Esoknya Presiden Parlemen Paris memerintahkan gedung teater itu ditutup. Uskup Agung melarang siapa saja membaca, mendengarkan, atau mementaskan komedi itu. Selama lima tahun Tartuffe dalam keadaan dibredel. Moliere ber- sumpah: bila ini terus, ia akan mengundurkan diri dari dunia sandiwara. Hidup memang tak selamanya mudah bagi Moliere. Ayahnya, seorang pegawai Istana Louis XIV, mengirimnya bersekolah di College de Clermont untuk menjadi "orang baik-baik". Tapi anak yang bernama Jean-Baptiste Poquelin sebelum memakai nama Moliere ini telah memutuskan untuk jadi orang teater, ketika ia berumur 21 tahun. Akibatnya tak begitu cerah. Dua kali, dalam umurnya yang masih 23 tahun, ia harus masuk penjara karena tak bisa membayar utang. Sebelum akhirnya berhasil mendapat nama dan uluran tangan Raja, selama 13 tahun grup sandiwara Moliere mengembara dari daerah ke daerah, dengan prestasi yang tak tercatat dalam sejarah. Bahkan, setelah ia diundang Louis XIV untuk bekerja di Versailles, Moliere tetap harus mementaskan karya-karya peng- hibur yang enteng agar bisa meneruskan hidup awak pentasnya. Konon, di zaman itu Raja biasa menjanjikan subsidi uang, tapi sering dana itu tak datang. Toh Moliere beruntung bahwa Raja melindunginya. Terutama bila harus menghadapi Gereja Katolik. Louis XIV sendiri bukan orang alim -- terutama dalam soal perempuan -- dan mungkin sekali Baginda diam-diam menyenangi cemooh Moliere terhadap para "Tartuffe" yang mengontrol moralitas Paris dengan sikap yang sok suci. Kita tahu siapa Tartuffe, orang yang menyuruh Babu Dorine menutupi dadanya dengan sapu tangan karena, "Barang itu menyakiti sukma dan mendorong masuk pikiran berdosa," katanya. Kita tahu siapa Tartuffe, sebuah pikiran cabul yang dicoba ditutup-tutupi hingga soal dada Dorine itu jadi penting. Tak mengherankan bila Tartuffe, orang yang sering tampak khusyuk di gereja ini, akhirnya tak segan-segan mencoba berzina dengan istri Orgon, orang yang sangat mempercayainya. "Merupakan suatu ilmu," kata Tartuffe memberi alasan, "untuk merentang tali hati-nurani menurut kebutuhan yang berbeda-beda." Per- buatan yang tak bermoral, katanya pula, bisa dibenarkan oleh "kemurnian niat baik". Sebenarnya aneh, bagaimana mungkin kaum agamawan bisa murka dengan lakon seperti ini. Tapi mungkin zaman itu satu zaman ketika kealiman biasa dipertontonkan dan didesak-desakkan. Hipokrisi meluas. Di kota besar seperti Paris ada gereja yang bagus tapi keyakinan sedang goyah dan rasa cemas mengganggu tidur banyak orang. Maka, ada seorang pastor, bernama Pierre Roulle, yang mungkin juga tak nyenyak tidur. Ia mengecam Moliere dengan pekik yang mengerikan: penulis Tartuffe itu "seharusnya dihukum bakar sebagai pendahuluan merasakan api neraka." Untung, Moliere berakhir tanpa dibakar: suatu indikasi perubahan dunia yang tak bisa dicegah. Februari 1669, Tartuffe dipentaskan dengan penonton yang berjubel. Masyarakat pun segera tahu bahwa yang lucu, yang "komik", dalam komedi Moliere, adalah tampilnya ketidakcocokan antara yang gila dan yang bijak, yang masuk akal dan yang tidak masuk akal -- sekaligus. Satirenya adalah untuk itu. Tapi kita tahu Moliere menjadi klasik karena ia tahu makna lain dari cemooh. Seperti Charlie Chaplin, ia bisa membuat kita tertawa terpingkal-pingkal tapi pada saat yang sama, secara mendadak atau pelan-pelan, ber- simpati kepada manusia yang kita tertawakan itu. "Saya tidak tahu apakah saya harus menangis atau tertawa melihatnya," kata seorang tokoh dalam Le Bourgeois Gentil- homme, sandiwara yang oleh Teater Koma disadur dengan kocak dan asyik itu (meskipun dengan judul OKB dan latar sosial yang kurang cocok). Kita tak tahu apakah haus menangis atau tertawa -- tapi akhirnya sama: keduanya adalah persentuhan kita dengan hidup yang utuh, bukan hidup yang dirumuskan oleh ajaran, atau instruksi dari atas, dari bawah ataupun samping. Untuk hidup yang utuh itulah kita bersyukur bahwa Moliere ada, dan ia tak jadi dibungkam. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini