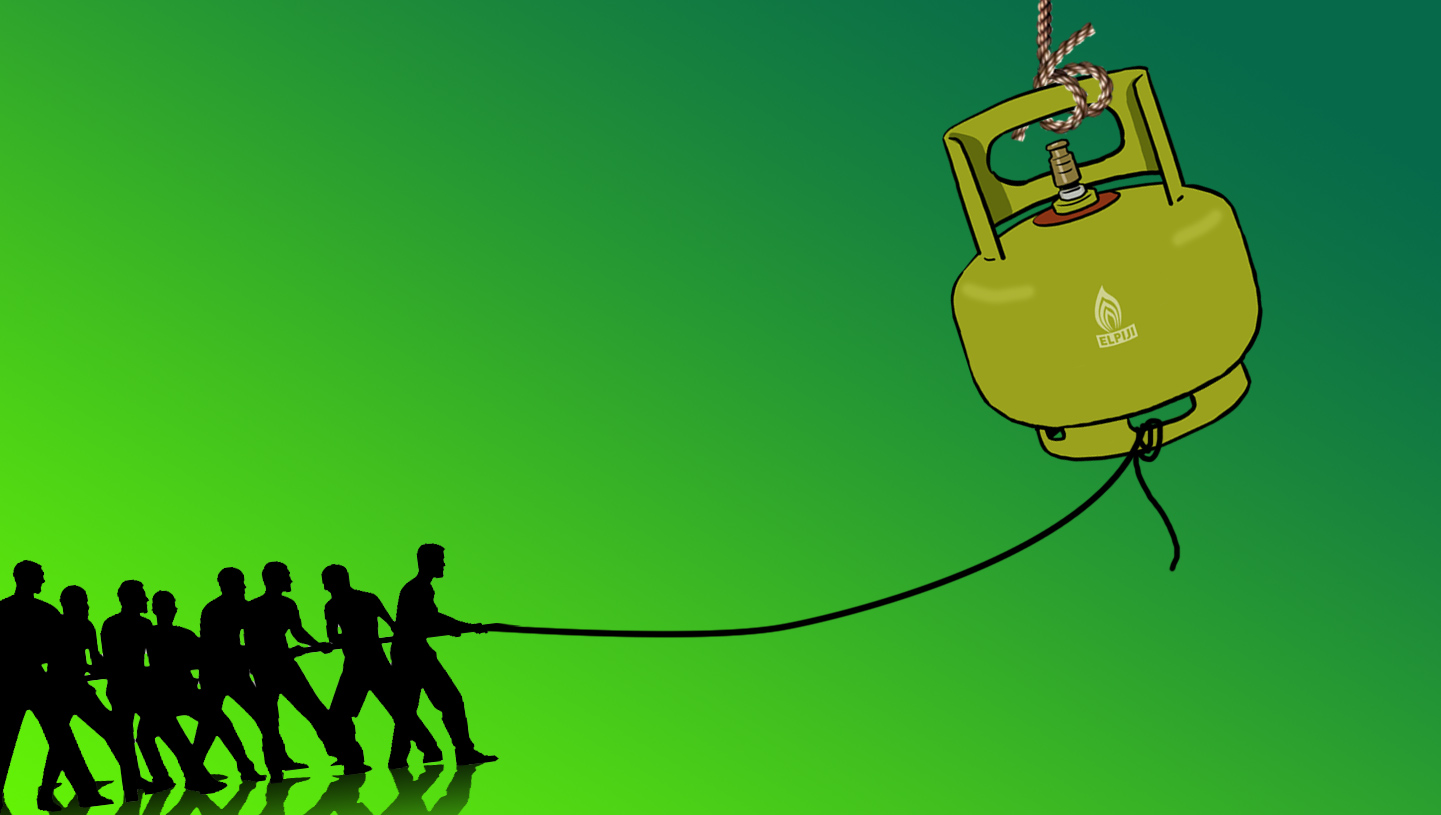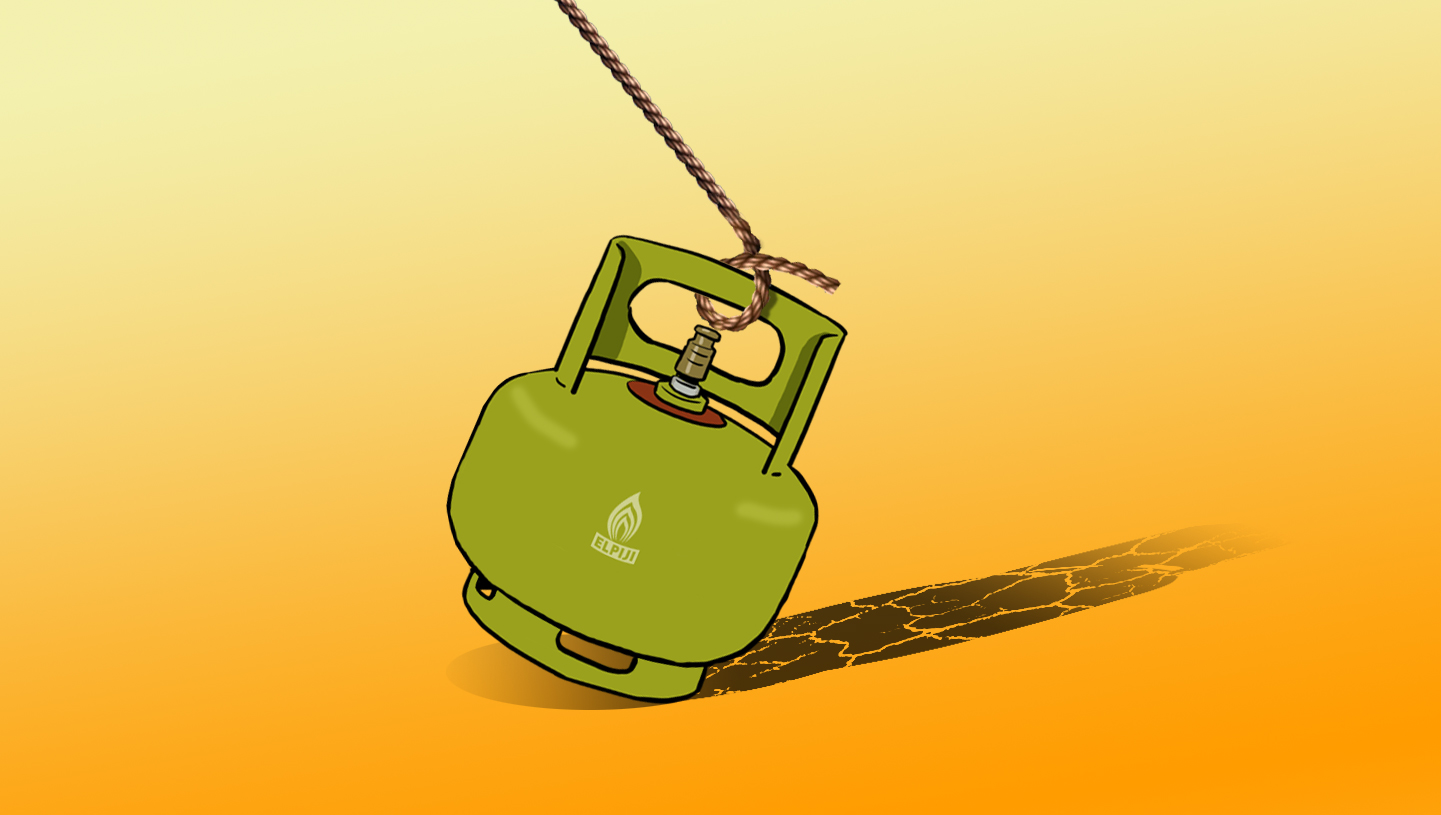Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Zen Hae
*) Penyair, kritikus sastra
SEORANG karyawan di kantor kami meninggal baru-baru ini. Seorang kawan, Asikin Hasan, yang juga telah mendengar kabar duka itu, mengirim ucapan belasungkawa di grup WA: "Semoga damai di pangkuan Ilahi." Ungkapan itu tentu saja metaforis. Namun ia memperlihatkan satu pemandangan yang sangat indrawi—bahkan jika diukur dengan nalar anak-anak: Tuhan memangku orang mati. Dengan perumpamaan kita mengharapkan Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak menyia-nyiakan manusia yang berpulang ke haribaan-Nya.
Ada dua hal menarik dari ungkapan ini. Pertama, bahasa Indonesia ternyata punya banyak ungkapan untuk melukiskan kematian. Tesamoko: Tesaurus Bahasa Indonesia Edisi Kedua (2016) susunan Eko Endarmoko mendaftar sinonim mati adalah berkalang tanah, berlalu, berpulang, berputih tulang, binasa, lewat (cak), mangkat, mendahului (ki), mengembuskan napas penghabisan, meninggal, putus jiwa, tewas, wafat..., dan seterusnya.
Saya menduga, karena situasinya yang menyedihkan dan menyakitkan, masyarakat kita pandai membuat beraneka perumpamaan agar situasi ini menjadi lebih mudah diterima atau tidak menambah duka lara keluarga yang ditinggalkan. Bahkan, dalam lagu kepahlawanan Gugur Bunga (1945) karya Ismail Marzuki, seorang pejuang yang tewas di medan perang diibaratkan sebagai bunga yang harum, "gugur bungaku di taman bakti, di haribaan pertiwi...".
Ungkapan "di pangkuan Ilahi" sejajar dengan "di sisi-Nya". Dengan ungkapan ini, kita menempatkan Tuhan dalam ruang dan waktu manusia. Kita sebenarnya tengah meneruskan pandangan antropomorfisme dalam mengalami Tuhan. Kita membubuhkan anasir manusiawi kepada Tuhan Yang Mahagaib. Kita memandang-Nya sebagaimana kita memandang manusia lain, dengan rupa tubuh sebagaimana kita. Ia memangku orang mati sebagaimana kita pernah melihat seorang ibu memangku bayi; atau seorang kekasih memangku pujaan hatinya; atau sebagaimana Yesus dan Maria dalam patung The Pietà karya Michelangelo.
Dalam teologi Islam, soal antropomorfisme ini—yang muasalnya bisa dilacak hingga ke pandangan religius masyarakat Yunani kuno—menjadi tema yang penting dan penuh perdebatan. Sebab, dalam Quran ada gambaran Tuhan yang memiliki wajah, tangan, mata, di samping berbicara dan duduk di singgasana-Nya. Bahkan ada hadis yang melukiskan Nabi Muhammad SAW (bermimpi) melihat Tuhan dalam sosok pemuda amrad (yang belum bermisai dan berjanggut).
Dalam kehidupan sehari-hari, kita pandangan antropomorfis ini bisa diperpanjang dengan ungkapan yang lain lagi: "Rezeki kita di tangan Tuhan"; "Segalanya saya serahkan pada Yang di Atas". Atau kita menyebut orang naik haji sebagai "tamu Allah" atau "pergi ke baitullah". Belum lagi ungkapan "gol tangan Tuhan" Maradona yang membuat Argentina menjadi juara Piala Dunia FIFA 1986.
Memang cukup banyak argumen teologis, dalam Islam terutama, yang mencoba menangkis kecenderungan antropomorfis ini. Salah satunya adalah bahwa Tuhan tidak menyerupai makhluk-Nya dan Ia tidak berada dalam ruang dan waktu manusia. Tapi semua itu tidak menghentikan cara kita dalam mengalami Tuhan secara antropomorfis itu.
Sastra memberi kita pelukisan sosok Tuhan yang tak kurang imajinatifnya. Dalam puisi "Padamu Jua", misalnya, Amir Hamzah menggambarkan Tuhan yang pencemburu dan bercakar—satu lukisan yang diturunkan dari Perjanjian Lama. Ihwal Tuhan Yang Mahagaib itu Amir Hamzah mengatakan: Satu kekasihku/ aku manusia/ rindu rasa/ rindu rupa. Di mana engkau/ rupa tiada/ suara sayup.... Sementara itu, tentang hubungan manusia dan Tuhan yang akrab dan setara, Chairil Anwar mengatakan: Kami pun bermuka-muka (sajak "Di Mesjid").
Memang, dalam sastra, imajinasi manusia tentang Tuhan bisa tanpa batas, tapi bukan tanpa sandungan sama sekali. Dalam cerpen "Langit Makin Mendung" karya Kipanjikusmin yang terbit di majalah Sastra, Agustus 1968, misalnya, penggambaran Tuhan sebagai lelaki tua berkacamata telah menuai protes keras dan berujung ke pengadilan. H.B. Jassin selaku Pemimpin Redaksi Sastra mesti menerima hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun.
Sastra dalam hal ini telah mengajak kita untuk mengalami Tuhan dengan segenap imajinasi kita—sebagai alternatif sekaligus tafsiran Kitab Suci. Dengan cara begini, sebenarnya kita justru mendapatkan citra Tuhan yang akrab, yang serupa dengan kita (sebab manusia diciptakan berdasarkan citra Tuhan). Jika ungkapan "Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang" tampak masih terlalu abstrak, kita bisa menemukan ungkapan yang lebih konkret pada "di pangkuan Ilahi" atau "di sisi-Nya". Konsep "kuasa Tuhan" yang abstrak dan metafisis bisa menemukan wujudnya yang ragawi dan manusiawi dalam ungkapan "tangan Tuhan".
Dengan pelbagai lukisan yang antropomorfis itu, akhirnya kita juga bisa menerima kehidupan ini dengan lebih relaks dan penuh harapan. Orang yang mati itu bukan lagi putus hubungan dengan segala yang hidup, tapi ia hanyalah kembali ke sisi Tuhan, ke pangkuan-Nya. Di tengah pelbagai kesulitan, kita masih berharap suatu ketika Tuhan mengulurkan tangan-Nya. Kita membutuhkan pelbagai kemampuan mengalami Tuhan yang ragawi seperti di atas, dan itu dipenuhi oleh bahasa.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo