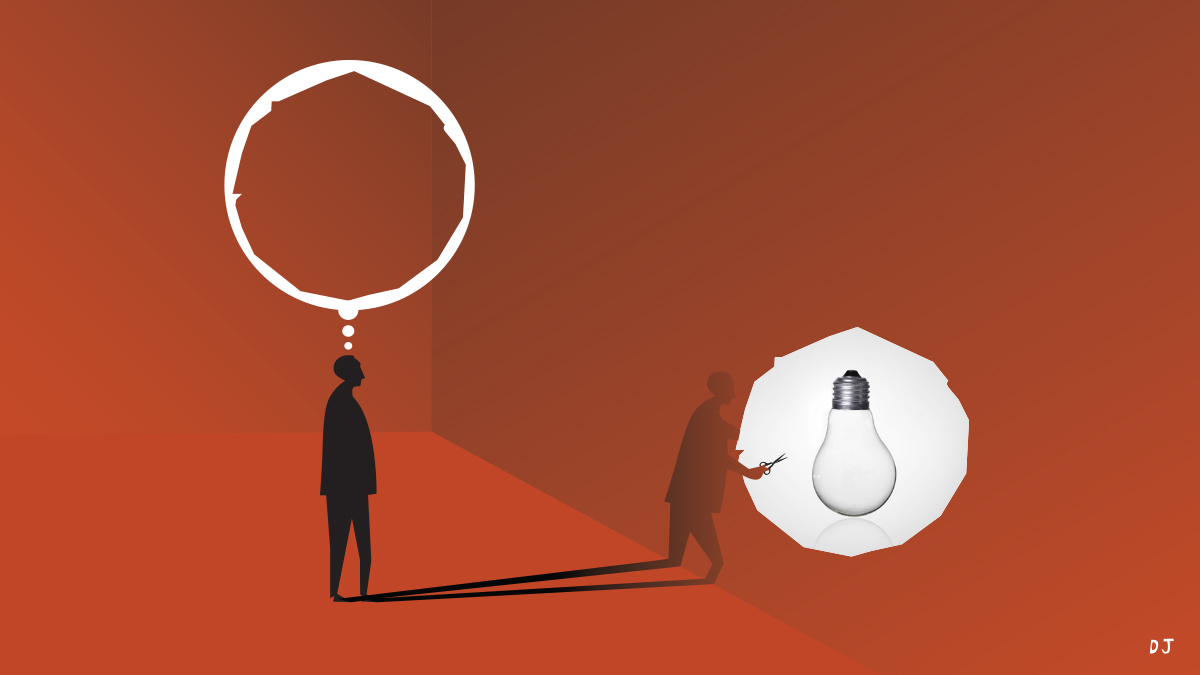Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Poin penting
Dalam kampanye, politikus melakukan berbagai cara untuk memastikan agar dosa atau kesalahan masa lalu tidak menyakiti atau mengurangi potensi perolehan suara.
Pencuciputihan dosa merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan atau menutupi keburukan, tindak kriminal, ataupun skandal.
Pencuciampunan ini berbahaya bagi penegakan dan perlindungan HAM serta demokrasi.
PADA 2024, ada setidaknya 70 negara di seluruh penjuru dunia yang menyelenggarakan pemilihan umum, termasuk Indonesia pada Februari lalu. Berbagai upaya dilakukan para kandidat, baik sebelum, selama, maupun setelah masa kampanye, untuk memikat para pemilih agar mempercayakan suara kepada mereka.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Para kandidat menggunakan narasi-narasi dan slogan-slogan kampanye yang tidak hanya bertujuan menyampaikan visi serta misi, tapi juga memoles dan membangun persona individu. Tujuannya agar mereka terlihat sebagai kandidat yang paling layak untuk dipilih sebagai pemimpin tertinggi negara. Termasuk di antaranya adalah memastikan agar dosa atau kesalahan masa lalu tidak akan menyakiti atau mengurangi potensi perolehan suara.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Pada pemilu Filipina 2022, misalnya, nuansa menutupi dosa masa lalu begitu kental saat Ferdinand "Bongbong" Romualdez Marcos Jr. mencalonkan diri sebagai kandidat presiden. Bongbong adalah putra mantan presiden Ferdinand Marcos yang terkenal akan kekejamannya selama masa darurat militer pada 1972-1981. Catatan Amnesty International menunjukkan, pada masa itu, sebanyak 70 ribu orang—termasuk pendeta, pejuang hak asasi manusia, pimpinan kelompok buruh, dan jurnalis—yang dianggap menentang Marcos dipenjara. Lebih dari 34 ribu orang disiksa dan lebih dari 3.000 orang dibunuh pada periode itu.
Keluarga Marcos juga terkenal akan korupsi serta gaya hidup super-mewahnya. Mahkamah Agung Filipina bahkan pernah memutuskan bahwa keluarga Marcos menjarah keuangan negara paling tidak sebanyak US$ 658 juta, yang dikumpulkan saat utang negara terus menumpuk dan berjuta warga Filipina hidup dalam kemiskinan. Akibat kerakusan dan kekejaman Marcos, kemarahan rakyat Filipina memuncak dalam pemberontakan People’s Power pada 1986. Peristiwa ini memaksa Marcos kabur ke Hawaii. Ia meninggal setelah tiga tahun menetap di sana.
Meski catatan sejarah Marcos senior sedemikian kelamnya, alih-alih menjauhkan dirinya dari citra ayahnya, Bongbong malah memanfaatkan figur ayahnya sebagai bagian dari bangunan kampanyenya. Ia menulis ulang sejarah dengan mengecilkan kekejaman ayahnya dan menggambarkan masa kepresidenan ayahnya sebagai "masa emas" Filipina.
Upaya pencuciputihan (whitewashing) ini didukung oleh banjirnya disinformasi di berbagai platform media sosial terkait dengan warisan Marcos. Contohnya adalah video viral yang mengklaim tidak ada satu orang pun yang ditangkap selama masa darurat militer. Ada juga video yang menuduh akun-akun yang menyatakan adanya pelanggaran hak asasi manusia pada masa pemerintahan Marcos senior hanya ingin memeras negara agar memberikan ganti rugi kepada mereka. Video-video ini ditonton jutaan pemirsa.
Upaya pencuciputihan ini merupakan penghapusan sejarah yang, menurut Nicole Curato, dilakukan melalui narasi good vibes dan toxic positivity. Hal ini melibatkan selebritas, atlet terkenal, aktor, dan politikus terkenal melalui acara-acara talkshow serta kampanye yang gegap gempita, penuh aura sukacita, dan kegembiraan.
Ketika Presiden Duterte memutuskan memberikan pemakaman pahlawan (hero’s burial) kepada mendiang Ferdinand Marcos, disinformasi yang menihilkan kejahatan dan meninggikan kepahlawanan Marcos senior kian merebak. Hal ini berujung pada kemenangan Bongbong. Pencuciputihan sukses terjadi. Reputasi keluarga Marcos berubah total dari yang tadinya dianggap korup, rakus, dan kejam menjadi pahlawan rakyat, menyenangkan, kontemporer, serta dekat dengan anak muda.
Pencucian Dosa Prabowo
Sama seperti Filipina, Indonesia pun menyaksikan penggunaan metode pencuciputihan ini dalam pemilu. Istilah yang sudah dipergunakan dalam konteks politik selama beberapa abad ini merujuk pada tindakan yang dilakukan untuk meminimalkan atau menutupi keburukan, tindak kriminal, ataupun skandal. Pencuciputihan juga digunakan untuk menghapus pihak yang bersalah melalui investigasi asal-asalan ataupun dengan presentasi data yang bias, yang tujuan untuk meningkatkan reputasi seseorang.
Selama tiga pemilu presiden terakhir di Indonesia, kita menyaksikan bagaimana Prabowo Subianto—kala menjadi kandidat calon presiden—berupaya keras membuat publik berpaling dari keterlibatannya dalam penculikan aktivis pro-demokrasi saat memimpin Komando Pasukan Khusus pada 1997-1998.
Sama seperti Bongbong, Prabowo berusaha mengingkari sejarah kelam tersebut dan memunculkan citra dirinya sebagai tentara militer yang gagah, kuat, nasionalis, serta mengabdi pada negara. Bahkan, pada Pemilu 2019, ia pun menambahkan citra islamis pada jejeran karakter yang diharapkan dapat mendongkrak penerimaan pemilih terhadapnya. Namun upaya ini tidak berhasil karena narasi pelanggar HAM banyak dimanfaatkan oleh tim pendukung kandidat lawan saat itu, Joko Widodo.
Tahun ini, setelah Prabowo tiga kali maju sebagai calon presiden, upaya pencuciputihannya berhasil. Yang berbeda dari Filipina, upaya pencuciputihan dalam putaran pemilu ini nyaris tidak melibatkan disinformasi. Bahkan, menurut Ross Tapsell, kampanye Prabowo pada Pemilu 2024 seakan-akan seperti kampanye palsu tanpa kabar palsu (hoaks).
Berbeda dengan yang ia lakukan dalam dua pemilu sebelumnya, pada pemilu ini, Prabowo tidak lagi menyangkal keterlibatannya dalam penculikan aktivis. Bahkan, secara terbuka dan terang-terangan, ia mengakui tuduhan tersebut. Dalam sebuah acara di Jakarta, secara santai, ia berkata kepada eks-aktivis Budiman Sudjatmiko yang kini merapat ke kubu Prabowo. “Saudara Budiman Sudjatmiko. Ini juga sorry, Man, dulu kejar-kejar lu juga. Tapi gue udah minta maaf sama lo, ya." Tuturan ini menyiratkan upaya Prabowo mengecilkan pelanggaran HAM yang dilakukannya di masa lalu serta secara halus mengajak publik menutup lembar hitam ini dan meninggalkannya di masa lalu.
Sesuai dengan harapan tim kampanye Prabowo, masyarakat yang selama berbulan-bulan dijejali kampanye yang dipenuhi citra Prabowo yang gemoy sekaligus menyenangkan, merespons dengan menerima pengakuan ini. Prabowo justru dipandang sebagai seseorang yang berjiwa besar dan pemberani karena bersedia mengakui kesalahan masa lalunya.
Pernyataan seperti “bangsa kita adalah bangsa pemaaf”, “mari tinggalkan masa lalu dan saatnya melangkah maju”, serta ajakan untuk “move on” menjadi narasi yang menguatkan penerimaan tersebut. Hal ini tentu saja makin mereduksi kebrutalan dan kekejaman tindakan masa lalu Prabowo serta menihilkan luka korban dan keluarga korban.
Pengakuan yang dilakukan oleh Prabowo ini jelas merupakan upaya pencuciputihan. Namun, berbeda dengan pencuciputihan yang mengandalkan pengingkaran atas kejahatan masa lalu, pengakuan ini justru mengandalkan penerimaan dan pengampunan publik atasnya. Saya melihat ini adalah sebuah varian pencuciputihan yang saya sebut sebagai pencuciampunan (absolventwashing).
Tujuan pencuciampunan ini tidak hanya untuk meminimalkan atau menutupi kejahatan masa lalu, tapi juga untuk membentuk citra diri sebagai orang yang sudah menerima ampunan publik (sudah termaafkan), dan dengan demikian terbebas dari tuduhan, vonis, tanggung jawab, serta hukuman yang terkait dengan kejahatan tersebut.
Pencuciampunan ini jelas sangat berbahaya bagi penegakan dan perlindungan HAM serta demokrasi. Hal ini tidak hanya meremehkan dan mengecilkan kejahatan serta pelanggaran atas HAM, tapi juga menihilkan dan mengabaikan korban serta keluarga korban. Lebih jauh lagi, pencuciampuan dapat digunakan untuk menormalisasi impunitas dan mengakibatkan pelaku kejahatan serta pelanggaran HAM dapat melenggang tanpa harus bertanggung jawab atas kejahatannya. Bahkan dapat dengan mudah mengikuti pemilu dan dipilih sebagai presiden.
Pencuciwarasan dan Kemenangan Donald Trump
Contoh kasus pencucian dosa kandidat presiden juga terjadi di Amerika Serikat. Pada pemilu AS yang baru selesai pada pekan lalu, salah satu kandidatnya, yakni Donald Trump—yang kemudian keluar sebagai pemenang—oleh pengadilan telah divonis bersalah atas 34 kasus pidana dan perdata. Namun para pemilihnya seakan-akan tutup mata atas semua kejahatan dan vonis ini dengan berbagai alasan.
Dalam kasus pemilu AS ini, bentuk pencucian dosa yang terjadi tidak hanya pencuciputihan serta pencuciampunan, tapi juga pencuciwarasan (sanewashing). Pencuciwarasan adalah tindakan mengemas pernyataan-pernyataan radikal dan memalukan sedemikian rupa sehingga membuat pernyataan tersebut terlihat normal.
Sepanjang masa kampanye, Donald Trump kerap berbicara panjang-lebar tanpa arah, tidak berfokus, menceracau, dan tak jelas. Sering pula pernyataan-pernyataannya sangat ekstrem, radikal, tanpa dasar, dan diambang memalukan. Akibatnya, pernyataan-pernyataannya banyak yang sulit dipahami, dan bahkan, dalam pidatonya, ia sering terlihat seperti orang yang asal bicara tanpa data serta basis argumentasi.
Atas kondisi ini, tentu kita bisa memahami bilamana tim kampanyenya sibuk melakukan pencuciwarasan terhadap pernyataan-pernyataannya. Sebagai contoh, dalam acara Fox News Town Hall, saat Trump ditanya penonton ihwal isu kesehatan reproduksi perempuan, ia menyatakan dirinya adalah Bapak Bayi Tabung (the Father of In Vitro Fertilization/IVF). Untuk mencuciwaras hal ini, tim kampanyenya mengatakan ia hanya bercanda. Masalahnya, akibat pernyataan Trump ataupun pencuciwarasan timnya, calon pemilih menjadi tidak memahami posisi Trump yang sesungguhnya terkait dengan kebijakan dalam isu ini.
Contoh lainnya adalah ketika Trump mengatakan, dari lapangan kerja baru yang dibuka oleh Presiden Biden, sebanyak 107 persennya diambil oleh imigran ilegal. Angka yang sangat aneh ini kemudian dicuciwaraskan oleh tim pendukungnya dengan menyatakan bahwa pernyataan Trump justru memperkuat fakta bahwa imigran telah merampas pekerjaan orang Amerika asli.
Hal yang menarik, pencuciwarasan ini tidak dilakukan oleh tim kampanye dan para pendukung Trump saja, tapi juga dilakukan oleh media arus utama. Ada kecenderungan para jurnalis melakukan pencuciwarasan ini agar pembaca memahami intisari pernyataan yang diutarakan Trump. Dengan kata lain, jurnalis menyaring, mencuci, dan menerjemahkan pernyataan-pernyataan Trump sehingga dalam pemberitaan, pernyataannya terlihat normal serta waras. Keinginan jurnalis melakukan hal ini didasari dorongan untuk membuat pemirsanya mudah memahami isi berita.
Persoalannya, pemberitaan atas pernyataan Trump menjadi tidak representatif terhadap apa yang sebenarnya ia sampaikan serta bagaimana kondisinya saat menyampaikan. Selain itu, cuci waras ini dilakukan agar pernyataan Trump tampak sebagai pernyataan politik yang kuat, seperti yang biasa disampaikan para politikus. Bagi sebagian media dan jurnalis, hal ini penting untuk menjaga keberimbangan sehingga media serta jurnalisnya tidak tampak berpihak pada salah satu kandidat.
Alasan lain yang mungkin mendorong jurnalis melakukan pencuciwarasan ucapan Trump adalah pernyataan-pernyataan aneh dan ekstrem yang keluar dari mulutnya dianggap sebagai hal yang sangat biasa terjadi setiap saat ia berkampanye. Karena itu, inkoherensi dan lanturannya bukan lagi hal baru dan tidak perlu lagi diberitakan. Masalahnya, lanturan Trump yang bertele-tele dan inkoheren tersebut adalah sebuah realita. Dengan menerjemahkan lanturan inkoherennya ke dalam kalimat-kalimat yang cukup masuk akal, jurnalis meninggalkan bagian yang sangat penting: memberitakan ketidakmasukakalan Trump.
Pencuciwarasan yang terjadi dalam pemilu AS ini memang belum tentu berpengaruh terhadap hasil pemilu pekan lalu karena kondisi masyarakat AS yang sudah sangat terpolarisasi. Terlebih, pendukung Trump cenderung sudah tidak mempercayai pemberitaan media arus utama. Namun, dalam konteks integritas informasi serta integritas pemilu, penting bagi media membuat pemberitaan yang utuh dan memberikan gambaran yang paling riil serta akurat. Pemberitaan yang akurat krusial sebagai catatan sejarah yang utuh.
Fenomena pencucian dosa politikus dalam berbagai bentuk saat ini masih menuai perdebatan. Berbagai kritik yang datang dari dalam tubuh media, jurnalis, serta para sarjana politik terus bermunculan sehingga menghasilkan proses diskursus yang cukup dinamis. Beberapa media telah mencanangkan bahwa mereka tidak akan melakukan pencuciwarasan serta mengajak media-media lain, terutama yang dimiliki oleh konglomerasi, untuk berani melawan pencuciwarasan. Pihak-pihak lain yang juga bergerak untuk mendukung jurnalisme berkualitas menyediakan analisis-analisis serta kiat-kiat agar tidak terjebak dalam pencuciwarasan.
Tulisan ini sejatinya hendak memperlihatkan bahwa dalam konteks politik, terutama dalam masa pemilu, operasi informasi (termasuk di dalamnya pencuciputihan dengan berbagai variannya) akan selalu berkembang dan sangat mengikuti situasi serta kondisi yang menuntutnya. Sebagian bisa dengan sengaja dirancang dan diluncurkan sebagai sebuah strategi matang berlapis untuk mencapai tujuan tertentu, seperti yang kita lihat pada kasus Filipina, Indonesia, serta AS.
Pencucian dosa ini bisa juga terjadi tanpa disengaja dan tanpa niatan untuk kepentingan tertentu, seperti yang terjadi pada kasus pencuciwarasan Trump oleh media di AS. Kita pun bisa memahami bahwa media dan jurnalis menghadapi dilemanya sendiri serta memiliki pertimbangan-pertimbangan valid yang berujung pada pencuciwarasan.
Meski demikian, kita perlu menjaga integritas informasi, terutama dalam konteks pemilu. Kita perlu mampu memperlebar kapasitas untuk mendeteksi modus-modus pencuciputihan yang ada, serta yang akan muncul di kemudian hari. Kita juga perlu mulai memikirkan mitigasi-mitigasi strategis yang bisa kita bangun dari sekarang untuk menghadapi pemilu-pemilu berikutnya.
Dialektika Digital merupakan kolaborasi Tempo bersama KONDISI (Kelompok Kerja Anti Disinformasi Digital di Indonesia). KONDISI beranggotakan para akademikus, praktisi, dan jurnalis yang mendalami dan mengkaji fenomena disinformasi di Indonesia. Dialektika Digital terbit setiap pekan.
Redaksi menerima tulisan opini dari luar dengan syarat: panjang sekitar 5.000 karakter (termasuk spasi) atau 600 kata dan tidak sedang dikirim ke media lain. Sumber rujukan disebutkan lengkap pada tubuh tulisan. Kirim tulisan ke e-mail: [email protected] disertai dengan foto profil, nomor kontak, dan CV ringkas.