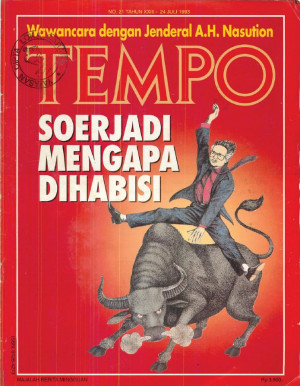BEBERAPA tahun yang lalu ada seorang tetangga yang gemar berlatih lari pagi. Namanya Piet. Ia masih muda dan punya ketekunan yang besar, dan bisa menempuh jarak yang jauh. Bersama seorang tetangga lain, seorang yang gemar melukis, kami sering berlari bersama, ke arah daerah bandar udara lama, tempat pohon-pohon asam berjajar rindang dan rumput basah diberkati embun dan disinggahi dini hari. Bagi saya dan Bus, tetangga yang gemar melukis itu, itulah bagian pokok lari pagi: mendekati pohon-pohon, menghirup bau rumput, menyentuh embun yang kadang-kadang terhimpun seperti sarang yang gemerlap. Bagi Piet? Suatu pagi, sehabis lari bersama, ia berkata sambil memandangi beberapa pelari lain yang melintas: ''Tujuan semuanya sama yaitu duit.'' Bus terbelalak. Ia, yang dengan nafkah yang sporadis masih punya percintaan dengan waktu senggang yang panjang, tak percaya bahwa ada hubungan antara lari pagi dan duit. Tapi ini argumen Piet: berlatih lari adalah agar badan sehat, dan kita bisa menghemat ongkos berobat, dan lebih punya stamina, dan akhirnya lebih bisa menghasilkan. Ergo: uang pun terkumpul. Kami hanya diam. Setelah 10 km berlari, dengan singlet dan sepatu yang basah oleh peluh, saya tak ingin berbantah, sedangkan Bus sudah menarik konklusi: Piet memang hidup dengan paradigma yang berbeda. Bus adalah sebuah sisa dari sebuah zaman, sebelum ada Orde Baru, Reaganomika, dan kapitalisme Thatcher. Paradigma Bus adalah paradigma kanvas yang tengah dilukis: hidup adalah mengisi diri kita dan ruang sekitar kita, dengan bentuk dan ritme, dengan hal-hal yang renyah secara indriawi tetapi juga ranum oleh rohani. Hidup adalah sebuah proses jouissance, kenikmatan orgasmik, tetapi yang tak seluruhnya berkenaan dengan tubuh. Piet lain lagi. Ia unsur yang antusias, sadar dan asyik merayakan pertumbuhan ekonomi dan menyambut dampaknya bagi perilaku. Baginya prestasi adalah apa yang oleh para eksekutif disebut sebagai the bottom line, perhitungan laba-rugi. Neracalah yang menerangkan ikhtiar manusia, dan angka yang berperan. Orang semakin jelas ukuran kepuasan dan kekecewaannya, dan semakin diketahui bagaimana memacu dan merangsangnya. ''Duit'' hanyalah petandanya. Paradigma Piet adalah paradigma tata buku. Kelebihan paradigma Piet ialah bahwa ia membuat hidup tak lagi seperti sebuah novel yang ruwet, walaupun indah. Sebab dengan tata buku semua bisa ditaksir dengan lugas, mungkin persis, dan kita bisa berbicara secara meyakinkan tentang ''maju'' dan ''mundur''. Tujuan tak lagi remang dan rancu. Remang dan rancu hanyalah ulah manja perasaan, tak bisa dikuantifikasikan, sesuatu yang irasional, mirip kesadaran klenik orang Jawa. Paradigma Piet sebenarnya adalah bentuk karikatural dari semangat modern, sesuatu yang di tahun 1930-an diserukan S. Takdir Alisjahbana, yang di tahun 1960-an dimimpikan sebagian intelektuil Indonesia, menjelang Orde Baru. Dengan semangat ini, kata para penganjur modernisasi itu, dunia dan manusia bisa direncanakan. Pelan-pelan hubungan antara manusia dan benda pun jadi kian objektif, kian bisa dirumuskan dalam hitungan dan catatan. Bahkan tak cuma hubungan dengan benda, tapi juga dengan pahala Ilahi. Perhubungan antara manusia (dan manusia dengan Tuhan) berarti ''menawarkan'' dan ''memperoleh'', sebuah proses tukar- menukar di mana ''memberi'' hanya satu tahap dari ''mendapat''. Di sini kepentingan, atau interest, menjadi sesuatu yang galib dan beradab. Maka orang pun terdorong kepada ''hak'', lebih dari ''kewajiban''. Kebersamaan, yang oleh orang Jawa disebut bebrayan dan oleh orang Yunani disebut polis (atau ''negeri''), pun tak lagi tergerak oleh kehidupan politik yakni ''politik'' dalam arti sesuatu yang berkaitan dengan hidup komunitas melainkan oleh perdagangan. Tak mengherankan bila akhirnya kita melihat pertikaian dalam partai politik kita lebih berupa konflik tentang person, kursi, dan rezeki, bukan karena beda paham dan beda program yang menyangkut orang ramai. Berangsur-angsur, partai politik tak bisa lagi menggugah kebersamaan. Orang seperti telah kehilangan minat untuk bekerja, memberi, berkorban, untuk polis tempat mereka hidup. Bahkan pengabdian dan pembelotan yang umumnya jadi bahan cerita yang mengharukan juga berubah. John Le Carre tak lagi menulis tentang spion-spion Inggris dan Soviet yang saling jebak karena rasa bertugas untuk tanah air masing-masing. Tokoh Smiley dan Karla punah bukan saja karena ''Perang Dingin'' habis. Le Carre kini menulis The Night Manager, tentang pedagang senjata dan pengurus hotel. Motif utama konfrontasi tinggal satu: duit. ''Pengkhianatan dan keculasan jenis ini telah jadi sebuah simbol zaman kita,'' ujar Le Carre. Ia mungkin masygul. Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini