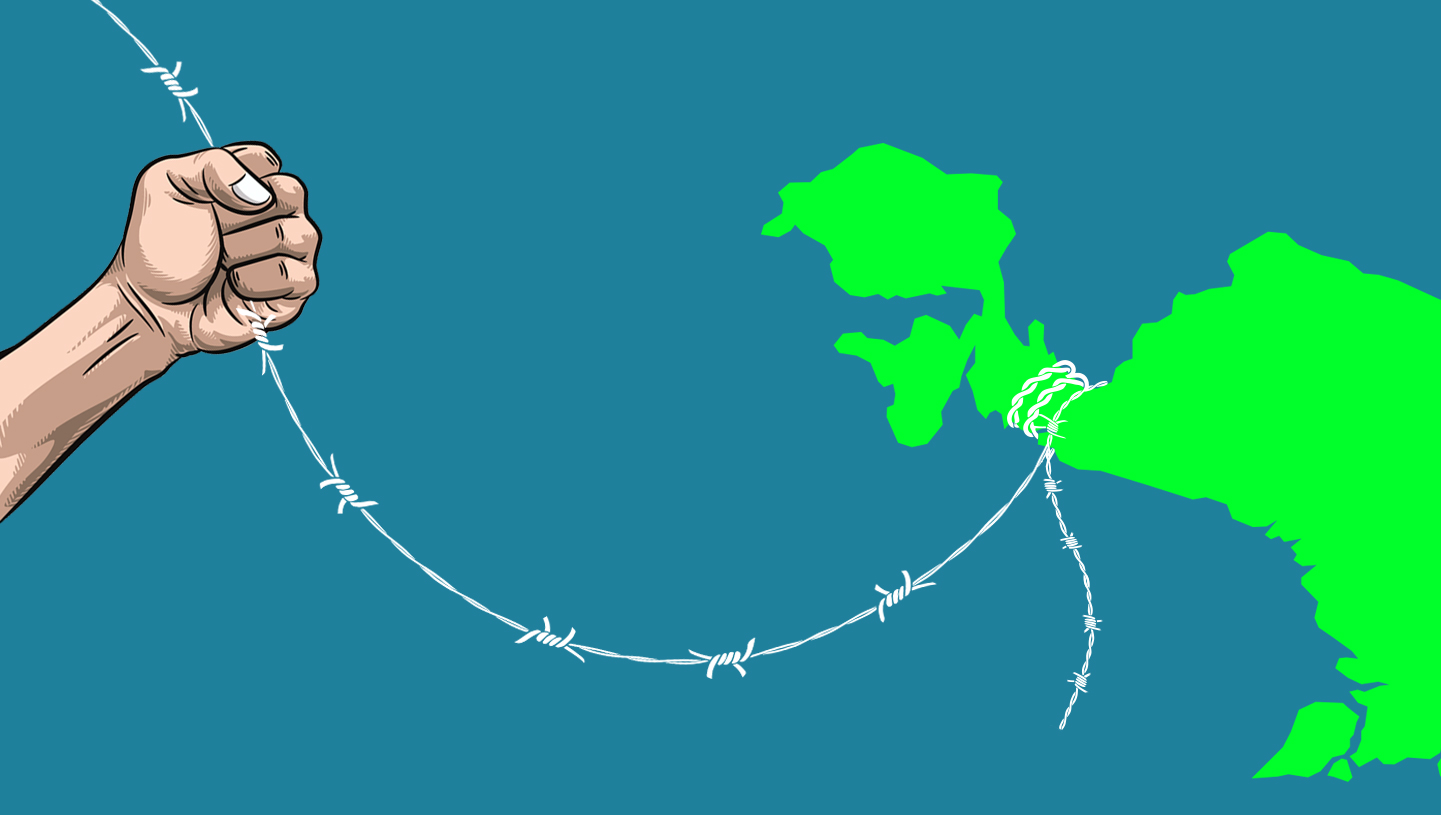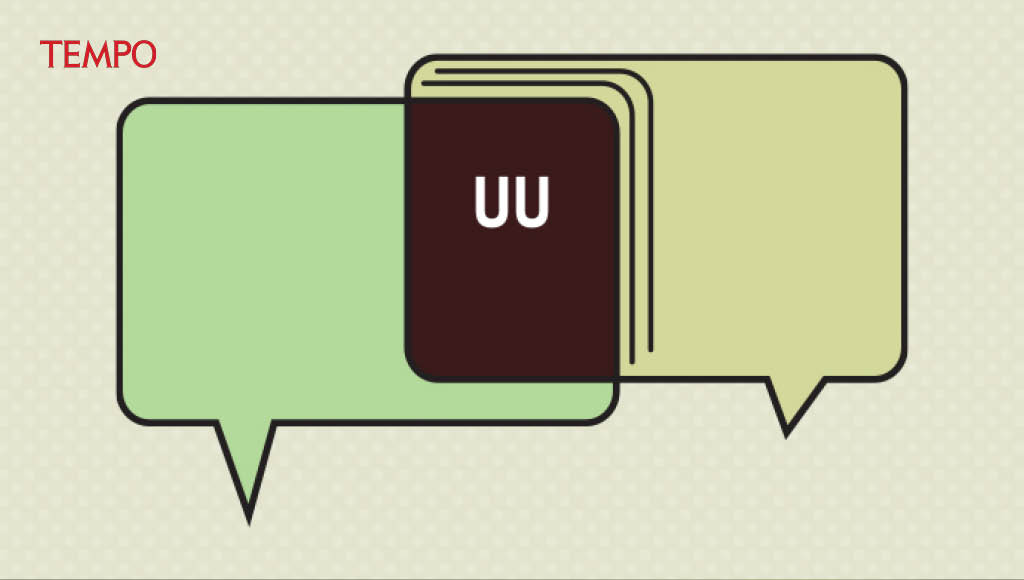Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
SEJARAH masuknya Islam di Indonesia adalah sejarah tentang toleransi, akulturasi, dan inklusivitas.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Syahdan, tersebutlah Abdul Rauf al-Singkili. Ia lahir di Singkil, Aceh, pada 1615. Nenek moyangnya berasal dari Persia, yang pindah ke Singkil pada akhir abad ke-13. Mula-mula belajar agama dari ayahnya, Rauf lalu menetap di Timur Tengah selama 19 tahun dan belajar agama di sana. Belakangan, ia dikenal sebagai penyebar Islam di pantai barat Sumatera.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Meski mendapat ilmu agama dari ulama ortodoks, Rauf pandai membawa diri. Dalam periode dakwahnya, Kerajaan Aceh dipimpin empat raja perempuan. Tapi Rauf tak pernah mempersoalkan kepemimpinan wanita betapapun itu bertentangan dengan ajaran yang diyakininya.
Datuk Ri Bandang lain lagi. Penyebar agama di Makassar, Sulawesi Selatan, itu menyebarkan Islam dengan cara yang sangat rileks. Ia tidak pernah mempersoalkan penduduk yang gemar minum arak dan berjudi. Jika mereka mau mengucapkan syahadat, baginya, itu sudah cukup.
Ciri akulturasi lain adalah kentalnya elemen mistis pada para penyebar agama itu. Waliyah Zainab, penyebar Islam lain di Gresik, Jawa Timur, pada abad ke-16, dipercaya kerap bepergian dengan mengendarai kelopak bunga pohon kelapa. Ri Tiro, ulama tasawuf yang menyebarkan Islam di Bulukumba, Sulawesi Selatan, diyakini bisa mendatangkan air hanya dengan menancapkan tongkat ke tanah. Menjalani hidup yang penuh warna, sebelas wali Nusantara yang diangkat majalah ini memang tak banyak dibicarakan—setidaknya dibanding Wali Sanga, yang sudah sangat terkenal.
Memang banyak versi cerita tentang masuknya Islam ke Indonesia. Ada ahli yang menyebutkan Islam dibawa pedagang dari Gujarat, India. Versi lain mengatakan Islam dibawa dari Mesir, Irak, Persia, Bengali, Kelantan, bahkan Campa dan Cina. Semua teori memiliki argumen arkeologisnya sendiri-sendiri. Menurut peneliti Azyumardi Azra, kepulauan Nusantara merupakan titik silang dari pergerakan para penyebar Islam tersebut.
Satu benang merah yang bisa dipelajari dari para penyebar religi itu adalah kesadaran akan pentingnya kebudayaan lokal. Itulah sebabnya praktik saling mempengaruhi antara Islam dan kebudayaan lokal tak terhindarkan. Praktik akulturasi, bahkan sinkretisme, itu berlangsung terus untuk waktu yang lama.
Di Sumatera Barat, gugatan untuk mengembalikan kemurnian agama kemudian datang dari kaum Padri pada 1803-1837. Dipimpin Tuanku Imam Bonjol, kaum Padri melihat kelemahan lain pada kelompok adat: korup dan kolaboratif terhadap penguasa kolonial.
Terlepas dari konteks politik itu, pertanyaannya: adakah dan apakah ajaran yang murni tersebut? Pertanyaan itu belakangan diajukan kembali oleh para sarjana Islam abad ke-21. Di Indonesia, salah satu yang terkenal adalah Nurcholish Madjid.
Bagi Cak Nur—demikian Nurcholish biasa disapa—Islam mula-mula muncul sebagai ajaran keselamatan. Dengan kata lain, Islam adalah pesan universal yang longgar dan berlaku umum. Anjuran Islam agar manusia bertakwa tidak diukur dari ibadah ritual yang diperintahkan belakangan, tapi dari kewajiban untuk menghargai sesama: menghormati ibu, menyantuni fakir miskin, dan tidak menghardik anak yatim. Beratus tahun setelah Nabi Muhammad wafat, lewat pelbagai proses politik dan sosial, barulah Islam menjadi organized religion—dengan pranata, struktur, dan hierarki di dalamnya.
Mun’im Sirry, sarjana Indonesia yang kini mengajar di University of Notre Dame, Amerika Serikat, memisahkan Islam teologis dan Islam historis. Lewat pelbagai studi kesejarahan, Mun’im menemukan diskoneksi antara teologi Islam dan sejarah Islam yang kerap diklaim para ulama. Dengan kata lain, baik Nurcholish maupun Mun’im menolak adanya Islam yang murni. Bagi keduanya, ajaran Islam tak bisa dilepaskan dari proses sejarah.
Di tengah bangkitnya konservatisme pemeluk agama, gugatan kedua sarjana itu layak direnungkan kembali. Kehendak sebagian umat Islam untuk mengembalikan kemurnian agama, termasuk dengan cara kekerasan, karena itu, tidak relevan lagi. Maraknya pengajian di kalangan masyarakat hendaknya disyukuri hanya jika ia menghadirkan kebajikan universal bagi orang ramai. Kita patut cemas jika sebaliknya yang terjadi: meluasnya eksklusivisme pemeluk agama, termasuk dengan memusuhi mereka yang dianggap tidak “murni”.
Para wali Nusantara sesungguhnya telah mempraktikkan apa yang disampaikan para sarjana Islam abad ke-21 itu: Islam sebagai proses sosial dan proses kultural. Yang juga penting: Islam merupakan rahmat bagi alam semesta ketika ia menghargai perbedaan, bersedia berinteraksi dengan keyakinan lain, dan tidak menganggap kebenaran hanya datang dari diri sendiri.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo