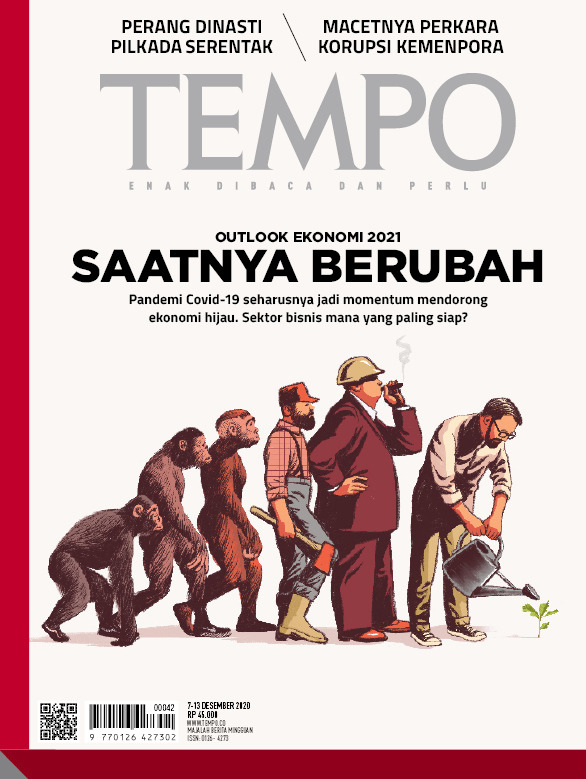Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
RASANYA baru kemarin kita mendengar instruksi Presiden Joko Widodo kepada jajaran pemerintahannya untuk menekan angka penularan virus corona. Pada pertengahan September lalu, masih terngiang di telinga kita bagaimana Jokowi memerintahkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengendalikan wabah di sembilan daerah “dalam dua pekan”.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sayangnya, wabah Covid-19 bukan prajurit, yang bisa tunduk kepada perintah atasan. Dua pekan berlalu dan sekarang kita semua bergidik melihat kurva penderita Covid-19 di Indonesia yang terus naik kian tajam. Pada Kamis pekan lalu, jumlah warga yang positif terkena Covid-19 tercatat 8.369 orang. Jumlah ini memecahkan rekor penularan harian tertinggi sejak Maret. Angka ini juga naik dua setengah kali lipat dibanding jumlah penularan satu bulan sebelumnya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Di banyak rumah sakit, kita mendengar kabar pilu soal ruang gawat darurat yang kian penuh dan ketersediaan ventilator yang menipis. Sejumlah pasien Covid-19 meninggal karena terlambat mendapat akses ventilator. Dengan sekitar 70 ribu kasus aktif di seluruh Indonesia sampai akhir pekan lalu, tekanan terhadap sistem layanan kesehatan tentu amat berat. Kondisi ini amat mengkhawatirkan.
Apalagi pekan depan kita akan mengikuti pemilihan kepala daerah serentak dan mengalami libur panjang Natal serta tahun baru. Tiga kegiatan itu bakal banyak diwarnai kerumunan. Dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat saja risiko tertular masih ada, apalagi tanpa protokol kesehatan sama sekali.
Sejak awal, Badan Kesehatan Dunia (WHO) sudah menganjurkan cara terbaik menghadapi wabah adalah menerapkan sistem cegah, deteksi, dan respons alias 3T (test, tracing and treatment). Pengetahuan ini datang dari pengalaman panjang dunia menghadapi wabah sejak flu Spanyol pada 1918 hingga polio, ebola, SARS, MERS-Cov, dan flu burung.
Masalahnya, pemerintah tak pernah benar-benar serius mengikuti saran ini. Alih-alih mencari solusi dengan pendekatan kesehatan berbasis sains, pemerintah malah condong memandang Covid-19 sebagai ancaman terhadap stabilitas keamanan dan pertumbuhan ekonomi. Karena itulah Presiden Jokowi menyerahkan kendali penanganan wabah kepada ekonom, politikus, dan tentara, bukan otoritas medis. Walhasil, setiap usul kebijakan pengendalian virus corona selalu dinilai dari apa dampak dan gangguannya terhadap perekonomian, bukan pada efektivitasnya mengekang penularan.
Ditambah, harus diakui, kapasitas aparatur pemerintah melakukan deteksi dan penelusuran riwayat kontak (tracing) belum sepenuhnya memadai. Sistem pendataan pasien juga masih amburadul. Padahal kedua hal tersebut merupakan faktor krusial dalam pendekatan medis dan sains. Tidak mengherankan, sembilan bulan berlalu, wabah justru makin sulit dikendalikan.
Kondisi ini diperparah oleh sikap tidak bertanggung jawab sejumlah elite. Mereka kerap memperlihatkan atau mendiamkan pelanggaran atas protokol kesehatan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, misalnya, nekat menemui Rizieq Syihab di rumahnya padahal pentolan Front Pembela Islam itu baru saja berinteraksi dengan puluhan ribu pendukungnya. Di daerah lain, elite lokal mengabaikan protokol kesehatan dalam kampanye dan membahayakan massa. Akibatnya, sejumlah kota dan kabupaten yang menyelenggarakan pilkada berubah statusnya menjadi zona merah Covid-19.
Kini pilihan Presiden Jokowi tak banyak lagi. Dia bisa belajar dari pengalaman sembilan bulan terakhir dan berbenah atau dia bisa bertahan dengan cara lama yang terbukti gagal. Satu hal yang pasti, Covid-19 bukan anak buah yang bisa enyah hanya dengan perintah.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo