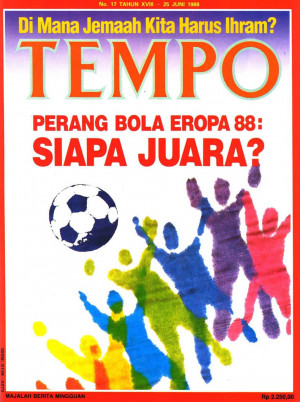GEPENG meninggal. Barangkali sejak Bing Slamet, tidak ada kematian seorang pelawak mendapat perhatian begitu besar dari masyarakat. Juga seperti pendahulunya itu, Gepeng mendapat penghormatan oleh deretan beribu manusia sepanjang jalan yang dilalui kereta jenazahnya, oleh lebih banyak lagi orang yang berjubelan di makam Banalaya dan liputan media massa di halaman depan mereka. Semua menundukkan kepala, menunjukkan simpati mereka dan tidak habisnya menyesali kepergian yang terlalu cepat dari pelawak itu. Barangkali lebih dari tokoh masyarakat lainnya, jarak seorang pelawak yang populer dengan khalayaknya jauh lebih dekat dan akrab, dan dengan demikian dituntut secara lebih keras oleh masyarakat. Pelawak yang populer terus dituntut agar ia tampil lucu. Sekali ia tidak berhasil tampil lucu, khalayaknya akan menghukumnya dengan meninggalkannya. Padahal, apakah sesungguhnya lucu itu? Lucu adalah pengenalan kembali hal-hal yang sesungguhnya pernah lewat dalam kehidupan sehari-hari kita, namun luput kita catat sebagai fenomena yang istimewa. Pelawak menunjukkan kepada kita akan keistimewaan fenomena itu dengan caranya yang khas. Semakin sang pelawak mampu memilih fenomena tersebut dari kehidupan sehari-hari kita dan menyuguhkannya dengan caranya yang.khas, semakin besar kemungkinannya ia berhasil menyuguhkan sesuatu yang "lucu". Tetapi mengapa begitu besar kita membutuhkan hal-hal yang "lucu" dalam kehidupan kita? Mungkin karena kehidupan semakin rutin kita lalui. Kehidupan telah semakin kita sekat-sekat dalam ritme yang ajek membosankan sehingga semakin banyak saja fenomena ulah manusia yang menarik luput dari perhatian kita. Fenomena itu kita onggokkan sebagai bagian dari keranjang sampah rutinisasi kita. Sementara itu, rutinisasi itu menjadi amat penting karena kepadanya kita bergantung untuk sesuap nasi kita. Maka, alangkah penting, bahkan mulia, profesi pelawak. Hidupnya dan sesuap nasinya dicurahkannya untuk mendeteksi cuwilan-cuwilan fenomena kehidupan yang tersuruk dalam keranjang sampah rutinisasi kita, sementara dia sendiri mungkin harus berjuang mati-matian untuk menghindari rutinisasi. Sekali dia terjerembab dalam rutinisasi, maka sang pelawak akan dimakan oleh rutin yang membosankan dan kemungkinannya akan seperti kita, kehilangan kepekaan mengenali kembali berbagai fenomena kehldupan yang menarik. Maka, leluconnya pun akan menjadi rutin yang membosankan pula. Barangkali kehidupan Gepeng yang bagaikan lakon Petruk Jadi Raja adalah, secara sadar atau tidak, upaya dia untuk berkelit dari ancaman rutinisasi. Suksesnya yang meteorik yang kemudian disertai oleh gaya hidup yang agak petentengan - membeli pistol, renggang dengan mentornya, Teguh, dan kawan-kawannya di Srimulat, kemudian Istri dan anak-anaknya, merasa mampu untuk mendirikan kelompok sendiri, mendalang - adalah mungkin rentetan bagian dari usahanya untuk tidak jatuh ke dalam satu rutinisasi hidup melawak. Agaknya, ada semacam obsesi pada dirinya untuk selalu tampil lucu. Dan kalau kita nilai bahwa penampilannya yang semula memang menunjukkan usaha untuk selalu maju dengan orisinil (yang dimulainya dengan "untung ada saya"), tetapi kemudian menunjukkan gejala yang semakin rutin dan tidak orisinil lagi, mungkin "mesin rutin" dalam kehidupan kita memang terlalu kuat untuk dilawan, bahkan oleh seorang pclawak yang sangat berbakat seperti Gepeng. Taksirannya tentang kehebatan kemampuannya mclawak rupanya disertai oleh salah taksir tentang kemampuannya untuk mengelola suatu organisasi pertunjukan. Dunia modern kita (bagaimanapun itu sosoknya) telah telanjur merangkul idiom rutinisasi sebagai suatu unsur penting dalam organisasi modern. Mungkin Gepeng terlambat gagal untuk mengenali organisasi pertunjukan sebagai suatu showbiz, suatu bisnis pertunjukan dengan segala uba rampe ritual barunya. Ketenarannya, bakatnya yang besar, ternyata tidak cukup tangguh dan liat untuk menghadapi tantangan suatu showbiz. Dan suatu siklus kegagalan dan frustrasi pun tidak dapat dihindarinya lagi. Insting dan intuisinya untuk melawak semakin tumpul. Kiat dan keterampilannya untuk mengelola suatu perusahaan tidak semakin berkembang karena memang bukan bidangnya. Gaya hidupnya yang cenderung bohemian, yaitu keterbatasan fisik tidak pernah menjadi perhatiannya yang utama, agaknya telah melengkapi pula kemunduran kesehatannya dalam lima tahun terakhir. Gepeng tidak bisa berkelit lagi. Di hadapannya suatu jalan buntu menunggu. Akan tetapi justru pada saat demikianlah Gepeng, sekali lagi, menunjukkan kemampuannya untuk berkelit dari impitan rutin - kali itu rutin kegagalan dan kesialan. Gepeng berbenah diri dengan memutuskan untuk rujuk kembali dengan istri dan anak-anaknya, dan juga dengan Srimulat, almamater yang membesarkannya. Dengan gagah Gepeng mengambil keputusan tersebut, mengabaikan kemungkinan untuk diejek sementara orang sebagai tindakan menelan ludah petentengan-nya di masa silam. Dengan gagah pula Gepeng mulai dengan perjuangannya untuk berkelit melawan impitan rutinisasi dengan lelucon baru yang segar, baik di panggung Srimulat, di panggung maleman Sriwedari, maupun di panggung pedalangan wayang kulitnya. Namun, berbagai macam penyakit yang sudah jauh menggerogoti tubuhnya mulai menyodorkan kuitansinya yang terakhir. Dan Gepeng harus membayarnya kontan pada tanggal 16 uni 1988 di rumah- saklt Pantl Waluyo, Solo. Pergilah sudah seorang pelawak berbakat, yang hanya dalam kurun waktu sepuluh tahun berdiri di depan kita, berusaha mengais-ngais dari sampah rutinisasi kita mutiara-mutiara kecil kehidupan kita, dan menunjukkan kepada kita akan lucu dan indahnya ulah kita sebagal manusia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini