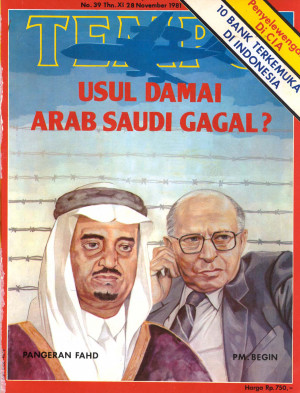". . . aku tidak mau jadi diktator. Fsukankah kamu tidak pula
menhendaki bahwa aku menjadi diktator?"
--Bung Karno, 17 Oktober 1952.
DI pagi Jakarta yang panas itu Bung Karno menolak untuk didesak
Ratusan demonstran berdiri di depan Istana Mereka itulah yang
beberapa saat sebelumnya memasuki gedung Parlemen. Di sana
serombongan orang berikat kepala merah mengobrak-abrik kursi.
DPR, bagi mereka, sudah jadi "Dewan Penipu Rakyat." Parlemen
harus bubar.
Bung Karno tak sependapat. Kita, katanya, "sebagai negara
demokrasi perlu alat demokrasi, yaitu suatu parlemen,
sebagaimana pula. halnya di negeri-negeri lainnya."
Kenapa di hari itu--yang kemudian dikenal sebagai hari
"peristiwa 17 Oktober" - orang banyak itu marah kepada DPI?
Sebagian analisa menyebut, bahwa massa itu digerakkan oleh para
pemimpin militer di Jakarta. Tentara memang tak puas dengan
dewan perwakilan yang jadi ajang partai-partai itu terutama
ketika di sana ada mosi yang menuntut, antara lain, peninjauan
kembali kepemimpinan Angkatan Perang Republik Indonesia.
Memang, di hari itu ke Istana menghadap sejumlah perwira tinggi.
Mereka menyatakan ketidakpuasan yang sama seperti yang
dinyatakan di kalangan demonstran. Tapi tentu saja harus diakui,
bahwa di luar para pemimpin partai, ada rasa capek umum terhadap
keadaan. Bukankah kabinet jatuh bangun oleh mosi demi mosi para
wakil partai, dan pemerintahan nyaris tak bisa bekerja?
Keadaan seperti itulah yang mendukung semangat antipartai yang
kemudian kian kuat suara dan langkahnya-sampai dengan hari ini.
Di tanggal 17 Oktober 1952 itu, Bung Karno memang belum setuju
betul. Seperti yang nampak dari studi yang menarik oleh Daniel
Dhakidae tentang tiga pemilihan umum Indonesia dalam majalah
Prisma September 1981, ada jarak jelas antara sang Presiden
dengan para pemimpin angkatan perang.
Tapi kemudian, dengan cepatnya jarak itu jadi jarak ntara dua
garis sejajar. Tanggal 28 Oktober 1956, Bung Karno bicara di
depan utusan pemuda. Dalam pidato yang kemudian dijuduli
Indonesia, Pilihlah Demokrasimu yang Sejati itu Bung Karno
menyebut mimpinya yang indah bahwa para pemimpin politik
bersedia menguburkan partai masing-masing.
Dan itu terjadi justru setelah pemilihan umum di tahun 1955 yang
berhasil membentuk DPR yang tak lagi "sementara".
Rupanya harapan Bung Karno tak terpenuhi. Ketika ia bicara di
depan massa 17 Oktober 1952, ia bicara bahwa pemilihan umum akan
menghasilkan suatu "parlemen yang sempurna". Tapi setelah pemilu
yang cukup bebas dan rahasia itu selesai, dan parlemen tersusun,
kenapa ia kecewa? Kenapa "parlemen yang sempurna" itu tak
terjadi?
JAWABNYA bisa banyak. Salah satunya mungkin karena Pemilu 1955
ternyata tak menghasilkan suatu mayoritas tunggal. Tak ada
pemenang yang dapat suara unggul di atas kontestan lain: PNI 57
kursi, Masjumi 57 kursi, NU 45 kursi dan PKI 39 kursi. Dan
karena partai-partai pemenang itu tak bisa bersama-sama
memerintah, stabilitas tak terjadi.
Syahdan, beberapa tahun kemudian -- setelah melalui banyak
kejadian yang keras dan berdarah - lahirlah Orde Baru. Pemilu
1971 menghasilkan suatu mayoritas tunggal, Golkar. Pemilu 1977
hanya mengulangi apa yang terjadi. Suatu pemerintahan yang
terkuat dalam sejarah Indonesia modern telah lahir, dan stabil.
Orang bisa bersyukur. Tapi orang bisa bertanya juga sejauh mana
suatu mayoritas tunggal berbeda dengan partai monopolistis --
yang misalnya ada di negeri komunis. Kita seharusnya tahu
jawabnya: monopoli lahir dari keserakahan, keserakahan lahir
dari ketidakpastian, dan ketidakpastian lahir mungkin karena
kaki palsu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini