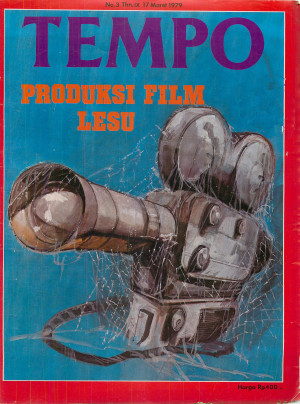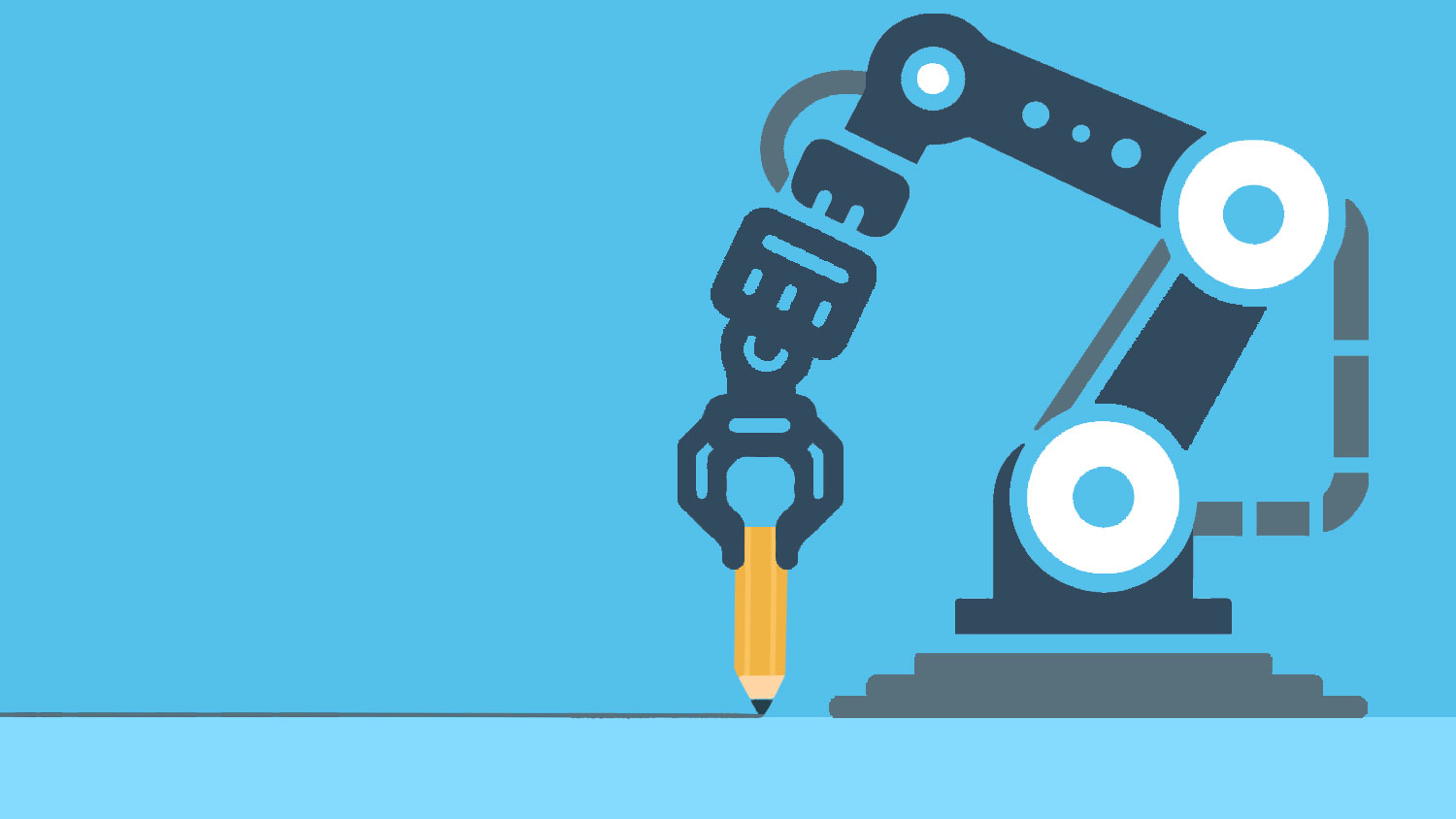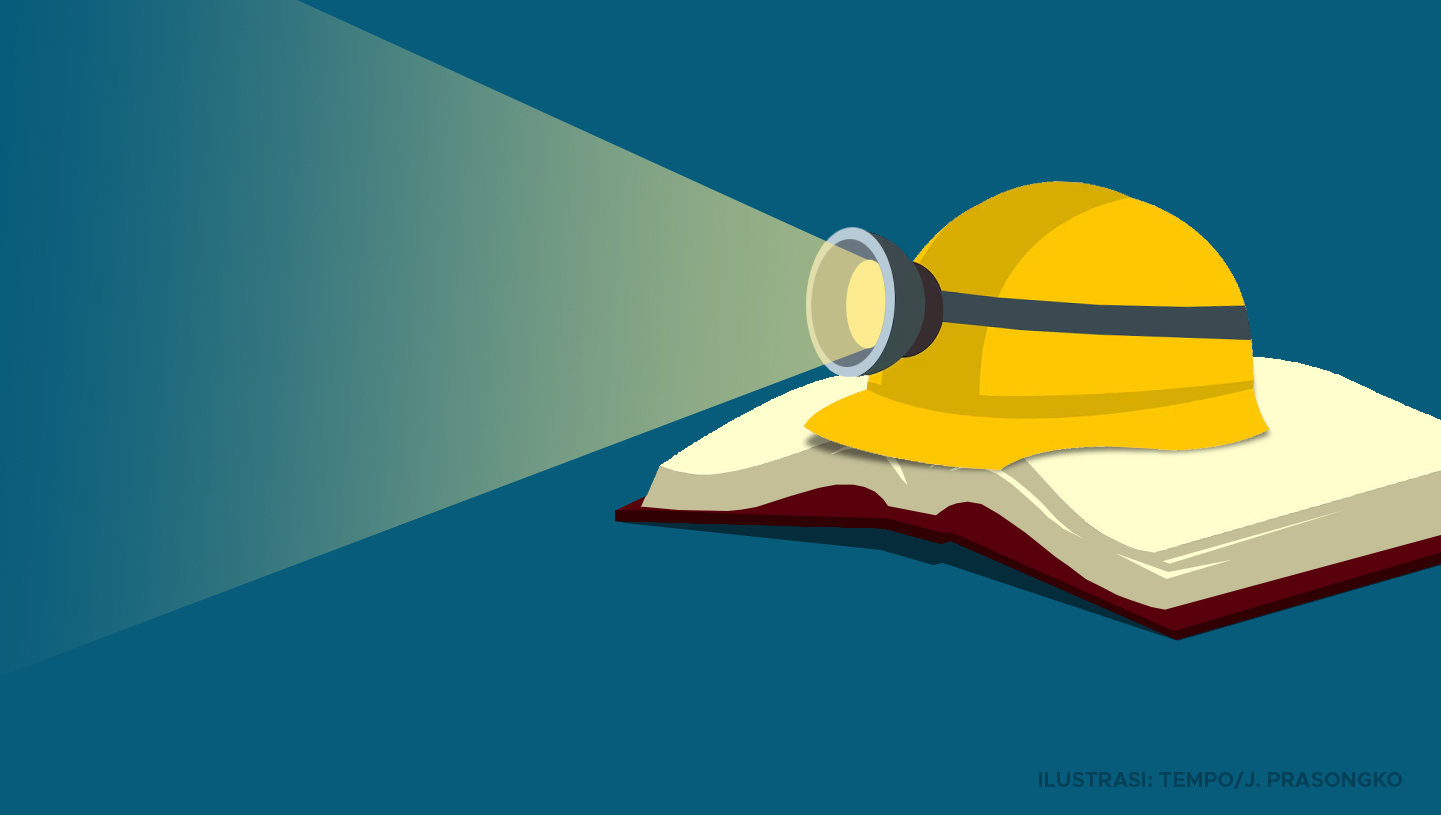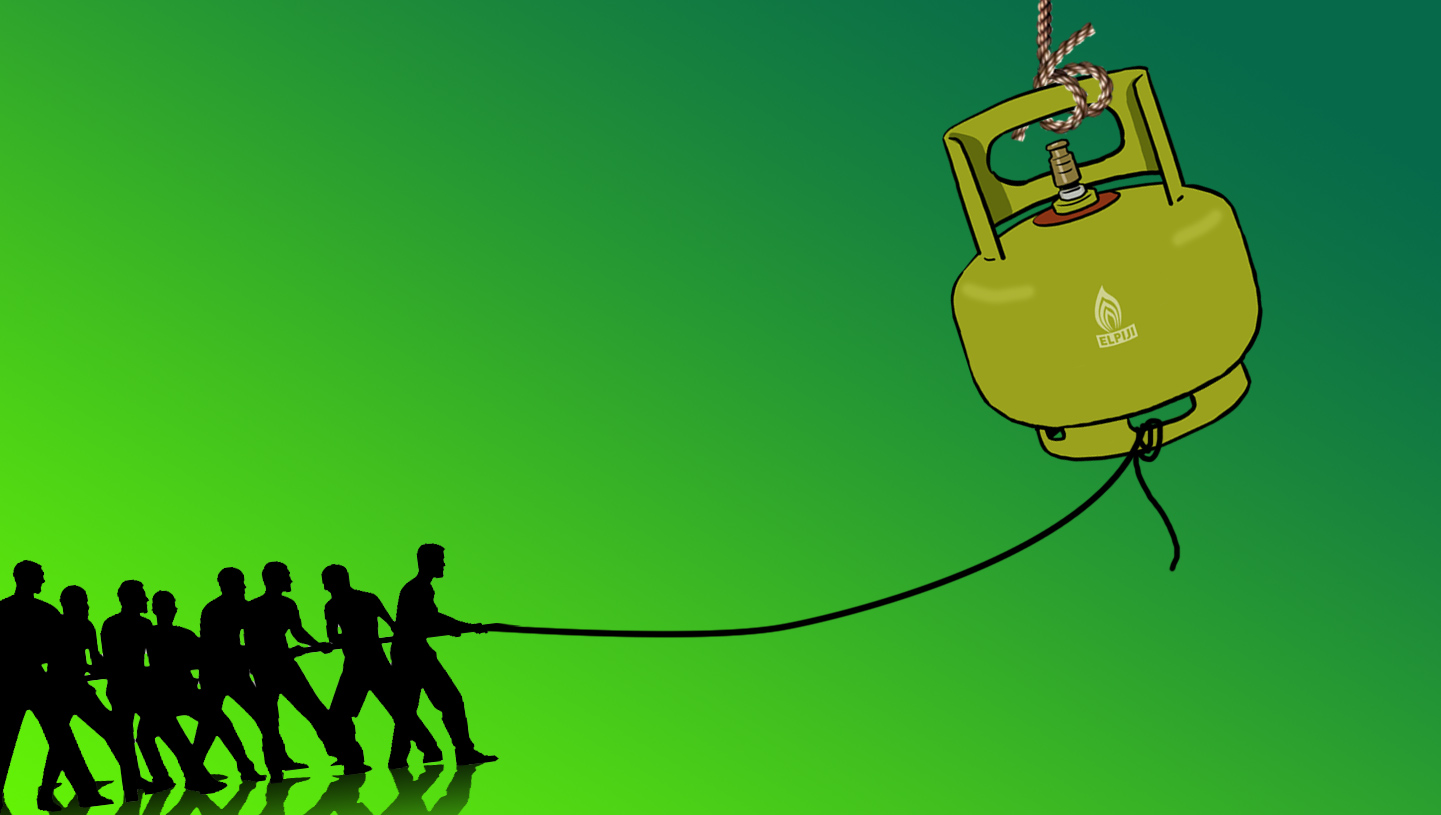SETIAP kali golongan agama di Dunia Arab atau negeri-negeri
Muslim lainnya mengalami arus pasang dalam tuntutan-tuntutan
politik mereka, khususnya yang menyangkut pelaksanaan syariat
Islam, orang pun segera menjadi waswas -- terhadap apa yang
dicemaskan sebagai suatu kebangkitan kembali dalam
fundamentalisme Islam.
Tak ada mimpi yang lebih buruk -- juga tidak di lapisan
cendekiawan dalam kelompok Islam sendiri -- daripada menampak
buya-buya fukaha (para ahli fiqh red) tampil mengatur jalannya
suatu pemerintahan, seperti yang didambakan Khomeini di Iran.
(Laporan Utama TEMPO 24 Pebruari tetap tak berhasil membuat
eksperimen dengan hukum Islam di berbagai negara Arab itu nampak
lebih simpatik, meskipun telah dicoba menampilkannya seobyektif
mungkin). Yang tersisa masih saja gambaran algojo berwajah
tegang dengan pedang teracung, siap mengerat lengan atau
memancung leher para warganegara bernasib malang.
Dan itu bukanlah khayal. Koran kita (kalau tak salah Berita
Buana) pernah menyiarkan foto sepotong tangan dengan darah yang
masih segar tergantung di depan publik yang lalu lalang di
sebuah pasar negeri Mekkah. Atau foto orang yang dihukum dera
atau digantung di muka umum. Ingatlah juga, kasus Faisal ibn
Musaid yang dipenggal di depan khalayak. Belum lagi, amit-amit,
panorama khas ini: setiap azan ditempikkan dari moncong-moncong
pengeras suara, orang pun dihalau dengan pentungan karet ke
mesjid-mesjid.
Lalu gerombolan peminta-minta itu, yang berkerumun di setiap
mulut pintu mesjid atau makam-makam keramat, siap menukar
sedekah para peziarah dengan seulas ayat Quran. Dan somewhere di
bawih langit-langit kemah yang mewah, sang Menteri Urusan Minyak
bersantai dengan isteri seorang diplomat dari negara superpower
sambil berbincang mengenai bukunya tentang "ekonomi Islam".
Potret klasik "negara Islam" macam itulah yang agaknya membuat
Shapur Bakhtiar merasa alergi. Sesaat sebelum kejatuhannya ia
berkata getir "Republik Islam ini tidak dapat saya fahami. Saya
belum pernah melihatnya dalam buku. Yang saya inginkan bukan
kediktatoran Shah, bukan juga republik Islam seperti Libya atau
Pakistan."
Kalau mau jujur, sebenarnya tokoh-tokoh pemikir Islam lainnya
sama saja dengan Bakhtiar -- mereka juga belum faham benar
dengan ide "negara islam" itu. Karena itulah tokoh seperti Muh.
Natsir, Wakil Presiden Muktamar Alam Islami itu, ketika ditanya
TEMPO tentang kedudukan non-Muslim di negara Islam segera 'lari'
ke zaman Nabi. Sebab hati kecii Natsir pasti merasa, negara
macam Saudi bukanloh model yang ideal bagi suatu negara islam
kontemporer. Tentu saja di zaman Nabi Muhammad seorang Muslim
yang memutuskan untuk pindah agama menjadi Kristen, misalnya)
tidak perlu diadili di hadapan regu tembak, seperti yang konon
diundangkan di Mesir atas nama syariat Islam.
Paling-paling, Nabi Suci akan berkomentar: "Mau percaya silakan,
mau kafir silakan" (Faman sya-a falyukmin, waman sya-a
falyakfur), sesuai dengan falsafah Quran tentang kebebasan
beragama, induk dari 'Madinah Charter' itu. Lebih jauh, sang
Nabi akan mamparsilakan umat Kristus itu bersembahyang di
mesjidnya sendiri. "You are welcome," sabdanya. Kenapa Arab
Saudi dan lain-lain tidak berani melakukannya sekarang?
Maka alangkah naifnya pernyataan Natsir, bahwa yang bukan-Muslim
seakan warganegara klas satu di negara Islamnya, hanya lantaran
mereka tidak dilarang minum alkohol atau berhari Minggu atau
Sabat. Jelas Natsir gagal menemukan contoh aktual tentang bentuk
jaminan yang pasti mengenai hak-hak asasi manusia di "negara
Islam", baik bagi yang muslim mapun yang non-Muslim.
Paling tidak, ia akan terbentur kepada pernyataan Syuba Khan,
Presiden Liga Kristen Nasional Pakistan, yang disiarkan liwat
s.k. Aman Karachi, 29 September 1974, di mana ia dengan keras
memperingatkan pemerintahnya (ketika itu Ali Bhutto), bahwa
melihat gencarnya tekanan fisik terhadap kaum minoritas
Ahmadiyah oleh kelompok mayoritas yang bergerak di bawah
bayang-bayang keputusan Majlis Nasional yang mengkafirkan kaum
Ahmadiyah, maka enam juta minoritas Kristen di negara Republik
Islam itu menyatakan tidak yakin hak-hak mereka benar-benar
terjamin dari ancaman mayoritas Muslim. Tercerminkah semangat
'Madinah Charter' dalam fakta ini? Wallahu alam.
Agaknya tak seorang Muslim pun masih sangsi, bahwa seperti juga
di zaman Nabi Suci dalam zaman mutakhir ini hukum Islam yang
sejati masih tetap mampu menyumbangkan sesuatu. Masih relevan.
Tinggal lagi bagaimana kita menyimak dari kandungan pesan sang
Nabi -- selain membaca yang tersurat belaka. Jangan sampai
keliru lagi dalam menangkap persepsi. "Buang abunya, ambil
apinya," bak kata Bung Karno.
MAHAR EFFENDI
Jl Gunung Batukaru 2,
Sesetan, Denpasar.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini