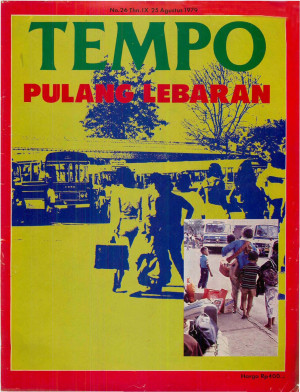BESOK 17 Agustus 1979. Malam itu karena sesuatu hal ia menemukan
dirinya di antara sejumlah kenalan, yang menyedot fruit punch
pelan-pelan di restoran sebuah hotel kelas satu di Jakarta,
sementara jam bergerak melewati pukul 23.00.
Apakah ia kesepian?
Tapi waktu mengalir dengan gurauan. Seseorang bercakap tentang
inflasi. Seseorang lain bercakap tentang gosip politik.
Seseorang mengeluh tentang rambut rontok pada usia ke-39. Apa
yang terjadi dengan bisnisnya anak pak Anu? Apakah kau masih
juga jogging, Yos? Seseorang berbicara tentang kejadian di
Siria-ria. Seseorang lain tentang aktifitas kepundan Krakatau.
Ayatullah Khomeini. Mana tempat sate yang terenak?
Jam bergerak melewati pukul 24.00.
"Kita minum untuk ulangtahun Republik," seseorang berseloroh.
Lalu seseorang berkata tentang rasa lapar larut malam, dan
mereka memesan makanan. Ia pesan bubur ayam, dengan telor mentah
yang kuningnya menggelinding.
Apakah ia sebenarnya merasa lapar?
Ia teringat orang tuanya yang bangkrut berjualan nasi di kampung
sewaktu masih hidup. Ia teringat bagaimana ia takut terlantar
dan tiap kali bergulat hebat untuk angka-angka ujian. Ia lulus
bagus, dapat beasiswa ke Jerman dan pulang dengan ijaah
arsitektur.
Ia menyapu mulutnya. Di ruangan restoran itu musik rupanya
berganti ke kaset-kaset lagu perjuangan dengan organ. Empat
orang tamu di sebelah kanan menyibukkan mulut mereka dengan
sirloin steak.
Ia tiba-tiba terfikir bahwa 34 tahun yang lalu -- juga sebuah
malam puasa -- orang-orang pernah bergadang menyiapkan
kemerdekaan. Tapi cuma sebentar.
Ketika acara makan larut malam yang dijuluki "sahur" itu
selesai, dan semua keluar ke tempat parkir ia melihat bulan
sabit samar-samar di iangit, melengkung di atas sebuah patung
dan sebuah spanduk "Dirgahayu .... "
Apakah ia gembira? Ia merasa kenyang.
PAGI itu ia berada di antara selusin orang yang ikut upacara
penaikan sang Merah-Putih di lapangan kecil RW-nya. Dan ikut
menyanyi, tapi tak persis benar, lagu Syukur.
Ada anak-anak berbaju putih-putih berbaris. Ada anak-anak
berbaju pramuka berbaris. Seperti biasa tak ada pidato karena
Pak Ketua RW memang tidak suka pidato dan kebetulan pula waktu
itu ia sakit gigi. Hanya ibu guru kepala sekolah setempat ingin
menyampaikan wejangan kepada anak-anak, sesuatu tentang hari
kemerdekaan, perjuangan, puasa, dan "rajin-rajinlah belajar."
Ia memasang kacamata hitamnya karena hari mulai panas.
Lalu acara selesai.
***
HARI 17 Agustus adalah hari libur dan ia pun berbaring di tempat
tidurnya seraya menatap langit langit. Ia coba membaca sebuah
novel murahan tapi hatinya tidak di lembar-lembar itu. Ia
mendengar radio tetangga sedang memperdengarkan lagu-lagu
revolusi Cornel Simanjuntak.
Apakah ia terharu
Lebih 20 tahun yang lalu ia masih seorang anak dan mendengarkan
kepala sekolahnya berpidato di lapangan, setelah bendera selesai
dinaikkan di pagi 17 Agustus. Kepala sekolah itu seperti
Napoleon, ia ingat kini: pendek dengan perut membuncit tapi
wajah angker -- terutama bila bercerita tentang pertempuran di
Surabaya.
Dan ia tidak memberi wejangan. Ia cuma bercerita, tentang
anak-anak muda di garis depan -- yang menggempur Nica seperti
orang gila. Para murid seperti ternganga menyimak, guru-guru
lain merunduk terharu, karena mereka tahu betul pak kepala
sekolah bukan mendongeng. Pak Kepala Sekolah, Napoleon coklat
itu, dulu juga di garis depan.
Tapi di mana Napoleon itu kini: benarkah ia meninggal di sebuah
penjara? Waktu mengalir. Ia tahu banyak hal yang hilang.
Kemudian banyak hal di peroleh. Ia merasa risau, mungkin sedih,
tapi Tuhan, benarkah ia tak bisa merasa bersyukur sama sekali?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini