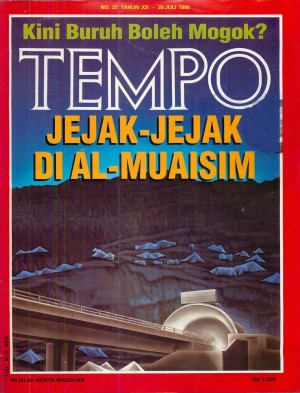AJIP ROSIDI* * Sastrawan dan bekas Ketua Ikapi (Ikatan Penerbit Indonesia) SECARA garis besar usaha perbukuan kita terbagi dalam tiga jalur: usaha penerbitan buku pelajaran untuk sekolah-sekolah, usaha penerbitan bacaan umum (termasuk sastra dan hiburan), dan usaha penerbitan buku agama. Pada masa penjajahan Belanda, penulisan dan penerbitan buku pelajaran sekolah dikuasai orang-orang Belanda. Kalaupun ada pribumi menulis buku pelajaran, umumnya sebagai pembantu atau ditunjuk orang Belanda. Sedangkan penerbitnya 100% di tangan orang Belanda. Penerbitan buku bacaan umum berbahasa Melayu pada masa itu dikuasai orang-orang Cina. Pribumi hanya bergerak dalam usaha penerbitan buku berbahasa daerah saja (meskipun ada juga usaha penerbitan buku bacaan yang dilakukan 100% oleh pribumi, mulai dari penulisan sampai penerbitannya, seperti dilakukan beberapa orang di Sumatera Barat dan Medan). Pemerintah Hindia Belanda, yang merasa khawatir akan dampak negatif usaha demikian, merasa perlu mengimbanginya dengan mendirikan penerbit buku bacaan rakyat (kantoor voor de volkslectuur), yang dinamakan Balai Pustaka, pada 1908. Sampai masa pendudukan Jepang boleh dikatakan Balai Pustaka tak pernah menerbitkan buku pelajaran karena bidang itu jadi garapan penerbit swasta Belanda. Usaha penerbitan buku agama dimulai dengan pencetakan buku-buku agama Kristen oleh misi dan zending -- umumnya oleh orang Belanda. Penerbitan buku agama Islam dimulai oleh orang-orang Arab, yang semula mengimpor buku-buku yang diperlukan dari Mesir atau negeri Islam lainnya. Kebanyakan buku itu dipakai di pesantren-pesantren. Sesudah Indonesia merdeka, terjadi berbagai perubahan dalam ketiga jalur itu: penerbitan buku pelajaran umumnya diambil alih pribumi. Dalam usaha penerbitan buku bacaan umum juga, orang-orang Cina sedikit demi sedikit mundur, kecuali dalam usaha penerbitan cerita silat, dan itu pun diimbangi oleh cerita silat pribumi. Tetapi usaha percetakan, pengadaan kertas, dan toko-buku umumnya tetap dikuasai orang-orang Cina. Hanya toko-toko "kitab" yang tetap dikuasai orang-orang Arab, meskipun dalam usaha penerbitan buku-buku agama Islam nampak kian aktifnya penulis-penulis pribumi, dan juga dalam bidang penerbitannya. Usaha penerbitan buku bacaan umum dan buku-buku agama (sebelum Departemen Agama turut campur dalam urusan kurikulum pesantren tatkala Prof. Mukti Ali menjadi menteri) boleh dikatakan berjalan dengan wajar. Tapi tidak demikian halnya dengan usaha penerbitan buku pelajaran. Pernah ada masa ketika inspeksi-inspeksi pengajaran di tingkat provinsi diberi wewenang menentukan buku pelajaran yang harus dipakai di daerahnya. Maka, para penerbit pun aktif mendekati para pejabat di kantor itu yang diikuti kegiatan luar biasa para inspektur menulis buku-buku pelajaran. Ekses-ekses timbul: seorang penerbit muda tak segan-segan "memotong" usaha penerbitan ayahnya sendiri dalam usaha "mendekati" pejabat yang berwewenang dalam bidang penentuan buku pelajaran sekolah. Seorang kacung berjiwa wiraswasta yang bekerja di sebuah penerbit di Bandung, setelah tahu caranya "mengegolkan" buku pelajaran untuk SD, menyusun sebuah buku atas namanya sendiri walaupun dia sendiri tak pernah tamat SD. Ternyata, buku ini plagiat dari buku lain yang sudah beredar. Yang menjadi korban adalah orangtua murid. Mereka harus membeli buku baru setiap ada penggantian pejabat. Keadaan itu baru berhenti tatkala Menteri P dan K Mashuri, S.H., pada awal masa Orde Baru menetapkan bahwa semua buku pelajaran disediakan oleh pemerintah dengan cuma-cuma. Penulisannya dilakukan oleh tim-tim yang diangkat pemerintah. Karena setiap buku untuk setiap bidang pelajaran dipakai di seluruh Tanah Air pada jenjang sekolah yang sama, maka nuansa budaya dan masalah setempat tidaklah dapat ditampung di dalamnya, termasuk juga dalam buku pelajaran bahasa nasional, padahal kesulitan dalam mempelajari bahasa Indonesia yang dihadapi anak-anak dengan latar belakang budaya Jawa misalnya berlainan dengan mereka yang berlatar belakang budaya Aceh atau Bugis. Karena pemakaiannya luas, maka setiap jilid buku dicetak sampai ada yang jutaan eksemplar. Maka, banyaklah penerbit buku pelajaran yang banting setir menjadi pencetak. Para inspektur penulis dan pengesah buku pelajaran menjadi kekeringan, dan yang menjadi basah bahkan kebanjiran adalah para pejabat yang mempunyai wewenang menetapkan percetakan yang akan mendapat order mencetak buku-buku pelajaran itu. Pemerintah tidak dapat terus-terusan menyediakan kebutuhan akan buku pelajaran yang dari tahun ke tahun kian meningkat. Mula-mula Balai Pustaka diberi hak mencetak buku-buku tersebut buat mencukupi kebutuhan pasar bebas. Penerbit swasta diberi kesempatan untuk menerbitkan buku-buku pelengkap, bahkan buku pelajaran untuk mata pelajaran tertentu. Di samping itu, untuk mengisi perpustakaan-perpustakaan sekolah akan buku-buku bacaan dilaksanakanlah Inpres Sekolah dan Buku Bacaan yang membeli buku-buku bacaan yang dianggap cocok untuk SD dalam jumlah puluhan sampai ratusan ribu eksemplar setiap judulnya. Tak pernah sebelumnya buku semacam itu dicetak sebanyak tersebut sehingga para pengarang dan para penerbit yang "kejatuhan Inpres" seperti dapat durian runtuh. Tapi dalam kesempatan-kesempatan demikian, sangatlah berperan mereka yang duduk dalam tim-tim penilai. Berbagai cerita burung beredarlah tentang adanya permainan dalam pemilihan buku-buku tersebut. Menteri P dan K ad interim waktu itu, Umar Ali, mengatakan bahwa dengan adanya Inpres itu diharapkan penerbit nasional dapat memperkuat modalnya. Ternyata, kebanyakan buku yang dipilih panitia bukan terbitan mereka yang telah memperlihatkan kesungguhannya dalam bidang penerbitan buku demikian, melainkan terbitan para penerbit "musiman" yang baru didirikan untuk menampung durian runtuh dari proyek Inpres. Karena pasaran buku yang besar masih juga sekolah-sekolah dan sampai sekarang sekolah-sekolah sendiri belum pernah diberi kebebasan untuk menentukan sendiri buku-buku yang akan dipakainya, maka keputusan-keputusan dari tim atau pejabat yang diberi wewenang untuk menetapkan buku-buku yang boleh dipakai di sekolah dianggap sebagai pedang sakti. Karena baru-baru ini Direktorat Sarana Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah membuat daftar bukan buku-buku yang boleh dipakai, melainkan "yang tidak memenuhi syarat" (artinya yang tak boleh dipakai), maka daftar itu di kalangan toko buku dan perbukuan disebut sebagai "daftar buku beracun". Apakah ada permainan sim salabim di belakang "daftar buku beracun" itu? Tentu saja tidak ada. Bukankah setiap pejabat negara kita adalah putra-putra bangsa terbaik yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan telah pula bersumpah untuk tidak menerima apa pun untuk pribadi dalam menjalankan tugas? Kalau sampai para pejabat yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan bangsa menyalahi sumpahnya sendiri, bagaimana nasib bangsa kita kelak?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini