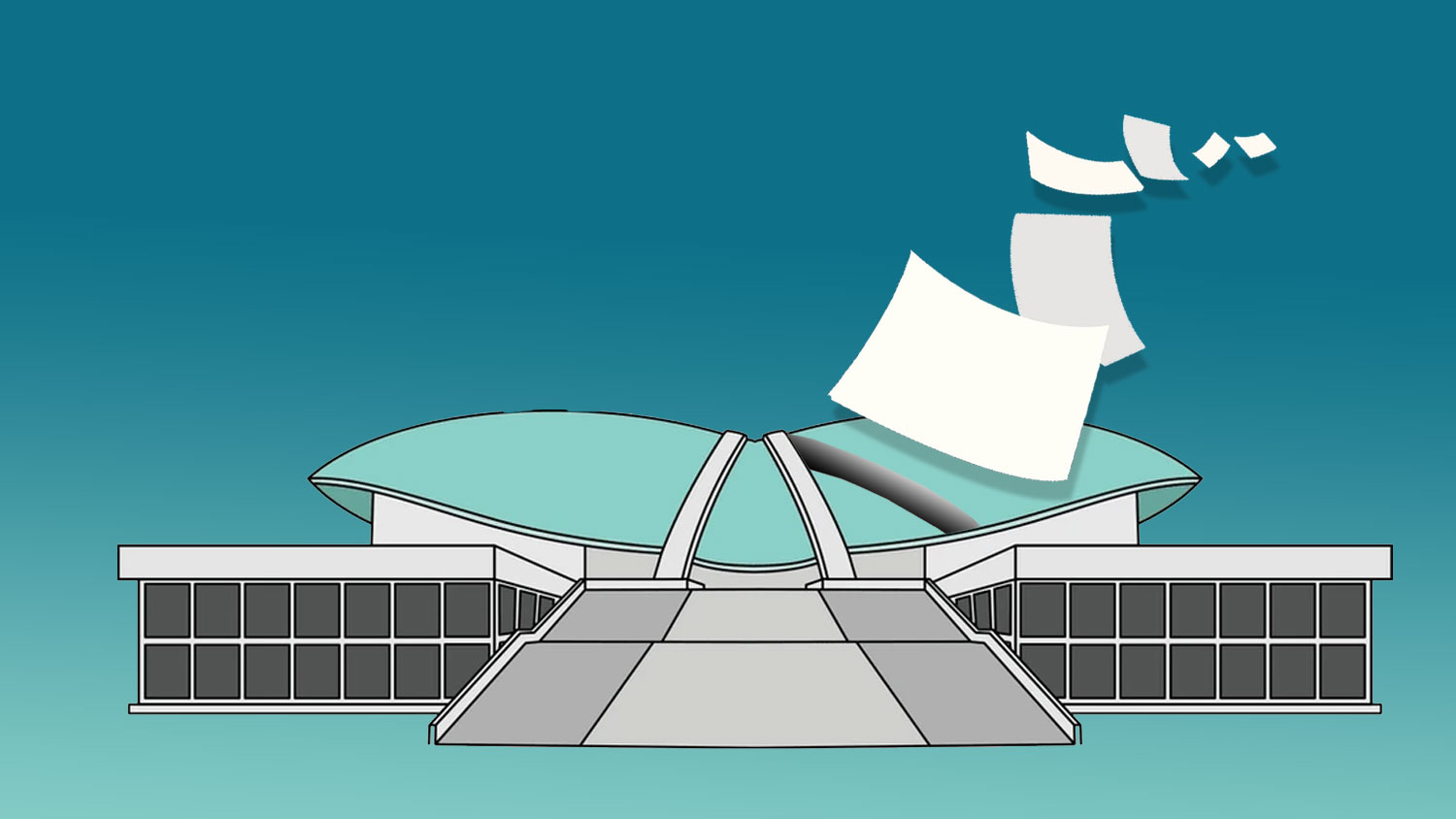Ibadah Haji dan Berseah Diri SOETJIPTO WIROSARDJONO AKHIRNYA dengan nawaitu dan bismillah, berangkat juga Pakde Modin ke Mekah. Kami semua bergembira. Betapa tidak. Tatkala Lik Kandar mengingatkan amanah semua kerabat agar sokoguru keluarga ini segera melengkapi rukun Islamnya yang kelima, Pakde Modin tak bergeming. Bahkan tatkala saya mengisyaratkan harapan agar Pakde Modin berkenan segera pergi haji, saya dibentak. "Haji itu urusan panggilan. Awas, jangan kamu ulang-ulang lagi imbauan itu. Yang paling tahu kapan saya istitha'ah dan siap memenuhi panggilan Nabi Brahim hanya saya sendiri. Bukan Kandar, bukan kamu." Sejak itu saya tak berani mengutik-utik perkara itu. Kenapa tiba-tiba Pakde Modin tahun ini bulat tekadnya untuk menunaikan ibadah haji? Kami semua tak berani menerka-nerka. Insya Allah, betul-betul karena panggilan Nabi Ibrahim as. Tatkala kami menawarkan untuk mengambil haji plus, Pakde Modin tersenyum saja. "Saya yakin beribadah haji, seperti umat Islam yang lainnya. Bukan mau tamasya jalan-jalan ke Mekah? Masa, saya tega makan enak, tidur nyenyak, di antara takbir umat Islam, yang menyerukan kebesaran Allah di sana," katanya pendek. Saya khawatir. Usia beliau sudah lanjut. "Nopo kaji plus niku pahalanya minus to, Pakde?" (Apakah haji plus itu pahalanya minus, Pakde) saya menggoda. "Saya berangkat kaji ini karena ikhlas, dan hanya mengharap ridho Allah. Memenuhi panggilan taukhid yang diserukan Nabi Brahim. Bukan mencari pahala! Ini kan ngibadah, bukan urusan nadar atawa ngalap berkah. Mana mungkin kamu hendak membedakan saya dari saudaraku umat Islam yang lain?" Sejak itu Pakde Modin sudah tidak sabar lagi. Kudanya si Jiteng, yang biasanya pagi dielus dengan kasih sayang, terabaikan. Ditinggalkan semua kareman dan klangenan yang dulu menjadi obsesi hidup duniawinya. Kuda, dokar, nasi soto, atau sapi-sapinya. Kini Pakde Modin benar-benar tampak sedang jatuh cinta pada khaliknya. Saya lalu teringat. Atas izinnya saya sudah mendahului berangkat haji beberapa tahun yang lalu. Tapi persiapan batin, astagfirullah, saya mesti bercermin pada Pakde saya ini. Memang, tatkala berdiri dan bertakbir di depan Maqam Ibrahim saya menengadah. Seraya mengangkat kedua tangan, saya mengagungkan kebesaran Allah semata. Tetapi saya toh masih juga tak bisa lupa istri yang setapak ada di belakang saya. Jangan-jangan dia terempas oleh gelombang manusia yang sedang tawaf. Jangan-jangan ia dijaili syaitan yang menjelma jadi jemaah yang usil tangannya. Mudah-mudahan tak demikian dengan Pakde saya. Memang, tatkala saya bertawaf bersama arus manusia yang gemuruh itu, saya tak mementingkan diri sendiri, ngalah, tawadhu, dan tasamuh. Tetapi tatkala kekhusyukan saya dipotong oleh barisan jemaah yang menerobos menyudut ke arah Hajar Aswat, hati saya nelongso juga. Seraya melanjutkan tawaf mengelilingi Ka'bah berulang-ulang, sebanyak kelipatan tujuh itu, saya menghibur diri. Barangkali ini cobaan juga, pikir saya. Siapa tahu, mereka itu adalah barisan para malaikat yang senantiasa tawaf pula, bukan hanya mengelilingi Ka'bah. Tetapi juga mengitari bumi dan jagat raya. Mencatat ulah dan pikiran yang ada di benak manusia, termasuk saya. Mudah-mudahan Pakde Modin nanti juga lapang dadanya, besar-besar maafnya. Memang, tatkala saya melempar jumroh, yang teringat adalah teladan Nabi Ibrahim as, Nabi Ismail as, dan Ibu Siti Hajar yang teguh menolak godaan syaitan. Saya sungguh berniat, hendak meneguhkan iman, mengukuhkan takwa. Tetapi tatkala payung saya terlempar oleh empasan angin, mata saya toh masih memaling ke belakang. Untuk mencari payung dekil yang tak ada harganya itu. Masya Allah, saya pun mengoreksi diri sendiri dan kembali " bersikap sempurna". Saya bersalawat untuk menolak godaan syaitan yang bisa macam-macam bentuknya itu. Mudah-mudahan Pakde Modin juga tak diganggu ingatan pada dokar, kuda, sapi, pabrik lestari, yang menjadi denyut klangenan selama hidup duniawinya. Memang, tatkala wukuf di Padang Arafah, saya dengan khusyuk salat berjamaah, mendengarkan khotbah dan doa dengan semangat serah diri yang menyayat hati. Tetapi ketika orang pada menangis bercucuran air mata, pandangan saya toh terantuk pada teman saya yang sesenggukan menemani ratapan istri yang ngglendot di pundaknya. Saya segera sadar, lalu saya beraminamin, seraya menatap lautan manusia berihram yang berwarna putih semua. Inikah simbol persamaan manusia di depan Tuhannya? Dan yang membedakan hanyalah amal dan ibadahnya? Apakah teman saya dan istrinya itu menyesali sesuatu? Di mana kekuasaan itu? Di mana harta itu? Di mana ilmu, seni, budaya, kecerdasan bahkan kewaskitaan yang telah dihimpunnya itu semua? Allahuakbar Walillahilhamd. Pakde Modin telah berangkat menunaikan ibadah haji. Insya Allah, ia akan memantabkan taukhidnya, menyempurnakan ibadahnya. Sebenarnya, untuk Pakde Modin, saya ingin menitipkan puisi Mas Taufiq Ismail yang mengingatkan perkara ziarah di kubur sendiri. Kata Mas Taufiq, karena diri kita ini hanyalah segumpal protein, air, dan jasad yang beragam- bak lempung beragam- yang dirakit dalam empat ratus tulang belulang dan tiga belas persendian utama, dirajut dengan urat saraf, pembuluh darah, dan sistem pencernaan yang sempurna, dilengkapi dengan sepuluh ribu juta netron yang ditebarkan di otak dan digerakkan oleh sinyal-sinyal panca indera yang dipinjamkan oleh Allah kepada kita, termasuk untuk Pakde Modin. Pakde Modin, setelah sempurna Islam sampeyan, siapkah Pakde memulangkan itu semua, beserta segala capaian yang terhimpun selama ini, berupa harta, kuasa, pangkat, derajat, semat, surat, anak-anak, cucu-cucu, pualam, kebesaran nama, kepahlawanan, bahkan pembangunan langgar, kepada Yang Maha Empunya semua? Kita akhirnya akan kembali kepada-Nya, dalam keadaan fakir dan fana. Seluruh pinjaman itu harus dikembalikan semua, tanpa kecuali, termasuk tumpukan dosa yang juga tak dapat kita sembunyikan dari perhitungan-Nya. Labbaik, Allahuma labbaik! Labbaika laa syariika lakalabbaik! Innal hamda, wani'mata laka walmulk! laa syariikalak ...!
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini