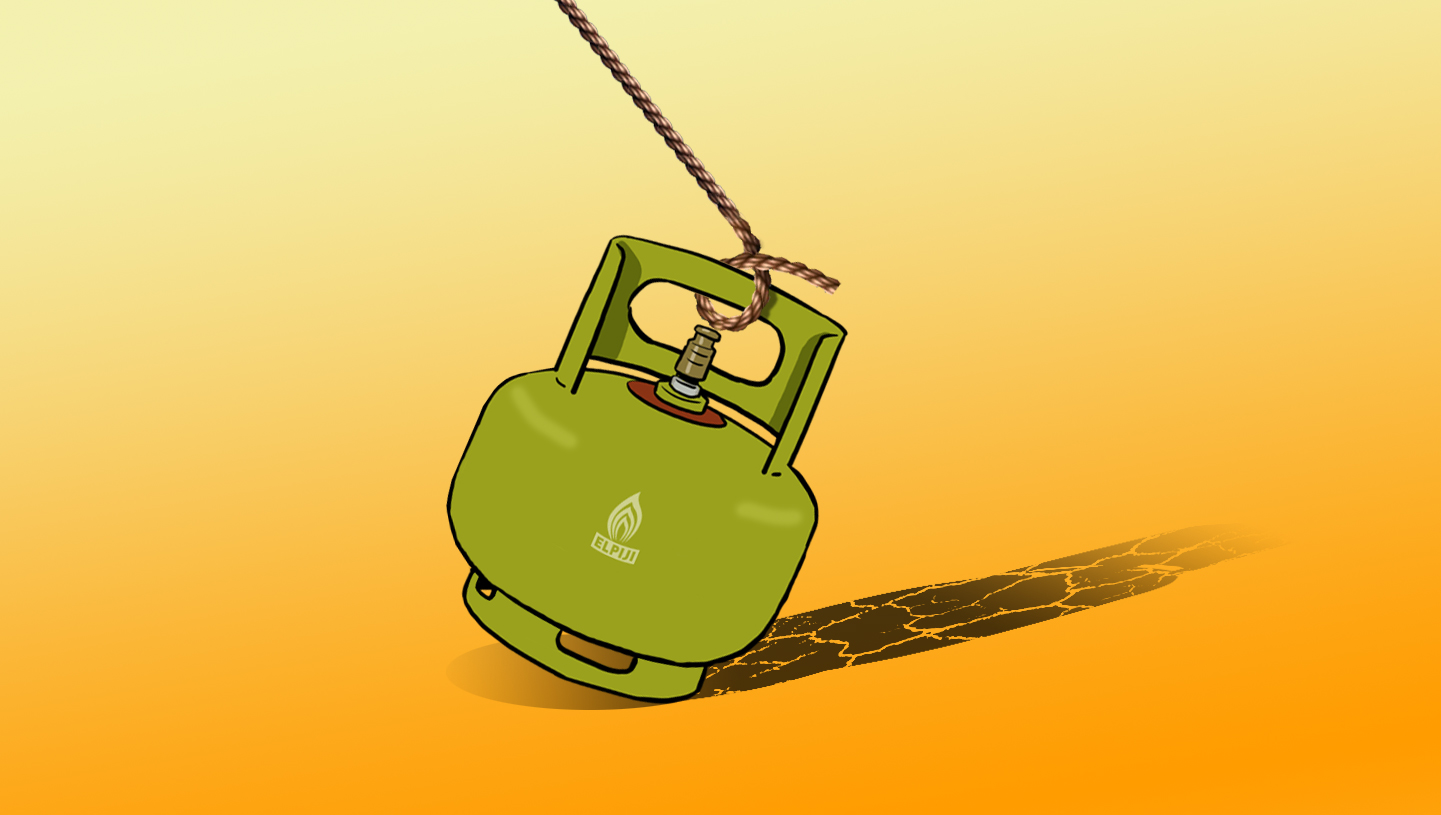Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Seorang aktor yang berprestasi di luar negeri dan penyanyi atau penulis yang kerap tampil di panggung negara lain selalu menjadi sumber berita yang dicari media. Berita tentang mereka dianggap mampu meningkatkan rasa bangga sebagai orang Indonesia. Cap “internasional” pun serta-merta melekat pada diri mereka: aktor internasional, penyanyi internasional, penulis internasional.
Beberapa tahun belakangan, bermunculan acara yang memakai kata “internasional” pada namanya, termasuk acara literasi. Sebutlah Indonesia International Book Fair (IIBF). Label “internasional” ditambahkan seolah-olah untuk menunjukkan kelas dan keakbaran acara tersebut sekaligus membedakannya dengan acara sejenis. Padahal acara serupa yang benar-benar berkelas dunia, semacam London Book Fair dan Frankfurt Book Fair, justru tidak menggunakan kata “internasional”. Dalam ranah sastra, gejala serupa terjadi, umpamanya Jakarta International Literary Festival (JILF) yang diselenggarakan Dewan Kesenian Jakarta. Gejala apakah ini?
Kata “internasional” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan “menyangkut bangsa atau negeri seluruh dunia; antarbangsa”. Namun fenomena akhir-akhir ini menunjukkan kata tersebut telah mengalami perubahan makna dan nilai. Makna kata “internasional” tidak lagi berhubungan dengan konsep wilayah dan/atau hubungan kerja sama semata. Ia telah bergeser menjadi kata yang berhubungan dengan kelas, prestise, atau kebanggaan dan, pada saat yang sama, mengalami peningkatan nilai rasa.
Hal yang mirip terjadi pada kata “kota” dan “desa”. Semula, posisi kedua kata tersebut sejajar. Seiring dengan modernisasi yang melanda perkotaan, kata “desa” mengalami penurunan nilai. Pada titik ini, meruaklah istilah ndeso yang berasal dari bahasa Jawa, yang kemudian digunakan untuk menunjukkan “kelas” seseorang atau sesuatu yang lebih rendah. Istilah ini lebih sering digunakan orang kota ketimbang warga desa. Hal sebaliknya terjadi pada kata “internasional”.
Gejala yang terjadi pada kata “internasional” hanya berlaku di negara bekas jajahan, seperti Indonesia, bukan di negara-negara penjajah atau yang berbahasa ibu bahasa Inggris. Itulah sebabnya sebutan penyanyi internasional atau film internasional tidak berlaku bagi penyanyi Inggris dan film buatan Hollywood. Gelar penulis internasional juga hanya terdengar digunakan dalam festival-festival sastra berlabel internasional yang diadakan di negara bekas jajahan. Di luar itu, para penulis tersebut hanya dikenal sebagai penulis buku laris atau novelis di negaranya.
Ania Loomba, dalam bukunya, Kolonialisme/Pascakoloni-alisme, memaparkan proses penginggrisan di negara-negara terjajah. Dia mengutip drama Brian Friel, Translations, yang menarasikan penginggrisan bahasa Irlandia. Di Donegal pada 1833, para kartografer Inggris mengalihtuliskan dan menginggriskan nama-nama tempat dari bahasa Gael dengan bantuan orang Irlandia sendiri. Loomba menyitir Declan Kiberd bahwa “makna akar dari translate adalah menaklukkan”.
Perubahan makna dan nilai yang terjadi pada kata “internasional” jelas berhubungan dengan lingkungan masyarakat pemakainya. Di tengah masyarakat bekas jajahan, gejala ini tidak hanya menambah aspek makna “internasional” menjadi “lebih berkelas” atau “lebih bermutu”, tapi juga aspek tujuan penggunaannya, yaitu penggelembungan.
Efek penggelembungan diri lewat label “internasional” jelas terasa pada penyebutan acara yang menggunakan bahasa Inggris. Misalnya IIBF, yang tidak disebut Pameran Buku Internasional Indonesia, atau JILF, yang tidak disebut Festival Literasi Internasional Jakarta. Hal serupa terasa pada acara sejenis yang lain, kendati tidak memakai kata “internasional”, seperti Jogja Literary Festival. Padahal semua acara itu diselenggarakan para penggiat literasi Indonesia. Seolah-olah penyelenggara malu menamai acaranya dengan bahasa bangsanya.
Sesungguhnya apa yang terjadi di balik label “internasional” dan seabrek acara semacam itu adalah penaklukan sebagaimana dikatakan Kiberd. Pertama, penaklukan bahasa nasional oleh bahasa Inggris. Kedua, penaklukan cara berpikir mengikuti negara tuan.
Saat ini, penjajahan tidak perlu lagi mesti menguasai sebuah negara, tapi cukup dengan menaklukkan bahasa dan cara berpikir masyarakat negara tersebut-—suatu bentuk penjajahan yang lebih irit dan tidak kasatmata. Penjajahan ini juga terbukti sangat efektif karena pihak yang terjajah justru dengan senang hati membiarkan diri digembala. Oleh iming-iming prestise dan naik kelas. Oleh obsesi yang membabi-buta pada globalisasi.
*) NOVELIS, ESAIS
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo