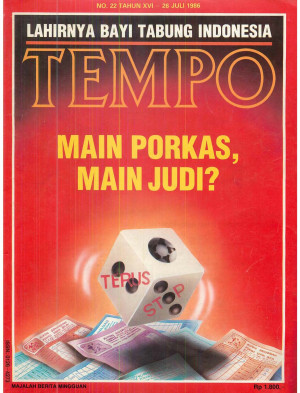PERMULAAN tahun ini, ada berita yang menarik perhatian saya. Tiga pemilik pasar swalayan (supermarket) di daerah permukiman Cinere, Kabupaten Bogor, berdemonstrasi, dengan membawa spanduk-spanduk, menentang peresmian sebuah pasar swalayan yang lebih besar di daerah tersebut. Pada spanduk, antara lain tertulis: "Lindungi pengusaha lemah!" "Madu dan racun, mana yang Bapak berikan pada kami?" dan "Keppres 29 tahun 1983, bapak angkatku." Apa yang terjadi kiranya jelas. Pengusaha kecil "berontak" melawan pengusaha yang bermodal lebih kuat. Kalau pemerintah tidak menolong para pengusaha yang modalnya lebih lemah ini, sudah hampir dipastikan, mereka akan gulung tikar. Betapa tidak? Bukankah pasar swalayan yang lebih besar akan memberi pelayanan lebih baik, dan harga lebih murah? Dengan modal yang lebih kuat, mereka sanggup bersaing bebas melawan para pemilik modal yang lebih kecil, dan sudah hampir dapat dipastikan pemilik modal besar akan memperoleh kemenangan. Kemudian pengusaha-pengusaha bermodal kecil itu menjerit minta bantuan pemerintah. Apa yang harus dilakukan pemerintah? Ada beberapa pertimbangan: Sebagaimana diketahui, kebijaksanaan pembangunan di Indonesia, pada saat ini, terutama ditekankan pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Kalau ini yang dijadikan dasar, maka pemilik modal besar harus dimenangkan, karena mereka merupakan pengusaha yang efisien. Mereka yang dapat memberikan tingkat pertumbuhan ekonoml yang tinggi. Karena efisiennya, mereka dapat memberikan pelayanan kepada konsumen secara lebih baik. Misalnya, pada kasus pasar swalayan tadi. Dengan memenangkan pengusaha swalayan yang besar, penduduk di sekitarnya, sebagai konsumen, akan diuntungkan. Kerugiannya, kalau pemerintah berpihak kepada mereka, pendapatan akan terpusat pada pemilik modal besar. Hal ini pada waktunya akan menimbulkan gejolak sosial. Sebaliknya, kalau pemerintah berpihak kepada tiga pengusaha pasar swalayan yang bermodal kecil, keuntungannya adalah pendapatan nasional akan tersebar lebih merata, paling sedikit di kalangan kelas menengah kota. Hal ini, sedikit banyak, akan membantu terjadinya stabilitas sosial politik. Tapi, penduduk di sekitarnya, sebagai konsumen, mungkin dirugikan. Juga, bila pemerintah terlalu memperhatikan para pemilik modal kecil (yang sering kali kurang efisien dalam menjalankan usahanya), mungkin tingkat pertumbuhan ekonomi akan terpengaruh secara negatif. Pemilik modal besar akan kurang bergairah melakukan investasi, karena mereka melihat pemerintah kurang bersimpati kepada mereka. Pemerintah, dalam kasus pasar swalayan ini, dapat berpihak kepada pemilik modal kecil, yakni kepada ketiga pemilik pasar swalayan yang melakukan demonstrasi. Tapi, sebenarnya, ketiga pengusaha pasar swalayan tadi merupakan pemilik modal besar, bila dibandingkan dengan para tukang sayur dari desa di sekitarnya, yang menjajakan dagangan dengan pikulan. Kita mengetahui, ada banyak pedagang bermodal kecil, yang menjajakan barang dagangannya (sayur-sayuran, buah-buahan, dan kadang-kadang juga daging dengan bersepeda) tersingkir akibat dibukanya pasar swalayan di banyak kompleks perumahan baru. Sayangnya, mereka tidak cukup canggih untuk melakukan demonstrasi seperti halnya pemilik ketiga pasar swalayan di atas. Kalau pemerintah mengutamakan pemerataan pendapatan dalam pembangunan, maka harus ditentukan golongan mana yang menjadi sasaran: kelas menengah atas, menengah bawah, atau kelas bawah sama sekali. Dalam kasus pasar swalayan di Cinere, atas perintah Bupati Bogor, peresmian pasar swalayan yang besar akhirnya ditunda. Ini artinya, pemerintah memperhatikan jeritan para pemilik modal kecil. Maka, menjadi jelas bahwa hanya mereka yang menjerit yang (kadang-kadang) mendapat pelayanan pemerintah. Para tukang sayur pikulan, dan tukang daging bersepeda, yang tidak tahu bagaimana cara menjerit, tergilas oleh pasar swalayan rumahan, yang meniamur sekarang ini. Apakah ini berarti pemerintah telah menentukan golongan menengah sebagai sasaran pemerataan hasil-hasil pembangunan? Saya kira tidak. Saya kira, yang terjadi adalah bahwa strategi pembangunan Indonesia pada dasarnya mengutamakan pertumbuhan yang tinggi melalui sistem kapitalisme. Tapi karena pemerintah juga sadar akan bahaya sistem kapitalisme bila dijalankan secara murni, apalagi dengan adanya ideologi Pancasila, maka kapitalisme ini direm sedikit-sedikit. Nah, yang belum kita miliki adalah sistem terpadu dalam menjalankan rem ini. Sampai saat ini, rem dipakai secara acak, terutama kalau ada tekanan dari bawah. Hasilnya, seperti pernah dinyatakan oleh Adi Sasono, pembangunan ekonomi kita adalah pembangunan ekonomi yang kaget-kagetan. Kadang-kadang pemerintah menganakemaskan pengusaha, tapi, tiba-tiba masalah pemerataan juga mendapat perhatian yang besar. Kasus yang hampir sama seperti pasar swalayan ini terjadi juga di bidang penerbitan pers. Pada permulaan tahun ini, terbit sebuah harian, Bisnis Indoncsia, yang dibiayai oleh pengusaha-pengusaha besar. Dengan modal besar, koran ini dapat melakukan bisnisnya secara profesional -- atau dengan kata lain, efisien. Dengan modal beberapa milyar rupiah, dengan iklan yang terjamin dari kelompok bisnis yang mendukung harian ini, maka dapat ditarik tenaga-tenaga profesional di bidang pers, dilengkapi dengan propaganda yang agresif (antara lain membagikan koran ini secara gratis kepada calon pelanggannya selama jangka waktu yang cukup lama) untuk merebut pasar yang ada. Segera, tindakan ini menimbulkan reaksi yang negatif dari penerbitan-penerbitan pers yang sudah ada. Tuduhan yang dllontarkan antara lain "tidak etis", "terlalu serakah", dan "pers akan jadi alat bisnis". Bagi saya, komentar-komentar semacam ini agak aneh kedengarannya. Bukankah kita, dan pemerintah, sedikit banyak sudah menyetujui bahwa kita mengambil jalan kapitalis dalam melakukan pembangunan? Bahkan perusahaan pers yang ada sekarang, sedikit banyak, sudah diuntungkan dengan sistem kapitalisme ini. Bagaimanapun juga, perusahaan pers sekarang merupakan usaha bisnis, yang etikanya adalah mencari keuntungan. Saya sendiri pernah terlibat dalam sebuah percakapan dengan seorang pimpinan dari sebuah perusahaan pers yang besar. Dia mengatakan, perusahaan pers yang dia pimpin pada dasarnya memang bertujuan mencari keuntungan. Tapi, katanya, dia tidak mau terlalu serakah. Dia masih berusaha memberikan kesempatan bagi yang lain untuk hidup. Saya nyatakan kepadanya bahwa apa yang dia lakukan itu salah, karena dia sedang melawan logika dakhil (inner logic) dari sistem yang ada, yakni kapitalisme. Cepat atau lambat, menurut saya, bisnis besar akan masuk di pers, kalau pers memang merupakan lahan yang memberi keuntungan. Buat pengusaha dalam sistem kapitalis, neraka pun akan dimasuki kalau di sana memang ada usaha yang memberikan keuntungan. Dan, kalau mereka masuk, mereka akan "memainkan bolanya" secara profesional. Segala dana dan daya akan diusahakan untuk mencapai sasaran yang dituju: meraih keuntungan. Saya katakan kepadanya, kalau kita sudah bersedia membasahkan diri dalam kapitalisme, maka kita tidak boleh takut menjadi basah seluruhnya. Kita harus mengikuti logika dakhil dari sistem ini, atau kita akan tergilas sendiri. Etika menolong orang lain bukan tidak bisa hidup dalam sistem kapitalisme. Tapi, sistem ini sudah mengatur tempat tersendiri untuk itu. Yakni, melalui lembaga derma. Lembaga derma ini tidak boleh dikacaukan dengan dunia bisnis. Dalam bisnis, hanya ada satu hukum: Anda harus mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Bahwa keuntungan yang sudah Anda miliki, kemudian Anda bagikan dalam bentuk derma, itu sudah di luar bidang bisnis. Karena itu, menurut saya, dalam sistem kapitalisme apa yang dilakukan harian Bisnis Indonesia pantas dan wajar, bahkan benar. Pada akhirnya, semua usaha pers akan bergerak ke sana. Mereka yang malu-malu untuk merebut sukses (baca: meraih keuntungan sebanyak-banyaknya) akan tersisih. Dari kedua kasus di atas, jelas bahwa kita (termasuk pemerintah) masih agak malu-malu dalam menerima sistem kapitalisme di Indonesia. Di satu pihak, kita sudah memakai sistem tersebut. Apalagi ternyata sistem ini telah berhasil menaikkan GNP per kapita kita selama tahun 1970-an, dan banyak pengusaha yang diuntungkan. Misalnya, para pengusaha pasar swalayan kelas menengah, atau para pengusaha pers yang relatif sukses sekarang ini. Tapi, di pihak lain, kita menjadi kaget kalau ternyata, sistem kapitalis ini mulai memperlihatkan sosoknya yang sesungguhnya, berupa sebuah raksasa yang mulai melahapi saingannya tanpa rasa etis. Kita pun, meminjam istilah Adi Sasono, menjadi kaget-kagetan. Maka, menjadi jelas wajah hipokrit pengusaha-pengusaha kita. Mereka menerima kapitalisme dengan prinsip persaingan bebannya kalau mereka diuntungkan. Tapi, begitu kapitalisme itu bangun, dengan mulai berdatangannya pemilik modal yang lebih kuat, para pengusaha ini mulai menjerit-jerit kepada pemerintah minta persaingan bebas dibatasi (baca: mereka dilindungi). Lalu, apa yang harus kita lakukan? Saya kira, kita harus mengkaji kembali strategi pembangunan kita secara radikal, sebelum terlambat. Atau, kita memang sudah terlambat?
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini