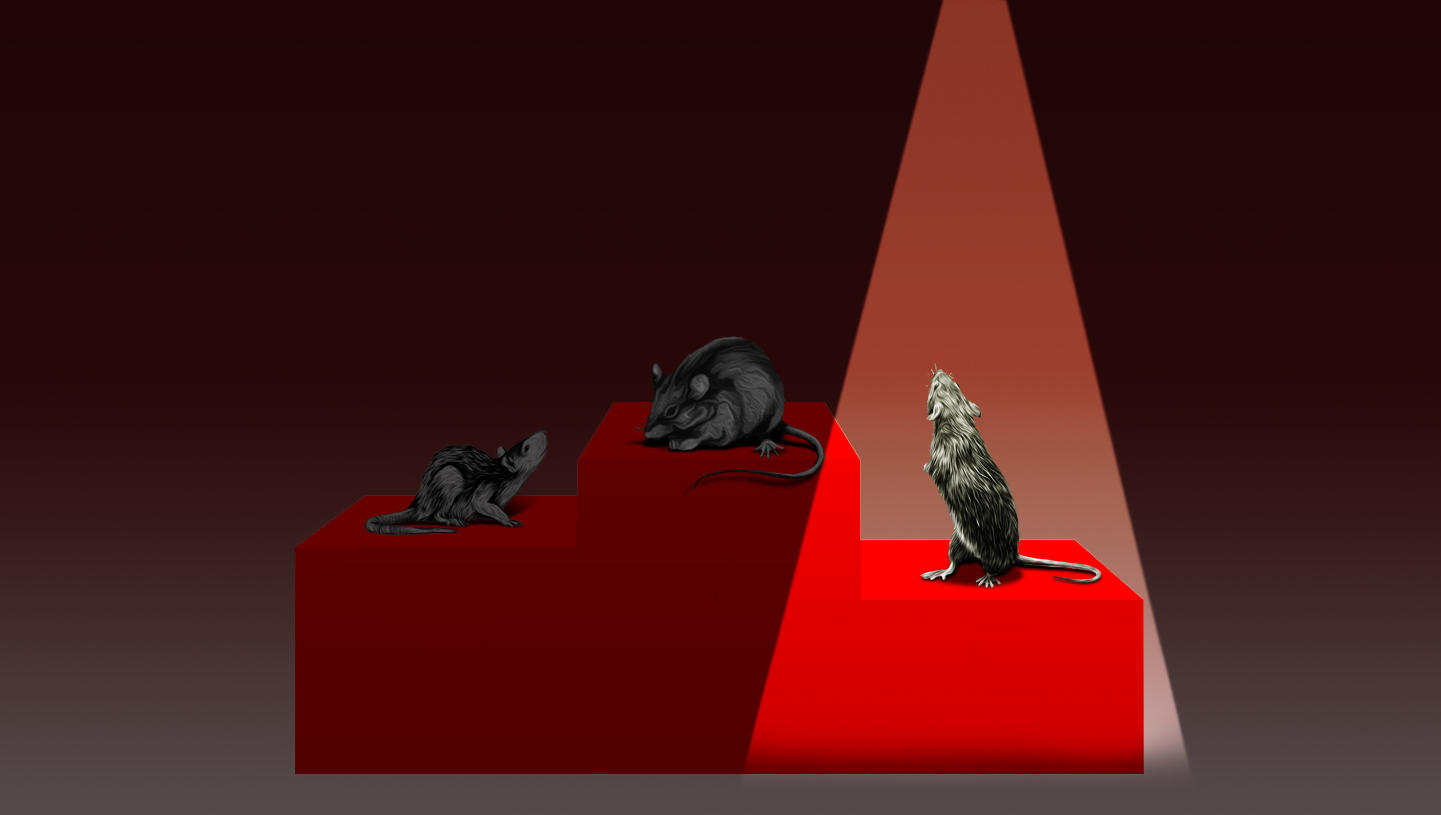JIKA saya pergi, gunung Himalaya pun akan menangis. Ali Bhutto
digantung Rabu dinihari jam 02.00 pekan lalu. Banyak orang sedih
dan menangis, tapi tidak Altaf Gauhar.
Gauhar kini ko-editor The Guardian Third World Review. Dulu ia
seorang pejabat tinggi Pakistan di masa Ayub Khan jadi Presiden.
Ia pun mulai jadi teman Bhutto sejak tokoh yang banyak gaya ini
jadi menteri perdagangan pada umur 30. Sayangnya, ia jadi musuh
ketika Bhutto jadi presiden.
Pada suatu hari Bhutto berkata, sebagaimana dikutip Gauhar,
bahwa bila ia pergi bahkan gunung-gunung Himalaya pun akan
menangis. Gauhar, yang waktu itu jadi editor harian Dawn,
memperingatkan dengan halus kesombongan itu. "Gunung-gunung,
tak akan menangis," tulisnya. Bhutto marah. Seperti biasa ia
menyimpan dendamnya dengan teliti. Tak lama kemudian rumah
Gauhar diketuk petugas. Ia ditahan.
Gauhar dilepaskan setelah 13 bulan. Nampaknya Bhutto ingin
memberi kesan bahwa ia membebaskan Gauhar bukan karena rasa
sesal atau karena tak ada bukti bersalah. Ia membebaskan Gauhar
karena ia berkuasa -- tanpa perlu mahkamah pengadilan. "Mahkamah
pengadilah tak ada dalam kamusku."
Beberapa tahun kemudian kekuasaannya rontok. Dan sebuah mahkamah
pengadilan (benda yang tak ada dalam kamusnya itu) mengirimnya
ke tiang gantungan. Bhutto mati pada usia 51. Himalaya tak
menangis. Gunung itu terlampau tua untuk tak mengenal riwayat
penguasa-penguasa yang jatuh, tentang sang penindas yang
berakhir sebagai tertindas -- atau sebaliknya.
KITA tak tahu kenapa Altaf Gauhar mengungkapkan wajah buruk Ali
Bhutto beberapa hari sebelum hukuman gantung dilaksanakan.
Mungkin wartawan ini pun menulis dengan dendam, dan dendam
selalu cenderung sewenang-wenang: ia memukul seorang yang sudah
tak berdaya. Atau mungkin ia ingin menghindarkan satu hal yang
sering terjadi: si A jadi martir hanya karena si A dihabisi oleh
pihak yang lebih kuat.
Tapi salah siapakah bila Bhutto jadi semacam martir? Kecuali
salah Jenderal Zia? Di aman ini begitu banyak saksi tentang
penguasa yang menghukum orang yang belum tentu bersalah. Di
zaman ini begitu banyak mahkamah-kongkalikong dan "hakim-hakim
yang makan bebek" sebagaimana disebut dalam salah satu sandiwara
Brecht, hingga keadilan memilih pihak yang lain. Si pesakitan
menjadi penggugat. Penjara menjadi tempat penyucian. Tuhan tidak
hadir dalam suara wakil kekuasaan yang berseru pro justicia...
TAPI mungkin Zia yakin Tuhan berada di pihaknya. Ia orang yang
taat beragama. Atau mungkin ia tak mengampuni Bhutto justru
karena ingin menyerahkan Bhutto ke akhirat: di sana ada
pengadilan yang lebih baik. Karena mahkamah di bumi hina-dina,
pada pedang algojo di Fribourg tertulis kata: "Tuhan Yesus,
Kau-lah sang Hakim."
Masalahnya ialah, dapatkah kita percaya kepada kerendahan-hati
seperti itu. Albert Carnus, yang menentang hukuman mati dalam
esei panjang Reflexions sur la peine capitale, mengatakan hanya
nilai-nilai agama-lah yang dapat berlaku sebagai dasar hukuman
terberat. Dalam nilai itu ada keyakinan bahwa hidup di dunia
hanyalah sebagian dari hidup. Hukuman mati, dengan demikian,
walaupun nampaknya tak bisa dikoreksi kembali begitu tulang
leher si terhukum patah, bersifat nisbi.
Tapi benarkah tulisan pada pedang algojo di Fribourg itu tanda
keterbatasan manusia sebagai hakim? Benarkah Jenderal Zia pernah
tergetar oleh suara simpang-siur tafsir manusia tentang
keadilan? Ataukah bagi orang seperti dia soalnya sederhana: si
pelanggar harus dihukum, si pembunuh harus dibunuh?
Zia ingin Syariah Islam berlaku sebagai hukum di Pakistan. Tapi
seperti kritik Seyyed Hossein Nasr dari Iran terhadap gerakan
"reformis" Islam yang puritan, baginya mungkin Tuhan hanya
diingat sebagai Kebenaran, dan agama terutama hanya kerangka
yuridis. Maka keindahan pun hanya sesuatu yang insidentil -- dan
agaknya begitu pula gairah untuk hidup tanpa tiang gantungan.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini