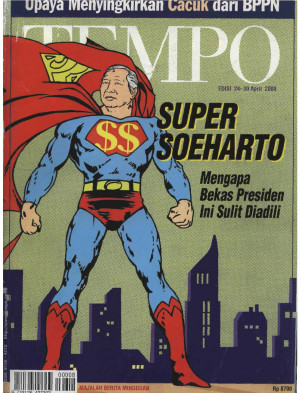Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Adrianus Meliala
Adrianus Meliala
Kriminolog dari UI
|
KEREPOTAN kita saat membicarakan keadilan, demikian pula rasa keadilan sebagai faktor imperatif yang menyertainya, adalah karena kita perlu mengaitkannya dengan konteks dan situasi setempat. Keadilan yang absolut, mono-interpretatif, dan tidak fleksibel akan cenderung dipandang sebagai tirani legal ketimbang suatu momentum keseimbangan antara hak dan kewajiban serta antara perbuatan dan konsekuensi perbuatan.
Namun, memang harus diakui, adakalanya kecenderungan keadilan sebagai tirani legal—yang bisa dipersepsikan menimbulkan ketidakadilan baru itu—ternyata lebih kuat dari keadilan kontekstual. Salah satu penyebabnya adalah optimalisasi penggunaan instrumen legal itu sendiri sebagai cara beroperasi mendapatkan keadilan. Karakteristik hukum memang sulit dan sebaiknya tidak fleksibel. Seperti telah dilansir banyak orang, kepastian hukum adalah sesuatu yang dipertaruhkan (at stake) bila hukum terlalu senjang atau diskrepansif dalam hal memberikan perlakuan, penanganan, ataupun penghukuman terhadap satu orang dengan yang lainnya. Bila hukum dan keadilan sulit bersifat kontekstual, bagaimana dengan rasa keadilan? Belum berapa lama perbincangan ini marak di antara kita sebagai warga bangsa yang—untuk sebagian—baru keluar dari cengkeraman hukum yang jauh dari rasa keadilan. Mendalami rasa keadilan mungkin bisa dilakukan dengan melihat bagaimana cara kita mempersepsikan "adil" itu sendiri: apakah menyangkut sesuatu yang terdistribusi secara merata (distributive justice), atau sesuatu yang disepakati pembagiannya secara sosial (social justice). Rasa keadilan, dengan demikian, bisa bervariasi, amat kontekstual, dan oleh karena itu bisa pula dipengaruhi emosi sesaat. Namun, para penganut pandangan hukum sebagai realitas sosial tidak mengkhawatirkan hal ini sebagai sumber ketidakadilan baru. Hal ini mengingat, pada akhirnya, rasa keadilan tadi juga harus linked up atau disesuaikan dengan prosedur dan bahasa hukum yang berlaku. Sedemikian jauh, pembahasan di atas bertujuan mengantarkan kita pada pemahaman bahwa hal itulah yang tengah terjadi di Indonesia dewasa ini. Di tengah situasi hukum dan prosedur hukum (berikut pula aparat-aparatnya) yang praktis belum banyak berubah, terdapat perubahan rasa keadilan yang begitu besar. Terdapat dua fenomena yang muncul dari perubahan tersebut. Pertama, dalam bentuk keinginan agar perilaku-perilaku yang sebelumnya tak tersentuh oleh hukum (antara lain karena tidak diatur oleh hukum) kini juga harus diminta pertanggungjawabannya. Peradilan terhadap para jenderal pelanggar hak asasi manusia, misalnya, adalah contoh paling nyata. Kedua, keinginan agar terjadi pemberatan hukuman (sebagai manifestasi peningkatan rasa keadilan) terhadap perilaku-perilaku yang walau sudah lama telah dimintai pertanggungjawaban hukum, dianggap dijatuhi sanksi terlalu ringan. Dalam hal ini, tuntutan bahwa aparat militer yang berbuat kriminal perlu diadili secara koneksitas dan terlepas sama sekali dari kemungkinan impunity (tak terjangkau oleh hukum) merupakan contoh relevan. Selain dua fenomena tersebut, juga muncul aneka fenomena lain yang seiring dan sewarna, seperti tuntutan pengungkapan kembali kasus-kasus pelanggaran hak asasi oleh militer, upaya reformasi di Mahkamah Agung, revisi Undang-Undang Hak Asasi Manusia, perlunya dimunculkan undang-undang perlindungan saksi, pemisahan polisi dari ABRI menjadi sipil, dan sebagainya. Perubahan-perubahan tadi pada dasarnya memperlihatkan bentuk teknis perbedaan perasaan keadilan antara kini dan masa-masa sebelumnya. Permasalahannya sekarang, kita sama-sama belum tahu apakah perubahan ini sudah berada pada tahap akhir atau tidak. Jangan-jangan, kita sebetulnya tengah berada pada masa transisi menuju perubahan yang lebih jauh dan lebih radikal. Bila kita telah berada pada tahap akhir, jelas tidak ada lagi masalah. Kita tinggal menyatukan kembali platform berpikir dan bertindak. Permasalahan muncul bila kita sepakat bahwa masa transisi sebenarnya belum dilewati. Itu berarti rasa keadilan yang kini tengah dan sudah berubah itu pun sebetulnya masih merupakan keadilan transisional (transitional justice). Pada fase ini, selalu mungkin mekanisme, prosedur, serta standar penilaian yang lama belum tergeser sepenuhnya, yang baru pun belum lagi lengkap dan mapan. Adanya resistensi dari beberapa pihak yang merasa posisinya digoyang oleh masyarakat, antara lain ditunjukkan oleh beberapa kalangan dalam TNI ataupun dalam lembaga-lembaga penegakan hukum sendiri, kiranya dapat mengindikasikan suasana transisi itu. Timbulnya konflik, atau setidak-tidaknya munculnya suasana canggung antara pihak yang ingin berubah dan yang resisten untuk tidak berubah, memang gejala biasa dalam setiap periode transisi. Adalah biasa pula bila dalam periode tersebut, selalu ada pihak yang merasa dikorbankan, dijadikan tumbal, dimarginalkan, atau dijadikan target. Bila kini banyak jenderal yang merasa dibidik secara tidak proporsional dalam kasus Timor Timur, itulah contoh kecanggungan khas masa transisi. Demikian pula, bakal timbul kecanggungan ketika belakangan ini timbul niat untuk mengungkap peran para petinggi polisi dan militer yang berperan dalam kasus penyerbuan kantor PDI, 27 Juli 1996. Yang patut dijaga bersama-sama adalah, baik dari pihak yang membidik maupun yang dibidik, bersama-sama segera keluar dari situasi keadilan transisional dengan cara kembali pada apa yang telah ditentukan oleh hukum berikut prosedur-prosedurnya. Jika kita tidak saling menahan diri, bisa-bisa kita nyelonong ke arah yang lebih radikal, yakni keadilan jalanan. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Jaringan Media © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |