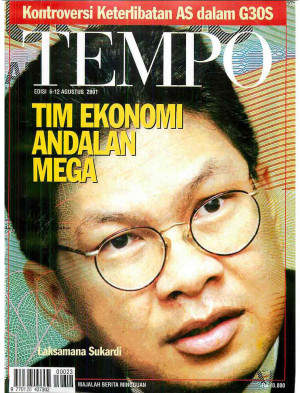Taufik Abdullah *)
*) Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
APAKAH Abdul Gafur & partner akhirnya dikukuhkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai gubernur dan wakil gubernur definitif dari provinsi baru Maluku Utara, ataukah pemilihan harus diulang, saya tidak tahu. Tetapi, yang saya tahu pasti, peristiwa ini sama sekali tidak aneh. Sejak Soeharto lengser keprabon, peristiwa seperti ini biasa terjadi. Hampir semua gubernur, apalagi bupati, yang terpilih oleh DPRD berdasarkan Undang-Undang No. 22/1999, harus memulai karir mereka dengan mengurut dada menghadapi tuduhan money politics. Mungkin saya salah ingat, tetapi rasanya sampai sekarang pun—setelah sekian bulan berlalu—calon bupati Sampang yang terpilih masih juga belum dilantik atau diganti.
Beralasan atau tidak, tetapi adanya tudingan money politics memang memperlihatkan bahwa secara formal ”zaman otoriter dan sentralistik” boleh dikatakan telah berakhir. Sekarang, melalui wakil mereka di DPRD, masyarakat pemilihlah yang menentukan siapa yang harus memimpin daerah mereka, tidak lagi seseorang yang jauh berada di sana, di pusat pemerintahan dan politik. Begitulah kira-kira argumen keren yang bisa dan tentu saja harus diberikan. Tetapi, sialnya, masyarakat pemilih itu sekarang telah terpecah-pecah ke dalam sekian banyak partai. Tentu bisa diperkirakan bahwa setiap pecahan, yang diwujudkan partai itu, menginginkan calon mereka atau calon lain yang dianggap sejalanlah yang terpilih sebagai pejabat nomor satu di daerah itu. Sialnya lagi, tidak ada jaminan bahwa kemenangan dalam pemilihan umum bisa dengan begitu saja disalin ke dalam kemenangan dalam pergulatan politik di dewan perwakilan. Maka, mestikah diherankan kalau sering sekali terjadi tuduhan money politics, bahkan juga tuduhan ”tidak becus” dilancarkan oleh para pendukung partai tertentu terhadap kegagalan wakil mereka di dewan perwakilan?
Jika saja seorang kepala da-erah telah memulai karirnya dengan segala macam tuduhan—beralasan ataupun tidak—sudah bisa dibayangkan bahwa masalah pertama, bahkan mungkin sepanjang masa jabatannya, yang harus dilaluinya ialah memupuk suasana saling percaya, memperoleh legitimasi moral dan politik, dan sekian banyak dari aspek proses ”pembentukan kepercayaan” yang lain. Maka, mestikah diherankan kalau hampir semua kepala daerah tergagap-gagap dalam menjalankan roda pemerintahan. Bukan saja otonomi daerah, yang bersumbu pada kabupaten, menyebabkan hubungan gubernur dan bupati mengalami revisi, tetapi masalahnya pun tentu semakin kompleks karena bimbingan dari pusat—yang di masa Orde Baru bukan saja selalu mengalir, tetapi juga harus selalu dipatuhi—kini hanya datang berupa pandangan umum. Jadi, kesimpulan bahwa pemerintah daerah sekarang sedang mengalami masa peralihan yang melemahkan adalah wajar. Kesimpulan ini bisa dibuktikan dengan memperlihatkan betapa tak berdayanya pemerintah daerah menghadapi—apalagi mengatasi—sekian banyak kasus, baik yang bisa diartikan sebagai perorangan terhadap wibawa pemerintah maupun yang sekadar menuntut keadilan atau peningkatan kinerja pemerintah.
Jika saja kelemahan struktural dan legitimasi moral yang kini sedang melanda pemerintah daerah dapat dibantu oleh kepemimpinan sosial daerah yang kuat, barangkali hal-hal mendasar dalam pengelolaan masyarakat di masa krisis relatif akan lebih mudah diatasi. Tetapi sentralisasi kekuasaan yang dijalankan Orde Baru di satu pihak telah mengisap wibawa pemerintah daerah, dan di pihak lain, secara bertahap tetapi pasti, telah menyebabkan terjadinya birokratisasi kepemimpinan. Kecenderungan yang kedua terjadi karena kooptasi negara terhadap masyarakat madani, dengan antara lain keharusan setiap organisasi sosial dan politik mendasarkan diri kepada asas Pancasila—yang tafsirnya telah berada di bawah hegomoni negara. Hal ini disebabkan semangat yang menggebu-gebu untuk menjadikan Golkar se-bagai ”mayoritas tunggal”. Dengan keinginan ini, segala usaha dilakukan untuk menghadapi proses Golkarisasi sistem kepemimpinan lokal.
Bisalah dibayangkan bahwa selama pemerintah pusat kuat dan legitimasi politiknya masih belum tercemar, semua bisa berjalan lancar. Tetapi, ketika legitimasi politik dan moral pemerintah pusat goyah, seluruh sistem kepemimpinan lokal pun serta-merta mengalami krisis. Saat itu, kita pun bisa melihat betapa mudahnya masyarakat dan massa terbuai oleh bujukan primordialisme yang sempit dan betapa leluasanya panggilan kepemimpinan yang tribalistik bisa menggerakkan massa untuk berbuat hal-hal yang tidak mereka inginkan. Vigilanteisme, yang bertolak dari keinginan untuk berbuat kebaikan tetapi diwujudkan dalam tindakan melanggar hukum, bahkan perilaku kejam--membakar orang yang dikira pencuri, membakar ruang pertemuan yang dinilai sumber maksiat, dan sebagainya—adalah gejala sosial yang tak terpisahkan dari krisis kepemimpinan lokal dan pemerintahan daerah.
Sukar untuk dibantah bahwa Orde Baru didirikan di atas puing-puing keruntuhan rezim Demokrasi Terpimpin. Bahkan, saya kira, kita bisa juga mengatakan bahwa rezim tersebut berdiri pada saat tragedi yang traumatis baru saja dilalui bangsa kita. Tetapi pendapat yang tak kurang pentingnya ialah Orde Baru mendapatkan legitimasi politik karena rezim ini secara hipotetis dianggap sebagai saluran untuk membawa bangsa ke masa depan yang lebih baik. Dalam suasana seperti inilah berbagai diskusi politik, ekonomi, dan sosial diadakan, dan dalam situasi ini pula, bukan saja strategi, tetapi juga ideologi pembangunan diperdebatkan. Sementara itu, berbagai usaha yang diperkirakan bisa menjembatani realitas hari ini dengan visi masa depan pun secara terpencar-pencar mulai diadakan.
Dalam hal ini saya teringat pada sebuah eksperimen yang diadakan di Sumatra Barat, ketika Harun Zain baru saja diangkat sebagai gubernur. Menyadari bahwa Sumatra Barat baru saja melewati dua krisis sosial-politik yang traumatis—peristiwa PRRI dan G30S—sang Gubernur merasa perlu lebih dulu membenahi sistem kepemimpinan. Ia melihat bahwa kepemimpinan yang baik adalah sumber yang teramat penting dalam proses pembangunan. Demikianlah, pada tahun 1969, pemerintah daerah mengeluarkan peraturan daerah yang menentukan bahwa setiap negeri mempunyai dua dewan atau kerapatan. Yang pertama, Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang anggotanya terdiri atas para penghulu adat, dan yang kedua Dewan Perwakilan Nagari (DPN), yang dipilih berdasarkan pembagian teritorial nagari. Dewan Perwakilan Nagari inilah yang memilih wali nagari—yang menjadi kepala pemerintahan. Dalam masa satu setengah tahun, eksperimen ini berjalan baik—DPN memerintah, KAN berfungsi sebagai penasihat sekaligus pemberi legitimasi DPN, yang harus berhubungan dengan birokrasi pemerintahan seperti camat. Tetapi keharmonisan ini tak berjalan lama. Hasrat untuk menang dalam pemilihan umum menyebabkan pemerintah daerah, secara tak resmi, mengharuskan semua wali nagari menjadi pendukung Golkar. Maka, perpecahan di kalangan DPN tak terhindarkan. Krisis kepemimpinan mulai terjadi di pedesaan. Dan hal itu semakin parah setelah adanya UU No. 5/1979, yang memaksakan uniformitas sistem pemerintahan dari Sabang sampai Merauke.
Sumatra Barat (dan Bali), karena berbagai alasan antropologis, adalah wilayah yang mengalami kerusakan yang relatif paling enteng daripada daerah lain. UU No. 5/1979 praktis secara keseluruhan telah merusak tatanan pemerintahan desa, ikatan komunitas desa yang organik, dan tentu saja sistem kepemimpinan desa. Begitulah, ketika konflik komunal terjadi—sesuatu yang diperkirakan bisa meletus dalam konteks masyarakat yang semakin majemuk—masyarakat telah kehilangan mekanisme pertahanan dirinya. Maka, ketika kepemimpinan formal dan birokrasi telah kehilangan wibawa dan di saat kepemimpinan masyarakat harus membentuk dirinya kembali akibat kooptasi dan birokratisasi kepemimpinan, apakah lagi yang bisa diharapkan? Mestikah diherankan kalau masyarakat bisa tergelincir pada kepemimpinan desakan yang bisa saja bersifat konfrontatif kepada siapa saja dan apa saja? Kalau sudah begini, konflik pun terus berjalan berkepanjangan dan batas antara vigilante dan ke-jahatan murni pun menjadi semakin kabur.
Ketika para elite politik yang berada di pusat, baik di legislatif maupun yang eksekutif, masih belum bisa melepaskan diri dari ”krisis saling percaya”, apakah yang bisa diharapkan dari mereka? Mereka telah kehilangan ”kesamaan perspektif”, suatu hal yang bisa mereka sumbangkan untuk mengatasi kerapuhan sistem kepemimpinan daerah yang kini sedang melanda negara kita.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini