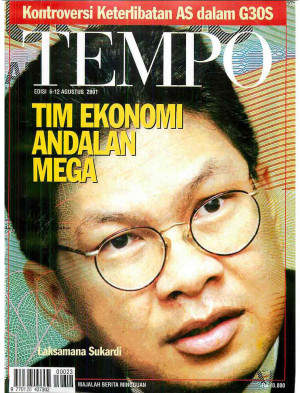Ignas Kleden*)
*)Sosiolog, Direktur The Go-East Institute (Lembaga Lintas Timur), Jakarta
INDONESIA adalah negeri kepulauan, mungkin negeri kepulauan terbesar di dunia. Dari seluruh keluasannya sebesar 1.923.715 kilometer persegi, dua pertiganya terdiri dari laut. Sekalipun daratan hanya membentuk sepertiganya, boleh dikatakan orientasi utama penduduk negeri ini adalah ke daratan. Padahal, sebelum kedatangan orang Barat pada awal abad ke-16, yang diteruskan dengan sejarah kolonisasi, pelayar-pelayar dari kawasan ini telah melanglang buana lewat lautan, dari Filipina hingga ke Madagaskar, dari Lautan Teduh hingga ke India. Pada masa sekarang, penduduk di daerah-daerah pesisir umumnya bukan menggantungkan hidupnya pada laut, melainkan pada pertanian, entah sawah entah ladang. Menangkap ikan dan mengolah sumber daya laut hanyalah pengisi waktu senggang untuk mendapatkan lauk-pauk dan memperoleh sedikit tambahan pendapatan kalau orang sedang tidak bekerja di kebun.
Mengapa penduduk NTT, misalnya, yang hidup di pulau-pulau kecil yang dikelilingi laut, tidak berorientasi ke laut dalam mata-pencahariannya, tetapi justru tetap lengket ke daratan, yang tidak begitu subur? Pertanyaan itu pernah saya dengar dari Sarwono Kusumaatmadja ketika dia masih menjadi Menteri Kelautan. Dibutuhkan studi kebudayaan yang cukup luas untuk mendapatkan jawabannya. Menurut dugaan saya, hal ini terjadi karena dalam mata pencaharian di laut, tidak terdapat sesuatu yang dapat menjadi ekuivalen pertanian. Tidak ada perasaan bahwa dalam menangkap ikan, orang juga mengontrol dan mengolah alam seperti halnya orang mengolah tanah dan menanam bibit dalam pertanian. Kehidupan di laut lebih mirip kehidupan berburu dan meramu hasil hutan di daratan. Orang datang mengambil hasil yang diberikan oleh alam, dan kemudian meninggalkannya. Perasaan ini mungkin menyebabkan orang tidak terlalu berbangga bekerja mencari penghidupannya di laut, dan tetap mengandalkan nafkahnya pada pertanian.
Persoalannya adalah apakah di laut dapat diciptakan suatu bentuk usaha yang mirip pertanian, tempat para pekerjanya merasa mengawasi dan mengolah alam sebagaimana petani membuat saluran air di sawah dan mengawasi padinya. Hal ini mungkin dilakukan kalau di berbagai daerah di Indonesia dapat dikembangkan budidaya laut, tempat potensi sumber daya laut tidak hanya diambil, tetapi juga dipelihara dan dikembangkan secara terencana. Budidaya udang, teripang, rumput laut, dan mutiara adalah beberapa contoh yang sudah dicobakan di banyak tempat. Kalau saja usaha budidaya ini dapat menciptakan persepsi baru bahwa di laut orang dapat mengawasi dan mengolah alam, mungkin perhatian untuk menggarap potensi laut akan meningkat sebanding dengan perhatian kepada pertanian.
Preokupasi dengan daratan dan sikap mengabaikan laut terlihat tidak saja dalam bidang ekonomi penduduk, tetapi juga dalam bidang yang lebih canggih seperti pola kepemimpinan, khususnya kepemimpinan politik. Yang dominan dalam politik Indonesia semenjak kemerdekaannya adalah pola kepemimpinan dengan warna feodal yang kuat dari latar belakang pertanian. Para bangsawan yang menguasai tanah menjadi patron untuk para petani yang menjadi klien mereka. Bangsawan memerintah para kawulanya sambil menjaga kebudayaan, sedangkan para petani menerima perintah dan mengurus ekonomi. Tukar-menukar berlangsung antara kekuasaan dan kebudayaan yang turun dari atas dan hasil-hasil pertanian yang diserahkan dari bawah. Petani terlalu lugu untuk mengurus politik dan terlalu kasar untuk mengurus kebudayaan, sementara para pangeran terlalu halus untuk mencangkul di sawah. Dengan pola seperti itu, sifat utama hubungan feodal adalah orientasi ke atas yang kuat, patronisme yang paternalistis, penekanan kepada ketundukan dan nilai-nilai yang mendukung ketundukan, konsep waktu yang siklusnya seperti musim yang selalu berulang, dan legitimasi yang bersifat turun-temurun, meskipun selalu ada ruang untuk mobilitas vertikal untuk lapisan bawah. Hak dan kewajiban ditempatkan dalam asimetri. Yang di atas memberi petunjuk, yang di bawah melaksanakan. Yang di bawah memohon, yang di atas berkenan.
Alam juga tidak begitu sulit diramalkan, sehingga pengetahuan yang sederhana saja sudah memadai untuk keperluan tersebut. Keteraturan alam hanya diselang-selingi oleh bencana seperti kemarau panjang, banjir, atau letusan gunung berapi. Kehidupan sosial relatif stabil. Dalam pola seperti ini, waktu adalah suatu sumber daya yang tak akan habis (renewable resource), dan keputusan seperti mufakat dapat diambil dengan menghabiskan waktu yang panjang. Tidak mengherankan, seorang pemimpin tidak begitu mendatangkan banyak risiko, sekalipun dia ditentukan begitu saja dari atas.
Ketidakpuasan terhadap pola ini sudah sering kali diungkapkan dalam berbagai kritik, tapi usaha untuk mencari pola kepemimpinan alternatif belum banyak dilakukan. Tak adanya alternatif ini menyebabkan kita mudah terjebak dalam kesadaran palsu, ketika seseorang dengan sengit mengkritik feodalisme, sementara dia sendiri sedang asyik mempraktekkan cara-cara feodal. Dalam beberapa studi yang diadakan tentang kebudayaan pesisir, khususnya yang dilakukan oleh almarhum Prof. Dr. Mattulada, telah diidentifikasi suatu pola kepemimpinan yang berasal dari tradisi kelautan yang dinamai kepemimpinan kapitan perahu. Kepemimpinan jenis ini sekarang layak dipertimbangkan karena ia dapat memberi warna baru dalam kepemimpinan politik Indonesia sekarang. Selain itu, kepemimpinan ini digali dari suatu latar belakang yang amat dominan di masa lampau, dan mencerminkan kedudukan Indonesia sebagai negara kepulauan yang dikelilingi oleh laut dan lautan. Pola kepemimpinan ini ditandai oleh beberapa ciri yang secara mencolok berbeda dari kepemimpinan dengan latar belakang pertanian.
Pertama, seorang kapitan perahu tidak dapat ditentukan begitu saja dari atas. Tentu saja dropping bisa saja dilakukan, tetapi risikonya amat tinggi karena langsung berhadapan dengan ujian dalam prakteknya. Seorang kapitan yang tidak berpengalaman tidak bisa dijamin membawa perahunya dari Surabaya ke kepulauan Riau, misalnya, sementara perahunya bisa saja mendarat di sebuah tempat di Lombok atau Sumbawa. Demikian pun tanpa pengetahuan yang memadai mengenai laut, dia dapat membawa perahunya menabrak karang atau terhunjam di tempat yang dangkal. Risiko tersesat, terdampar, dan karam adalah demikian tingginya sehingga mengangkat sembarang orang menjadi kapitan perahu akan tak terbayangkan dalam tradisi kelautan. Demikian pun kesanggupan untuk berlayar dengan selamat menempuh jarak jauh mempersyaratkan adanya pengetahuan yang cukup mendalam mengenai navigasi, peta di laut, arah angin, letak bintang, gerak arus, dan saat-saat datangnya topan. Perubahan di laut jauh lebih cepat dan bervariasi dari perubahan alam di darat. Karena itulah kehidupan di atas laut menjadi dinamis, penuh antisipasi terhadap perubahan cuaca, yang mengharuskan keputusan baru dan penyesuaian baru dari waktu ke waktu.
Kedua, dalam menghadapi krisis seperti topan atau gelombang besar, seorang kapitan perahu tidak bisa mengajak berunding para awak kapal selama beberapa jam atau menunggu tercapainya mufakat setelah bermusyawarah seharian penuh. Keputusan harus diambil, katakanlah, pada pukul 23.05, dan barangkali harus dikoreksi pada pukul 23.10. Pengambilan keputusan yang cepat dan tegas, dan mengoreksi keputusan yang keliru dalam waktu singkat, adalah imperatif. Kalau dia terlambat mengambil keputusan atau terlambat mengoreksi keputusan yang keliru, dapat berakibat tenggelamnya kapal, yang bisa mengakhiri hidup para penumpangnya. Adapun tepat-tidaknya keputusan yang diambil langsung mengalami ujian pada saat itu, yaitu apakah kapalnya tetap terjebak dalam topan atau dapat meloloskan diri dari bahaya. Akuntabilitas seorang kapitan perahu hampir-hampir merupakan akuntabilitas alamiah karena benar-salah keputusannya akan diuji oleh kekuatan alam sendiri.
Ketiga, kalau kapalnya karam dan para penumpang terancam bahaya, seorang kapitan perahu terikat oleh semacam "sumpah jabatannya" yang biasanya dipegang teguh, yakni bahwa dia tetap berada di perahunya sampai penumpang dan awak perahunya yang terakhir telah mendapat kesempatan menyelamatkan diri. Secara tradisional, seorang kapitan perahu dapat saja mengkhianati "sumpah jabatannya" ini, tetapi dengan itu secara sosial dia telah mati. Orang-orang di kampungnya tidak pernah akan memaafkan dia, dan barangkali anak-cucunya juga akan tetap menanggung aib ini bahwa pernah ada seorang kapitan perahu yang demikian pengecut meninggalkan penumpang perahu dan para awaknya begitu saja dalam keadaan terlunta-lunta ketika kapalnya karam. Mentalitas cari selamat sendiri adalah hal yang ditabukan.
Tentu saja etos ini ada risikonya sendiri. Seorang kapitan perahu cenderung menjadi pemimpin dengan one-man leadership. Ketegasan yang dituntut daripadanya dapat berubah menjadi sikap otoriter. Kepemimpinan tunggal ini masih sering kita dengar dari ungkapan sehari-hari bahwa tidak mungkin ada dua orang kapitan di atas satu perahu. Dalam kehidupan di atas perahu, kepemimpinan tunggal ini relatif diterima karena diimbangi dengan tanggung jawab yang sangat besar dari sang kapitan. Dia juga didukung oleh legitimasi yang kuat berupa pengakuan dan penerimaan para awak perahunya. Di samping itu, patut diingat bahwa risiko otoritarianisme adalah risiko yang ada pada segala jenis kepemimpinan dan segala jenis kekuasaan. Dalam hal ini, legitimasi dapat menjadi kontrol yang kuat. Seorang pemimpin yang selalu menunjukkan sikap otoriter terhadap bawahannya, dengan atau tanpa alasan, lambat-laun akan kehilangan legitimasinya. Sebab, legitimasi adalah unsur yang masih menyelamatkan rasionalitas penggunaan kekuasaan. Kalau orang yang diperintah merasa bahwa kekuasaan itu bukannya dipergunakan untuk menyelamatkan seluruh perahu dan penumpang melainkan sudah menjadi tanda kesewenang-wenangan kapitannya, bisa saja terjadi pembangkangan di atas perahu.
Kalau kita ingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan, dan bila diingat juga bahwa tradisi kelautan mempunyai akar sejarah yang demikian mendalam, patutlah dipikirkan, apakah mungkin, dan bagaimana caranya, pola ini dapat diterapkan dalam politik Indonesia saat ini, yang menghadapi masalah serius mengenai kepemimpinan. Penyair Chairil Anwar sudah menulis pada tahun 1946: Beta Pattiradjawane/ Kikisan laut/ Berdarah laut/ Beta Pattiradjawane/ ketika lahir dibawakan/ Datu dayung sampan (sajak Cerita Buat Dien Tamaela). Sayangnya, baris-baris sajak itu sudah terlalu lama tidak dibacakan dalam politik Indonesia.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini