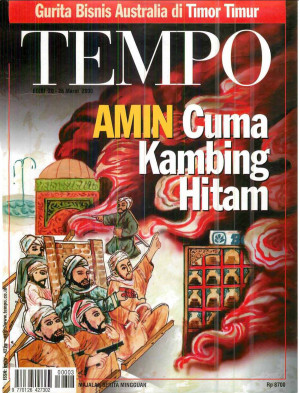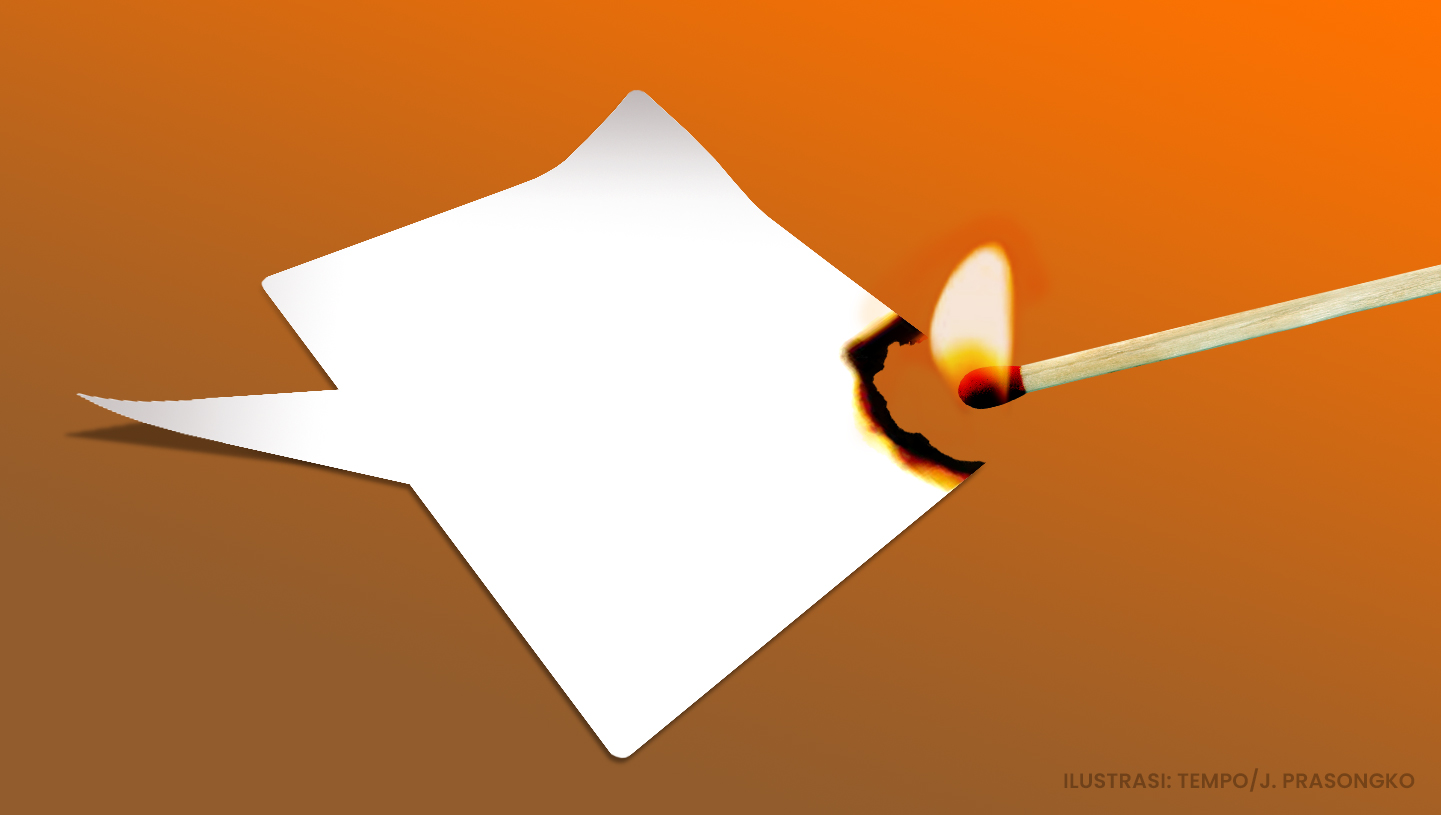Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
![]() Azyumardi Azra
Azyumardi Azra
Pengamat sosial keagamaan
|
ADA nada ironi pada lead rubrik Moni-tor TEMPO, 19 Maret lalu. "Nama Kartini mengingatkan kita kepada tokoh pergerakan wanita asal Jepara. Adapun Kartini yang dibicarakan di sini... juga seorang 'pejuang'. Setidaknya, Kartini ini—pembantu rumah tangga di Uni Emirat Arab (UEA)—sedang memperjuangkan nasibnya. Kartini ditahan oleh pemerintah UEA bersama bayinya yang masih berusia sebulan."
Kartini binti Karim, yang sudah punya suami dan anak yang ditinggalkannya di Karawang, terbukti berzina dengan Muhammad Sulaiman Frangoan, yang telah menghilang. Terpaksalah Kartini menghadapi sendiri pengadilan syariah Islam di Fujairah, UEA, yang menjatuhinya hukuman rajam, akhir Februari lalu. Hukuman ini belum dilaksanakan karena Kartini naik banding. Kasus Kartini mau tidak mau telah membangkitkan wacana tentang rajam sebagai suatu bentuk hukuman hudud (Islamic penal laws). Kesan yang segera muncul adalah: hukuman hudud terhadap perbuatan zina sangat mengerikan. Ini hanya akan memperkuat stigma yang bertahan begitu lama terhadap hukum hudud. Dan sebaliknya mengabaikan kenyataan, Kartini telah melakukan zina, apakah secara sukarela atau terpaksa (jabr). Bagaimanakah sebenarnya hukum rajam secara doktrinal dan historis? Rajam sampai mati (stoning to death) bagi pezina laki-laki dan perempuan yang sudah atau pernah menikah (muhshan), harus diakui, merupakan hukum hudud yang kontroversial, termasuk di kalangan ulama dan fukaha. Terdapat khilafiah, perbedaan pendapat, di antara mereka tentang dasar hukum (dalil naql) penetapan hukuman rajam, dan metode pelaksanaannya. Dalil naql yang lazim dijadikan dasar penetapan hukuman rajam adalah sebuah hadis ahad—yang diriwayatkan seorang perawi saja, dalam hal ini 'Ubadah bin Shamit. Ia mengutip Nabi Muhammad yang menyatakan: "Ambillah olehmu dariku, Allah telah membukakan jalan bagi mereka; lajang dengan lajang dicambuk seratus kali dan dibuang selama setahun; janda dengan duda dicambuk seratus kali dan dirajam." Perbedaan muncul karena tidak ada ayat Alquran yang secara eksplisit menyebut hukuman rajam. Yang ada hanyalah perintah mencambuk para pezina di depan publik sebanyak seratus kali (Surat al-Nur 24: ayat 2). Tapi ada ayat lain dalam Alquran yang sering ditafsirkan sebagian ulama sebagai landasan hukuman rajam bagi perempuan yang melakukan zina, yakni surat al-Nisa' 4:15-16. Ayat ini menyatakan, perempuan-perempuan yang melakukan fahisyah, "perbuatan keji", berdasarkan pembuktian empat saksi terpercaya, haruslah dijatuhi hukuman kurungan di dalam rumah mereka sendiri sampai mati. Tapi ulama berbeda dalam menafsirkan kata fahisyah tadi. Sebagian menafsirkannya sebagai perzinaan antara perempuan dan laki-laki, sebagian lagi memahami sebagai praktek lesbian di antara perempuan-perempuan. Memandang dalil-dalil tersebut, sebagian ulama menyatakan, rajam sampai mati merupakan hukuman tambahan saja berdasarkan hadis ahad tadi. Tapi menjadi kesepakatan ulama, sebuah hadis—apalagi hadis ahad—tidak boleh menjadi dasar hukum mengatasi Alquran. Sebab itu, Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, misalnya, hanya berpegang pada apa yang telah ditetapkan Alquran tentang hukuman bagi pezina. Ia tidak memberi hukuman tambahan kepada mereka, termasuk rajam. Dalam perspektif ini, sebagian ulama berpendapat, hukuman cambuk yang disebutkan dalam Alquran adalah hukuman maksimal. Bisa dikurangi berdasarkan ta'zir, yaitu pertimbangan tertentu dari hakim atau negara. Penolakan lebih tegas terhadap hukuman rajam datang dari ulama Khawarij, yang percaya hukuman itu bukanlah hukum Islam. Alasannya, rajam adalah hukuman yang kelewat batas dan sangat berat dilaksanakan. Kalau memang agama menghendaki hukuman rajam, kenapa tidak disebut tegas dalam Alquran? Mempertimbangkan argumen ulama Khawarij itu, lantas dari mana sumber hukuman rajam? Abdullahi Ahmed an-Naim, ahli syariah asal Sudan yang terkenal dengan karyanya Toward an Islamic Reformation (1992), mengutip Syaikh 'Abd al-Qadir al-Awdah dalam kitabnya al-Tasyri' al-Jan'i al-Islami (1960), yang menyatakan bahwa rajam sebagai hukuman bagi pezina yang telah kawin merupakan bagian dari hukum agama Yahudi. Menurut Syaikh al-Awdah, Nabi Muhammad menerapkan hukuman rajam itu terhadap orang-orang Yahudi yang berada dalam kekuasaan negara-kota Madinah. Pengalaman penerapan hukuman rajam di sejumlah negara Islam pada masa kontemporer juga kontroversial. Negara-negara yang berlandaskan hukum Alquran, seperti Arab Saudi dan negara-negara Teluk, berusaha menerapkannya. Sebaliknya, negara Arab yang mengadopsi hukum pidana Barat seperti Mesir, Syria, Maroko, Aljazair, tidak memberlakukan hukuman rajam. Dalam gelombang "Islamisasi hukum", Pakistan pernah mencoba menerapkannya melalui Ordinansi Penerapan Hadd (1979), disusul Sudan dengan memberlakukan Hukum Pidana Islam (1983). Di Pakistan, kontroversi besar pecah pada kasus Hazoor Baksh versus Negara Pakistan, dan Chaudry versus Republik Islam Pakistan. Ketika kasus terakhir dibawa ke meja pengadilan syariah, dua hakimnya, Salahuddin Ahmed J. dan Aftab Hussain J., terlibat perdebatan panjang untuk mengambil qiyas dari empat kasus rajam pada masa Nabi. Akhirnya, mereka sepakat, hukuman rajam tidak ada dalam Alquran. Karena itu, rajam merupakan hukuman tambahan berkenaan dengan hak Allah (hududullah, yang diputuskan secara ta'zir, kebijakan hakim.) Sedangkan di Sudan, menurut an-Na'im, banyak ambiguitas, terutama pada ta'zir hakim untuk menetapkan hukuman (tambahan) selain hukum cambuk bagi pelaku zina. Padahal, hukuman cambuk itu sendiri dalam Hukum Pidana Islam Sudan Pasal 64 (8) dinyatakan maksimal 100 kali dan minimal 25 kali, tergantung ta'zir hakim. Seperti diingatkan an-Na'im, pemberian ta'zir kepada hakim sulit dibenarkan dalam sistem pidana modern. Sebab, selain mengandung ketidakpastian, juga potensial bagi penyalahgunaan kekuasaan hakim. Wallahualam bisawab. Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini  Berlangganan Tempo+ untuk membaca cerita lengkapnyaSudah Berlangganan? Masuk di sini
 Edisi 1 Januari 2001  PODCAST REKOMENDASI TEMPO cari-angin marginalia bahasa  Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini © 2024 Tempo - Hak Cipta Dilindungi Hukum |