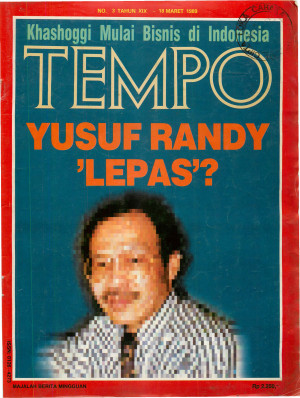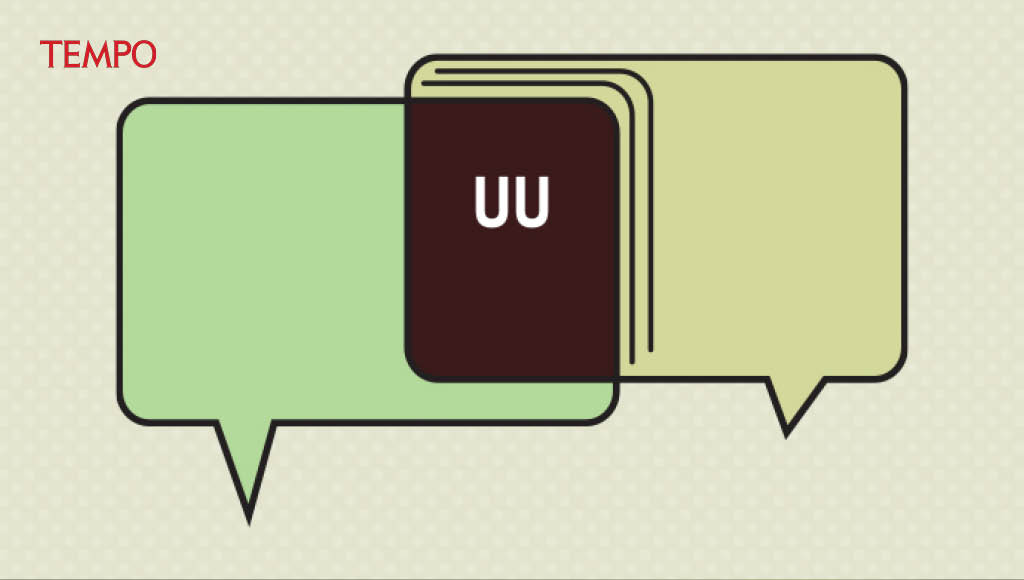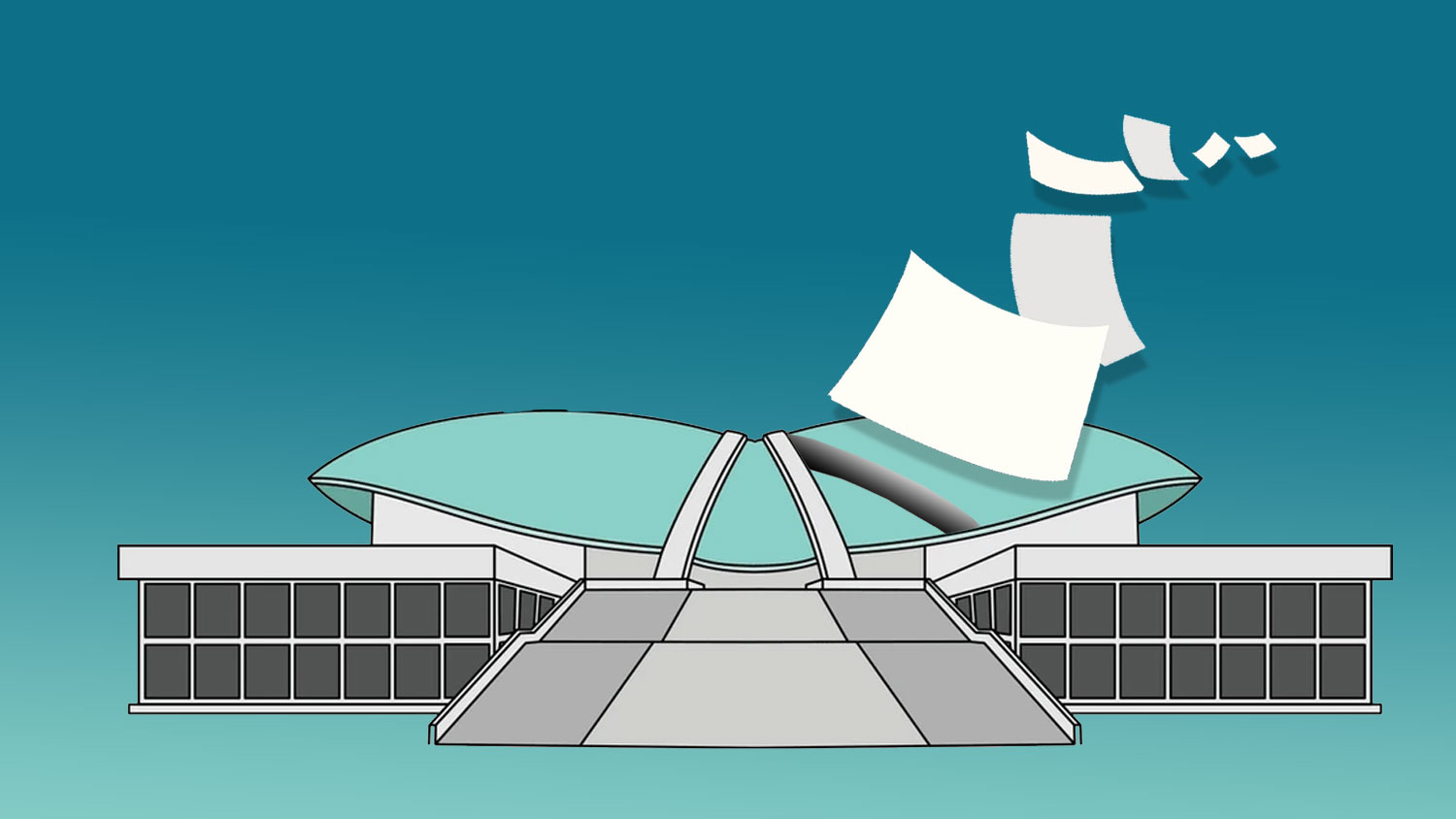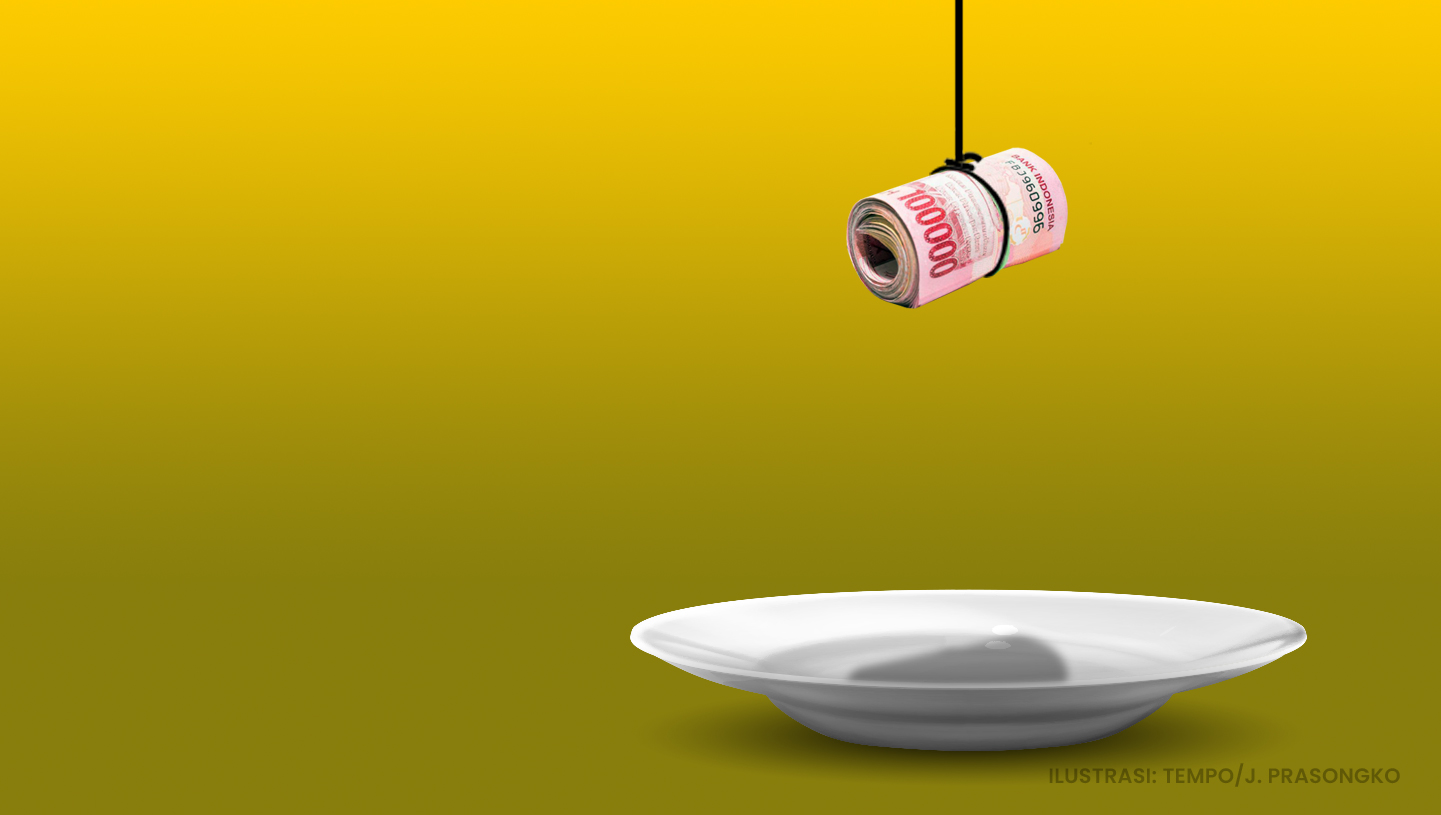BERANGSUR tapi pasti, mereka tenggelam. Tanah mereka terbenam. Desa itu sedang diubah menjadi suatu yang bukan desa: sebuah bendungan. Tapi di mantan desa itu orang-orang itu bertahan. Tiap kali air yang menggenang itu naik -- dan perkarangan serta gubuk mereka seperti dilulur pelan-pelan oleh bah -- mereka pun membongkar tempat tinggal mereka itu, lalu memindahkannya ke bagian tanah yang lebih tinggi. Dari hari ke hari, tingkat air kian mengancam. Kenapa mereka tetap di sana? Apa yang mereka cari? Apa yang mereka pertahankan? Sebagian penduduk toh sudah pindah ke tanah yang sudah di sediakan pemerintah. Tapi kelompok kecil ini seperti tak hendak beranjak. Maka, di luar waduk itu -- pamong, penjabat, mahasiswa, intelektual, teknokrat, wartawan, rohaniwan, calo tanah, dan entah apa lagi -- menunggu. Tengang. "Mereka akan mati tenggelam!" teriak seorang mahasiswa yang prihatin. "Tidak!" jawab seorang teknokrat. "Pemerintah telah menyiapkan segala sesuatunya -- perahu karet, selimut, makanan, kopi hangat, obat masuk angin -- untuk menolong mereka. Jangan sok dramatis!" Sementara itu, air menjalar, melingkar, membubung. "Saya tak paham," kata seorang pamong desa, yang capek. "Dasar bandel. Dasar koppig. Apa mau mereka? Sudah saya terangkan bahwa waduk yang dibangun itu perlu buat kepentingan rakyat juga. Katanya kita perlu makan dan perlu listrik. Kita kan perlu berkorban sebentar, buat anak-cucu. Apalagi sudah disediakan tanah pengganti. Mereka kan tidak disia-siakan. Kok, tidak mau! Saya tidak paham." "kulo mboten purun pindah,Pak," kata seorang petani yang ambang gubuknya hampir tenggelam. "Saya tidak mau pindah. Sayatak tahu bagaimana hidup saya jika saya pergi dari sini. Saya sedih. Yang saya tahu pasti ialah di tanah ini saya pernah punya sesuatu, yang diberikan orangtua saya dulu." "Apa sampeyan tidak sentimentil?" tanya seorang wartawan. "Ah,jij," cetus seorang intelektual, mencemooh sang wartawan. "Petani kok dibilang sentimentil. Petani itu berkorban, Bung. Ia berkorban dari ketidakberdayaan mengambil resiko. Nasibnya begitu kepepet, hingga ia tak bisa bergerak banyak, apalagi mencoba loncat ke suatu keadaan yangtak dikenalnya. Seluruh perilaku dan nilai-nilainya ditentukan oleh perhitungan ekonomi orang terjepit itu. Itulah yang disebut the moral economy of the peasant. Pernah baca?" Malam tiba. Di dalam sebuah gubuk yang mulai dimakan air, terdengar ada seorang anak menangis. "Ada anak menagis!" teriak seorang mahasiswi. "Tenaglah," kat seorang rohaniwan. "Kita bersimpati kepada mereka, tetapi mereka bukan minta kita kasihani. Kita justru kagum. Saya tak setuju jika kita hanya melihat petani itu sebagai korban. Buku dan teori tak bisa menjelaskan semuanya. Yang kita hadapi justru para pahlawan: mereka tahu akan sia-sia, tetapi dengan bertahan seperti itu mereka mengajari kita, juga pemerintah, supaya lain kali rakyat perlu didengar suaranya. Saya tahu, pemerintah maunya baik. Tapi, bagaimanapun rakyat tak bisa dihilangkan haknya -- yang diberikan Tuhan -- untuk memilih jalan hidup sendiri." "Bapak kok begitu," sahut seorang pejabat. "Jika kita biarka tiap orang punya hak memilih jalan hidup sendiri, apa jadinya negeri ini? Kita bukan bangsa Barat, yang dengan arogan membusungkan hak dan kemerdekaan. Hati-hati. Jangan meniru-niru Barat, deh. Mosok, kekuatan anti Pancasila dibiarkan atas nama kebebasan? Apa Bapak mau kalau pencandu narkotik dibiarkan, juga PKI dan Salman Rosyadi?" "Saya protes ,Pak," sela S. Rosyadi, seorang mahsiswa. "Jangan bicara terlalu jauh. Yang dimaksudkan kan cuma: kita harus selalupunya alternatif. Apa pemerintah selalu benar, hingga kalau ada orang bicara lain, dianggap tak boleh dibiarkan? Lantas dimusuhi, kalau perlu dibasmi?" "Wah. Yang omong terlalu jauh kan situ, to Nak," jawab pamong desa, membela pak pejabat. "Apa, sih, salahnya pemerintah kali ini? Kita tidak pakai kekerasan, lho, untuk memindahkan orang-orang itu." "Mboten purun pindah, Pak," kembali kini petani itu berkata. "Saya tak kepingin pindah. Saya tak punya banyak. Tapi setidaknya di sini saya punya sesuatu yang dekat dengan hati saya, sesuatu yang bisa saya cintai. Mumpung, Pak. Besok saya akan kehilangan itu." "Sentimentil, ah. Seperti film India," pikir si wartawan. Yang tak diketahui si wartawan ialah bahwa ia sedang menyaksikan satu hal: bahwa hati dan perasaan sering punya pilihan dan ungkapannya sendiri. Tak selalu mudah kita memahaminya, tak selalu mudah kita mengkalkulasikannya. Juga tak selalu mudah kita menilainya dengan doktrin, dengan teori.Goenawan Mohammad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini