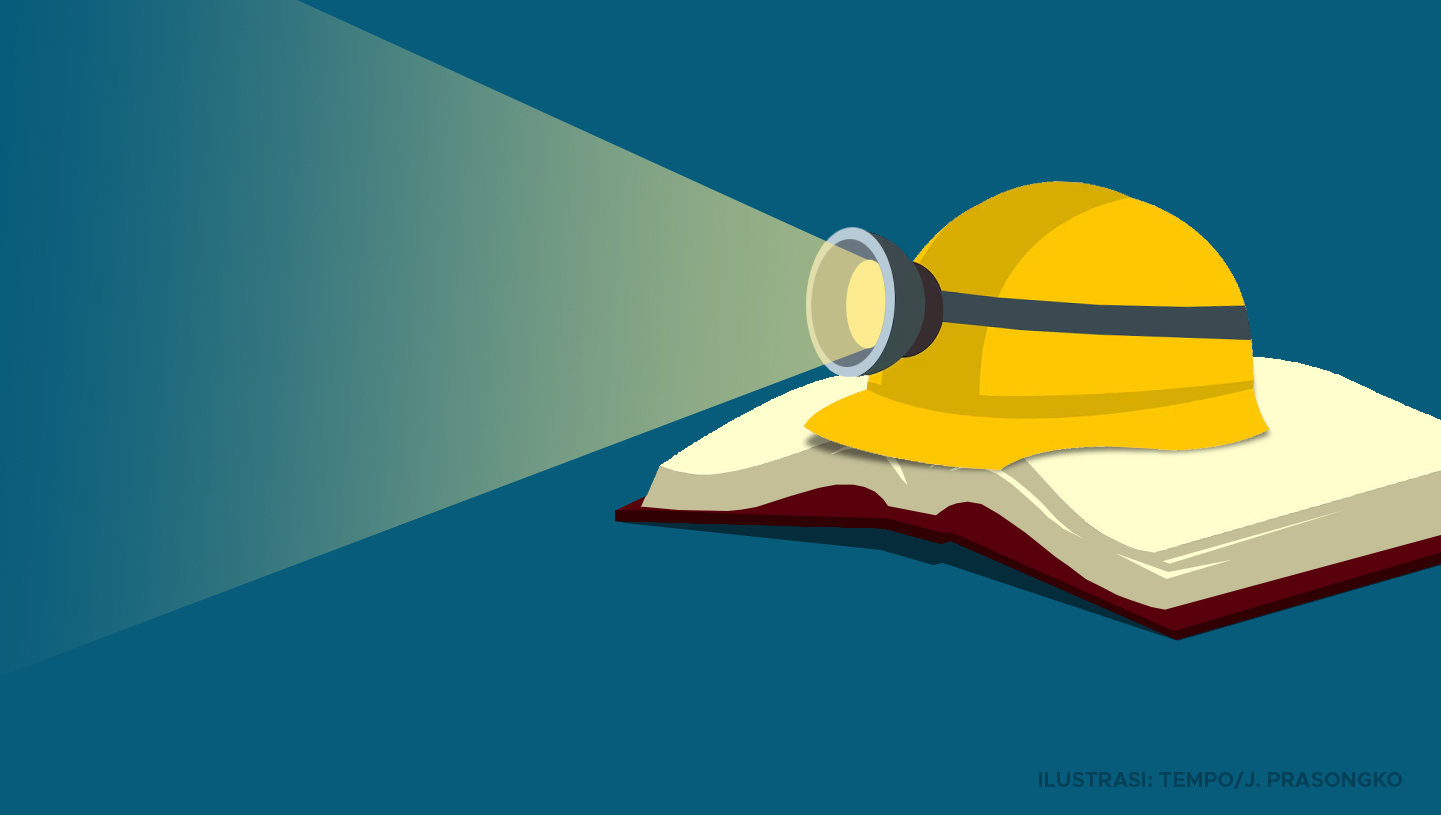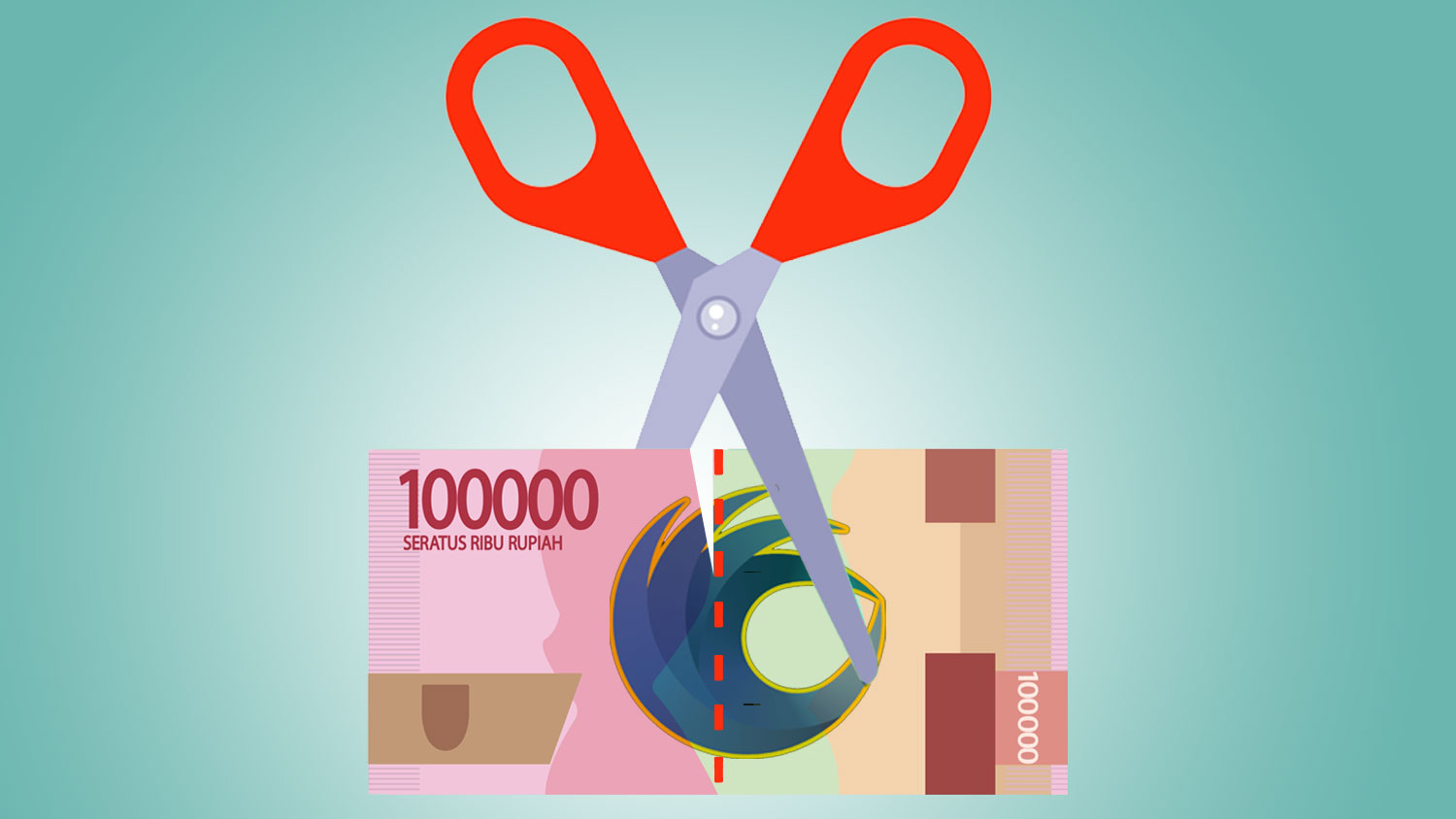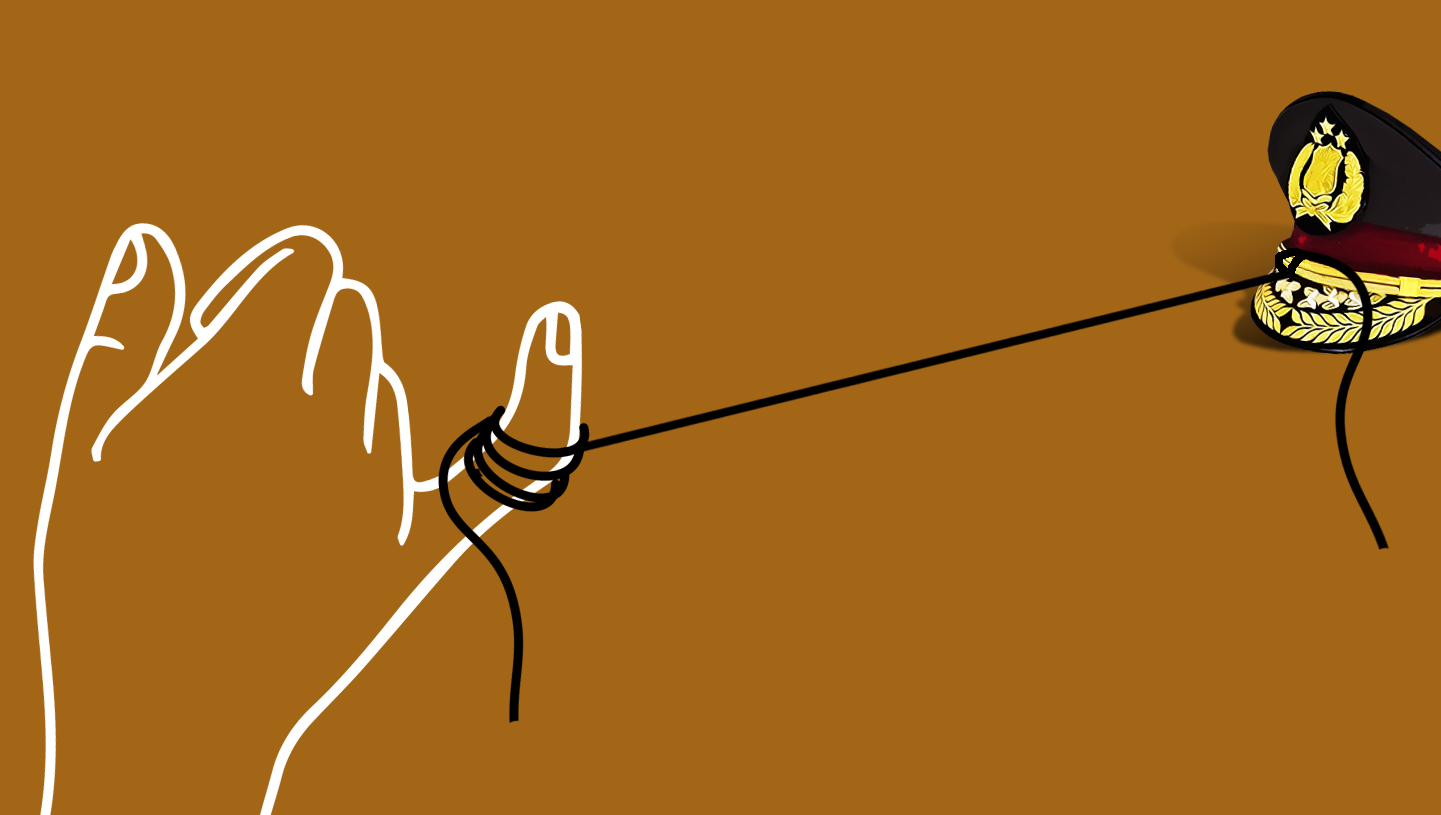Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
TIDAK ada negara yang berhasil jika pemerintahannya hanya mementingkan pembangunan ekonomi. Kemaslahatan publik tercapai hanya jika pembangunan ekonomi tidak mengorbankan demokrasi, keadilan sosial, dan kebebasan sipil. Tiga hal ini yang terabaikan ketika Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Desember lalu mengesahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Sejumlah pasal di dalam undang-undang itu membatasi banyak hak mendasar, termasuk privasi warga negara. Aturan itu akan digunakan aparat untuk memidanakan banyak orang, terutama mereka yang memiliki aspirasi politik berbeda, kelompok minoritas, dan kalangan kritis. KUHP baru yang seharusnya bisa memperbaiki produk hukum kolonial itu justru menjauhkan kita dari usaha menyelenggarakan negara yang demokratis dan modern.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini

Sebelum DPR mengesahkan rancangan undang-undang usulan pemerintah tersebut, berbagai kalangan telah memberi masukan. Namun wakil pemerintah menganggap kekhawatiran banyak pihak terhadap sejumlah pasal dalam RUU itu sebagai paranoia. Bukannya meninjau alasan moral dan filosofis mengapa pasal itu seyogianya dihapus, mereka malah menyodorkan klausul teknis yang memoderasi proses pemidanaan.
Di dalam bab penjelasan tentang pasal penghinaan presiden, misalnya, disebutkan bahwa penghinaan kepada kepala negara hanya bisa diadukan ke polisi oleh presiden sendiri—tidak oleh pendukung atau pihak lain. Penjelasan itu ingin memberi kesan bahwa pasal ini tidak mudah dipakai dan presiden tidak bisa lepas tangan atas delik yang diadukannya. Padahal pangkal masalahnya bukan pada urusan teknis, melainkan pada dilanggarnya hak masyarakat untuk beropini dan mengekspresikan pendapatnya secara merdeka, sesuatu yang dijamin konstitusi.
Ancaman pidana kepada pengkritik presiden mungkin akan membuat presiden, termasuk Joko Widodo, tenang. Mereka akan leluasa mengambil keputusan tanpa takut disalahkan masyarakat atau menimbulkan “gaduh”—terminologi yang akhir-akhir ini telah jadi lazim. Tapi praktik demokrasi yang paling primitif sekalipun mengajarkan kita bahwa setiap kebijakan pasti mengandung “lancung” yang hanya dapat diperbaiki lewat adu pendapat secara terbuka.
Di sini kritik publik dan kemerdekaan berpendapat menjadi relevan—juga kebebasan pers yang ikut dikebiri dalam undang-undang ini. Dengan ditakut-takuti lewat pasal pidana, pers akan melakukan swasensor, laku yang mengingatkan kita pada praktik di negara totaliter. Tanpa pers yang bebas, tak ada demokrasi dan publik kehilangan kesempatan untuk mengetahui hal ihwal yang menjadi haknya.
Terhadap Pancasila, KUHP baru sangat defensif. Undang-undang itu memberikan sanksi pidana terhadap mereka yang menyebarkan ideologi di luar Pancasila. Boleh jadi aturan itu berangkat dari kecemasan pada paham radikal yang dituding menjadi biang kerok sejumlah kekerasan berbasis agama. Tapi, tanpa memperjelas apa yang dimaksud dengan ideologi di luar Pancasila, pasal ini akan mulur-mengkeret sesuai dengan kehendak hati penguasa. Marxisme-Leninisme memang secara jelas disebut sebagai ajaran yang penyebarnya dapat dihukum. Tapi bukankah Pancasila merupakan resultante atas ideologi-ideologi yang berkembang di awal Republik yang salah satunya adalah sosialisme? Atas dasar apa pembahasan terhadap salah satu ideologi pembentuk Pancasila dapat dihukum?
Berlaku tiga tahun dari sekarang, pemerintah menyarankan mereka yang berkeberatan dapat mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Terdengar konstitusional, saran ini sesungguhnya merupakan laku lajak yang menyebalkan. Mahkamah Konstitusi kita tahu bukan bagian dari proses legislasi. Apalagi akhir-akhir ini independensi Mahkamah kerap dipertanyakan.
KUHP, sebagaimana undang-undang lain, adalah hasil negosiasi politik. Politikus berbasis agama mendapat manfaat dari undang-undang ini lewat pemidanaan terhadap pelaku kohabitasi. Pemerintah dan sebagian pendukungnya mendapat manfaat dengan dibelenggunya kebebasan sipil. Di tempat lain, ada pula pasal-pasal yang meringankan hukuman kepada koruptor, aspirasi gila yang entah diajukan oleh siapa.
Dengan demikian, KUHP setidaknya buah kolaborasi mereka yang ingin mengembalikan otoritarianisme Orde Baru; mereka yang ingin membawa ajaran agama, yang semestinya privat, ke ranah publik; dan pendukung korupsi. Sebuah “hadiah” buat publik di tahun-tahun terakhir pemerintahan Jokowi.
- Akses edisi mingguan dari Tahun 1971
- Akses penuh seluruh artikel Tempo+
- Baca dengan lebih sedikit gangguan iklan
- Fitur baca cepat di edisi Mingguan
- Anda Mendukung Independensi Jurnalisme Tempo