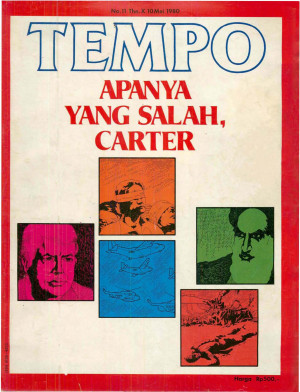ADA musuh, ada lawan. Kedua kata itu berbeda. Hanya kita sering
melupakannya.
Marilah kita bermula pada kamus. Kamus Umum Bahasa Indonesia
susunan W.J.S Poerwadarminta (diolah kembali oleh Pusat
Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan) sepintas menyebut lawan sebagai sinonim musuh. Tapi
tak seluruhnya.
Kita misalnya tidak bisa mengatakan musuh kata", melainkan lawan
kata". Kita juga misalnya tidak bisa mengatakan, "Siapakah
musuhmu bercakap-cakap tadi?", melainkan "Siapakah lawanmu
bercakap-cakap tadi?"
Dengan kata lain: dalam pengertian lawan tidak ada antagonisme
yang total. Kesebelasan Warna Agung tidaklah memusuhi
kesebelasan Jayakarta, melainkan melawannya. Yang satu tak
bermaksud menegasikan yang lain. Yang satu tidak hendak
meniadakan yang lain. Bahkan dalam kata lawan bercakap-cakap
yang tersirat adalah peneguhan perlunya kehadiran pihak yang
lain.
Tapi terkadang si-yang-lain cenderung diperlakukan dengan
antagonisme yang total. Kita sering menyebut lawan sebagai
musuh, dan kita tak menyadari implikasinya.
Bagi agitasi, terutama dalam ideologi totaliter, kekaburan
pengertian lawan dengan musuh memang lazim. Dan barangkali
disengaja. Dalam perbendaharaan kata revolusi Kambodia yang
dipimpin Pol Pot, misalnya, setiap sisa kekuatan Lon Nol adalah
musuh, dan karena itu harus dibasmi. Maka di sana beribu-ribu
orang pun dibunuh. Baru ketika Pol Pot begitu terdesak, hingga
ia menyatakan mau bekerjasama dengan sisa-sisa rezim lama, ia
memberikan arti lawan kepada apa yang semula ia nyatakan sebagai
musuh.
Dalam hubungan ini baik juga kita telaah, sejauh mana kekalutan
telah terjadi di tempat lain. Benarkah misalnya pemerintahan
Khomeini di Iran merupakan musuh Amerika Serikat? Para diplomat,
seperti Cyrus Vance, cenderung mengatakan bukan. Mereka yang di
Qom dan Teheran itu adalah lawau Amerika Serikat. Dengan
demikian selalu terbuka kemungkinan untuk hubungan baik kembali.
Tapi para diplomat, yang terlatih sabar, memang jarang laku di
masa kampanye pemilu.
Sebaliknya benarkah pemerintahan. Carter dan Amerika merupakan
musuh Iran? Ayatullah Khomeini konon menyebut Amerika Serikat
dan Carternya sebagai "setan"? yang tentu saja "memusuhi Islam"
-- seperti jNga Ayatullah Khomeini menyebut Iraq "memusuhi
Islam". Dan bila apa saja yang sedang adl lawan Iran dianggap
"memusuhi klam' jelaslah antagonisme itu telah diikm total --
sama halnya bila setiap suara yang menentang pemerintah dianggap
"anti-Pancasila". Artinya ada keharusan melenyapkan
si-yang-lain. Setidaknya itulah seruan dalam revolusi -- yang
memang sering berlebihan.
Untunglah sejarah mengajarkan, bahwa apa yang dikatakan di masa
panas tak harus terus menerus berlaku di masa sejuk. Contoh baik
ialah yang terjadi di Zimbabwe. Tatkala Mugabe memimpin gerilya,
pekik peperangan seakan hendak membetot orang-orang bule dari
bumi Rhodesia. Tapi setelah kemenangan lewat pemilu ternyata
Mugabe tidak menidakkan orang putih. Bahkan ia mempertahankan
Letnan Jenderal Peter Walls, perwira kulit putih yang dulu
memimpin pasukan keamanan mengejar-ngejar kaum gerilya.
Kisah Zimbabwe tentu saja kisah indah yang jarang terjadi,
tentang kebesaran manusia mengatasi kebencian untuk bisa berbaik
kembali dengan siyang-lain. Kisah itu juga suatu cerita tentang
perkembangan dialektis dari pengertian lawan dan musuh. Suatu
ketika yang lawan bisa menjadi musuh tapi dalam hubungan
permusuhan itu tetap ada hubungan perlawanan. Dan setelah lawan
jadi musuh, musuh pun kembali jadi lawan -- lawan dalam
pengertian seperti yang terdapat dalam bahasa kita: peneguhan,
bukan peniadaan, kehadiran pihak yang lain itu.
Karena itulah ada hubungan diplomatik. Karena itulah ada
Olympiade. Karena itulah ada Parlemen. Karena itulah ada PBB.
Tiap-tiap fungsi mungkin tak selamanya efektif. Tapi hidup
bersama perlu jembatan-jembatan yang tak terbakar karena kita
tak bisa hidup sendirian lagi.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini