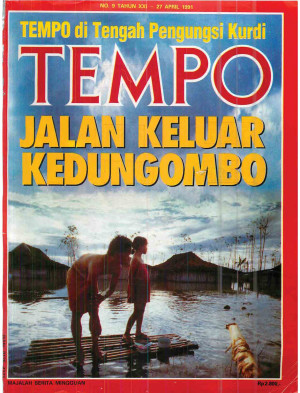Lupa MOCHTAR PABOTTINGGI SEBENTAR lagi babak Saddam-Bush sudah akan dilupakan, betapapun banyak yang telah dikorbankan. Rangkaian peristiwa lain akan segera menyita perhatian kita. Dengan lupa itu, peluang ke arah agresivitas antarbangsa pun kembali dibuka. Belasan tahun lalu, Milan Kundera juga mengingatkan kita akan musabab lupa, yaitu ketika peristiwa demi peristiwa meredam satu sama lain. "Pembantaian berdarah di Bangladesh dengan cepat menghapus ingatan orang akan invasi Rusia di CekoSlovakia. Pembunuhan Allende menenggelamkan rintihan orangorang Bangladesh. Perang di Gurun Sinai membuat orang lupa akan Allende. Pembantaian di Kamboja membuat orang lupa akan Sinai, dan seterusnya. Hingga akhirnya tiap orang membiarkan apa saja terlupakan." Ketika Saddam merebut Kuwait dan bersikukuh menolak mundur, agaknya ia telah melupakan pahitnya perang melawan Iran yang baru dua tahun berlalu. Dibawakan ke diri sendiri, masihkah teringat rangkaian tragedi yang telah dialami oleh bangsa kita? Atau pencabik-cabikan tubuh rakyat Vietnam? Atau, yang kini berketerusan, pembantaian panjang rakyat Palestina, justru oleh mereka yang sebagai bangsa juga pernah mengalami penindasan yang kejam. Banyak dari agresivitas kita terhadap satu sama lain memang berakar dari lupa. Lupa sudah kodrat manusia. Tepat sekali jika Kundera menegaskan bahwa "perjuangan manusia melawan kekuasaan adalah perjuangan ingatan melawan lupa". Namun, pernahkah kita berpikir bahwa lupa bukanlah semata-mata kodrat? Lupa adalah sesuatu yang bisa direncanakan. Lebih dari sekadar "tidak ingat". Lupa berarti "ingat yang lain". Lebih dari sekadar kalimat berita, "ingat yang lain" diangkat menjadi kalimat perintah. Suatu perencanaan dalam skala global telah berlangsung dalam jalinan media massa, para penguasa dan usahawan raksasa. Ramalan Orwell sudah menjadi kenyataan bahkan jauh sebelum tahun 1984. Kehancuran dan polusi di kawasan Teluk Persia selama beberapa minggu dari pertengahan Januari berjalan seiring dengan polusi dalam media massa yang umumnya dikuasai oleh kepentingan adidaya. Lupa makin lama makin terkait dengan peradaban modern. Amat banyak bukti yang menunjukkan bahwa modernitas memang dimaksudkan orang untuk berarti lupa. Tidak terhitung banyaknya kegiatan politik dan ekonomi yang tujuan utamanya ialah membuat orang lupa. Dengan demikian, lupa makin menjadi hasil rekayasa. Seperti pernah dinyatakan oleh Nietzsche, lupa "bukanlah semata-mata visinersiae". Lupa justru bisa merupakan agresivitas. Simaklah iklan-iklan seperti "Creative generation" atau "Pria punya selera". Direncana-lupakan di situ adalah penyakit kanker dan paru-paru. Simaklah janji Presiden Bush kepada rakyat Amerika dalam konfrontasinya dengan Saddam bahwa "takkan ada Vietnam kedua". Yang diingat di situ hanya serdadu-serdadu Sekutu. Rakyat Irak dilupakan. Bagi mereka tetap tersedia "Vietnam" dalam porsi besar. Simaklah istilah seperti "kecemburuan sosial" yang terus begitu fasih diucapkan oleh sementara kalangan. Di situ yang dipersalahkan selalu adalah orang-orang miskin, mereka yang perekonomiannya tak kunjung bertumbuh, barisan pencemburu. Direncana-lupakan adalah kenyataan bahwa masalah kemiskinan tak pernah lepas dari masalah struktural dan bahwa cetak biru bangsa kita adalah untuk melenyapkan berbagai kesenjangan ekonomi dan politik yang sudah berabad-abad berlaku. Begitu masif dan merasuknya "proyek lupa" ini sehingga tak lagi kita sadari, lupa yang berlangsung pada diri atau di sekitar kita tiap hari. Kita lupa bahwa bukan hanya lingkungan ekologi kita yang dilanda polusi. Juga alam pikiran kita. Pada alam pikiran yang keruh itulah antara lain kita harus melacak miopia dan agresivitas kita. Riuh rendah alat, sarana, dan program-program komunikasi modern justru telah menghapus komunikasi sejati antarmanusia. Di depan kotak ajaib bernama televisi, misalnya, berapa di antara keluarga-keluarga kita yang dalam sehari sempat saling menatap wajah, saling mendengar suara, saling menjajaki lubuk hati dengan anak, orangtua, saudara sendiri? Jika pada sesama anggota keluarga sudah jarang terjadi percakapan yang sesungguhnya, dan jika keadaan ini pun sudah mengalami globalisasi, alangkah luasnya dukungan atas proyek lupa itu dengan mengorbankan daya kasih. Alangkah rawan fondasi sosial kita sebagai keluarga, kelompok, bangsa, dan warga dunia. Apakah yang harus kita lakukan? Salah satunya mungkin ialah melawan segenap proyek lupa, baik yang disengaja maupun yang tidak, dengan meregulerkan refleksi. Di tengah-tengah polusi peristiwa dan suara di sekitar kita, semakin perlu kita menemukan kembali nurani manusiawi dan sejarah kita yang bening. Semakin perlu kita melepaskan diri dari polusi peristiwa dan suara dari waktu ke waktu, melakukan renungan agar jiwa kita dapat kembali bernapas dan memetik hikmah dari pengalaman umat manusia. Masihkah kita bicara tentang sejarah dengan anak-anak kita? Adakah pada hari-hari tertentu tersedia waktu dalam rumah kita untuk bisa sungguh-sungguh saling menatap wajah dan mendengarkan suara hati? Masihkah kita sekali-sekali bangun tengah malam, memasuki "ruang" khusyuk untuk sungguh-sungguh bersimpuh di depan Sang Mahacahaya? Masihkah kita meluangkan waktu untuk membaca tentang kalangan atau bangsa lain dengan niat untuk benar-benar mengenal mereka, bukan melulu untuk tujuan-tujuan instrumental? Sudahkah kita meluaskan ruang dari personal space kita sehingga kemalangan yang menimpa kalangan atau bangsa lain juga ikut kita rasakan sebagai kemalangan sendiri? Sedikit demi sedikit, lupa bertumpuk dari negasi atas semua pertanyaan ini. Dalam rimba suara, meruaklah agresivitas kita terhadap satu sama lain dan ... terhadap diri kita sendiri.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini