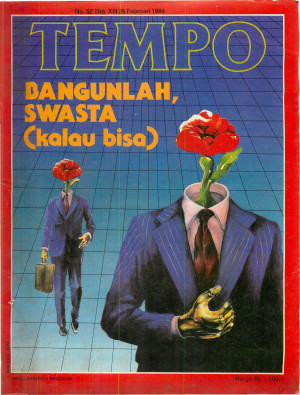ALANGKAH aneh kadang-kadang hubungan manusia dengan habitatnya. Di tengah lingkungan tempat dia bermukim, mencari nafkah, dan membesarkan keluarganya, kadang-kadang dia merasa perlu menyesali tempat yang dipilihnya. Dan membandingkannya dengan lingkungan lain yang seakan tampak lebih indah. Kisah terkenal tentang dua orang petani yang tinggal di dua buah bukit yang berdampingan, dan saling membandingkan, dan saling menganggap buhit tetangganya lebih bagus dari bukitnya sendiri, menjadi cerita klasik - karena naluri manusia untuk tidak gampang puas mengiakan kisah itu. Maka. bagaimanapun semu romantika penghuni kota untuk membayangkan desa sebagai model ketenteraman dan keindahan, agaknya ia tetap bukan impian yang dibuat-buat. Demikian pula cara orang desa merendah-rendah menganggap kota yang bermandi cahaya listrik sebagai model kehebatan dan kemakmuran. Ia bukan sekadar menyatakan basa-basi kelas yang minder. Ia pernyataan kekaguman yang tulus, genuine, dari orang desa yang sehari-hari hidup dalam keremangan cahaya lampu minyak dan belepot lumpur. Akan segerakah mereka memutuskan untuk membedol keluarga, pergi menyongsong impian indah? Pengalaman sering justru menunjukan hal sebaliknya. Mereka akan alot sekali meninggalkan lingkungan permukimannya - bagaimanapun kusam dan tidak romantis. Sesudah memandang bukit di sebelah dan menghela napas panjang, agaknya dia masih akan sekali lagi menghela napas melihat bukitnya sendiri - menerima kekusamannya, tapi sekaligus kehangatan dan kekukuhan tancapan akarnya. * * * Malioboro, jalan legendaris yang membelah jantung Kota Yogya, sekali lagi dibenahi. Entah lewat berapa wali kota sudah jalan sepanjang dua kilometer ini dirombak, dibongkar, dirombak. Seakan, kalau hendak dinyatakan dengan mitos Mataram, jalan ini pengejawantahan Nyai Loro Kidul, yang pada setiap pergantian raja Mataram menuntut suatu perkawinan sakral-spiritual dengannya. Bagaimanapun, tidak dapat disangkal daya tarik istimewa - kalau tidak dapat dikatakan magis - jalan ini. Sejak zaman kejayaan Kasultanan Yogyakarta dahulu, jalan yang lurus bagai poros singgasana sultan hingga tugu di perempatan bagian utara kota ini telah menyaksikan berbagai peristiwa. Prosesi kirab-dalem Sri Sultan di kereta kencana Kiai Garuda Yeksa, lengkap dengan segala pengiring. Iring-iringan kanjeng tuan gubernur Belanda dengan para pejabat tinggi pemerintah kolonial. Prosesi Kiai Tunggul Wuung, pusaka keramat keraton yang mampu menghalau wabah penyakit pes yang menghantui seluruh kawula. Dan pada zaman Yogya sebagai ibu kota revolusi: iring-iringan mobil butut para pemimpin yang pada duduk dengan kepala tegak, dengan bendera merah-putih berkibar-kibar dan pekik merdeka rakyat yang seakan tiada putus, para pejuang berambut gondrong dengan pistol bergelantungan, mondar-mandir di jalan yang jadi remang-remang karena kurangnya cahaya listrik. Semua itu direkam oleh rakyat, para kawula Yogya. Tidak semuanya memancarkan kebesaran, grandeur, kesukaan. Sering bahkan kedukaan dan keprihatinan. Tapi selalu saja rakyat, para kawula berdiri tegak menyaksikannya dengan kepatuhan, kekaguman, kesetiaan. Panes et circus, roti dan permainan, sabda sang Caesar pada zaman Romawi kuno. Di Yogya, mungkin circus saja - seperti terlihat dalam segala macam prosesi di Malioboro - ditambah sedikit beras dan gaplek, sudah akan membuat rakyat tenteram. Bagi mereka circus seperti itu bukan hanya permainan, tetapi juga upacara pernyataan solidaritas total terhadap jagat semesta yang dicerminkan oleh Kerajaan Ngayogyakarta. Maka, Malioboro yang dijebol dan dibangun berkali-kali itu diharapkan rakyat akan mengembalikan lagi fungsinya sebagai koridor circus, gang panjang yang mampu mengikat grandeur dan romantika perjuangan dan pengorbanan. Harapan itu tidak kunjung terkabul. Sebab perencanaan yang tambal-sulam hanya mampu menggeser-geser trotoar dan toko hingga beberapa meter ke belakang, tanpa menciptakan unsur suasana grandeur apa pun. Maka, ketika akhirnya pemerintah pusat berketetapan ikut turun tangan membenahi Malioboro, dengan anggaran yang jauh lebih besar dan perencanaan yang lebih mewah, harapan akan kembalinya grandeur di Malioboro tumbuh kembali. Dan memang. Jalan itu sekarang memiliki trotoar pejalan kaki yang lebih lebar, jalan khusus untuk sepeda motor dan becak, serta jalan khusus untuk mobil dan andong. Mobil tidak lagi boleh diparkir di jalan itu, melainkan di jalan-jalan samping di sebelah timur dan barat. Tiang-tiang lampu gaya antik bermunculan, menambah cerahnya sinar Malioboro di waktu malam. Pohon-pohon di pinggir jalan mulai ditanam, toko-toko serta hotel-hotel ikut berbenah. Pedagang kaki lima berjejeran di trotoar hingga pukul 9 malam, dan sesudah itu hingga larut ganti si mbok penjual gudeg, nasi liwet, dan warung Padang lesehan berderetan di depan toko-toko yang sudah tutup. Tetapi grandeur yang ditunggu itu? Akan dengan sendirinya datang, bersama perombakan "struktur" Malioboro? Grandeur ternyata hanya datang bersama aura wibawa suatu kurun waktu yang khas. Wibawa keraton dengan kereta kencana dan segala regalia berbagai bentuk, wibawa revolusi dengan mobil butut, para pemimpin yang melarat tetapi kepalanya selalu tegak, wibawa kota yang redup tetapi penuh gairah hidup. Dan aura wibawa itu lampau sudah. Sekarang koridor itu hanya dilewati prosesi rutin para pedagang impian, yang mengejawantah dalam etalase toko yang berjubelan dengan produk negara industri maju, para wisatawan yang diharap akan terus berdatangan dengan kocek yang padat, para cendekiawan, birokrat, teknokrat, priayi yang menyangga gaya hidup industri maju. Dengan bahan seperti itu, teater kolosal bagaimana yang bisa diharap dapat dipentaskan di koridor Malioboro? Aura sang raja hanya lamat-lamat terasa, karena sang raja hanya sempat datang di kerajaannya dua hingga tiga bulan sekali dalam beberapa hari. Dan para pemimpin yang melarat, tetapi sanggup berjalan dengan kepala tegak, hilang diserap roda sejarah. Teater kolosal tidak akan terpentaskan lagi. Malioboro yang akan ceria, bersinar-sinar, dan bersih, akan hanya menjadi koridor circus kitsch. * * * Di tengah Kota Yogya mengalir Code. Ini bukan sungai yang istimewa cantik. Berkelok-kelok mengahr darl utara ke selatan, dengan airnya yang lumayan jernih dan batu-batu lahar Gunung Merapi berserakan sepanjang alur, sungai ini menjadi istimewa karena ia membelah bagian pusat kota. Maka tebing-tebingnya yang tidak curam menjadi bagian yang menarik, bagi mereka yang tidak mampu membuat rumah di kampung-kampung dan daerah elite dan mau dekat fasilitas pusat kota. Waktu permukiman ledok-ledok ini semakin padat, serta arus penduduk melarat terus saja masuk kota, maka lahan-lahan yang lebih sempit di bawah-bawah tebing, praktis di pinggir sungai, mulai juga dipadati rumah penduduk. Apa yang disebut lahan di pinggir sungai adalah tanah-tanah lunak dan pasir yang sesungguhnya masih "bergerak" - wedi kengser, kata penduduk. Code, yang sepanjang generasi selalu menerima kotoran para penghuni Yogya bagian tengah dan mengalirkannya ke selatan, makin megap-megap kemampuannya menampung dan mengalirkan segala sampah - dari tidak hanya penduduk kota yang makin padat, tetapi terutama dari sangat berjubelnya para penghuni sepanang sungai. Apa mau dikata? Orang melarat, banyakkah pilihannya? Meskipun tanah pinggiran itu adalah tanah empuk bercampur pasir yang sewaktu-waktu bergerak? Bila hujan turun dengan derasnya, wedi kengser akan bergeser dan rumah-rumah di atasnya pun ikut hanyut. Penduduk lari mengungsi ke para tetangga di lahan tebing sebelah atas. Bila hujan berhenti, mereka turun lagi, membangun lagi rumah mereka. Kehidupan pun kembali "normal". Sampah-sampah dan kotoran lain terus juga dibuang ke sungai. Penduduk pada mandi, buang air, berkumur, mencuci beras dan pakaian di sungai seperti biasa. Anak-anak bersembur-semburan, ibu-ibu dengan kain basahan memandikan anak mereka. Dari atas jembatan Code pemandangan itu bagai lukisan lanskap Bali dari Walter Spies. Indah, tenteram, damai, gembira, sementara Code makin menyempit juga. Maka musim hujan 1984 tibalah. Tanpa satu ramalan yang jelas, apalagi penerangan, curah hujan dengan dahsyatnya mengguyur Yogya dalam ukuran yang jauh melampaui tahun-tahun yang sudah. Jalan-jalan di daerah permukiman "elite", yang biasanya tidak kebanjiran, tahun ini harus mengalaminya. Dan Code? Dengan kesakitan yang sangat, air pun naik dengan cepatnya. Dan Code mengamuk dahsyat. Rumah-rumah wedi kengser di lahan bawah dan rumah-rumah di ledok dihajarnya dan hanyut bagai rumah-rumahan kertas. Jembatan-jembatan, yang agaknya sudah lama tidak diperiksa keselamatannya, "tiba-tiba" jebol atau amblas. Kembali pemandangan rutin pada musim hujan terlihat. Mereka yang kehilangan rumah mengungsi. Mereka yang tinggal di bagian ledok atas pun menerima mereka. Dapur umum disiapkan. Para pejabat pada turun meninjau, membagikan bantuan, menjabat tangan penduduk, mencolek pipi bayi-bayi mereka. Untuk kesekian kali pun diberikan penerangan akan bahaya tinggal di lahan-lahan sempit pimggiran sungai, serta bahaya penyumpalan sampah serta kotoran di sungai. Penduduk mendengarkan dan manggut-manggut. Sesudah hujan reda, dan mereka tahu bahwa tuan rumah sudah sampai pada batas kemampuan menerima pengungsian, mereka pun berduyun kembali ke lahan bawah - memilih bagian mana sekarang yang kebagian wedt kengser yang agak padat, yang akan dapat menyangga rumah mereka, sampai musim hujan yang akan datang. * * * Mungkin saja Malioboro satu koridor circus kitsch. Tapi bagi para kawula yang dipaksa nasib memilih habitat di lahan-lahan sempit di ledok dan wedi kengser, di bawah sana di sepanjang Code, terlalu pentingkah lagi kategori circus kitsch dan pentas yang menghadirkan teater kolosal? Para kawula agaknya tahu, ledok dan wedi kengser itu "bukit-bukit" mereka yang kusam dan tidak romantis. Dengan tarikan napas panjang mereka menerimanya bersama rutin musim hujan mereka. Sebaliknya mereka tahu, Malioboro adalah "bukit-bukit" di seberang sana yang sewaktu-waktu mereka butuhkan untuk mereka pandangi dan kagumi. Dan Malioboro di bukit "sana" itu bagian yang tak terpisahkan dari bukit "sini", di Code. Mungkin akhirnya keyakinan itu lebih penting daripada kategori circus kitsch dan teater kolosal itu. Grandeur yang telah mencala, mengubah diri, menjadi kemewahan kecil-kecilan, mungkin akan tetap nampak bercahaya indah bagi rakyat penghuni bukit di "sini". Asal Malioboro tetap bersedia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari mereka, dalam menyangga jagat Mataram. Panes et circus. Apa pula makna sesungguhnya kata-katamu itu.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini