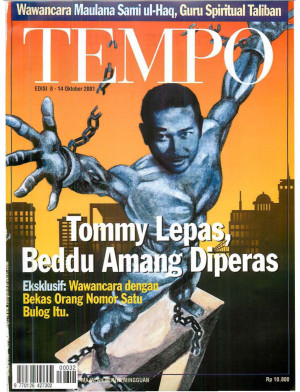Saya tahu engkau marah di hari-hari ini. Tentu, peradaban juga dapat dimulai dari kemarahan. Tapi tak ada peradaban seandainya kemarahan tak tumbuh menjadi politik. Maka tiap perang punya elemen antiperang, dan tiap kemarahan punya tutup. Bukankah pada tiap jam dalam hidupnya, manusia sadar bahwa selalu ada orang lain? Dengan yang lain itu--yang kadang kala aneh, menakutkan, mencurigakan, atau menggelikan--saya atau engkau harus bercakap-cakap.
Politik dimulai dari percakapan seperti ini. Juga niaga, proses saling meniru, saling berkabar, mengucapkan selamat pagi dan membentangkan jalan. Dari sinilah sejarah terjadi, sebab sejarah umumnya bukanlah cerita penaklukan. Pada akhirnya seorang panglima perang toh akan mengatakan bahwa menaklukkan adalah upaya yang amat mahal.
Hari ini kemarahanmu tak sendirian. Orang tampaknya marah di mana-mana. Hanya sedikit elemen penangkal yang didengar. Tapi di mana pun juga, tiap unsur antikemarahan harus bersuara. Justru di saat semacam ini. Di New York, metropolis yang terluka itu, orang mencoba. Sejak sepekan ini tampak orang-orang mengenakan baju hitam berkabung, dengan membawa tulisan: "Our grief is not a cry for war." Beberapa hari kemudian orang berdatangan ke plaza utara Taman Union Square. "Kami berhimpun di sini sementara bom berjatuhan di Kabul," kata Peter Laarman, pendeta senior di Gereja Judson Memorial di Greenwich Village, di antara kerumunan orang yang berhimpun itu. The New York Times mencatat, mereka datang pukul setengah tiga siang. Mereka berbaris, kian banyak, sampai 10 ribu, berlarat sepanjang tujuh blok kota besar itu, menuju ke arah 42nd Street dan Broadway. Di barisan itu mereka berseru, "Peace, Salaam, Shalom."
Tiga bahasa, tiga patah kata dari tiga agama, dan sekian banyak perasaan sedih: sedih karena hampir 5.000 orang hilang dan mati di World Trade Center pada tanggal 11 September itu, sedih karena kehilangan itu telah membangkitkan patriotisme yang menyempitkan diri dan kemarahan yang menjatuhkan bom. Juga sedih karena Tuhan disebut, dikibarkan, dengan sengit, dan keadilan mengalami metamorfosis: menjadi kebencian.
Mungkin sebab itu hari itu, di 42nd Street, orang Kristen, Yahudi, Islam, dan Hindu bertemu. Pidato digelar. Injil, Quran, dan teks suci lain dibacakan. Rabbi Ellen Lippmann dari sebuah sinagog di Brooklyn berkata, "Ketakutan saya yang paling besar adalah bila kita akan membunuh ribuan orang yang tak ikut berperang." Margarita Lopez, seorang anggota dewan perwakilan dari daerah Lower East Side, mengucapkan apa yang saat itu memang ingin diutarakan kepada para jenderal dan presiden mereka di Washington, DC: "Tidak atas nama saya, tidak atas nama New York, tidak atas nama distrik saya, Tuan bisa membunuh siapa pun di Afganistan, di Pakistan, atau siapa pun di Timur Tengah!"
Di 42nd Street hari itu, kau lihat, kata "saya" menjadi "kami". Tapi mungkin kau bertanya, tidakkah kata "kami" punya batas? Bukankah selamanya akan ada orang yang berada di luar lingkaran?
Ya, memang "kami" punya batas. Tapi justru dengan itulah manusia membutuhkan apa yang politis: sesuatu yang lahir dari keterbatasan. Justru dengan itu peradaban menemukan sendinya. Peradaban adalah sebuah proses yang mengubah "kami" menjadi "kita". Tapi tentu kau bertanya: bagaimana dua musuh bisa menyebut diri bersama sebagai "kita"?
Hari-hari ini, kekerasan membuat banyak hal jadi mustahil. Kekerasan melontarkan gambaran sebuah dunia yang sebenarnya tak kita kenal sehari-hari: dunia yang terdiri dari dua sisi yang terpisah seperti arang patah. Ketika Samuel Huntington berbicara tentang "bentrokan peradaban", ia menggunakan sebuah metafora kekerasan--dan sebab itu ia salah, karena hubungan peradaban, "Islam", dan "Barat" (sebenarnya kita tak tahu persis apa arti kedua kata itu) tak pernah berada dalam keadaan patah-arang.
Saya kira itulah yang tampak di hari itu, di 42nd Street. Di sana dua orang pemenang hadiah Nobel untuk Perdamaian hadir. Salah satunya Mairead Maguire, yang memelopori gerakan perdamaian di Irlandia Utara yang dikoyak-koyak teror, di tengah perang antara kaum militan Kristen dan Katolik. "Kita tak perlu menggunakan kekerasan lagi," kata Maguire. "Seperti yang saya lihat di Irlandia, kekerasan hanya akan menghasilkan kekerasan."
Kau mungkin akan menyahut, "Ah, kuno." Mungkin bagimu kalimat Maguire telah jadi sebuah klise yang tak sempat direnungkan lagi. Apa alternatif bagi kemarahan ketika sebuah kaum dizalimi? Dan bukankah seruan damai sering diucapkan dengan hipokrisi? Bukankah orang yang kini mengutuk perang melawan Taliban sebelumnya tak pernah mengecam perang terhadap orang Serbia? Bukankah orang yang menangisi kematian 5.000 orang di World Trade Center tak menangisi kematian prajurit Irak yang tetap ditembaki tentara Amerika meskipun telah menyerah, kematian anak-anak yang menderita blokade ekonomi? Bukankah orang yang mengutuk pembantaian di Lebanon tak bicara apa-apa tentang pembantaian di Aljazair?
Daftar itu bisa diperpanjang. Tapi hipokrisi, atau alpa, atau ketidaktahuan, justru tak seharusnya mereproduksi terus-menerus sikap berat-sebelah. Satu tanda titik harus diletakkan: sudahlah, kita memang pernah bersalah, atau akan bersalah; setiap kita bisa tak adil. Dan selepas tanda titik itu, kita berangkat: kita mengerti bahwa bersikap adil, juga kepada musuh, adalah saat ketika manusia menemukan yang-universal, ketika Tuhan disebut sebagai satu Tuhan bagi semua manusia: Yang Maha Esa. Pengakuan bersalah itu, sikap yang adil itu, dan dikukuhkannya apa yang universal itu, mempertalikan manusia kembali. Perang, teror, kebencian akan tampak sebagai insiden yang tak bisa lanjut. Mereka bukan pola utama hidup.
Saya tahu engkau marah hari ini. Tapi yang saya coba katakan ialah bahwa marah punya sebuah tepi. Di balik tepi itu, hadir maaf. Bahkan maaf dalam pengertiannya yang paling radikal: maaf yang dikemukakan oleh Derrida (dengan bahasa yang terang) sebagai maaf bagi "apa yang tak termaafkan". Dengan kata lain: maaf yang tanpa prasyarat, maaf yang tak bisa dilakukan melalui undang-undang dan lembaga peradilan, atau melalui rekonsiliasi.
Memang ada "kegilaan" dalam maaf ini, kata Derrida; tapi dalam pengalaman seorang korban teror, ada sebuah zona pengalaman yang selamanya "tak terjangkau". Wilayah itu sebuah rahasia yang harus dihormati. Pada akhirnya, memang siapa saja yang marah--Bush, Usamah, prajurit Taliban, Ariel Sharon, orang-orang Palestina yang dianiaya, juga kau dan aku--perlu tahu: kita tak bisa menjangkau zona itu, seutuhnya.
Marah memang punya tepi: maaf dan kerendahan hati.
Goenawan Mohamad
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini