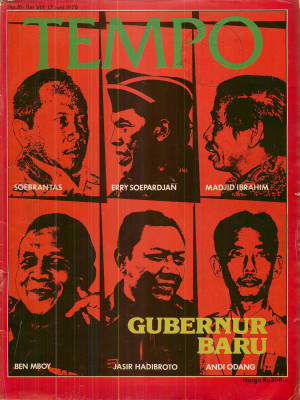SEBUAH pagi yang mengagumkan. Minggu 11 Juni itu, 1.700 orang
berlari 17 km dan 10 km di Jakarta. Di sepanjang jalan yang
biasanya didesak dan dikotori mobil itu, mereka nyaris
berhimpitan. Berkeringat. Terengah-engah. Mencoba mengejar waktu
dan meraih jarak. Dan tak semuanya muda. Di antaranya ada yang
di atas 60 tahun.
Telah lahirkah sebuah gerakan baru? Atau sebuah tradisi?
Apa pun juga, itu adalah pemandangan yang tak tersangka-sangka.
Rupanya begitu banyak orang Indonesia yang "nekad". Rupanya
cukup banyak orang Indonesia yang merasa tertantang, untuk
menghentakkan beribu kali tulang dan otot kaki mereka ke aspal,
yang mulai panas, sepanjang 10 atau 17 km.
Ada yang tak sampai, tentu. Ada yang menempuh sisa jarak itu
dengan terseot-seot jalan kaki. Ada yang terjatuh, pingsan atau
kesakitan. Ada yang mencret di tengah jalan, dengan kotoran
mengalir dari celananya ke paha. Ada yang sempoyongan sampai
garis finis. Ada yang mengigau. Tapi yang sampai atau yang tidak
mereka tidak gentar.
Mungkin jarak 17 km belum apa-apa bagi sebuah maraton. Maraton
Boston yang termashur di Amerika Serikat itu (yang diikuti orang
dari pelbagai umur dan pelbagai profesi), lebih bisa bikin
keder. Di setiap 'Hari Patriot' di pertengahan April, beberapa
ribu pria dan wanita mengenakan sepatu lari mereka, bersiap-siap
di sebuah jalan yang tak menyolok di dusun Hopkinton,
Massachussetts. Ada yang mereguk minumannya sebagai persiapan
terakhir. Ada yang kencing di kebun sayur dekat situ. Ada yang
berpeluk dan berciuman dengan sanak-saudara, seakan-akan mereka
bakal tak bersua lagi. Lalu, tepat tengah hari, pistol
ditembakkan. Dan beberapa ribu umat manusia itu menghambur lari
-- untuk menempuh jarak 41 km...
Apa yang ingin mereka dapat? Mereka pasti tak mencari hadiah.
Tapi jawaban tak selalu mudah dirumuskan oleh banyak orang yang
ikut dalam kegiatan seperti itu. Sebab pemandangan di garis
finis di Boston itu, misalnya, sering mengerikan: ada yang
sampai dengan darah bercucuran, ada yang tersedu-sedu seraya
saling merangkul sepanjang jalan bak prajurit terpukul mundur
dengan cara ganas.
Seorang penulis yang juga ikut lari pernah melukiskan proses
pedih itu begini: "Beda antara jarak satu mil dengan maraton
adalah beda antara rasa jari yang terbakar geretan dengan rasa
terpanggang pelan-pelan di atas bara yang panas."
Toh bebcrapa ribu orang terus saja ikut berlomba di Maraton
Boston tiap tahun dan 1.700 orang muncul di Jakarta pagi itu.
Maka orang pun bicara tentang "masokhisme", tentang keanehan
jiwa yang merasakan nikmat di saat tersiksa.
Benar atau tidak, seorang pelari jauh (meskipun "jauh" itu cuma
5 km) konon bisa mengetahui hubungan gaib antara kedua rasa itu.
Dengan intim pedih dan nyaman membersit jauh di syaraf-syaraf
tubuh. Di saat keringat menderas dan pori kulit menganga
menyedot sisa-sisa dingin pagi, di saat tulang-tulang kaki
terhantam-hantam lewat telapak yang membentur bumi, seluruh
tubuh seakan-akan menyambut angin, matahari, warna, gerak, juga
suara burung.
Ekstase? James F. Fixx, penulis buku The Complete Book of
Running (1977) menyatakan sesuatu yang mungkin berlebihan.
Ketika ia membaca karya William James, Varieties of Religious
Experience, ia kaget menemukan betapa miripnya bahasa para
pelari jauh dengan bahasa kaum mistik ....
Barangkali, ini adalah sebuah eulogia bagi lari. Mungkin orang
butuh mendramatisir suatu kegiatan, yang bagi banyak "orang
luar" (yakni: yang bukan pelari sama sekali tidak dramatis,
membosankan, dan yang jika diterus-teruskan mirip kesibukan
orang tak normal. Apalagi jika diterus-teruskan lari toh tak
menghasilkan tubuh yang elok: yang muncul dari singlet
basah-kuyup setelah hampir tiap hari 15 km itu biasanya badan
yang mirip orang cacingan -- dengan pipi kempot.
Tapi, "It's a treat, being a long-distance runner . . . ," tulis
novelis Alan Sillitoe dalam The Loneliness of the Long-Distance
Rumer. Mungkin karena tersedia cukup kebanggaan (yang terkadang
mendekati kepongahan anak-anak) dalam sport ini. Mungkin karena
tersedia cukup alasan untuk mengejek kekenyangan yang berlebih,
di zaman ini, ketika "banyak" tak berarti "hik."
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini