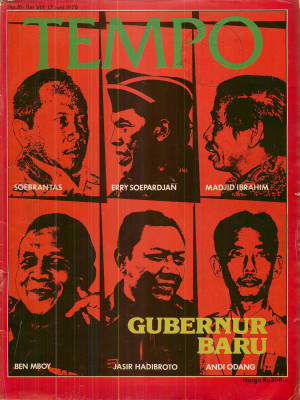BOLA normalisasi kampus bergulir di kaki anggota DPR pekan lalu.
Konsep Menteri P&K Daoed Joesoef yang ingin mengembalikan
peranan mahasiswa sebagai "manusia penganalisa" dan sekaligus
"membangkitkan kekuatan penalaran individuil", banyak mendapat
kritik. Pertemuan mahasiswa UI misalnya, tetap menghendaki
mahasiswa bukan saja sebagai manusia penganalisa, tapi juga
sebagai "pelopor dan penggerak pembaharuan bangsa dan negara."
Ny. Theodora Walandouw, anggota fraksi PDI khawatir kalau konsep
yang dilontarkan Menteri P&K itu akan menimbulkan mahasiswa dan
tenaga yang "menganggap dirinya sebagai barang yang
diperjual-belikan untuk digunakan oleh teknostruktur".
Mengenakan kebaya biru muda kembang-kembang, berkaca mata,
penampilan Walandouw, 58 tahun, tambah menarik hadirin ketika
dikutipnya pendapat Erich Fromm, ahli ilmu jiwa dan filosof
sosial yang terkenal dengan bukunya The Sane Society, suatu
kritik kepada masyarakat Barat. Walandouw khawatir kalau konsep
Menteri P&K itu akan melahirkan generasi yang kelak punya
pandangan "saya ini adalah sebagai yang diharapkan anda", dan
bukan "saya ini adalah yang saya perbuat". Kalau sampai timbul
pikiran yang begitu, menurut Walandouw, "itu bertentangan secara
diametral dengan gagasan pembangunan manusia seutuhnya
berdasarkan Pancasila."
Tak Hanya Ijazah
Tapi ketika memberi penjelasan di depan Komisi IX (bidang
Pendidikan) beberapa hari sebelumnya, Daoed Joesoef tegas
menyatakan tak setuju kalau mahasiswa itu hanya ingin memburu
ijazah. Ia beranggapan mahasiswa "seharusnya merupakan penghasil
gagasan yang disajikan dalam bentuk pemikiran yang teratur."
Dalam rapat kerja perkenalan itu dibaginya bidang teknostrktur
itu menjadi 3 bagian sosial politik, sosio ekonomi dan sosio
kebudayaan, yang semuanya membutuhkan warganegara yang punya
penalaran kuat, yang "sanggup mengajukan reason jauh lebih dulu
dan lebih banyak daripada feeling." Pendeknya, menurut Menteri
P&K, "penalaran yang korek sekaligus juga merupakan dasar yang
kuat bagi keluhuran dan kemantapan budi pekerti."
Ny. Walandouw punya pendapat yang berbeda tentang konsep
penalaran itu. Dia melihat fungsi utana dalam eksistensi
manusia terdiri dari akal, karsa atau rasa. "Karena akal dapat
memilih jalan yang keliru, maka akal tidak dapat menjadi unsur
pimpinan dalam realisasi kehidupan Karsa atau rasa itulah yang
harus mengambil tampuk pimpinan," katanya.
Dalam keterangannya pada TEMPO, Sarwono Kusumaatmadja, anggota
FKP, menyebut manusia penganalisa itu perlu dilengkapi. "Jangan
hanya yang mengagungkan rasio, tapi manusla yang punya rasa dan
cita harus pula ditampung," katanya. Dia khawatir kalau konsep,
yang belum dilihatnya relevan dengan GBHN, tak memenuhi harapan
pemerintah sendiri. Sebab menurut Sarwono, "selama terjadi
proses alienasi pemerintah dan masyarakat, konsep itu secara
materiil tak akan jalan."
Mengutip bab Pendidikan di dalam GBHN, wakil ketua Komisi APBN
Ridwan Saidi beberapa hari sebelumnya, kepada TEMPO, juga
mengingatkan "kekurangan" akan konsep manusia penganalisa itu.
"Manusia penganalisa itu kan hanya satu elemen saja dari manusia
Pancasila seperti yang dicita-citakan GB HN," kata Ridwan. Hal
yang senada juga diutarakan anggota FPP Amir Hamah, dalam
dengar pendapat dengan Menteri P&K.
Kebijakan Politik
Tapi menurut Menteri P&K, "sebagai manusia penganalisa bukan
berarti, mahasiswa tidak dapat menjalankan aksi politik tanpa
keluar dari hakikat kepribadiannya." Ia menanggapi politik itu
dalam 3 pengertian konsep, kebijakan (policy) dan arena
percaturan.
Kalau mahasiswa mengambil artian yang kedua -- dalam bentuk aksi
dan kebijakan politik seperti yang terjadi belakangan ini --
sebenarnya mereka melakukan aktifitas yang tidak sesuai dengan
hakikat kemahasiswaan. "Aksi beginilah yang telah mengubah
kampus dari dunia berpikir menjadi satu arena politik (politik
dalam artian ketiga), mengubah dunia mahasiswa menjadi satu
dunia sindikat," Daoed Joesoef menegaskan. "Aksi seperti itu
harus dilakukan di luar kampus, dengan predikat pemuda."
Bisakah itu dilakukan dalam kondisi Indonesia kini? Sarwono
Kusumaatmaja menjawab: "Selama institusi politik itu lemah,
selama itu pula institusi yang punya potensi berperan sebagai
kekuatan politik akan mempengaruhi kampus." Menurut Sarwono,
yang merasa DPR belum berperanan baik, dengan tidak
menyelesaikan problem dasarnya, "normalisasi kampus itu sia-sia
saja. Saya lebih senang menyebut normalisasi bangsa dan
negara."
Kenapa terjadi demikian? "Sebab pemerintah terlalu kuatir
terhadap dinamika, yang kalau dilihat dari kacamata sekuriti
selalu memancing kekacauan. Seharusnyalah pemerintah memberi
mekanisme sehingga dinamika itu bisa ditampung," kata Sarwono.
Ridwan Saidi berpendapat, selain pengambilan keputusan dalam
organisasi ekstra berbelit, "organisasi ekstra tidak dengan
sendirinya bisa menampung aspirasi mahasiswa, yang tidak
spesifik." Masih dalam nada serupa, Amir Hamzah mengatakan,
ketika aksi politik di dalam kampus dilarang, sementara itu aksi
di luar kampus tersendat-sendat karena fungsi dan peranannya
yang belum jelas. Apabila aksi politik ini tidak tersalur secara
wajar, "pada saatnya hanya akan menggalakkan ekstremitas yang
tidak terkontrol," katanya.
Baca berita dengan sedikit iklan, klik di sini